Makalah Project Based Learning
-
Upload
adelita-dwi-aprilia -
Category
Documents
-
view
32 -
download
8
description
Transcript of Makalah Project Based Learning
MAKALAH PROJECT BASED LEARNING (PJBL) “Hipertiroid, Hipotiroid, Cushing Syndrome”
Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah blok Sistem Endokrin
Disusun Oleh:
Irfan Marsuq Wahyu (135070201111002)Dwi Kurnia Sari (135070201111003)Puput Lifvaria Panta (135070201111004)Adelita Dwi Aprilia (135070201111005)Wahyuni (135070201111006)Ratna Juwita (135070201111007)Zahirotul Ilmi (135070201111008)Ni Putu Ika P. (135070201111009)Ni Luh Saptya W. (135070201111028)Kadek Essidiana U. (135070201111029)Luluk Wulandari (135070201111030)Zaifullah Ipung (135070218113021)
Kelompok 5
PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERANUNIVERSITAS BRAWIJAYA
Jalan Veteran MalangSeptember 2015
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kortisol merupakan g
Diabetes insipidus mempunyai angka kejadian 3: 100.000 populasi umum, jika tidak
diobati akan dapat mengancam jiwa. Meskipun jarang terjadi, kasus diabetes insipidus
harus segera diidentifikasi dan diperbaiki. Oleh karena itu, penulis membuat makalah ini
agar bermanfaat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya pembaca
makalah ini yang membahas diabetes insipidus serta asuhan keperawatan yang tepat untuk
mengatasi masalah ini. (Price, 2005)
1.2.Batasan Topik
1.2.1. Definisi Cushing Syndrome
1.2.2. Etiologi Cushing Syndrome
1.2.3. Faktor Risiko Cushing Syndrome
1.2.4. Epidemiologi Cushing Syndrome
1.2.5. Klasifikasi Cushing Syndrome
1.2.6. Manifestasi klinis Cushing Syndrome
1.2.7. Patofisiologi Cushing Syndrome
1.2.8. Pemeriksaan diagnostik Cushing Syndrome
1.2.9. Penatalaksanaan medis Cushing Syndrome
1.2.10. Komplikasi Cushing Syndrome
1.2.11. Diagnosa Keperawatan
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. DEFINISI CUSHING SYNDROME
Sindrom cushing merupakan kumpulan abnormalitas klinis yang disebabkan
oleh keberadaan hormone korteks adrenal (khususnya kortisol) dalam jumlah berlebih
atau kortikosteroid yang berkaitan, dan hormone androgen serta aldosteron (dalam
tahap lebih rendah). (Kowalak,2011)
Sindrom Cushing adalah suatu keadaan yang diakibatkan oleh efek metabolik
gabungan dari peninggian kadar glukokortikoid dalam darah yang menetap. Kadar yang
tinggi ini dapat terjadi secara spontan atau karena pemberian dosis farmakologik
senyawa –senyawa glukokortikoid. (Sylvia A. Price; Patofisiologi, Hal. 1088).
Sindrom Cushing adalah keadaan yang disebabkan oleh hiperadrenokortikisme,
lebih sering ditemukan pada perempuan, akibat adanya neoplasma di korteks
adrenal/hipofisis anterior, atau akibat asupan glukokortikoid jangka panjang untuk
kepentingan teraupetik.(Dorland)
2.2.ETIOLOGI CUSHING SYNDROME
Sindrom Cushing dapat disebabkan oleh pemberian glukortikoid jangka panjang
dalam dosis farmakologik (latrogen) atau oleh sekresi kortisol yang berlebihan
akibat gangguan aksis hipotalamus-hipofise-adrenal (spontan). Pada sindrom cusing
spontan, hiperfungsi korteks adrenal terjadi sebagai akibat ransangan belebihan
oleh ACTH atau sebagai akibat patologi adrenal yang mengakibatkan produksi
kortisol abnormal. (Sylvia A. Price; Patofisiologi, hal 1240)
Sindrom Cushing disebabkan oleh sekresi kortisol atau kortikosteron yang
berlebihan, kelebihan stimulasi ACTH mengakibatkan hyperplasia korteks anal ginjal
berupa adenoma maupun carcinoma yang tidak tergantung ACTH juga
mengakibatkan sindrom Cushing. Demikian juga hiperaktivitas hipofisis, atau tumor
lain yang mengeluarkan ACTH. Syndrome Cushing yang disebabkan tumor hipofisis
disebut penyakit Cushing. (buku ajar ilmu bedah, R. Syamsuhidayat, hal 945).
Selain itu, penyebab sindrom cushing meliputi:
Kelainan hormone hipofisis anterior (kortikotropin)
Sekresi kortikotropin yang bersifat otonom dan ektopik oleh tumor di luar kelenjar
hipofisis (biasanya bersifat malignan, kerap kali berupa karsinoma oat cell pada
paru-paru)
Pemberian kortikosteroid yang berlebihan, termasuk pemakaian yang lama
(Kowalak, 2011)
2.3.FAKTOR RESIKO CUSHING SYNDROME
1. Orang yang mengkonsumsi kortikosteroid (seperti prednison) yang berlebihan,
termasuk pemakaian yang lama. (Kowalak, 2001)
Sindrom cushing terjadi pada orang yang harus menggunakan kortikosteroid
dosis tinggi karena keadaan medis serius. Gejala-gejalanya bisa kadangkala terjadi
bahkan jika kortikosteroid dihirup, seperti untuk asma, atau digunakan khususnya
untuk sebuah kondisi kulit (Sylvia, 2006).
kortikosteroid yang berlebihan juga mempengaruhi distribusi jaringan
adiposa yang terkumpuk didaerah sentral tubuh yang menyebabkan obesitas, wajah
bulan (moon face), memadatnya fosa supraklavikularis dan tonjolan servikodorsal
(punuk kerbau). Obesitas trunkus dengan ektremitas atas dan bawah yang kurus
akibat atropi otot memberikan penampilan klasik berupa cushingoid. (Sylvia, 2006).
Gukokortikoid mempunyai efek minimal pada kadar elektrolit serum. Akan
tetapi, kalau diberikan atau dihasilkan dalam kadar yang terlalu besar, dapat
menyebabkan retensi natrium dan pembuangan kalium, mengakibatkan edema,
hipokalemia dan alkalosis metabolik. (Sylvia, 2006).
2. Orang dengan gangguan primer kelenjar adrenal, dimana kelenjar adrenal
memproduksi kortisol secara berlebihan diluar stimulus dari ACTH. Biasanya terjadi
akibat adanya tumor jinak pada korteks adrenal (adenoma). Selain itu dapat juga
tumor ganas pada kelenjar adrenal (adrenocortical carcinoma).
3. Orang yang mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Sindrom chusing alkoholik
yaitu produksi alkohol berlebih, dimana akohol mampu menaikkan kadar kortisol.
2.4.EPIDEMIOLOGI CUSHING SYNDROME
Sindrom Cushing (disebabkan oleh pengobatan dengan kortikosteroid) adalah
bentuk paling umum dari sindrom cushing. Berdasarkan penelitian dan survey terhadap
rumah sakit di Indonesia tentang penyakit Cushing Sindrom pada tahun 2000-2001, hasil
menyebutkan bahwa kejadian Cushing Sindrom terjadi pada 200 orang dewasa berusia
antara 20-30 tahun. Pada kelompok usia 20-30 tahun, resiko terkena Cushing Sindrom
mencapai 10 persen. Dalam penelitian secara global didapat hasil sedikitnya 1 dari tiap 5
orang populasi dunia berkemungkinan terkena kelainan ini tanpa membedakan jenis
kelamin. Namun sumber lain mengatakan rasio kejadian antara wanita dan pria untuk
sindrom cushing adalah sekitar 3:1 berhubungan dengan tumor adrenal atau pituitary.
2.5.KLASIFIKASI CUSHING SYNDROME
Sindrom cushing dapat dibagi menjadi dua jenis:
Dependen ACTH
Peningkatan kadar kortisol tergantung pada ACTH dan tidak dapat menekan sekresi
ACTH dari hipofisis. Pada tipe ini hipersekresi glukokortikoid disebabkan oleh hipersekresi
ACTH. Yang temasuk dalam syndrome ini adalah
a. Hiperfungsi korteks adrenal non tumor
Diantara jenis dependen ACTH, hiperfungsi korteks adrenal mungkin disebabkan oleh
sekresi ACTH oleh kelenjar hipofisis yang abnormal. Karena tipe ini mula-mula dijelaskan
oleh Harsey Cushing pada tahun 1932, maka keadaan ini juga disebut sebagai penyakit
cushing.
b. Sindrom ACTH ektopik
Sejumlah besar neoplasma dapat menyebabkan sekresi ektopik ACTH. Neoplasma-
neoplasma ini biasanya berkembang dari jaringan-jaringan yang berasal dari lapisan
neuroektadermal selama perkembangan embrional. Karsinoma sel oat paru, karsinoid
bronchus, timoma, dan tumor sel-sel pulau dipankreas, merupakan contoh-contoh yang
paling sering ditemukan. Beberapa tumor ini mampu menyekresi CRH ektopik. Pada
keadaan ini, CRH ektopik merangsang sekresi ACTH hipofisis, yang menyebabkan
terjadinya sekresi kortisol secara berlebihan oleh korteks adrenal. Pada kebanyakan
pasien tidak menunjukkan gambaran sindrom cushing yang khas ,gejala klinis dapat di
tandai dengan penyakit yang cepat menjadi berat,penurunan berat badan,edema dan
pigmentasi
Independen ACTH
Peningkatan kadar kortisol tidak tergantung ACTH (autonom) dan dapat menekan
sekresi ACTH dari hipofisis. Pada tipe ini ditemukan peningkatan glukokortikoid dalam darah
sedangkan kadar ACTH menurun karena mengalami penekanan. Yang termasuk dalam
sindrom ini adalah:
a. Hyperplasia korteks adrenal autonom
Sekunder terhadap kelebihan produksi ACTH hipofisis, yaitu berupa disfungsi
hipothalamik-hipofisa dan mikro dan makroadenoma yang menghasilkan ACTH hipofisis.
b. Hiperfungsi korteks adrenal tumor (adenoma dan karsinoma)
Hiperfungsi korteks adrenal dapat terjadi tanpa tergantung pada kontrol ACTH
seperti pada tumor atau hyperplasia korteks adrenal nodular bilateral dengan
kemampuannya untuk menyekresi kortisol secara autonomi dalam korteks adrenal.
Tumor korteks adrenal yang akhirnya menjadi sindrom cushing dapat jinak (adenoma)
atau ganas (karsinoma). Adenoma korteks adrenal dapat menyebabkan sindroma
cushing yang berat, namun biasanya berkembang secara lambat, dan gejala dapat
timbul bertahun-tahun selama diagnosis ditegakkan. Sebaliknya, karsinoma
adrenokortikal berkembang cepat dan dapat menyebabkan metastasis serta kematian.
Kadangkala tumor yang tidak bersifat kanker (adenoma) terjadi pada kelenjar
adrenalin, yang menyebabkan kelenjar adrenalin menghasilkan kortikosteroid secara
berlebihan. Adrenal adenomas sangat umum. Setengah orang mengalaminya pada usia
70. hanya bagian kecil pada adenomas menghasilkan hormon berlebihan, meskipun
begitu tumor yang tidak bersifat kanker pada kelenjar adrenalin sangat langka. (Price,
2005)
2.6.PATOFISIOLOGI CUSHING SYNDROME
(terlampir)
2.7.MANIFESTASI KLINIS CUSHING SYNDROME
1. Henti pertumbuhan, obesitas, perubahan musculoskeletal, dan intoleransi glukosa
2. Gambaran klasik pada orang dewasa dengan Sindrom Chusing menunjukkan
obesitas sentral, dengan lemak “buffalo hump” di leher dan area supraklavikula,
trunkus yang besar, dan ekstremitas yang secara relative lebih kurus. Kulit menipis,
rapuh, mudah mengalami trauma; ekimosis dan perkembangan striae.
3. Kelemahan dan lemas; terjadi gangguan tidur karena terjadi perubahan sekresi
kortisol diurnal
4. Katabolisme protein yang berlebihan dengan kehilangan masa otot dan
osteoporosis; kifosis, sakit pinggang, dan fraktur kompresi vertebra.
5. Terjadi retensi natrium dan air, menunjang terjadinya hipertensi dan gagal jantung
kongestif.
6. Penampilan “moon face” dan kulit berminyak serta berjerawat
7. Peningkatan kerentanan terhadap infeksi
8. Hiperglikemia atau diabetes
9. Penambahan berat badan, penyembuhan luka kecil dan memar lambat
10. Pada wanita semua usia mungkin terjadi virilasi akibat kelebihan androgen:
penampilan sifat maskulin dan penurunan sifat feminine; pertumbuhan banyak
rambut pada wajah, atrofi payudara, penurunan menstruasi, pembesaran klitoris,
dan suara menjadi lebih dalam. Libido menghilang pada pria dan wanita.
11. Terjadi perubahan pada suasana hati dan aktivitas mental; mungkin terjadi psikosis
12. Jika Sindrom Cushing terjadi sebagai akibat tumor hipofisis, maka dapat terjadi
gangguan visual karena tekanan pada khiasma optikus
2.8.PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK CUSHING SYNDROME
1. Pemeriksaan kadar ACTH plasma
Pemeriksaan kadar ACTH plasma dapat digunakan untuk membedakan berbagai
penyebab Sindrom Cushing, terutama memisahkan penyebab dependen ACTH dan
independen ACTH. Pada sindrom ACTH ektopik,kadar ACTH bisa jadi meningkat >
110 pmol/L (500pg/mL), dan pada kebanyakan pasien, kadar ACTH berada di atas 40
pmol/L (200pg/mL). Pada sindrom Cushing sebagai akibat mikroadenoma atau
disfungsi hopotalamik pituitari, kadar ACTH berkisar 6-30pmol/L (30-150pg/mL)
[normal : < 14 pmol/L (< 60pg/mL) ] (Bahri,2006).
2. Pemeriksaan Laboratorium
Pada pemeriksaan laboratorium sederhana, didapati limfositofeni, jumlah netrofil
antara 10.000 – 25.000/mm3. eosinofil 50/ mm3 hiperglekemi (Dm pada 10 %
kasus) dan hypokalemia. Hipokalemia, hipokloremi, dan alkalosis metabolik
biasanya ditemukan pada kasus ACTH ektopik (Stephen,2010).
3. Pemeriksaan kadar kortisol
Pemeriksaan kadar kortisol dan“overnight dexamethasone suppression test” yaitu
memberikan 1 mgdexametason pada jam 11 malam, esok harinya diperiksa lagi
kadar kortisol plasma. Pada keadaan normal kadar ini menurun sehubungan dengan
supresi ACTH yang diinduksi kortisol dan involusi zona retikularis yang menghasilkan
androgen (Gordon H, et al. 2005)
4. Pemeriksaan radiologi
Pemeriksaan radiologi untuk memeriksa adrenal adalah pencitraan tomografi
komputer (CT Scan) abdomen. CT Scan bernilai untuk menentukan lokalisasi tumor
adrenal dan untuk mendiagnosis hiperplasia bilateral. CT scan resolusi tinggi pada
kelenjar hipofisis dapat menunjukkan daerah-daerah dengan penurunan atau
peningkatan densitas yang konsisten dengan mikroadenoma pada sekitar 30% dari
penderita-penderita ini. CT scan kelenjar adrenal biasanya menunjukkan
pembesaran adrenal pada pasien dengan sindrom Cushing dependen ACTH dan
massa adrenal pada pasien dengan adenoma atau karsinoma adrenal (Gordon H, et
al. 2005)
2.9.PENATALAKSANAAN MEDIS CUSHING SYNDROME
Menurut Rubenstein,dkk, 2007, penalaksanaan yang dapat dilakukan pada
penderita Cushing Syndrom adalah dengan melakukan hipofisektomi namun
tergantung dari hipofisis penderita. Bila dilakukan adrenalektomi bilateral untuk
mengobati sindrom ini akibat adenoma basophil atau kromofob hipofisis, bisa
terjadi sindrom Nelson disertai hiperpigmentasi akibat β-lipotropin berlebihan
(melanocyte-stimulating hormone (MSH) dan ACTH) yang tak ditekan oleh kadar
kortisol darah yang tinggi.
Jika penyakit adrenal primer, dilakukan adrenalektomi unilateral atau
bilateral dan bila dilakukan dengan bilateral diikuti dengan terapi pengganti
menggunakan kortisol 20-40 mg/hari dan fludrokortison 0,1 mg/hari.
Metirapon adalah inhibitor kompertitif untuk β-hidroksilasi II pada korteks
adrenal dan bisa digunaka untuk membantu mengendalikan gejala umum cushing
sindrom atau menyiapkan pasien untuk melakukan pembedahan. Obat ini
menghambat produksi kortisol sehingga menyebabkan peningkatan kadar ACTH dan
bisa digunakan sebagai tes untuk fungsi hipofisis.
Menurut Price, 2005, penatalaksanaan untuk penderita cushing sindrom
dengan dependen ACTH tidak sama, bergantung pada sumber ACTH hipofisis atau
ektopik. Beberapa pendekatan terapi dapat digunakan pada pasien dengan
hiperskresi ACTH hipofisis. Jika dijumpai tumor hipofisis sebaiknya diusahan reseksi
tumor transfenidal. Tetapi jika terdapat bukti hiperfungsi hipofisis namun tumor
tidak dapat ditemukan dapat dilakukannya radiasi kobalt pada kelenjar hipofisis.
Obat-obatan kimiayang mampu menyekat (ketonazol dan aminoglutemid) atau
merusak sel-sel korteks adrenal penghasil kortisol (mitotane) juga mampu
mengontrol kelebihan kortisol. Sedangkan untuk pengobatan ACTH ektopik
berdasarkan pada reaksi neoplasma yang menyekresikan ACTH atau adrenalektoi
atau supresi kimia fungsi adrenal.
2.10. KOMPLIKASI
1. Osteoporosis
Matriks protein tulang menjadi rapuh dan menyebabkan osteoporosis,
sehingga dapat dengan mudah terjadi fraktur patologis. Seseorang dengan
osteoporosis telah kehilangan struktur tulang normal yang membuat tulang kuat.
Massa tulang dan kepadatan tulang menurun, dan tulang-tulang menjadi lemah.
Osteoporosis membuat tulang lebih rentan untuk melanggar. Sebuah patah tulang
pergelangan tangan , patah tulang pinggul , atau fraktur kompresi vertebral adalah
lebih umum pada mereka dengan osteoporosis. Sekitar 35 persen wanita di AS
mengalami osteoporosis.
Gejala osteoporosis
Gejala osteoporosis meliputi kehilangan tinggi, kifosis tulang belakang, nyeri
punggung kronis , sakit pinggul , dan nyeri pergelangan tangan . Gejala patah tulang
meliputi tiba-tiba, nyeri tulang yang parah.
2. Peningkatan kerentanan terhadap infeksi
Hormon ini juga melalui pembentukan protein lipokortin dan fosokortin,
menekan pelepasan histamin, interleukin dan limfokin. Dengan menghambat
fogfolipose, glukokortikoid menekan pembentukan prostaglandin dan leukotrien,
hormon ini menghambat pembentukan anti bodi dan karna itu bekerja sebagai
imunosupresif
3. Hirsutisme
Sindrom Cushing. Sindrom Cushing adalah suatu kondisi yang terjadi ketika
tubuh terkena/terpapar hormon kortisol dalam tingkatan yang tinggi. Hormon
kortisol adalah hormon steroid yang berpengaruh dalam respons tubuh terhadap
stres. Hal ini dapat berkembang ketika kelenjar adrenal, yakni hormon kelenjar
sekresi yang terletak tepat di atas ginjal, membuat kortisol terlalu banyak, atau
dapat terjadi karena konsumsi obat seperti kortisol dalam jangka waktu lama.
Peningkatan kadar kortisol mengganggu keseimbangan hormon seks dalam tubuh,
yang dapat menyebabkan hirsutisme
4. Batu ureter
Jika penderita cushing syndrome sudah terkena masalah penurunan
kekebalan tubuh terhadap infeksi, maka kemungkinan terkena batu ureter juga
semakin besar. Karena bisa terjadi infeksi pada kandung kemih.
2.11 DIAGNOSA KEPERAWATAN
Daftar Pustaka
Kowalak, Jennifer P. 2011. Buku Ajar Patofisiologi. Jakarta: EGC
Dorland, W.A. Newman. 2011. Kamus Saku Kedokteran Dorland. Jakarta:EGC
R. Syamsuhidayat. 1997. Buku Ajar Ilmu Bedah. Jakarta:EGC
Price, Sylvia Anderson. 1994. Patofisiolgi Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit. Jakarta:EGC
Baughman, Diance C. 2000. Keperawatan Medikal-bedah: Buku Saku untuk Brunner dan
Suddarth. Jakarta: EGC
Price, Sylvia Anderson. 2005. Patofisiologi: Konsep Klinis Proses-proses Penyakit. Edisi 6.
Jakarta: EGC
Stephen J, McPhess, Maxine A. 2010. Current Medical Diagnosis and Treatment.
Chapter 26-Cushing Syndrome. USA : McGraw-Hill
Piliang S, Bahri C. 2006. Hiperkortisolisme. In : Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Jilid
III. Jakarta: Pusat Penerbitan Departemen Ilmu Penyakit Dalam. Edisi IV FKUI.
Gordon H, et al. 2005. Disorders of the Adrenal Cortex-Cushing syndrome. In:
Kasper D, et al, editors. Harrison Principle Of Internal Medicine Sixteenth
Edition. USA : Mc. Graw-Hill.
Rubenstein, David, dkk. 2007. Lecture Note Kedokteran Klinis, Ed.6. Jakarta : Erlangga















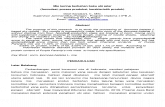










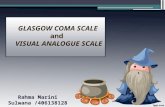




![Untitled-1 [sim.ihdn.ac.id]sim.ihdn.ac.id/app-assets/repo/repo-dosen-132002102122-34.pdfJudul Makalah Penulis Makalah Identitas Makalah Kategori Publikasi Makalah KARYA ILMIAH : PROSIDING](https://static.fdocuments.in/doc/165x107/606da3f0eca44539572e29f4/untitled-1-simihdnacidsimihdnacidapp-assetsreporepo-dosen-132002102122-34pdf.jpg)
