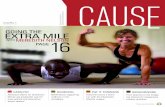BIMKGI VOL 2 NO 1
-
Upload
helsi-nadia-riani -
Category
Documents
-
view
115 -
download
17
description
Transcript of BIMKGI VOL 2 NO 1
-
i
BIMKGI Volume 2 No.1 | Juli- Desember 2013
Pelindung
Sekretaris Jendral Persatuan Senat Mahasiswa
Kedokteran Gigi Indonesia (PSMKGI)
Penasehat
drg. Retno Ardhani, M.Sc. Universitas Gadjah Mada
Pimpinan Umum
Mutma Inna Universitas Gadjah Mada
Pimpinan Redaksi
Failasofia Universitas Gadjah Mada
Sekretaris
Nanda Nur Andityas Universitas Gadjah Mada
Bendahara
Rika Putri S. Universitas Gadjah Mada
Penyunting Ahli
drg. Tetiana Haniastuti, M.Kes, Ph.D Universitas Gadjah Mada
Dr. drg. Widjijono, S.U. Universitas Gadjah Mada
drg. Lisdrianto Hanindriyo, MPH. Universitas Gadjah Mada
drg. Margareta Rinastiti, M.Kes, Ph.D Universitas Gadjah Mada
drg. Christnawati, M.Kes, Sp.Ort Universitas Gadjah Mada
Penyunting Pelaksana
Septika Prismasari Universitas Gadjah Mada
Apriliani Astuti Universitas Gadjah Mada
Novi Atmania D. Universitas Gadjah Mada
Inten Pratiwi Universitas Gadjah Mada
Youvanka Arsy Winmirah Universitas Gadjah Mada
Humas dan Promosi
Navilatul Ula Universitas Gadjah Mada
Isti Noor Masita Universitas Gadjah Mada
Muhammad Fahmi Alfian Universitas Gadjah Mada
Nur Rahmawati Sholihah Universitas Gadjah Mada
Diftya Twas Galih Atyasa Universitas Gadjah Mada
Novaria Universitas Gadjah Mada
Tata Letak dan Layout
Mika Cendy Permatasari Universitas Gadjah Mada
Ratihana Nurul Indias Universitas Gadjah Mada
Amalia Rachmawati S. Universitas Gadjah Mada
Nur Amalia Puspitasari Universitas Gadjah Mada
SUSUNAN PENGURUS
-
ii
BIMKGI Volume 2 No.1 | Juli- Desember 2013
Susunan Pengurus................................................................................................................................... i
Daftar Isi...................................................................................................................................................... ii
Petunjuk Penulisan ......................................................................................................................... iii
Sambutan Pimpinan Redaksi.............................................................................................................. ix
Research Hubungan Antara Durasi Hemodialisis Dengan Periodontitis Pada Pasien Dengan Gagal
Ginjal Kronik (Kajian di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh)
Dara Mauliza, Oki Tristanty
............................................................................................................................. ..................................................................................................... 1
Aktivitas Antibakteri Tepung Cacing Tanah (Lumbricus rubellus) terhadap Enterococcus
faecalis secara In Vitro
Dian R. Rinanda, Andi Y. Daulay
............................................................................................................................. ..................................................................................................... 8
Literature Study Potensi Enzim Bromelin Pada Bonggol Nanas (Ananas comosus) Sebagai Bahan Anti Plak
Dalam Pasta Gigi
Muhammad A. Najib, Hendri J. Permana, Fatkhur Rizqi
............................................................................................................................. ..................................................................................................... 16
Pentingnya Data Status Kesehatan Gigi dan Mulut Pada Kartu Menuju Sehat Ibu Hamil
(Upaya Menunjang Program MDGS 2015)
Irma Ariany Syam, Baiq Miftahul Fatia, Andi Fatima T
............................................................................................................................. ..................................................................................................... 23
Ort-Card (Orthodontic Card) Sebagai Upaya Melindungi Masyarakat Terhadap Kesalahan
Perawatan Akibat Pemasangan Kawat Gigi Ilegal
Irma Ariany Syam, Akmalia Rosyada, Ayu Putri Djohan
............................................................................................................................. ..................................................................................................... 30
Perawatan Apeksogenesis Dengan Mineral Trioxide Aggregate (MTA) Pada Gigi
Permanen Muda
Febrina Audina
............................................................................................................................. ..................................................................................................... 36
Papain-Based Gel Sebagai Agen Chemo-Chemical Caries Removal Yang Ramah Lingkungan
Dian R. Rinanda, Andi Y. Daulay ............................................................................................................................. .....................................................................................................41
DAFTAR ISI ISSN : 2302-6448
-
iii
BIMKGI Volume 2 No.1 | Juli- Desember 2013
Pedoman Penulisan Artikel
Berkala Ilmiah Mahasiswa Kedokteran Gigi Indonesia (BIMKGI)
Indonesian Dental Student Journal
Berkala Ilmiah Mahasiswa Kedokteran Gigi Indonesia (BIMKGI) merupakan publikasi ilmiah yang terbit
setiap 6 bulan sekali setiap bulan maret dan September berada dibawah Dirjen Perguruan Tinggi.
Dalam mempublikasikan naskah ilmiah dalam berkala ini, maka penulis diwajibkan untuk menyusun
naskah sesuai dengan aturan penulisan BIMKGI.
Ketentuan umum :
1. BIMKGI hanya memuat tulisan asli yang belum pernah diterbitkan oleh publikasi ilmiah lain.
2. Naskah dengan sampel menggunakan manusia atau hewan coba wajib melampirkan lembar
pengesahan laik etik dari institusi yang bersangkutan.
3. Penulisan naskah :
a. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan baik dan benar, jelas,
lugas, serta ringkas.
b. Naskah diketik menggunakan microsoft word dengan ukuran kertas A4, dua (2) spasi,
kecuali untuk abstrak satu (1) spasi, dengan batas margin atas, bawah, kiri dan kanan
setiap halaman adalah 2,5 cm.
c. Ketikan diberi nomor halaman mulai dari halaman judul.
d. Naskah terdiri dari minimal 3 halaman dan maksimal 15 halaman.
4. Naskah dikirim melalui email ke alamat [email protected] dengan menyertakan
identitas penulis beserta alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
Ketentuan menurut jenis naskah :
1 Penelitian asli: hasil penelitian asli dalam ilmu kedokteran gigi, kesehatan gigi masyarakat,
ilmu dasar kedokteran. Format terdiri dari judul penelitian, nama dan lembaga pengarang,
abstrak, dan isi (pendahuluan, metode, hasil, pembahasan/diskusi, kesimpulan, dan saran).
2 Tinjauan pustaka: tulisan naskah review/sebuah tinjauan terhadap suatu fenomena atau
ilmu dalam dunia kedokteran dan kesehatan gigi, ditulis dengan memperhatikan aspek aktual
dan bermanfaat bagi pembaca.
3 Laporan kasus: naskah tentang kasus yang menarik dan bermanfaat bagi pembaca. Naskah ini
ditulis sesuai pemeriksaan, diagnosis, dan penatalaksanaan sesuai kompetensi dokter gigi dan
dokter gigi muda. Format terdiri dari pendahuluan, laporan, pembahasan, dan kesimpulan.
PETUNJUK PENULISAN
-
iv
BIMKGI Volume 2 No.1 | Juli- Desember 2013
4 Artikel penyegar ilmu kedokteran dan kesehatan gigi: naskah yang bersifat bebas ilmiah,
mengangkat topik-topik yang sangat menarik dalam dunia kedokteran atau kesehatan gigi,
memberikan human interest karena sifat keilmiahannya, serta ditulis secara baik. Naskah
bersifat tinjauan serta mengingatkan pada hal-hal dasar atau klinis yang perlu diketahui oleh
pembaca.
5 Editorial: naskah yang membahas berbagai hal dalam dunia kedokteran dan kesehatan gigi,
mulai dari ilmu dasar, klinis, berbagai metode terbaru, organisasi, penelitian, penulisan di
bidang kedokteran, lapangan kerja sampai karir dalam dunia kedokteran. Naskah ditulis sesuai
kompetensi mahasiswa kedokteran gigi.
6 Petunjuk praktis: naskah berisi panduan diagnosis atau tatalaksana yang ditulis secara tajam,
bersifat langsung (to the point) dan penting diketahui oleh pembaca (mahasiswa kedokteran
gigi).
7 Advertorial: naskah singkat mengenai obat atau material kedokteran gigi dan kesimpulannya.
Penulisan berdasarkan metode studi pustaka.
Ketentuan khusus :
1. Untuk keseragaman penulisan, khusus naskah Penelitian asli harus mengikuti sistematika
sebagai berikut:
a. Judul karangan (Title)
b. Nama dan Lembaga Pengarang (Authors and Institution)
c. Abstrak (Abstract)
d. Isi (Text), yang terdiri atas:
i. Pendahuluan (Introduction)
ii. Metode (Methods)
iii. Hasil (Results)
iv. Pembahasan (Discussion)
v. Kesimpulan
vi. Saran
vii. Ucapan terima kasih
e. Daftar Rujukan (Reference)
2. Untuk keseragaman penulisan, khusus naskah Tinjauan pustaka harus mengikuti sistematika
sebagai berikut:
a. Judul
b. Nama penulis dan lembaga pengarang
c. Abstrak
d. Isi (Text), yang terdiri atas:
i. Pendahuluan (termasuk masalah yang akan dibahas)
-
v
BIMKGI Volume 2 No.1 | Juli- Desember 2013
ii. Pembahasan
iii. Kesimpulan
iv. Saran
e. Daftar Rujukan (Reference)
3. Judul ditulis dengan Sentence case, dan bila perlu dapat dilengkapi dengan subjudul. Naskah
yang telah disajikan dalam pertemuan ilmiah nasional dibuat keterangan berupa catatan kaki.
Terjemahan judul dalam bahasa Inggris ditulis italic.
4. Nama penulis yang dicantumkan paling banyak enam orang, dan bila lebih cukup diikuti
dengan kata-kata: dkk atau et al. Nama penulis harus disertai dengan institusi asal penulis.
Alamat korespondensi ditulis lengkap dengan nomor telepon dan email.
5. Abstrak harus ditulis dalam bahasa Inggris serta bahasa Indonesia. Panjang abstrak tidak
melebihi 200 kata dan diletakkan setelah judul naskah dan nama penulis.
6. Kata kunci (key words) yang menyertai abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa
Indonesia. Kata kunci diletakkan di bawah judul setelah abstrak. Tidak lebih dari 5 kata, dan
sebaiknya bukan merupakan pengulangan kata-kata dalam judul.
7. Kata asing yang belum diubah ke dalam bahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring (italic).
8. Tabel dan gambar disusun terpisah dalam lampiran terpisah. Setiap tabel diberi judul dan
nomor pemunculan. Foto orang atau pasien apabila ada kemungkinan dikenali maka harus
disertai ijin tertulis.
9. Daftar rujukan disusun menurut sistem Vancouver, diberi nomor sesuai dengan pemunculan
dalam keseluruhan teks, bukan menurut abjad.
Contoh cara penulisan daftar pustaka dapat dilihat sebagai berikut :
1. Naskah dalam jurnal
i. Naskah standar
Vega Kj, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for
pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996 Jun 1;124(11):980-3.
atau
Vega Kj, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for
pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996;124:980-3.
Penulis lebih dari enam orang
Parkin Dm, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Freidl HP, Ivanov E, et al. Childhood
leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br j Cancer 1996;73:1006-12.
ii. Suatu organisasi sebagai penulis
The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety
and performance guidelines. Med J Aust 1996;164:282-4.
-
vi
BIMKGI Volume 2 No.1 | Juli- Desember 2013
iii. Tanpa nama penulis
Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994;84:15.
iv. Naskah tidak dalam bahasa Inggris
Ryder TE, Haukeland EA, Solhaug JH. Bilateral infrapatellar seneruptur hos tidligere frisk
kvinne. Tidsskr Nor Laegeforen 1996;116:41-2.
v. Volum dengan suplemen
Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational lung
cancer. Environ Health Perspect 1994;102 Suppl 1:275-82.
vi. Edisi dengan suplemen
Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women`s psychological reactions to breast cancer.
Semin Oncol 1996;23(1 Suppl 2):89-97.
vii. Volum dengan bagian
Ozben T, Nacitarhan S, Tuncer N. Plasma and urine sialic acid in noninsulin dependent
diabetes mellitus. Ann Clin Biochem 1995;32(Pt 3):303-6.
viii. Edisi dengan bagian
Poole GH, Mills SM. One hundred consecutive cases of flap laceration of the leg in ageing
patients. N Z Med J 1990;107(986 Pt 1):377-8.
ix. Edisi tanpa volum
Turan I, Wredmark T, Fellander-Tsai L. Arthroscopic ankle arthrodesis in rheumatoid
arthritis. Clin Orthop 1995;(320):110-4.
x. Tanpa edisi atau volum
Browell DA, Lennard TW. Immunologic status of cancer patient and the effects of blood
transfusion on antitumor responses. Curr Opin Gen Surg 1993;325-33.
xi. Nomor halaman dalam angka Romawi
Fischer GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction.
Hematol Oncol Clin North Am 1995 Apr;9(2):xi-xii.
2. Buku dan monograf lain
i. Penulis perseorangan
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY):
Delmar Publishers; 1996.
ii. Editor, sebagai penulis
Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill
Livingstone; 1996.
iii. Organisasi dengan penulis
Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program. Washington:
The Institute; 1992.
-
vii
BIMKGI Volume 2 No.1 | Juli- Desember 2013
iv. Bab dalam buku
Philips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors.
Hypertension: patophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: raven
Press; 1995.p.465-78.
v. Prosiding konferensi
Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings
of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-
19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.
vi. Makalah dalam konferensi
Bengstsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in
medical information. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO
92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10;
Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Hollan; 1992.p.1561-5.
vii. Laporan ilmiah atau laporan teknis
a. Diterbitkan oleh badan penyandang dana/sponsor:
Smith P, Golladay K. Payment for durable medical equipment billed during
skilled nursing facility stays. Final report. Dallas (TX): Dept. of Health and
Human Services (US), Office of Evaluation and Inspection; 1994 Oct. Report No.:
HHSIGOEI69200860.
b. Diterbitkan oleh unit pelaksana
Field MJ, Tranquada RE, Feasley JC, editors. Helath services research: work
force and education issues. Washington: National Academy Press; 1995.
Contract no.: AHCPR282942008. Sponsored by the Agency for Health Care
Policy and research.
viii. Disertasi
Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly/access and utilization
[dissertation]. St. Louis (MO): Washington univ.; 1995.
ix. Naskah dalam Koran
Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates 50,000 admissions
annually. The Washington Post 1996 Jun 21;Sect A:3 (col. 5).
x. Materi audiovisual
HIV + AIDS: the facts and the future [videocassette]. St. Louis (MO): Mosby-Year book;
1995.
-
viii
BIMKGI Volume 2 No.1 | Juli- Desember 2013
3. Materi elektronik
i. Naskah journal dalam format elektronik
Morse SS. Factors in the emergence of infectious disease. Emerg Infect Dis [serial online]
1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5]:1(1):[24 screens]. Available from: URL: HYPERLINK
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
ii. Monograf dalam format elektronik
CDI, clinical dermatology illustrated [monograph on CD-ROM]. Reeves JRT, Maibach H.
CMEA Multimedia Group, producers. 2nd ed. Version 2.0. San Diego: CMEA; 1995.
iii. Arsip computer
Hemodynamics III: the ups and downs of hemodynamics [computer program]. Version
2.2. Orlando (FL): Computerized Educational Systems; 1993.
-
ix
BIMKGI Volume 2 No.1 | Juli- Desember 2013
Assalamualaikum wr. Wb.
Salam Sejahtera untuk kita semua. Menciptakan sebuah karya bukanlah hal yang mudah,
dibutuhkan waktu dan proses yang panjang. Diawali dari ide yang cemerlang dan diikuti kemauan
yang besar untuk merealisasikannya. Karya tulis merupakan salah satu bentuk realisasi dari ide-ide
yang ada. Proses realisasi ini membutuhkan proses yaitu proses pembelajaran yang yang harus
dilakukan agar mendapatkan hasil yang optimal. Mahasiswa Kedokteran Gigi saat ini dihadapkan
pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, sehingga pola berfikirnya pun
dituntut untuk berkembang saling beriringan. Keadaan ini memicu munculnya ide-ide baru di dunia
Kedokteran Gigi dari para mahasiswa. Banyak ide-ide yang sudah terealisasi melalui sebuah tulisan,
namun masih sedikit yang muncul ke permukaan. BIMKGI inilah wadah bagi seluruh mahasiswa
kedokteran gigi se-Indonesia untuk mempublikasikan karya terbaiknya.
Publikasi karya ilmiah ini tidak hanya suatu usaha apresiasi dengan menampilkan karya
tetapi juga suatu bentuk usaha ikut mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang
Kedokteran Gigi. Selain itu, merupakan suatu usaha untuk berbagi ilmu pengetahuan bagi sesama.
Proses pembelajaran dalam pe-nulisan, dari munculnya ide sampai terealisasikan menjadi sebuah
karya tulis itu akan tersirat dan menjadi motivasi bagi yang lain untuk ikut berkontribusi. Banyak
sekali ilmu yang dapat diambil dari seluruh karya yang dipublikasikan dalam BIMKGI baik. Seluruh
artikel penelitian dan studi pustaka yang dipublikasikan dalam volume 2 edisi 1 ini dapat diakses
oleh seluruh mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat umum.
Sebagai pimpinan redaksi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus BIMKGI
atas ker-jasa dan kerja kerasnya sehingga dapat menerbitkan berkala ilmiah ini. Terima kasih dan
apresiasi kepada seluruh penulis atas kerja keras yang dilakukan dalam usaha ikut mengembangkan
ilmu pengetahuan, serta kepada Mitra Bebestari yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk
menilai karya ilmiah ini demi hasil yang terbaik.Semoga seluruh karya yang dipublikasikan dalam
BIMKGI kali ini dapat memberikan man-faat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ,
serta motivasi bagi seluruh mahasiswa kedokteran gigi untuk ikut berkontribusi dalam BIMKGI.
Akhir kata, semoga seluruh harapan kami tercapai dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan
selama proses penyusunan hingga diterbitkannya Berkala Ilmiah Mahasiswa Kedokteran Gigi
Indonesia ini. Kritik dan saran sangat kami nantikan demi perbaikan diedisi selanjutnya. Together
We Can, Together We Serve The Best!
Wassalamualaikum wr.wb
Yogyakarta, 5 Januari 2014
Failasofia (Pimpinan Redaksi)
SAMBUTAN PIMPINAN REDAKSI
-
1
BIMKGI Volume 2 No.1 | Juli- Desember 2013
Research
ABSTRAK Gagal ginjal kronik merupakan masalah kesehatan dunia, dengan jumlah penderita yang bertambah setiap tahun. Gagal ginjal kronik adalah penurunan fungsi ginjal secara perlahan yang berkaitan dengan penurunan laju filtrasi glomerulus. Pasien gagal ginjal kronik biasanya diberikan terapi hemodialisis untuk mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit, serta mengeluarkan produk sisa metabolisme.Pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis sering terjadi periodontitis akibat kondisi kebersihan mulut yang buruk danmenjadi semakin parah seiring bertambahnya durasi hemodialisis yang dijalani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara durasi hemodialisis dengan periodontitis. Penelitian analitik cross sectional ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Subjek penelitian sebanyak 99 orang dengan usia 20-59 tahun. Pemeriksaan kedalaman poket periodontal dan pemeriksaan OHI-S dilakukan terhadap subjek penelitian.Berdasarkan hasil uji chi-square terdapat hubungan yang bermakna antara durasi hemodialisis dengan periodontitis (p < 0,05)sehingga pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara durasi hemodialisis dengan periodontitis. Katakunci: durasi hemodialisis, periodontitis, gagal ginjal kronik.
ABSTRACT Chronic renal failure is a worlds health problem, with a number of patients growing rapidly each year. Chronic renal failure is a progressive decline in the renal function associated with a reduced glomerular filtration rate. Patients with chronic renal failure are usually treated by hemodialysis to maintain fluid and electrolyte balance and eliminate metabolic waste products. In chronic renal failure patients who are undergoing hemodialysis teraphy, they often experiencing periodontitis as a result of poor oral hygiene, and periodontitis can be more serious along with the increasing of undergoing hemodialysis duration. This study was aimed to analyze the relationshipbetween hemodialysis duration and periodontitis. This cross sectional study was done in Regional General Hospital dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. The subjects of this study was 99, aged between 20-59 years old.Subject was clinically examined in periodontal pocket depth and oral hygiene. Based on chi-square test, it found that there was significant relationshipbetween hemodialysis duration and periodontitis (p < 0,05). It can be concluded that in this study, there was significant relationship between hemodialysis duration and periodontitis. Keywords: hemodialysis duration, periodontitis, chronic renal failure.
HUBUNGAN ANTARA DURASI HEMODIALISIS DENGAN
PERIODONTITIS PADA PASIEN GAGAL GINJAL KRONIK
(Kajian di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh)
Dara Mauliza1, Oki Tristanty
1
1Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Jln. Tgk. Tanoh Abee Kompleks FK Unsyiah Darussalam, Banda Aceh 23111 Email: [email protected]
-
2
BIMKGI Volume 2 No.1 | Juli- Desember 2013
1. PENDAHULUAN
Gagal ginjal kronik merupakan
penurunan fungsi ginjal secara progresif dan
ireversibel yang berkaitan dengan penurunan laju
filtrasi glomerulus. Hipertensi kronik, diabetes
melitus dan glomerulonefritis merupakan
penyebab paling sering dari gagal ginjal kronik.1
Hemodialisis menjadi salah satu terapi yang
sangat dibutuhkan oleh penderita gagal ginjal
kronik untuk mengeluarkan sisa-sisa
metabolisme dalam darah.2
Gagal ginjal kronik serta hemodialisis
dapat mempengaruhi kondisi rongga
mulut.Diperkirakan 90% pasien gagal ginjal
kronik mengalami perubahan pada jaringan lunak
mulut serta tulang rahang.3Salah satu
manifestasi oral yang dapat timbuladalah
periodontitis.Periodontitispada penderita gagal
ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis
dapat disebabkan oleh produksi vitamin D yang
tidak adekuat pada ginjal sehingga terjadi
resorbsi tulang, keadaan xerostomia, dan
buruknya kebersihan mulut.4 Pasien cenderung
lebih fokus terhadap penyakitnya dan terapi
hemodialisis yang sangat menyita waktu menjadi
alasan kurangnya menjaga kesehatan mulut.5
Penelitian Bayraktar dkk (2007)
menunjukkan bahwa perbedaan kedalaman
poket periodontal signifikan pada pasien yang
telah menjalani terapi hemodialisis kurang dari
tiga tahun dibandingkan dengan pasien yang
telah menjalani terapi lebih dari tiga tahun.6
Poket periodontal merupakan tanda klinis dari
periodontitis.Metode yang dapat dilakukan untuk
mengetahui keberadaan poket periodontal serta
seberapa besar kedalamannya adalah dengan
melakukan probing.7
Penelitian mengenai kondisi periodontal
khususnya periodontitis pada pasien gagal ginjal
kronik yang menjalani hemodialisis belum pernah
diteliti di Banda Aceh. Berdasarkan hal tersebut,
peneliti tertarik untuk melihat hubungan antara
durasi hemodialisis dengan periodontitis pada
pasien gagal ginjal kronik di Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
2. METODE
Jenis penelitian adalah penelitian analitik
cross sectional. Penelitian dilaksanakan pada
tanggal 25 Maret 8 April 2013.Subjek dalam
penelitian ini adalah pasien gagal ginjal kronik
yang menjalani terapi hemodialisis di Instalasi
Hemodialisis Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Zainoel Abidin Banda Aceh yang memenuhi
kriteria inklusi. Pengambilan subjek dilakukan
secara non probability sampling yaitu dengan
purposive sampling.
Kriteria Inklusinya yaitu bersedia menjadi
subjek penelitian, usia 20-59 tahun dan memiliki
salah satu gigi insisivus sentralis di setiap
rahang, salah satu gigi insisivus lateralis di regio
dua dan empat, salah satu gigi premolar di regio
dua dan empat, dan gigi molar satu atau molar
dua di setiap regio.
Kriteria Eksklusinya yaitu sedang
menjalani perawatan periodontal8, sedang
mengkonsumsi antibiotik.8, pasien dengan
kondisi yang sangat lemah, sehingga tidak
memungkinkan dilakukan pemeriksaan, pasien
yang memakai alat ortodonti cekat danpasien
yang memiliki tambalan overhanging.
Alat penelitian yang digunakan yaitu kaca
mulut no. 4, prob periodontal UNC 15, pinset,
autoklaf, medi pack, masker, sarung tangan,
gelas plastik, kapas, ember kecil, tissue, alat
tulis, lembar informed consent, lembar kuisioner
seleksi subjek penelitian, lembar identitas subjek
penelitian, lembar pemeriksaan poket periodontal
dan lembar pemeriksaan OHI-S.
-
3
BIMKGI Volume 2 No.1 | Juli- Desember 2013
Bahan yang digunakan yaitu
Hemiseal.Hemiseal adalah suatu bahan
hemostatik cair dengan komposisi feracrylum
(1%).
Cara kerja penelitian dilakukan dengan
cara melihat daftar registrasi serta rekam medik
pasien termasuk diagnosis gagal ginjal, usia, dan
jenis kelamin. Kemudian dilakukan pengisian
kuisioner seleksi subjek penelitian untuk
menentukan pasien yang masuk ke dalam
kriteria inklusi dan eksklusi.
1. Informed Consent
Pasien yang memenuhi kriteria inklusi
akan diberikan informed consent serta dijelaskan
tujuan dan manfaat penelitian, prosedur
pemeriksaan, risiko, antisipasi terhadap risiko
dan hak untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.
Pasien yang bersedia menjadi subjek penelitian
kemudian diminta untuk menandatangani lembar
persetujuan menjadi subjek penelitian dan
kemudian dilakukan pemeriksaan klinis berupa
kedalaman poket periodontal dan OHI-S.
2. Universal Precaution
Peneliti menggunakan sarung tangan
dan masker pada saat melakukan pemeriksaan.
Satu set peralatan yang dipakai untuk
pemeriksaan, seperti kaca mulut, prob
periodontal, dan pinset hanya dipakai sekali
untuk satu orang pasien. Alat-alat tersebut telah
disterilisasi terlebih dahulu menggunakan
autoklaf dengan suhu 1210C dan tekanan 15 psi
(2 atm) selama 60 menit.
3. Pemeriksaan Poket Periodontal
Pemeriksaan poket periodontal dilakukan
pada bagian mesial gigi. Gigi yang akan
diperiksa yaitu gigi 16, 21, 24, 36, 41, dan 44.4
Pemeriksaan dilakukan dengan memasukkan
probe periodontal ke dalam sulkus gingiva gigi
yang akan diperiksa.7 Kemudian diukur
kedalaman poket periodontal, yaitu jarak dari
margin gingiva sampai ke dasar sulkus gingiva
atau poket periodontal.Hasilnya dicatat pada
formulir pemeriksaan.
4. Pemeriksaan OHI-S
Pemeriksaan oral hygiene diperiksa
dengan menggunakan Oral Hygiene Index-
Simplified dari Green dan Vermilion
(1964).Pengukuran dilakukan dengan cara
menjumlahkan Indeks Debris dan Indeks
Kalkulus.Pengukuran dilakukan pada gigi 16, 11,
26, 36, 31, dan 46.
5. Analisis Data
Analisis statistik dengan uji chi-square
untuk melihat hubungan antara durasi
hemodialisis dengan periodontitis.
6. Masalah Etik
Penelitian ini telah mendapat ijin dari berbagai
pihak terkait diantaranya Badan Etik Penelitian
Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala,
Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas
Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan Rumah
Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin. Pada
pelaksanaan penelitian, seluruh subjek penelitian
diberikan informed consent terlebih dahulu
3. HASIL
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Subjek Penelitian
Variabel Jumlah
(N)
Persentase
(%)
Durasi
Hemodialisis
(tahun)
< 1 33 33,3
13 33 33,3
>3 33 33,3
Usia (tahun)
-
4
BIMKGI Volume 2 No.1 | Juli- Desember 2013
20 29 7 7,1
30 39 13 13,1
40 49 28 28,3
50 59 51 51,5
Jenis Kelamin
Laki-laki 65 65,7
Perempuan 34 34,3
Merokok
Merokok 0 0
Tidak merokok 99 100
Diabetes Melitus
Diabetes Melitus 22 22,2
Tidak Diabetes
Melitus
77 77,8
OHI-S
Baik 0 0
Sedang 33 33,3
Buruk 66 66,7
Periodontitis
Tidak
periodontitis
18 18,2
Periodontitis
moderat
39 39,4
Periodontitis
parah
42 42,4
Berdasarkan Tabel 1. di atas diketahui
bahwa jumlah subjek untuk ketiga kelompok
durasi hemodialisis adalah sama, yaitu sebanyak
33 subjek (33,3%) pada setiap kelompok.
Seluruh subjek penelitian, yaitu 99 subjek (100%)
tidak merokok. Jumlah subjek yang tidak
menderita diabetes melitus lebih banyak
dibandingkan dengan yang menderita diabetes
melitus, yaitu 77 subjek (77,8%). Jumlah subjek
yang mengalami periodontitis parah lebih banyak
dibandingkan dengan yang mengalami
periodontitis moderat, yaitu 42 subjek (42,4%).
1. Tabulasi Silang Durasi Hemodialisis
dengan Periodontitis
Pada Gambar 1. terdapat hasil tabulasi
silang antara durasi hemodialisis dengan
periodontitis yang menunjukkan bahwa
periodontitis parah paling banyak dialami oleh
kelompok dengan durasi hemodialisis >3 tahun.
2. Tabulasi Silang Durasi Hemodialisis
dengan OHI-S
0
5
10
15
20
25
3Ju
mla
h S
ub
jek
Durasi Hemodialisis (tahun)
Tidakperiodontitis
Periodontitismoderat
Periodontitisparah
0
5
10
15
20
25
30
< 1 1-3 > 3
Ju
mla
h S
ub
jek
Durasi Hemodialisis (tahun)
OHI-S baik
OHI-Ssedang
OHI-Sburuk
Gambar1. Diagram Batang Tabulasi Silang. Durasi
Hemodialisis dengan Periodontitis. Keterangan: Tidak ada
periodontitis = poket < 4 mm; Periodontitis moderat =
poket 4-6 mm; Periodontitis parah = poket > 6 mm.
Gambar 2. Diagram Batang Tabulasi Silang Durasi
Hemodialisis dengan OHI-S. Keterangan: OHI-S baik
= skor 0,0-1,2; OHI-S sedang = skor 1,3-3,0; OHI-S
buruk = skor 3,1-6,0.
-
5
BIMKGI Volume 2 No.1 | Juli- Desember 2013
Pada Gambar 2. terdapat hasil
tabulasisilang antara durasi hemodialisis dengan
OHI-S yang menunjukkan bahwa OHI-S buruk
paling banyak dialami oleh kelompok dengan
durasi hemodialisis >3 tahun.
3. Tabulasi Silang Periodontitis dengan OHI-S
Tabel 2. Tabel Periodontitis dengan OHI-S
OHIS
Sedang Buruk
Jumlah
(N)
Persentase
(%)
Jumlah
(N)
Persentase
(%)
Tidak
Periodontitis 11 33,3 7 10,6
Periodontitis
moderat
13 39,4 26 39,4
Periodontitis
parah 9 27,3 33 50,0
Total 33 100 66 100
Pada Tabel 2. terdapat hasil tabulasi
silang antara periodontitis dengan OHI-S yang
menunjukkan bahwa periodontitis lebih banyak
terjadi pada kelompok subjek dengan OHI-S
buruk dibandingkan kelompok subjek dengan
OHI-S sedang.
Tabel 3. Analisis Hubungan Durasi Hemodialisis
dengan Periodontitis (1)
Variabel Nilai p
Durasi hemodialisis
Periodontitis
0,012*
Keterangan: * = Uji chi-square, signifikansi: p < 0,05
Diabetes melitus merupakan faktor risiko
yang sangat mempengaruhi terjadinya
periodontitis, di pihak lain diabetes melitus
merupakan salah satu etiologi tersering dari
penyakit gagal ginjal kronik. Pada penelitian ini
diabetes melitus tidak dimasukkan dalam kriteria
ekslusi.Oleh karena itu dilakukan uji analisis
hubungan durasi hemodialisis dengan
periodontitis tanpa memasukkan subjek yang
memiliki riwayat diabetes melitus dapat dilihat
pada Tabel 4.
Tabel 4. Analisis Hubungan Durasi Hemodialisis
dengan Periodontitis (2)
Variabel Nilai p
Durasi hemodialisis
Periodontitis
0,024*
Keterangan: * = Uji chi-square, signifikansi: p < 0,05
Berdasarkan hasil uji chi-square pada
Tabel 3.dan Tabel 4. antara durasi hemodialisis
dengan periodontitis menunjukkan hubungan
yang bermakna (p 3 tahun, yaitu 52,4%, periodontitis
moderat terbanyak terjadi pada kelompok
dengan durasi hemodialisis 1-3 tahun, yaitu
41,0%, sementara subjek yang tidak mengalami
periodontitis paling banyak terjadi pada kelompok
dengan durasi hemodialisis < 1 tahun, yaitu
sebesar 50,0%.
-
6
BIMKGI Volume 2 No.1 | Juli- Desember 2013
Periodontitis dapat terjadi pada pasien
hemodialisis akibat kombinasi beberapa faktor,
yaitu produksi vitamin D yang tidak adekuat
akibat kerusakan ginjal yang dialami, kondisi
xerostomia, serta kondisi oral hygiene yang
buruk.4,11
Pada penderita gagal ginjal kronik,
terjadi penurunan produksi vitamin D, sehingga
kelenjar paratiroid terstimulasi untuk mensekresi
hormon paratiroid. Kadar vitamin D tidak dapat
bertambah karena kerusakan nefron yang
dialami, akibatnya hormon paratiroid, TNF dan
IL-I kemudian mengaktivasi terjadinya
remodeling tulang.12
Pada lain hal, kondisi xerostomia
berkontribusi terhadap terjadinya periodontitis
akibat penurunan kadar Imunoglobulin A pada
saliva yang berfungsi sebagai pertahanan
terhadap mikroorganisme penyebab terjadinya
periodontitis.13
Oral hygiene merupakan faktor penting dalam
terjadinya periodontitis.Pasien hemodialisis
memiliki prioritas yang rendah terhadap
kesehatan dan kebersihan rongga mulut, baik
dikarenakan oleh stres psikologis yang dialami
pasien maupun karena terapi hemodialisis yang
dijalani sangat menyita waktu.9
Sebagaimana hasil penelitian ini yang
menunjukkan bahwa tidak ada subjek yang
memiliki OHI-S baik. Jumlah subjek terbanyak
adalah yang memiliki OHI-S buruk, yaitu 66,7%.
Kelompok yang memiliki OHI-S buruk terbanyak
adalah kelompok dengan durasi hemodialisis > 3
tahun, yaitu 37,9%. Hal ini sesuai dengan
penelitian yang 4,9,10
Diabetes melitus merupakan faktor risiko
periodontitis, di sisi lain diabetes melitus
merupakan salah satu etiologi dari gagal ginjal
kronik.14
Pada penelitian ini diabetes melitus
tidak dimasukkan dalam kriteria eksklusi untuk
menghindari kurangnya jumlah subjek penelitian
dikarenakan diabetes melitus merupakan
penyebab paling sering dari gagal ginjal
kronik.Oleh karena itu,Diabetes melitus menjadi
faktor pengganggu dalam penelitian ini. Riwayat
diabetes melitus ditentukan dari diagnosis dokter
bagian penyakit dalam di Rumah Sakit Umum dr.
Zainoel Abidin sebagaimana yang tertera pada
rekam medik pasien. Dari 99 subjek terdapat 22
subjek dengan riwayat diabetes melitus dan
seluruhnya mengalami periodontitis.15
Merokok juga merupakan salah satu faktor
risiko dari periodontitis.Akan tetapi pada
penelitian ini ditemukan bahwa tidak ada subjek
yang memiliki kebiasaan merokok. Hal ini diakui
pasien bahwa mereka berhenti merokok
semenjak didiagnosis menderita gagal ginjal
kronik oleh dokter bagian penyakit dalam Rumah
Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda
Aceh.
Berdasarkan hasil uji chi-square, pada
penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat
hubungan yang bermakna antara durasi
hemodialisis dengan periodontitis pada pasien
gagal ginjal kronik yang menjalani terapi
hemodialisis di Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Zainoel Abidin Banda Aceh (p < 0,05).
Pengujian dilakukan kembali dengan
mengekslusikan subjek yang memiliki riwayat
penyakit diabetes melitus, kemudian didapatkan
hasil yang serupa.Durasi hemodialisis dikaitkan
dengan oral hygiene yang buruk sebagai salah
satu faktor penyebab terjadinya periodontitis.Oral
hygiene ditemukan semakin buruk seiring
dengan bertambahnya durasi hemodialisis akibat
perilaku yang mengabaikan kebersihan rongga
mulut pada pasien hemodialisis.4,6,9
5. SIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat
-
7
BIMKGI Volume 2 No.1 | Juli- Desember 2013
hubungan antara durasi hemodialisis dengan
periodontitis pada pasien gagal ginjal kronik di
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh..
6. SARAN
Bagi instansi kesehatan, diharapkan agar
dapat mensosialisasikan penyakit periodontal
sebagai salah satu penyakit yang berhubungan
dengan gagal ginjal kronik, serta mengedukasi
pasien agar dapat lebih menjaga kebersihan dan
kesehatan rongga mulut.
DAFTAR PUSTAKA
1. Proctor R, Kumar N, Stein A, Moles D,
Porter S. Oral and dental aspect of
chronic renal failure. Journal of Dental
Research.2005; 84(3): 199-208.
2. Cerver AJ, Bagn JV, Soriano YJ,
Roda RP. Dental management in renal
failure: patient on dialysis. Med Oral
Patol Oral Cir Bucal.2008; 13(7): E419-
26.
3. DeRossi SS, Cohen DL. Renal Disease.
In: Greenberg MS, Glick M, Ship JA,
editors. Burkets Oral Medicine. 11th ed.
Hamilton: BC Decker; 2008.p.363-65.
4. Bhatsange A, Patil SR. Assessment of
periodontal health status in patients
undergoing renal dialysis: a descriptive,
cross-sectional study. Journal of Indian
Society of Periodontology.2012; 16(1):
41
5. Gavalda C, Bgan JV, Scully C, Silvestre
FJ, Milian MA, Jimenez Y. Renal
Hemodialysis Patients: Oral, Salivary,
Dental and Periodontal Findings in 105
adult cases. Oral Disease.1999; 5: 300-
1
6. Bayraktar G, Kurtulus I, Duraduryan A,
Cintan S, Kazancioglu R, Yildiz A, et al.
Dental and periodontal findings in
hemodialysis patients. Oral
Disease.2007; 13:395.
7. Eickholz P. Clinical Periodontal
Diagnosis: Probing pocket depth,
vertical attachment level and bleeding
on probing. Perio.2004; (1): 75-80.
8. Marakoglu I, Gursoy UK, Demirer S,
Sezer H. Periodontal status of chronic
renal failure patients receiving
hemodialysis. Yonsei Medical
Journal.2003; 44(4): 648-52.
9. Sekiguchi RT, Pannuti CM, Silva HT,
Pestana JO, Rumito GA. Decrease in
oral health may be associated
withlength of time since beginning
dialyisis. Spec Care Dentist.2012; 32(1):
7-9.
10. Cengiz MI, Sumer P, Cengiz S, Yavuz
U. The effect of the duration of the
dialysis patients on dental and
periodontal findings. Oral Disease.2009;
15: 339-340.
11. Akar H, Akar GC, Carrero JJ, Stenvinkel
P, Lindholm B. Systemic consequences
of poor oral health in chronic kidney
disease patients. Clin J Am Soc
Nephrol. 2011; 6: 218-26.
12. Little JW, Falace DA, Miller CS, Rhodus
NL. Dental Management of Medically
Compromised Patient. 6th ed. Missouri:
Mosby; 2002.p.149.
13. Marcotte H, Lavole MC. Oral microbial
ecology and the role of salivary
immunoglobulin a. Microbiology and
Molecular Biology Review.1998: 71.
14. Novak KF, Novak MJ. Risk Assessment.
In: Newman MG, Takei HH, Klokkevold
PR, Carranza FA, editors. Carranzas
Clinical Periodontology. 10th ed.
Philadelphia: Saunders Elsevier;
2006.p.602-4.
15. Mittal M, Teeluckdharry. Prevalence of
Periodontal Disease in Diabetic and
Non-diabetic Patients- A Clinical Study.
Journal of Epidemiology.2011;10(1).
-
8
BIMKGI Volume 2 No.1 | Juli- Desember 2013
Research
ABSTRAK Latar Belakang: Enterococcus faecalis adalah bakteri anaerob fakultatif yang dapat menyebabkan
infeksi periapikal sekunder dan sangat resisten terhadap berbagai bahan antimikroba yang biasa
digunakan pada perawatan saluran akar. Cacing tanah (Lumbricus rubellus) mengandung peptida
antibakteri Lumbricin-1 dan diketahui dapat menghambat pertumbuhan bakteri Gram positif, Gram
negatif dan jamur, namun sangat jarang menyebabkan timbulnya resistensi. Tujuan Penelitian:
Penelitian ini bertujuan untuk melihat aktivitas antibakteri tepung cacning tanah (Lumbricus rubellus)
terhadap Enterococcus faecalis secara in vitro. Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan
penelitian eksperimental laboratoris yang bertujuan untuk melihat aktivitas antibakteri Lumbricin-1 dari
tepung cacing tanah terhadap pertumbuhan E. faecalis secara in vitro. Enterococcus faecalis dikultur
pada media CHROMagar VRE dan diinkubasi secara anaerob selama 24-48 jam pada suhu 37C. Bakteri diidentifikasi dengan melihat warna koloni bakteri yang tumbuh pada media CHROMagar VRE
dan pewarnaan Gram, sementara uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi cakram.
Hasil Penelitian: Hasil analisis statistik dengan one way ANOVA dan uji Duncan menunjukkan bahwa
terdapat perbedaan yang nyata (p < 0,05) antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan, namun
tidak terdapat perbedaan yang nyata di antara masing-masing kelompok perlakuan. Kesimpulan:
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tepung cacing tanah memiliki aktivitas
antibakteri yang kuat terhadap pertumbuhan E. faecalis.
Katakunci: Enterococcus faecalis, Lumbricus rubellus, peptida antibakteri, Lumbricin-1
ABSTRACT Background: Enterococcus faecalis is a facultative anerobic bacterium which can cause secondary
periapical infection and is very resistant to numerous antimicrobial substances normally used during
the root canal treatment. Earthworm (Lumbricus rubellus) possess antimicrobial peptide, known as
Lumbricin-1 which is known to hinder the growth of Gram positive and Gram negative bacteria as well
as fungi, but rarely caused resistance. Objectives: This study was conducted to observe the
antibacterial activity of earthworm powder (Lumbricus rubellus) towards Enterococcus faecalis in vitro.
Methods: This research was an experimental laboratory study conducted to observe the antibacterial
activity of Lumbricin-1 contained in earthworm powder towards the growth of E. faecalis in vitro.
Enterococcus faecalis was cultured on CHROMagar VRE media and incubated anaerobically for 24-
48 hours in the temperature of 37C. The bacterium was identified by observing the colour of the
colony of the bacterium growing on the CHROMagar VRE medium and Gram staining, while
antibacterial activity test was performed using disk diffusion method. Results: Statistical analysis
using one way ANOVA and Duncan test showed that there was a significant difference (p < 0,05)
between test and control group. Conclusion: The result of the study showed that earthworm powder
possessed strong antibacterial activity towards the growth of Enterococcus faecalis.
Keywords: Enterococcus faecalis, Lumbricus rubellus, antimicrobial peptide, Lumbricin-1 1. PENDAHULUAN Enterococcus faecalis merupakan bakteri
Gram positif fakultatif anaerob dengan prevalensi
AKTIVITAS ANTIBAKTERI TEPUNG CACING TANAH
(Lumbricus rubellus) TERHADAP Enterococcus Faecalis
SECARA IN VITRO
Dian R. Rinanda1, Andi Y. Daulay
1
1Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Jln. Tgk. Tanoh Abee Kompleks FK Unsyiah Darussalam, Banda Aceh 23111 Email: [email protected]
-
9
BIMKGI Volume 2 No.1 | Juli- Desember 2013
resistensi antibiotik yang semakin meningkat.1
Bakteri ini ditemukan pada 4-40% infeksi
endodontik primer namun sering ditemukan
dalam jumlah yang banyak pada gigi paska
perawatan endodontik dengan lesi periapikal
yang persisten.17
Enterococcus faecalis memiliki
kemampuan untuk melekat di dinding saluran
akar dan membentuk biofilm sehingga lebih
resisten terhadap fagositosis, antibodi dan
antibakteri yang diberikan.2 Selain sebagai
penyebab kegagalan perawatan saluran akar, E.
faecalis juga dikenal sebagai patogen bagi
manusia dan menjadi penyebab dari 80% infeksi
yang biasa disebabkan oleh Enterococci.4
Prevalensi resistensi E. faecalis yang
semakin tinggi telah menjadi suatu permasalahan
serius di bidang kedokteran, khususnya
kedokteran gigi.4 Tingginya jumlah E. faecalis
yang ditemukan pada saluran akar paska
perawatan endodontik telah lama dikaitkan
dengan kegagalan perawatan itu sendiri.3
Salah
satu upaya yang kerap dilakukan untuk
mengatasi masalah tersebut adalah dengan
melakukan penelitian mengenai bahan-bahan
alami yang bersifat antibakteri. Cacing tanah
(Lumbricus rubellus) merupakan salah satu
bahan alam yang diketahui memiliki aktivitas
antibakteri. Hal ini telah dibuktikan oleh enelitian
yang dilakukan Cho et al. pada tahun 1998 telah
berhasil mengisolasi peptida yang bersifat
antibakteri dari cacing tanah.5,6
Aktivitas antibakteri cacing tanah
sebagian besar disebabkan oleh adanya peptida
antibakteri yang berfungsi untuk melindungi
cacing tanah dari mikroorganisme patogen yang
hidup di lingkungan yang sama dengannya.
Peptida antibakteri merupakan substrat yang
sangat penting karena antibodi yang ada pada
cacing tanah tidak cukup untuk mempertahankan
diri dari serangan mikroorganisme patogen.7,8
Lumbricin-1 merupakan peptida antibakteri yang
telah berhasil diidentifikasi dari cacing tanah
Lumbricus rubellus dan diduga bekerja dengan
cara melubangi dinding sel bakteri dan dapat
mengakibatkan kematian bakteri. Peptida ini
terbukti mempunyai aktivitas antibakteri terhadap
bakteri Gram negatif, Gram positif dan jamur.5
Penelitian yang dilakukan oleh Sandra
(2012) membuktikan bahwa tepung cacing tanah
(L. rubellus) dengan konsentrasi 5%, 10%, 20%,
40% dan 80% dalam pelarut akuades dapat
menghambat pertumbuhan Shigella dysentriae.
Biblio (2011) juga telah membuktikan bahwa
tepung cacing tanah (L. rubellus) dapat
menghambat pertumbuhan bakteri
Staphylococcus aureus dan Salmonella typhii.9
Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui aktivitas antibakteri tepung cacing
tanah (Lumbricus rubellus) terhadap E. faecalis.
Pemilihan tepung cacing tanah dari spesies L.
rubellus sebagai bahan alam yang akan diuji
berdasarkan pada teori adanya senyawa peptida
antibakteri yaitu Lumbricin-1 yang bersifat
antibakteri. Senyawa ini diharapkan dapat
menghambat pertumbuhan E. faecalis secara in
vitro, sehingga dapat dikembangkan pada
penelitian-penelitian selanjutnya.
2. METODE
Bahan dan alat yang digunakan adalah
tepung cacing tanah dari spesies Lumbricus
rubellus yang didapatkan dari LIPI Yogyakarta,
kultur bakteri Enterococcus faecalis ATCC 29212
yang berasal dari Laboratorium Mikrobiologi
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia,
media CHROMagar VRE, media MHA, akuades,
NaCl 0,9%, perangkat warna Gram, asam asetat
50%, Chlorhexidine (CHX) 2%, air steril, alkohol
70%, kertas cakram, anaerogen, timbangan
analitik, gelas ukur, cawan petri, tabung reaksi,
-
10
BIMKGI Volume 2 No.1 | Juli- Desember 2013
jarum ose, labu Erlenmeyer, pipet Eppendorf,
lampu spiritus, autoklaf, sterilisator, inkubator,
kaleng, kapas lidi steril, vortex, jangka sorong
Kultur dan identifikasi E. faecalis
dilakukan pada media CHROMagar VRE.14
Kultur E. faecalis dilakukan dengan
menggunakan teknik goresan (streaking).
Goresan diambil dari biakan murni dengan jarum
ose yang sebelumnya telah dipijarkan di atas
lampu spiritus. Jarum ose yang telah
mengandung biakan lalu digoreskan secara zig-
zag di atas media CHROMagar VRE. Cawan
petri yang telah digoreskan bakteri dimasukkan
ke dalam kaleng yang sebelumnya telah diisi
dengan anaerogen, lalu diinkubasi dalam
inkubator selama 24 jam pada suhu 37C.15,16
Koloni E. faecalis akan tampak berwarna biru
toska di atas media CHROMagar VRE.10
Langkah identifikasi selanjutnya dilakukan
dengan pewarnaan Gram.21,22,23
Pembuatan suspensi E. faecalis
dilakukan dengan memindahkan 1-2 ose koloni
E. faecalis dari cawan petri ke dalam tabung
reaksi berisi larutan NaCl 0,9% dengan
menggunakan jarum ose. Selanjutnya kekeruhan
suspensi diukur menggunakan spektrofotometer
dengan panjang gelombang 625 nm dan nilai
absorbansi 0,08-0,1 atau setara dengan
McFarland 0,5 atau 1,5x108 colony forming unit
(CFU)/ml.15,17
Pembuatan larutan tepung cacing tanah
dilakukan dengan menambahkan 300 mg, 400
mg, 500 mg dan 600 mg dimasukkan dalam
tabung reaksi steril. Sebanyak 2,5 ml asam
asetat 50% ditambahkan pada tiap-tiap tabung
lalu dihomogenkan dengan vortex selama 8
menit. Berikutnya ditambahkan lagi 2,5 ml asam
asetat 50% pada setiap tabung dan divortex lagi
selama 7 menit. Supernatan pada permukaan
larutan diambil sebanyak 0,1 ml dengan
mikropipet dan dipindahkan ke tabung reaksi
steril lainnya. Supernatan dicampurkan dengan
4,5 ml air steril dengan tujuan normalisasi asam
asetat 50% hingga mencapai konsentrasi 1%.18
Suspensi bakteri yang telah diukur
kekeruhannya tadi diswab dengan menggunakan
kapas lidi steril secara merata pada media MHA
dan didiamkan selama 5 menit. Kertas cakram
berdiameter 6 mm yang telah disediakan masing-
masing direndam dalam 1 ml larutan tepung
cacing tanah, CHX 2% dan asam asetat 1%
selama 30 menit lalu diletakkan di atas media
MHA dengan menggunakan pinset steril. Kertas
cakram yang direndam dalam CHX 2%
digunakan sebagai kontrol positif, sementara
kertas cakram yang direndam dalam asam asetat
1% digunakan sebagai kontrol negatif.
Selanjutnya media dimasukkan ke dalam kaleng
yang sebelumnya telah diisi dengan anaerogen,
lalu diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37C.
Setelah 24 jam, zona terang yang terbentuk akan
diukur dengan menggunakan jangka sorong.
Perlakuan akan dilakukan pengulangan
sebanyak 4 kali.6,16,17,18
Hasil pengukuran yang didapat
dinyatakan dalam satuan milimeter (mm) dan
diinterpretasikan berdasarkan kategori daya
hambat antibakteri menurut Davis dan Stout.19,20
Data yang diperoleh dari penelitian ini akan
dianalisis menggunakan one way ANOVA yang
kemudian akan dilanjutkan dengan uji Duncan.21
3. HASIL
Hasil uji aktivitas antibakteri
menunjukkan bahwa tepung cacing tanah pada
konsentrasi 300mg/5ml, 400mg/5ml, 500mg/5ml
dan 600mg/5ml dalam pelarut asam asetat 50%
dapat menghambat pertumbuhan E. faecalis.
Berdasarkan klasifikasi Davis dan Stout,
diameter zona hambat yang terbentuk dari
-
11
BIMKGI Volume 2 No.1 | Juli- Desember 2013
larutan tepung cacing tanah konsentrasi
300mg/5ml, 400 mg/5ml, 500mg/5ml dan
600mg/5ml dengan pelarut asam asetat 50%
termasuk dalam kategori kuat dengan rata-rata
diameter zona hambat 11,25 mm, 13 mm, 12,25
mm dan 11,75 mm.
Gambar 1. Hasil Uji Larutan Tepung Cacing
Tanah terhadap E. faecalis
Gambar 2. Diagram Batang Zona Hambat
Berbagai Konsentrasi Larutan Tepung Cacing
Tanah dengan Pelarut Asam Asetat 50% dan
Kelompok Kontrol terhadap Enterococcus
faecalis.
Data pada Gambar 2 menunjukkan rata-
rata diameter zona terang terbesar terdapat pada
konsentrasi 400mg/5ml yaitu 13 mm, dan rata-
rata diameter zona terang terkecil pada
konsentrasi 300mg/5ml yaitu 11,25 mm,
sedangkan pada kontrol negatif (asam asetat
1%) tidak terbentuk zona hambat. Berdasarkan
hasil analisis dengan menggunakan Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS), hasil uji
normalitas menunjukkan sebaran data pada
keseluruhan konsentrasi larutan tepung cacing
tanah normal. Selain itu pada hasil uji
homogenitas diperoleh nilai Sig. 0,077 yang
berarti nilai p > 0,05 sehingga dapat disimpulkan
bahwa data tersebut homogen.
Hasil uji one way ANOVA menunjukkan
bahwa nilai Fhitung sebesar 172,655 lebih besar
daripada nilai Ftabel yang bernilai 3,06 sehingga
dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima.
Dengan kata lain tepung cacing tanah memiliki
aktivitas antibakteri yang nyata terhadap E.
fecalis. Hasil uji Duncan penelitian ini dapat
dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Perbandingan Aktivitas Antibakteri
Tepung Cacing Tanah terhadap E. faecalis
dengan Uji Duncan pada Taraf Kritis 5%
Keterangan: Superscript huruf yang berbeda
menunjukkan perbedaan yang nyata.
Tabel 1. menunjukkan bahwa semua
konsentrasi uji menunjukkan perbedaan yang
nyata dengan kontrol negatif (yang ditunjukkan
dengan superscript yang berbeda). Hal ini
menunjukkan bahwa kontrol negatif mampu
menekan heterogenitas galat dan terlihat jelas
11.25 13 12.25 11.75
26.25
0 0
10
20
30
Rata-rata Zona Hambat Enterococcus faecalis Pada
Berbagai Perlakuan
Perlakuan X SD
P0 (Asam asetat 0,1%) 0,00a 0,00
P1 (Larutan tepung cacing
tanah konsentrasi 300mg/5ml) 11,25
b 1,26
P2 (Larutan tepung cacing
tanah konsentrasi 400mg/5ml) 13,00
b 0,82
P3 (Larutan tepung cacing
tanah konsentrasi 500mg/5ml) 12,25
b 0,96
P4 (Larutan tepung cacing
tanah konsentrasi 600mg/5ml) 11,75
b 0,50
P5 (CHX 2%) 26,25c 2,50
-
12
BIMKGI Volume 2 No.1 | Juli- Desember 2013
bahwa larutan tepung cacing tanah dalam
berbagai konsentrasi memiliki aktivitas antibakteri
terhadap E. faecalis. Larutan tepung cacing
tanah konsentrasi 300mg/5ml, 400mg/5ml,
500mg/5ml dan 600mg/5ml menunjukkan
aktivitas antibakteri yang sama. Aktivitas
antibakteri yang paling kuat ditunjukkan oleh
kontrol positif, yaitu CHX 2%.
4. PEMBAHASAN
Kemampuan tepung cacing tanah
(Lumbricus rubellus) dalam menghambat
pertumbuhan E. faecalis menunjukkan bahwa
cacing tanah L. rubellus mengandung Lumbricin-
1 yang bersifat antibakteri.5,6
Hasil tersebut juga
menunjukkan bahwa konsentrasi larutan tepung
cacing tanah yang tinggi tidak selalu
menghasilkan diameter zona hambat yang besar
pula. Pada konsentrasi 300mg/5ml tepung cacing
tanah yang digunakan lebih sedikit dibandingkan
yang lain, begitu juga peptida yang terlarut
sehingga aktivitas antibakterinya lebih sedikit
dibandingkan yang lain. Aktivitas antibakteri
meningkat pada konsentrasi 400mg/5ml, namun
kembali menurun pada konsentrasi 500mg/5ml
dan 600mg/5ml. Penurunan aktivitas ini
disebabkan oleh kadar tepung cacing tanah yang
terlalu tinggi dibandingkan dengan pelarutnya,
sehingga larutan menjadi jenuh dan sulit untuk
larut.6
Kelarutan peptida sangat bergantung
pada faktor karakteristik pelarut dan zat terlarut
merupakan faktor penting yang harus
diperhatikan. Lumbricin-1 adalah peptida yang
bermuatan +1 yang dibentuk dari 10 asam amino
bermuatan positif dan 9 asam amino yang
bermuatan negatif.7 Peptida yang memiliki
muatan +1 atau lebih hanya akan larut dalam
larutan yang bersifat asam. Oleh sebab itu pada
penelitian digunakan pelarut yang bersifat asam,
yaitu asam asetat.22
Hidrofobisitas Lumbricin-1 menentukan
aktivitas antibakteri yang dimilikinya, karena
hidrofobisitasnya akan berhubungan secara
langsung dengan cara pelarutannya. Lumbricin-1
merupakan peptida yang 22% molekulnya
bersifat hidrofobik.5 Peptida yang
hidrofobisitasnya
-
13
BIMKGI Volume 2 No.1 | Juli- Desember 2013
yang bermuatan negatif, sedangkan peptida
antibakteri, khususnya Lumbricin-1 memiliki
muatan positif.5,8,25
Perbedaan muatan ini akan
menyebabkan peptida tertarik ke sel hingga
akhirnya memasuki membran sel bakteri.5,8,12,13
Penelitian sebelumnya menyimpulkan
bahwa peptida antibakteri dapat membunuh
mikroorganisme dengan membuat lubang-lubang
kecil, meningkatkan permeabilitas dan merusak
membran sel. Setelah berhasil memasuki sel,
peptida antibakteri akan mengikatkan dirinya
pada DNA sel dan menghambat sintesis
makromolekul dan DNA sel sehingga
menyebabkan kematian sel.5,24
Karakteristik lainnya yang dimiliki oleh
Lumbricin-1 adalah kandungan asam amino
prolinnya yang sangat tinggi, dimana dari 62
asam amino yang dimiliki oleh Lumbricin-1, 15%
diantaranya merupakan prolin, seperti yang
ditunjukkan oleh Gambar 6.1.5
Prolin memiliki
kemampuan untuk mengubah bentuk rantai
peptida dan menutupi bagian yang dikenali
sebagai antigen oleh sel bakteri. Saat memasuki
membran sel, peptida akan dikenali sebagai
bagian dari sel bakteri, bukan suatu benda asing
sehingga peptida antibakteri tidak akan diserang
oleh sel. Mekanisme ini dapat mencegah
aktivitas membranolitik sel bakteri sampai
peptida antibakteri dapat menetukan target dan
menyerang sel dengan leluasa. Hal inilah yang
menyebabkan Lumbricin-1 dapat menyerang
berbagai sel bakteri tanpa menyebabkan
toksisitas sel pejamu.5,12
Gambar 6. Prolin pada Struktur Asam Amino
Lumbricin-1
Sampai saat ini telah banyak ditemukan
peptida antibakteri dari berbagai sumber yang
kaya akan prolin, seperti apidaecin, drosocin,
metchnikowin, bactenecin dan PR-39. Semua
peptida antibakteri ini bermuatan positif dan
memiliki kandungan prolin yang tinggi, namun
memiliki aktivitas antibakteri yang berbeda.
Apidaecin, bactenecin dan PR-39 hanya memiliki
aktivitas antibakteri terhadap bakteri Gram positif.
Drosocin memiliki aktivitas antibakteri terhadap
bakteri Gram positif dan Gram negatif, namun
tidak aktif terhadap jamur. Metchnikowin aktif
terhadap bakteri Gram positif dan jamur, namun
tidak aktif terhadap bakteri Gram negatif.
Lumbricin-1 diketahui memiliki aktivitas
antibakteri terhadap bakteri Gram positif, Gram
negatif dan jamur. Hal ini menunjukkan bahwa
Lumbricin-1 memiliki mekanisme yang berbeda
dengan peptida antibakteri kaya-prolin yang lain,
namun sayangnya sampai saat ini mekanisme
kerja Lumbricin-1 dalam menghambat
pertumbuhan bakteri dan jamur belum diketahui
dengan pasti.5,15
5. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa tepung cacing tanah
(Lumbricus rubellus) dapat menghambat
pertumbuhan Enterococcus faecalis. Hal ini
-
14
BIMKGI Volume 2 No.1 | Juli- Desember 2013
disebabkan karena tepung cacing tanah
mengandung peptida Lumbricin-1 yang bersifat
antibakteri.
Penelitian ini menunjukkan bahwa
aktivitas antibakteri tepung cacing tanah
(Lumbricus rubellus) berasal dari peptida
antibakteri yang dimilikinya, yaitu Lumbricin-1.
Berdasarkan hasil tersebut, perlu dilakukan
penelitian lanjutan untuk mengoptimalkan
aktivitas antibakteri Lumbricin-1 terhadap
Enterococcus faecalis dan berbagai
mikroorganisme resisten lainnya. Hal ini penting
untuk dilakukan agar potensi Lumbricin-1
sebagai bahan antibiotik baru yang non-resisten
dan non-toksik serta mudah disintesis dapat
dikembangkan dengan baik di masa yang akan
datang.
DAFTAR PUSTAKA
1. Hidron AI, Edwards JR, Patel J, Horan TC,
Sievert DM, Pollock DA, et al. Antimicrobial-
resistant pathogens associated with
healthcare-associated infections: annual
summary of data reported to the national
healthcare safety network at the Centers for
Diseases Control and Prevention. CDC
2008; 29: 996-1010.
2. Matthew S, Boopathy T. Enterococcus
faecalis: an endodontic challenge. KSR
2011; 33-7.
3. Stuart CH, Schwartz SA, Beeson T J, Owatz
CB. Enterococcus faecalis: Its role in root
canal treatment failure and current concepts
in retreatment. J Endod 2006; 32: 93-8.
4. Portenier I, Waltimo TMT, Haapasalo M.
Enterococcus faecalis: the root canal
survivor and star in post-treatment
disease. Endodontic Topics 2003; 6: 135-
59.
5. Cho JH, Park CB, Yoon YG, Kim SC.
Lumbricin I, a novel proline-rich
antimicrobial peptide from the earthworm:
purification, cDNA cloning and molecular
characterization. Biochimica et Biophysica
Acta 1998; 1408: 67-76.
6. Julendra H, Sofyan A. Uji in vitro
penghambatan aktivitas Escherichia coli
dengan tepung cacing tanah (Lumbricus
rubellus). Media Peternakan 2007; 30: 41-7.
7. Karaca, A. Soil Biology: biology of
earthworms. Berlin: Springer, 2011. p. 1.
8. Tasiemski A. Antimicrobial peptides in
annelids. ISJ 2008; 5: 75-82.
9. Sandra M. Uji efektivitas tepung cacing
tanah Lumbricus rubellus dalam
menghambat pertumbuhan bakteri Shigella
dysenteriae secara in vitro. Jakarta:
Fakultas Kedokteran Universitas
Pembangunan Nasional Veteran, 2012. p.
6-7.
10. Kayaoglu G, Orstavik D. Virulence factors of
Enterococcus faecalis: relationship to
endodontic disease. Crit Rev Oral Biol Med
2004; 15: 308-20.
11. Ekasari, Tjahjaningsih W, Cahyoko Y. Daya
antibakteri tepung cacing tanah (Lumbricus
rubellus) terhadap pertumbuhan bakteri
Vibrio harveyi secara in vitro. Jurnal Ilmiah
Perikanan dan Kelautan 2012; 4: 1-6.
12. Yeaman MR, Yount NY. Mechanism of
antimicrobial peptide action and resistance.
Pharmacol Rev 2003; 55: 27-55.
13. Zasloff M. Antimicrobial peptides of
multicellular organisms. Nature 2002; 415:
389-95.
14. Anonymous. CHROMagar VRE. Access on:
http://chromagar.com/fichiers/1259769034IF
U_CHROMagar_VRE.pdf, Oktober 2012.
-
15
BIMKGI Volume 2 No.1 | Juli- Desember 2013
15. Brown AE. Bensons Microbiological
Applications: laboratory manual in general
microbiology. 9th
ed. New York: McGraw-
Hill, 2005. p. 73, 96.
16. Hadioetomo RS. Mikrobiologi Dasar dalam
Praktek: teknik dan prosedur dasar
laboratorium. Jakarta: Gramedia, 1985. hal.
32.
17. Vandepitte J, Verhaegen J, Engbaek K,
Rohner P, Piot P, Heuck CC. Basic
Laboratory Procedures in Clinical
Bacteriology. 2nd
ed. Geneva: World Health
Organization, 2003. p. 84, 86-9.
18. Rinanda T, Hidayaturrahmi, Juwita.
Karakterisasi SDS-Page lumbricin-1 serta
uji aktivitas antibakteri tepung cacing tanah
(Lumbricus rubellus) terhadap isolat klinis
Pseudomonas aeruginosa resisten
ciprofloxacin dan meropenem. Fakultas
Kedokteran Universitas Syiah Kuala, 2012.
hal. 25. Laporan Hasil Penelitian Dosen
Muda.
19. Marsa, RD. Efek antibakteri ekstrak lerak
dalam pelarut etanol terhadap Enterococcus
faecalis (penelitian in vitro). Medan:
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas
Sumatera Utara, 2010. hal. 19. Skripsi.
20. Dharmawati IG. Efek ekstrak mengkudu
dalam menghambat pertumbuhan
Streptococcus mutans penyebab dental plak
secara in vitro. Program Studi Ilmu
Kedokteran Biomedik Universitas Udayana,
2011. hal. 4. Tesis.
21. Dahlan, MS. Statistika untuk Kedokteran
dan Kesehatan. ed.4. Jakarta: Salemba
Medika; 2009. hal. 83-95.
22. ProImmune. Peptide solubility. Access on:
http://www.thinkpeptides.com/peptidesolubili
ty.html, Desember 2012.
23. AnaSpec Inc. Peptide Solubility Guidelines.
Fremont: EGT Group, 2008. p. 1-2.
24. Park CB, Kim HS, Kim HC. Mechanism of
action of the antimicrobial peptide buforin II:
buforin II kills microorganisms by
penetrating the cell membrane and inhibiting
cellular functions. Biochemical and
Biophysical Research Communications
1998; 1: 253-257.
25. Madigan MT, Martinko JM, Parker J. Brock
Biology of Microorganism. 10th ed. Illinois:
Southern Illinois University, 2003. p. 110.
-
16
BIMKGI Volume 2 No.1 | Juli- Desember 2013
Literature Study
ABSTRAK Pembentukan plak diawali dari adanya proses kolonisasi bakteri yang berinteraksi dengan pelikel pada permukaan gigi. Pembentukan pelikel pada dasarnya merupakan proses perlekatan protein dan glikoprotein saliva pada permukaan gigi. Bakteri melekat pada pelikel dengan bantuan suatu molekul spesifik pada permukaanya. Penggunaan pasta gigi dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut lazim digunakan dalam masyarakat. Penambahan zat aktif pada pasta gigi sudah banyak dilakukan oleh para ahli. Bonggol nanas merupakan limbah dari buah nanas yang jarang dimanfaatkan. Bonggol nanas mengandung enzim bromelin yang merupakan suatu enzim proteolitik. Kajian ini bertujuan untuk membahas manfaat enzim bromelin sebagai bahan anti plak yang ditambahkan ke dalam dalam pasta gigi. Kandungan asam amino yang terbanyak dalam pelikel adalah arginin dan glutamin. Enzim bromelin dapat memecah ikatan asam amino antara arginin-alanin dan glutamine-alanin yang digunakan bakteri sebagai media perlekatan, sehingga dapat menghambat perlekatan antara bakteri dengan pelikel. Selain itu, enzim bromelin pada bonggol nanas sudah teruji biokompabilitas terhadap jaringan rongga mulut, sehingga aman pada saat pemakaiannya. Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa enzim bromelin pada bonggol nanas berpotensi sebagai bahan anti plak melalui mekanisme penguraian media perlekatan bakteri pada permukaan gigi. Kata kunci: bonggol nanas,bromelin, anti plak.
ABSTRACT Early plaque formation begins of colonizing bacteria which interact with surface pellicle tooth. Pellicle formation is essentially a process of attachment of salivary proteins and glycoproteins on the tooth surface. Bacteria attached to the pelikel with the help of specific molecules on the surface. Generally, the people use dentrifrice to keep healthy teeth and mouth. The addition of active ingredient in dentrifrice has been caried out by the experts. Pineapple hump is a waste product rarely used. Hump pineapple contains the enzyme bromelain which is a proteolytic enzyme. This study aims to discuss enzyme bromelain as an anti-plaque material can be added in toothpaste. The highest amino acid content in pellicle are arginine and glutamine. The enzyme bromelain can break the bond between the amino acids (arginin-alanine and glutamine-alanine ) for bacterial attachment, so that it can inhibit the attachment of bacteria to pellicle. In addition, the enzyme bromelain in pineapple lamp test the biocompatibility of the oral tissues, so it is safe when used. Based on this study can conclude that the enzyme bromelain in pineapple hump as anti-plaque material, which really through decomposition mechanism of bacterial attachment on tooth surfaces. Keywords: Pinnaple hump, bromelain, anti-plaque.
POTENSI ENZIM BROMELIN PADA BONGGOL NANAS (Ananas
comosus) SEBAGAI BAHAN ANTI PLAK DALAM PASTA GIGI
Muhammad A. Najib,1 Hendri J. Permana,
1 Fatkhur Rizqi
1
1 Fakultas Kedokteran Gigi
Correspondence : Universitas Jember
Jalan Kalimantan no. 37, Jember-Jawa Timur Email:[email protected]
-
17
BIMKGI Volume 2 No.1 | Juli- Desember 2013
1. PENDAHULUAN
Nanas (Ananas comosus) merupakan
tanaman yang tumbuh subur didaerah yang
beriklim tropis termasuk indonesia. Nanas
mengandung enzim proteolitik yaitu bromelin
yang lebih banyak terdapat pada bonggolnya.
Enzim tersebut dapat mengurai atau memecah
protein.1,2
Enzim bromelin dapat memecah ikatan
protein termasuk glutamin-alanin yang digunakan
bakteri sebagai media perlekatan, sehingga
dapat menghambat perlekatan antara bakteri
dengan pelikel. Pelikel merupakan selapis tipis
glikoprotein yang mengawali terbentuknya plak.
Plak adalah faktor yang mendasari terjadinya
karies dan berbagai penyakit periodontal.3,4,5,6
Populasi mikroba dalam plak sekitar 72-102
juta/mg berat basah setelah 24 jam dan
meningkat menjadi 80-132 juta/mg setelah 3
hari.7
Pencegahan pembentukan plak
merupakan hal penting dalam menghindari karies
gigi. Pada dasarnya pembersihak plak dapat
dilakukan dengan alat-alat mekanis dan kimiawi.
Pembersihan mekanis dimaksudkan dapat
menghilangkan plak secara psikomotorik oleh
pasien dengan bantuan alat khusus seperti sikat
gigi dan dental floss.8,6
Faktor yang
mempengaruhi terbentuknya plak yaitu diet,
faktor saliva dan karakteristik permukaan gigi.9
Penggunaan pasta gigi dilakukan untuk
menambah pembersihan mekanis ketika
menggosok gigi. Perkembangan komposisi pasta
gigi terus mengalami perubahan, sejalan dengan
kemajuan di dunia kedokteran gigi. Efek yang
menguntungkan dari pasta gigi sangat
bergantung pada frekuensi, cara menyikat dan
komponen yang terkandung didalamnya.10
Pada
dasarnya komponen pasta gigi terdiri dari basis
pasta dan komponen aktif. Komponen aktif
berfungsi sebagai antibakteri, antiplak,
antisenisitivitas dan antiinflamasi. Tujuan
penambahan komponen aktif tersebut adalah
menghambat terbentuknya plak sehingga
dampaknya dapat mengurangi berbagai penyakit
gigi dan mulut lainya.
Pemanfaatan bahan herbal sebagai
komponen aktif dalam pasta gigi mulai
dikembangkan dalam kedokteran gigi seiring
dengan semangat back to nature saat ini. Bahan
herbal dianggap masyarakat relatif lebih aman
dibanding bahan-bahan sintetis. Oleh karena itu,
pencarian bahan herbal yang memiliki
kemampuan setara dengan bahan sintesis
sangat populer. Bahan herbal seperti enzim
bromelin dari bonggol nanas yang telah terbukti
biokompatibilitasnya diduga efektif sebagai
bahan aktif antiplak dalam pasta gigi.2
Berdasarkan latar belakang diatas, maka
penulis ingin mengkaji potensi enzim bromelin
pada bonggol nanas (Ananas comosus) sebagai
bahan antiplak pada pasta gigi.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Enzim Bromelin pada Bonggol Nanas
Nanas merupakan tanaman buah berupa
semak yang berasal dari Brasilia (Amerika
Selatan) dan memiliki nama ilmiah Ananas
comosus. Buah nanas mengandung satu enzim
yang penting yang dikenal dengan bromelin.2
Enzim bromelin merupakan enzim hidrolase yang
aktif pada protein. Berdasarkan sumbernya,
enzim protease ada bermacam-macam yaitu
papain, ficin, dan bromelin yang merupakan
protease asal tanaman; tripsin yang merupakan
enzim protease dari pankreas; pepsin dan renin
yang merupakan protease dari persit.11
Berdasarkan sifat-sifat kimia dari lokasi aktif,
maka enzim bromelin termasuk dalam golongan
enzim protease sulfihidril, yang artinya memiliki
-
18
BIMKGI Volume 2 No.1 | Juli- Desember 2013
residu sulfidril (sistenil dan histidil) pada lokasi
aktif. Susunan asam amino yang mengandung
gugus sistein pada sisi aktifnya sebagai berikut :
-Cys Gly Ala Cys Trp Asn Gly Asp
Pro Cys Gly Ala Cys Cys Trp.12
Konsentrasi enzim bromelin pada bagian bonggol
nanas lebih tinggi dibandingkan dengan daging
nanas. 13
Tabel 1. Kandungan Enzim Bromelin pada
Tanaman Nanas13
Bagian
Tanaman
Persen (%)
Buah utuh masak 0,060 0,080
Daging buah masak 0,080 0,125
Kulit buah 0,050 0,075
Tangkai 0,040 0,060
Batang 0,100 0,600
Buah utuh mentah 0,040 0,060
Daging buah mentah 0,050 0,070
Aktifitas enzim bromelin dipengaruhi oleh
beberapa hal, yaitu :
a. Kematangan buah
Semakin matang buah nanas, maka
keaktifan enzim bromelin dalam buah tersebut
semakin berkurang. Hal ini disebabkan pada
waktu pematangan buah terjadi pembentukan
senyawa tertentu, dalam hal ini enzim mungkin
ikut terpakai dalam senyawa tersebut sehingga
sebagian struktur enzim akan rusak, akibatnya
keaktifan berkurang.
b. pH
Aktivitas optimal dari enzim ini adalah
pada derajat keasaman (pH) sebesar 6,5. Nilai
pH terlalu tinggi atau rendah akan
mengakibatkan terjadinya beberapa perubahan
yaitu denaturasi protein dengan kecepatan
katalisa menurun.
c. Suhu
Suhu yang paling baik adalah 30C, suhu
diatas dan dibawah 30C mengakibatkan
keaktifan enzim lebih rendah karena energi
kinetik molekul substrat maupun enzim menjadi
rendah sehingga kecepatan reaksi menjadi
rendah.
d. Konsentrasi dan waktu
Konsentrasi enzim yang berlebih dan
waktu yang lebih lama akan mengakibatkan
kecepatan katalis enzim menurun, karena
konsentrasi substrat efektif untuk tiap molekul
enzim. Bertambahnya molekul enzim akan
menyebabkan daya kerja enzim sebagai
katalisator menjadi lebih lama yang tergantung
pula dengan konsentrasi yang ada.12
2.2 Plak Gigi
Acquired pellice merupakan suatu
lapisan tipis, amorf, translusen, halus, tidak
berwarna, tidak dijumpai adanya bakteri dan
apabila dilihat dengan menggunakan mikroskop
elektron akan tampak aseluler, afibriler, dan
merupakan masa yang homogen. Acquired
pellice terbentuk dalam waktu singkat yaitu
dalam beberapa menit setelah gigi dibersihkan
dan belum tampak adanya bakteri. 5,13,14
Protein merupakan komponen utama
dari acquired pellice. Pembentukan acquired
pellice pertama kali disebabkan adanya adsorbsi
selektif dari Ca2+
, F-, HPO4
2-, dan protein saliva
termasuk glikoprotein pada hidroksi apatit
dipermukaan enamel. Dalam hal ini kelompok
fungsional yang terlibat pada interaksi hidroksi
apatit protein adalah kelompok asam yang
bermuatan negatif, antara lain seperti karboksil
(COO-), fosfat (H2PO4 dan HPO4
2-) dan kelompok
sulfat (HSO4-) dan kelompok amino (NH
3+) yang
bermuatan positif. Kelompok asam yang
bermuatan negatif dapat langsung terikat pada
ion kalsium atau secara tidak langsung melalui
jembatan kalsium pada ion sulfat yang terdapat
pada permukaan hidroksi apatit. Sebaliknya,
-
19
BIMKGI Volume 2 No.1 | Juli- Desember 2013
kelompok basa yang bermuatan positif dapat
terikat langsung pada kelompok sulfat
permukaan mineral.15
Komposisi protein yang
terbanyak di kelenjar saliva parotis dan
submandibular terdiri dari asam
glutamat/glutamin dan tirosin. Selain itu, pada
kelenjar parotis juga terdapat histidin dan
arginin.16
Setelah terbentuknya acquired pellice
maka mulai tampak adanya koloni bakteri pada
permukaan gigi.13,14
Perlekatan bakteri terbentuk
melalui proses kimia (non spesifik) ataupun
proses interaksi fisiologis antar bagaian pada
permukaan sel bakteri sebagai adhesin dan
reseptor spesifik yang terdapat pada enamel
pelikel.17
Ikatan pada pelikel dapat dibagi menjadi
2 macam, yaitu :
a. Afinitas tinggi (spesifik) yang melibatkan
rantai sisi hidrat arang glikoprotein saliva
sebagai reseptor. Beberapa rantai sisi hidrat
arang glikoprotein saliva diketahui sebagai
reseptor terhadap mikroorganisme rongga
mulut tertentu, seperti asam sialat,
merupakan reseptor untuk S. sanguis,
galaktosa merupkan reseptor untuk
Actinomycoses viscosus dan lain-lain.
b. Afinitas rendah (non spesifik), dimana
tempat ikatan ini disebabkan adanya
interaksi hidrofobik yang tidak memerlukan
adnanya reseptor spesifik pada glikoprotein
saliva.15
Setelah proses awal kolonisasi, maka
selapis sel akan berproliferasi keseluruh
permukaan dan bergabung dengan bakteri di
dekatnya. Pada proses proliferasi bakteri akan
membutuhkan mekanisme retensi untuk
membentuk timbunan pada permukaan gigi yang
melekat antara satu dengan lainnya. Matriks dari
glikokaliks bakteri dan glikoprotein saliva akan
menahan bakteri pada permukaan gigi dengan
daya kohesi bakteri. Dengan demikian,
terbentuklah plak gigi, dimana akan terjadi
kolonisasi yang lebih lanjut dengan bakteri yang
akan membentuk lingkungan bakteri baru.17
2.3 Pasta gigi
Pengendalian plak adalah upaya
membuang dan mencegah penumpukan plak
pada permukaan gigi. Upaya tersebut dapat
dilakukan secara mekanis maupun kimiawi.
Pembuangan secara mekanis merupakan
metoda yang efektif dalam mengendalikan plak
dan inflamasi gingiva. Pembuangan mekanis
dapat meliputi penyikatan gigi dan penggunaan
benang gigi (dental floss).18
Bahan antiplak sering terdapat dalam
pasta gigi dan obat kumur. Setiap pasta gigi
mengandung bahan-bahan yang penting seperti
bahan abrasif, fluoride, air, bahan pemberi rasa,
bahan pemanis, pemadat, dan deterjen.
Tabel 2. Komposisi Pasta Gigi 1
Komposisi Bahan Persentase
(%)
Abrasif 20 40
Air 20 40
Pembasah 20 40
Deterjen/foaming agent 1 2
Pengikat >2
Pengharum >2
Pemanis >2
Pewarna & pengawet 5
Pasta gigi juga mengandung bahan aktif
yang dapat mencegah terjadinya penyakit gigi
dan mulut. Di bawah ini adalah tabel mengenai
kandungan bahan aktif yang biasa diaplikasikan
ke dalam pasta gigi:
-
20
BIMKGI Volume 2 No.1 | Juli- Desember 2013
Tabel 3. Kandungan dan Fungsi Bahan Aktif
dalam Pasta Gigi 19
Kandungan Bahan Fungsi
Potassium nitrat, sodium
sitrat, stronsium klorida
Mengurangi
hipersensitivitas
dentin
Pirofosfat, triklosan, zinc
citrate
Mengurangi plak
dan kalkulus
supragingiva
Triklosan, fluor Mengurangi
inflamasi gusi
Peroksida, sodium
tripolifosfat, sodium
heksaametafosfat
Mengurangi
pewarnaan pada
permukaan gigi
3. PEMBAHASAN
Enzim bromelin sebagai enzim proteolitik
yang dapat mengurai atau memecah molekul
protein komplek menjadi senyawa lebih
sederhana yaitu ikatan peptida dan asam
amino.20
Penambahan enzim bromelin dalam
pasta gigi berperan sebagai zat aktif antiplak.
Sifat proteolitik enzim bromelin mampu memecah
molekul protein komplek menjadi senyawa lebih
sederhana yaitu ikatan peptida dan asam amino
yang ada pada pelikel yang digunakan sebgai
media perlekatan bakteri.21
Plak merupakan awal dari timbulnya
karies gigi dan penyakit periodontal lainnya.
Pembentukan plak diawali dari adanya proses
kolonisasi mikroorganisme yang berinteraksi
dengan pelikel pada permukaan gigi. Pelikel
akan mengadsorpsi protein saliva secara selektif
bersama dengan ion-ion Ca2+
, F-, HPO4
2-,
sehingga dapat melekat kuat pada permukaan
gigi. Setelah adanya pelikel yang melapisi
permukaan gigi, maka mikroorganisme akan
melekat pada reseptor spesifik protein saliva dan
membentuk koloni.17
Enzim bromelin termasuk dalam
golongan enzim protease sulfihidril, yang artinya
memiliki residu sulfidril (sistenil dan histidil) pada
lokasi aktif.12
Susunan asam amino yang
mengandung gugus sistein pada sisi aktifnya.
Pemutusan atau pembentukan ikatan kimia
didahului dengan pembentukan ikatan dengan
substrat, seperti reaksi berikut.
E + S ES E + P
E adalah enzim, S merupakan substrat,
ES berupa kompleks enzim-substrat, dan P
adalah produk yang terbentuk.
Adanya ikatan sistein dengan asam
amino pelikel (arginin dan glutamin)
mengakibatkan terbentuknya asam amino lain
yang menyebabkan putusnya rantai media
perlekatan bakteri. Dengan demikian fungsi
penambahan zat aktif enzim bromelin pada pasta
gigi dapat mencegah terbentuknya plak.22
Begitu pentingnya pencegahan plak pada
permukaan gigi sehingga dalam kontrolnya
memadukan upaya secara mekanis maupun
kimiawi. Perubahan paradigma masyarakat
tentang peralihan penggunaan bahan sintetis ke
bahan alami atau herbal semakin menguat. Uji
biokompabilitas enzim bromelin terhadap
jaringan rongga mulut menunjukkan prosentase
jumlah sel hidup sel BHK-21 antara 95,22%-2-
16% dengan kosentrasi enzim bromelin 10%-
40%. Sel BHK-21 merupakan jenis sel fibroblas
penyusun jaringan ikat gingiva dan ligamen
periodontal.23
4. SIMPULAN
Berdasarkan kajian di atas, dapat
disimpulkan bahwa enzim bromelin pada bonggol
nanas berpotensi sebagai bahan antiplak pada
pasta gigi melalui mekanisme penguraian media
perlekatan bakteri pada permukaan gigi.
-
21
BIMKGI Volume 2 No.1 | Juli- Desember 2013
DAFTAR PUSTAKA
1. Harris, NO. dan Garcia-Godoy, F. 2004.
Primary Preventive Dentistry. New
Jersey: Pearson Education, Inc. h.123-
127.
2. Pujiastuti, Peni. 1997. Uji
Biokompatibilitas Ekstrak Bonggol Nanas
Sebagai Obat Kumur. Tesis.,
Pascasarjana, Universitas Airlangga.
Surabaya.
3. Caranza, FA. dan MG. 1990. Newman.
Clinical periodontology. Philadelpia: WB.
Sauders Co.
4. Lehner, T. 1995. Imunologi pada
Penyakit Mulut (Immunology of Oral
Diesease) Edisi 3. Jakarta: EGC.
5. Manson, J.D. dan B.M. Elley. 1993. Buku
Ajar Periodonti (diterjemahkan:
Anastasia) Ed. Ke-2, Jakarta: Hipokrates.
6. Sadoh, D. R., et al. Effect of Two
Toothcleaning Frequencies on
Periodontal Status in Patients with
Advance Periodontitis. Jurnal Of Clinical
Periodontology. 2004; 31: 470-474.
7. Freeman, B. A. 1985. Oral Microbiology,
dalam Textbook of Microbiology. Ed 22.
Philadelphia: WB Saunders Co. h. 711-
714.
8. Ruhadi, I. Efektifitas Pasta Gigi yang
Mengandung Bahan Bubuk Kayu Siwak
dalam Mengahambat Pembentukan Plak
Gigi. Maj. Ked. Gigi (Dent J). 2004;
37(1):24-27.
9. Dahan M, Timmermen MF, Van
Wilnkehoff AJ, Van der Velden U. The
effect of periodontal treatment on the
salivary bacterial load and early plaque
formation. J.Clin Periodontal. 2004;
31:972-977.
10. Prahasti, C. Pengaruh Penggunaan
Pasta Gigi Zinc Citrate/triclosan terhadap
Pembentukan Plak pada Gigi. Maj. Ked.
Gigi (Dent J). 2004; 37(4):154-156.
11. Reed, G. 1975. Enzymes in Food
Processing 2 nd. Ed. New York:
Academic Pres. h.146-148.
12. Tokkong, M.H. 1979. Proses Pelarutan
Protein Ikan Secara Enzymatis.
Bandung: Institut Teknologi Bandung.
13. Chairunnisa, H. 1987. Isolasi Enzim
Bromelin Kasar dari Bonggol Nanas
dalam Biproses dalam Industri Pangan.
Yogyakarta: PAU Pangan dan Gizi UGM
dan Liberty. h.319-325.
14. Newman, M. G., Takei, H. H.,
Klokkevold, P.R., Carranza, F. A. 2006.
Clinical Periodontology. Missouri:
Saunders Elsevier. h.137,140,732-733.
15. Amerogen, A.V.N. 1991. Ludah dan
Kelenjar Ludah bagi kesehatan gigi
(diterjemahkan Abyono R). Yogyakarta:
Gajah Mada University Press. h. 95-125.
16. Jensen, J.L., M.S. Lamkin and F.G
Openhaim. Adsorbtion of human salivary
protein to hidroksiapatit:a comprasion
Between Whole Saliva and Glandula
Salivary Secretion.. J Dent RES. 1992.
17. Sorensen, J.A. A rationale for
comparison of plaque reta