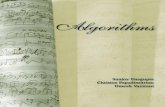cdk_141_asma
Transcript of cdk_141_asma


2003
http. www.kalbe.co.id/cdk
International Standard Serial Number: 0125 – 913X
1A
KDu
41. sma
Daftar isi : 2. Editorial 4. English Summary
Artikel
5. Patogenesis dan Patofisiologi Asma – Indah Rahmawati, Faisal Yunus, Wiwien Heru Wiyono
12. Peranan Infeksi Chlamydia pneumoniae dan Mycoplasma pneumo-niae terhadap Eksaserbasi Asma – Ira Melintira, Faisal Yunus, Wiwien Heru Wiyono
19. Pengaruh Infeksi Virus pada Perkembangan Asma – Adria Rusli, Faisal Yunus, Wiwien Heru Wiyono
Karya Sriwidodo WS23. Asma Akibat Kerja – Teguh H. Karjadi 27. Asma dan Polusi Udara – M. Yusuf Hanafiah Pohan, Faisal
Yunus, Wiwien Heru Wiyono a 30. Refluks Gastroesofagus pada Asma – Agus Dwi Susanto, Wiwien
eterangan Gambar Sampul: atura metel L. (kecubung) digunakan ntuk meredakan gejala antara lain asm
Heru Wiyono, Faisal Yunus 39. Imunoterapi pada Asma Alergi – Frans Abednego Barus, Wiwien
Heru Wiyono, Faisal Yunus 46. Peranan Magnesium pada Asma – Bambang Irawan Harsono,
Faisal Yunus, Wiwien Heru Wiyono 51. Carpal Tunnel Syndrome – Rudiansyah Harahap
54. Kapsul 55. Produk Baru 56. Kegiatan Ilmiah 59. Indeks Karangan Tahun 2003 60. RPPIK

Asma – istilah yang umum dipakai, bahkan awampun tidak asing
dengan perkataan ini; tetapi ternyata asma masih banyak mempunyai aspek yang belum sepenuhnya dipahami; mula-mula dianggap sebagai reaksi imunitas, tetapi akhir-akhir ini peranan infeksi juga mulai di-bicarakan, belum lagi mengenai pengaruh kualitas udara dan lingkungan hidup pada umumnya.
Kumpulan artikel yang sebagian besar berasal dari bagian Pulmono-logi dan Kedokteran Respirasi FKUI ini berusaha memberikan gambaran permasalahan asma dewasa ini, sekaligus juga membahas cara-cara penanggulangannya, baik melalui manipulasi lingkungan, pengobatan, pencegahan maupun faktor-faktor pencetusnya; tentu dengan harapan agar Sejawat dapat lebih memahami dan dengan demikian dapat me-nangani masalah asma dengan lebih baik.
Di akhir halaman, kami kembali mencantumkan daftar artikel yang diterbitkan oleh Cermin Dunia Kedokteran sepanjang tahun 2003.
Kami berharap dapat tetap bertemu di tahun mendatang dalam ke-adaan yang lebih baik dan sejahtera,
Redaksi
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 2

2003
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 3
REDAKSI KEHORMATAN
– Prof. DR. Sumarmo Poorwo Soedarmo
Staf Ahli Menteri Kesehatan, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
– Prof. Drg. Siti Wuryan A. Prayitno
SKM, MScD, PhD. Bagian Periodontologi, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, Jakarta
– Prof. Dr. R. Budhi Darmojo
Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang.
– Prof. DR. Hendro Kusnoto Drg.,Sp.Ort
Laboratorium Ortodonti Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti, Jakarta
– DR. Arini Setiawati Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta
DEWAN REDAKSI
KETUA PENGARAH Prof. Dr Oen L.H. MSc
PEMIMPIN UMUM Dr. Erik Tapan
KETUA PENYUNTING Dr. Budi Riyanto W.
PELAKSANA Sriwidodo WS.
TATA USAHA Dodi Sumarna
ALAMAT REDAKSI Majalah Cermin Dunia Kedokteran, Gedung Enseval, Jl. Letjen Suprapto Kav. 4, Cempaka Putih, Jakarta 10510, P.O. Box 3117 Jkt. Telp. (021)4208171 E-mail : [email protected] : http://www.kalbe.co.id/cdk NOMOR IJIN 151/SK/DITJEN PPG/STT/1976 Tanggal 3 Juli 1976
PENERBIT Grup PT Kalbe Farma
PENCETAK PT Temprint
– Dr. B. Setiawan Ph.D – Prof. Dr. Sjahbanar SoebiantoZahir MSc.
http://www.kalbe.co.id/cdk
PETUNJUK UNTUK PENULIS
Cermin Dunia Kedokteran menerima naskah yang membahas berbagai aspek kesehatan, kedokteran dan farmasi, juga hasil penelitian di bidang-bidang tersebut.
Naskah yang dikirimkan kepada Redaksi adalah naskah yang khusus untuk diterbitkan oleh Cermin Dunia Kedokteran; bila pernah dibahas atau dibacakan dalam suatu pertemuan ilmiah, hendaknya diberi keterangan me-ngenai nama, tempat dan saat berlangsungnya pertemuan tersebut.
Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris; bila menggunakan bahasa Indonesia, hendaknya mengikuti kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Istilah media sedapat mungkin menggunakan istilah bahasa Indonesia yang baku, atau diberi padanannya dalam bahasa Indonesia. Redaksi berhak mengubah susunan bahasa tanpa mengubah isinya. Setiap naskah harus disertai dengan abstrak dalam bahasa Indonesia. Untuk memudahkan para pembaca yang tidak berbahasa Indonesia lebih baik bila disertai juga dengan abstrak dalam bahasa Inggris. Bila tidak ada, Redaksi berhak membuat sendiri abstrak berbahasa Inggris untuk karangan tersebut.
Naskah diketik dengan spasi ganda di atas kertas putih berukuran kuarto/ folio, satu muka, dengan menyisakan cukup ruangan di kanan-kirinya, lebih disukai bila panjangnya kira-kira 6 - 10 halaman kuarto disertai/atau dalam bentuk disket program MS Word. Nama (para) pe-ngarang ditulis lengkap, disertai keterangan lembaga/fakultas/institut tempat bekerjanya. Tabel/ skema/grafik/ilustrasi yang melengkapi naskah dibuat sejelas-jelasnya dengan tinta hitam agar dapat langsung direproduksi, diberi nomor sesuai dengan
urutan pemunculannya dalam naskah dan disertai keterangan yang jelas. Bila terpisah dalam lembar lain, hendaknya ditandai untuk menghindari ke-mungkinan tertukar. Kepustakaan diberi nomor urut sesuai dengan pe-munculannya dalam naskah; disusun menurut ketentuan dalam Cummulated Index Medicus dan/atau Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (Ann Intern Med 1979; 90 : 95-9). Contoh: 1. Basmajian JV, Kirby RL. Medical Rehabilitation. 1st ed. Baltimore.
London: William and Wilkins, 1984; Hal 174-9. 2. Weinstein L, Swartz MN. Pathogenetic properties of invading micro-
organisms. Dalam: Sodeman WA Jr. Sodeman WA, eds. Pathologic phy-siology: Mechanisms of diseases. Philadelphia: WB Saunders, 1974;457-72.
3. Sri Oemijati. Masalah dalam pemberantasan filariasis di Indonesia. Cermin Dunia Kedokt. l990; 64: 7-10.
Bila pengarang enam orang atau kurang, sebutkan semua; bila tujuh atau lebih, sebutkan hanya tiga yang pertama dan tambahkan dkk.
Naskah dikirimkan ke alamat : Redaksi Cermin Dunia Kedokteran, Gedung Enseval, JI. Letjen Suprapto Kav. 4, Cempaka Putih, Jakarta 10510 P.O. Box 3117 Jakarta. Tlp. (021) 4208171. E-mail : [email protected]
Pengarang yang naskahnya telah disetujui untuk diterbitkan, akan diberitahu secara tertulis.
Naskah yang tidak dapat diterbitkan hanya dikembalikan bila disertai dengan amplop beralamat (pengarang) lengkap dengan perangko yang cukup.
International Standard Serial Number: 0125 – 913X
Tulisan dalam majalah ini merupakan pandangan/pendapat masing-masing penulisdan tidak selalu merupakan pandangan atau kebijakan instansi/lembaga/bagian tempat kerja si penulis.

English Summary
PATHOGENESIS AND PATHOPHYSIO-LOGY OF ASTHMA Indah Rahmawati, Faisal Yunus, Wiwien Heru Wiyono Department of Pulmonology and Respiratory Medicine, Faculty of Medicine, University of Indonesia/ Persahabatan Hospital, Jakarta, Indonesia
Asthma as manifestation of chronic inflammation of respiratory tract has complex mechanisms; one of the mechanism is inflam-matory process which is character-ized by increased eosinophyles, mast cells, macrophages and T lymphocytes in respiratory tract lining.
Other mechanism being con-sidered is the role of nervous system and certain neurotrans-mitters such as acetylcholine and epinephrine.
These mechanisms can irre-versibly change the structure of respiratory tract that can lead to obstruction of air passage shown in asthma patients, particularly during attacks.
Cermin Dunia Kedokt. 2003; 141: 5-11
brw
OCCUPATIONAL ASTHMA Teguh H. Karjadi Allergy – Immunology Subdivision, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, University of Indonesia/Cipto Mangunkusumo Ge-neral Hospital, Jakarta Indonesia
Occupational asthma is one
of the commonest occupational lung diseases. This condition can be triggered by irritation of agents in working environment through immunologic as well as pharma-cologic mechanisms.
Diagnosis is made if there is connection between asthma at-tack(s) and working environment, established through thorough anamnesis, physical examination and certain laboratory findings.
Cermin Dunia Kedokt. 2003; 141: 23-6
brw
GASTROOESOPHAGEAL REFLUX IN ASTHMA Agus Dwi Susanto, Wiwien Heru Wiyono, Faisal Yunus Department of Pulmonology and Respiratory Medicine, Faculty of Medicine, University of Indonesia/ Persahabatan Hospital, Jakarta, Indonesia
Gastrooesophageal reflux is considered one of the preci-pitating factors in asthma attack. The incidence among asthma patients is 34 – 89%. The occur-rence of reflux is influenced by factors such as autonomic (dys) regulation, intrathoracic and intra-abdominal pressure, hiatus hernia, function of diaphragm, and me-dication use.
The reflux can precipitate asthma attack through vagal reflex mechanism, bronchial hyperre-activity, microaspiration and neu-rogenic inflammation.
This condition can be de-tected through physical signs and esophageal pH monitoring; and be managed with antireflux medi-cation, and in certain condition with surgery.
Cermin Dunia Kedokt. 2003; 141: 30-8 brw
Redaksi Cermin Dunia Kedokteran Mengucapkan
Selamat Hari Raya : • Idul Fitri 1 Syawal 1424 H
• Natal 25 Desember 2003 dan Tahun Baru 2004
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 4

Artikel
TINJAUAN KEPUSTAKAAN
Patogenesis dan Patofisiologi Asma
Indah Rahmawati, Faisal Yunus, Wiwien Heru Wiyono
Bagian Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/ Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta
PENDAHULUAN
Pandangan tentang patogenesis asma telah mengalami perubahan pada beberapa dekade terakhir. Dahulu dikatakan bahwa asma terjadi karena degranulasi sel mast yang terinduksi bahan alergen, menyebabkan pelepasan beberapa mediator seperti histamin dan leukotrien sehingga terjadi kontraksi otot polos bronkus.1-3 Saat ini telah dibuktikan bahwa asma merupa-kan penyakit inflamasi kronik saluran napas yang melibatkan beberapa sel, menyebabkan pelepasan mediator yang dapat mengaktivasi sel target saluran napas sehingga terjadi bronko-konstriksi, kebocoran mikrovaskular, edema, hipersekresi mukus dan stimulasi refleks saraf.2-5
Asma merupakan gangguan inflamasi kronik saluran napas yang berhubungan dengan peningkatan kepekaan saluran napas sehingga memicu episode mengi berulang, sesak napas dan batuk terutama pada malam atau dini hari. Gejala ini ber-hubungan dengan luas inflamasi, menyebabkan obstruksi salur-an napas yang bervariasi derajatnya dan bersifat reversibel secara spontan maupun dengan pengobatan.3-8 Proses inflamasi pada asma khas ditandai dengan peningkatan eosinofil, sel mast, makrofag serta limfosit-T di lumen dan mukosa saluran napas. Proses ini dapat terjadi pada asma yang asimptomatik dan bertambah berat sesuai dengan berat klinis penyakit.2,4-6,9,10
INFLAMASI SALURAN NAPAS
Inflamasi saluran napas pada asma merupakan proses yang sangat kompleks, melibatkan faktor genetik, antigen, berbagai sel inflamasi, interaksi antar sel dan mediator yang membentuk proses inflamasi kronik dan remodelling.5,11-5
Mekanisme imunologi inflamasi saluran napas
Sistem imun dibagi menjadi dua yaitu imunitas humoral dan selular. Imunitas humoral ditandai oleh produksi dan sek-resi antibodi spesifik oleh sel limfosit B sedangkan selular di-perankan oleh sel limfosit T. Sel limfosit T mengontrol fungsi limfosit B dan meningkatkan proses inflamasi melalui aktivitas sitotoksik cluster differentiation 8 (CD8) dan mensekresi ber-bagai sitokin. Sel limfosit T helper (CD4) dibedakan menjadi
Th1 dan Th2. Sel Th1 mensekresi interleukin-2 (IL-2), IL-3, granulocytet monocyte colony stimulating factor (GMCSF), interferon-γ (IFN-γ) dan tumor necrosis factor-α (TNF-α) sedangkan Th2 mensekresi IL-3, IL-4, IL-5, IL-9, IL-13, IL-16 dan GMCSF.5,9,11,15,16 Respons imun dimulai dengan aktivasi sel T oleh antigen melalui sel dendrit yang merupakan sel pengenal antigen primer ( primary antigen presenting cells/ APC).5,11,15,17 (Gambar 1). Mekanisme limfosit T - IgE
Setelah APC mempresentasikan alergen / antigen kepada sel limfosit T dengan bantuan major histocompatibility (MHC) klas II, limfosit T akan membawa ciri antigen spesifik, ter-aktivasi kemudian berdiferensiasi dan berproliferasi. Limfosit T spesifik (Th2) dan produknya akan mempengaruhi dan me-ngontrol limfosit B dalam memproduksi imunoglobulin. Inter-aksi alergen pada limfosit B dengan limfosit T spesifik-alergen akan menyebabkan limfosit B memproduksi IgE spesifik aler-gen. Pajanan ulang oleh alergen yang sama akan meningkatkan produksi IgE spesifik. Imunoglobulin E spesifik akan berikatan dengan sel-sel yang mempunyai reseptor IgE seperti sel mast, basofil, eosinofil, makrofag dan platelet. Bila alergen berikatan dengan sel tersebut maka sel akan teraktivasi dan berdegranu-lasi mengeluarkan mediator yang berperan pada reaksi infla-masi.5,11,13-18
Mekanisme limfosit T – nonIgE
Setelah limfosit T teraktivasi akan mengeluarkan sitokin IL-3, IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 dan GMCSF. Sitokin bersama sel inflamasi yang lain akan saling berinteraksi sehingga terjadi proses inflamasi yang kompleks, degranulasi eosinofil, menge-luarkan berbagai protein toksik yang merusak epitel saluran napas dan merupakan salah satu penyebab hiperesponsivitas saluran napas (airway hyperresponsiveness / AHR).5,14,15
GAMBARAN HISTOPATOLOGI
Hasil pemeriksaan histopatologi penderita yang meninggal karena serangan asma menunjukkan gambaran inflamasi salur-
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 5

an napas. Lumen saluran napas tertutup oleh sumbatan mukus lengket yang terdiri atas protein plasma berasal dari pembuluh darah saluran napas dan glikoprotein mukus berasal dari sel epitel permukaan. Terjadi pelepasan sel epitel, penebalan lapis-an subepitel, penebalan lapisan otot polos karena hipertrofi dan hiperplasi sel goblet dan kelenjar mukus.4-6,12,18-21
an napas. Lumen saluran napas tertutup oleh sumbatan mukus lengket yang terdiri atas protein plasma berasal dari pembuluh darah saluran napas dan glikoprotein mukus berasal dari sel epitel permukaan. Terjadi pelepasan sel epitel, penebalan lapis-an subepitel, penebalan lapisan otot polos karena hipertrofi dan hiperplasi sel goblet dan kelenjar mukus.
Kurasan (lavage) bronkoalveolar penderita asma menun-
jukkan kenaikan jumlah limfosit, sel mast dan eosinofil serta aktivasi makrofag sedangkan biopsi bronkus menunjukkan infiltrasi eosinofil, pelepasan epitel dan fibrosis subepi-tel.4,6,19,20,22 Gambar 2 memperlihatkan gambaran saluran napas pada orang normal dan pada penderita asma yang me-nunjukkan penyempitan saluran napas. Gambar 3 menunjuk-kan gambaran mukosa normal dan pada penderita asma. Kurasan (lavage) bronkoalveolar penderita asma menun-
jukkan kenaikan jumlah limfosit, sel mast dan eosinofil serta aktivasi makrofag sedangkan biopsi bronkus menunjukkan infiltrasi eosinofil, pelepasan epitel dan fibrosis subepi-tel.
MHC kls II Limfosit T
IL-12+ IL-12- Th2
Keterangan : Keterangan : MHC = major histocompatibility Ig = imunoglobulin MHC = major histocompatibility Ig = imunoglobulin AHR = airway hiperresponsiveness eos= eosinofil, AHR = airway hiperresponsiveness eos= eosinofil, Bas = basofil Bas = basofil
Gambar 1. Mekanisme imunologi pada asma. Gambar 1. Mekanisme imunologi pada asma.
4-6,12,18-21
4,6,19,20,22 Gambar 2 memperlihatkan gambaran saluran napas pada orang normal dan pada penderita asma yang me-nunjukkan penyempitan saluran napas. Gambar 3 menunjuk-kan gambaran mukosa normal dan pada penderita asma.
Gambar 2. Gambaran saluran napas normal dan pada penderita asma.
Dikutip dari (20)
HI
berrandapdansen
nappernappooto
hipsep4, mepro
Sel dendrit Th1
IFN-γ, limfotoksin, IL-2
Imuniti seluler Inflamasi neurofilik
IL-13 IL-4 IL-9
IL-3 IL-5 GMCSF
IL-4 IL-3
IgE sel mast Bas Eos
Mediator inflamasi (histamin, prostaglandin, leukotrien, enzim)
AHR
GEJALA ASMA
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 6
Obstruksi saluran
Dikutip dari (5)Dikutip dari (5)PERESPONSIVITAS SALURAN NAPAS
Hiperesponsivitas saluran napas adalah respons bronkus lebihan yaitu berupa penyempitan bronkus akibat berbagai gsangan spesifik maupun nonspesifik. Respons inflamasi at secara langsung meningkatkan gejala asma seperti batuk rasa berat di dada karena sensitisasi dan aktivasi saraf sorik saluran napas.4,5,22,23 Hubungan antara AHR dengan proses inflamasi saluran
as melalui beberapa mekanisme; antara lain peningkatan meabilitas epitel saluran napas, penurunan diameter saluran as akibat edema mukosa sekresi kelenjar, kontraksi otot
los akibat pengaruh kontrol saraf otonom dan perubahan sel t polos saluran napas.5,11,22
Reaksi imunologi berperan penting dalam patofisiologi eresponsivitas saluran napas melalui pelepasan mediator erti histamin, prostaglandin (PG), leukotrien (LT), IL-3, IL-IL-5, IL-6 dan protease sel mast sedangkan eosinofil akan lepaskan platelet activating factor (PAF), major basic tein (MBP) dan eosinophyl chemotactic factor (ECF).11,19,22

(A)
(B) Gambar 3. Gambaran mukosa penderita asma (A) dan mukosa normal
(B). Dikutip dari (20)
SEL INFLAMASI
Banyak sel inflamasi terlibat dalam patogenesis asma mes-kipun peran tiap sel yang tepat belum pasti. Gambar 4 menun-jukkan berbagai macam sel dan mediator yang terlibat pada asma..1,4-6,8,11,17,22
Sel mast
Sel mast berasal dari sel progenitor di sumsum tulang.24,25 Sel mast banyak didapatkan pada saluran napas terutama di sekitar epitel bronkus, lumen saluran napas, dinding alveolus dan membran basalis.1,4,5,7,22,24,25 Sel mast melepaskan berbagai mediator seperti histamin, PGD2, LTC4, IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, GMCSF, IFN-γ dan TNF-α.17,24 Interaksi mediator dengan sel lain akan meningkatkan permeabilitas vaskular, bronkokonstriksi dan hipersekresi mukus.25
Sel mast juga melepaskan enzim triptase yang merusak vasoactive intestinal peptide (VIP) dan heparin. Heparin meru-pakan komponen penting granula yang berikatan dengan his-tamin dan diduga berperan dalam mekanisme antiinflamasi yang dapat menginaktifkan MBP yang dilepaskan eosinofil.1,22 Heparin menghambat respons segera terhadap alergen pada subyek alergi dan menurunkan AHR.8 Makrofag
Makrofag berasal dari sel monosit dan diaktivasi oleh aler-gen lewat reseptor IgE afinitas rendah.4,24 Makrofag ditemukan pada mukosa, submukosa dan alveoli yang diaktivasi oleh me-kanisme IgE-dependent sehingga berperan dalam proses infla-masi.1,4,6,8,24 Makrofag melepaskan berbagai mediator antara lain LTB4, PGF2 α, tromboksan A2, PAF, IL-1, IL-8, IL-10, GM-CSF, TNF α, reaksi komplemen dan radikal bebas. 1,5,6,8,24 Makrofag berperan penting sebagai pengatur proses inflamasi alergi. Makrofag juga berperan sebagai APC yang akan meng-hantarkan alergen pada limfosit T.4,22,24
Gambar 4. Gambaran sel dan mediator inflamasi.
Dikutip dari (22) Eosinofil
Diproduksi oleh sel progenitor dalam sumsum tulang dan diatur oleh IL-3, IL-5 dan GMCSF.17,24 Infiltrasi eosinofil me-rupakan gambaran khas saluran napas penderita asma dan membedakan asma dengan inflamasi saluran napas lain. 1,4,5,8,22,25 Inhalasi alergen akan menyebabkan peningkatan jumlah eosinofil dalam kurasan bronkoalveolar (broncho-alveolar lavage = BAL). Didapatkan hubungan langsung antara jumlah eosinofil darah tepi dan cairan BAL dengan AHR.1,4,5,11
SEL INFLAMASI Sel mast Makrofag Eosinofil Limfosit T Basofil Neutrofil Platelet SEL STRUKTURAL Sel epitel Sel otot polos Sel endotel Fibroblas Sel saraf
MEDIATOR Histamin Leukotrien Prostaglandin Tromboksan PAF Kinin Adenosin Endotelin Oksigen reaktif Sitokin Kemokin
EFEK Bronkokonstriksi Eksudasi plasma Hipersekresi mukus AHR Perubahan struktural
Eosinofil berkaitan dengan perkembangan AHR lewat pelepasan protein dasar dan oksigen radikal bebas.4 Eosinofil melepaskan mediator LTC4, PAF, radikal bebas oksigen, MBP, eosinophyl cationic protein (ECP) dan eosinophyl derived neurotoxin (EDN) sehingga terjadi kerusakan epitel saluran napas serta degranulasi basofil dan sel mast.1,5,7,8,11,17,22,24 Eosi-nofil yang teraktivasi menyebabkan kontraksi otot polos bron-kus, peningkatan permeabilitas mikrovaskular, hipersekresi mukus, pelepasan epitel dan merangsang AHR.5,6,8,11,17,22,24
Neutrofil
Peran neutrofil pada penderita asma belum jelas.1,5,6,10,22,24 Diduga neutrofil menyebabkan kerusakan epitel akibat pelepas-
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 7

an bahan-bahan metabolit oksigen, protease dan bahan ka-tionik. Neutrofil merupakan sumber beberapa mediator seperti PG, tromboksan, LTB4 dan PAF.1,22,24 Neutrofil dalam jumlah besar ditemukan pada saluran napas penderita asma kronik dan berat selama eksaserbasi atau setelah pajanan alergen.4-6,10 Biopsi bronkus dan BAL menunjukkan bahwa neutrofil me-rupakan sel pertama yang ditarik ke saluran napas dan yang pertama berkurang jumlahnya setelah reaksi lambat ber-henti.4,5,22,24
Limfosit T
Didapatkan peningkatan jumlah limfosit T pada saluran napas penderita asma yang dibuktikan dari cairan BAL dan mukosa bronkus.1,10,22,24 Biopsi bronkus penderita asma stabil mendapatkan limfosit intraepitelial atipik yang diduga merupa-kan limfosit teraktivasi.1,8 Limfosit T yang teraktivasi oleh alergen akan mengeluarkan berbagai sitokin yang mempeng-aruhi sel inflamasi. Sitokin seperti IL-3, IL-5 dan GM-CSF dapat mempengaruhi produksi dan maturasi sel eosinofil di sumsum tulang (sel prekursor), memperpanjang masa hidup eosinofil dari beberapa hari sampai minggu, kemotaktik dan aktivasi eosinofil.1,4,8,10,24
Basofil
Peran basofil pada patogenesis asma belum jelas, merupa-kan sel yang melepaskan histamin dan berperan dalam fase lambat. Didapatkan sedikit peningkatan basofil pada saluran napas penderita asma setelah pajanan alergen.4,6,22
Sel dendrit
Sel dendrit merupakan sel penghantar antigen yang paling berpengaruh dan memegang peranan penting pada respons awal asma terhadap alergen. Sel dendrit akan mengambil aler-gen, mengubah alergen menjadi peptida dan membawa ke lim-fonodi lokal yang akan menyebabkan produksi sel T spesifik alergen.4,6,8,22 Sel dendrit berasal dari sel progenitor di sumsum tulang dan sel di bawah epitel saluran napas. Sel dendrit akan bermigrasi ke jaringan limfe lokal di bawah pengaruh GMCSF.5,6
Sel struktural
Sel struktural saluran napas termasuk sel epitel, sel endo-tel, miofibroblas dan fibroblas merupakan sumber penting mediator inflamasi seperti sitokin dan mediator lipid pada respons inflamasi kronik.4,8,10 Pada penderita asma jumlah mio-fibroblas di bawah membran basal retikular akan meningkat. Terdapat hubungan antara jumlah miofibroblas dan ketebalan membran basal retikular.8 MEDIATOR INFLAMASI
Banyak mediator yang berperan pada asma dan mem-punyai pengaruh pada saluran napas. Mediator tersebut antara lain histamin, prostaglandin, PAF , leukotrien dan sitokin yang dapat menyebabkan kontraksi otot polos bronkus, peningkatan kebocoran mikrovaskular, peningkatan sekresi mukus dan pe-narikan sel inflamasi. Interaksi berbagai mediator akan mem-pengaruhi AHR karena tiap mediator memiliki beberapa peng-
aruh.1,2,4,10,22
Histamin
Histamin berasal dari sintesis histidin dalam aparatus Golgi di sel mast dan basofil.10,24 Histamin mempengaruhi saluran napas melalui tiga jenis reseptor. Rangsangan pada reseptor H-1 akan menyebabkan bronkokonstriksi, aktivasi refleks sensorik dan meningkatkan permeabilitas vaskular serta epitel. Rangsangan reseptor H-2 akan meningkatkan sekresi mukus glikoprotein. Rangsangan reseptor H-3 akan merang-sang saraf sensorik dan kolinergik serta menghambat reseptor yang menyebabkan sekresi histamin dari sel mast.1,2,10,22
Prostaglandin
Prostaglandin (PG)D2 dan PGF2 merupakan bronkokons-trikstor poten.10 Prostaglandin E2 menyebabkan bronkodilatasi pada subyek normal invivo, menyebabkan bronkokonstriksi lemah pada penderita asma dengan merangsang saraf aferen saluran napas.10,26 Prostaglandin menyebabkan kontraksi otot polos saluran napas dengan cara mengaktifkan reseptor trom-boksan-prostaglandin.1,2,22
Platelet activating factor (PAF)
Dibentuk melalui aktivasi fosfolipase A2 pada membran fosfolipid, dapat dihasilkan oleh makrofag, eosinofil dan neutrofil.10,22 Pada percobaan in vitro ternyata PAF tidak me-nyebabkan bronkokonstriksi otot polos saluran napas, jadi PAF tidak menyebabkan kontraksi otot polos saluran napas. Ke-mungkinan penyempitan saluran napas in vivo merupakan akibat sekunder edema saluran napas karena kebocoran mikro-vaskular yang disebabkan rangsangan PAF.1,10 Platelet activat-ing factor juga dapat merangsang akumulasi eosinofil, mening-katkan adesi eosinofil pada permukaan sel endotel, merangsang eosinofil agar melepaskan MBP dan meningkatkan ekspresi reseptor IgE terhadap eosinofil dan monosit.1,10,22
Leukotrien
Berasal dari jalur 5-lipooksigenase metabolisme asam ara-kidonat, berperan penting dalam bronkokonstriksi akibat aler-gen, latihan, udara dingin dan aspirin.2,22,27 Leukotrien dapat menyebabkan kontraksi otot polos melalui mekanisme nonhis-tamin dan terdiri atas LTA4, LTB4, LTC4, LTD4 dan LTE4. Leukotrien dapat menyebabkan edema jaringan, migrasi eosi-nofil, merangsang sekresi saluran napas, merangsang prolife-rasi dan perpindahan sel pada otot polos dan meningkatkan permeabilitas mikrovaskular saluran napas.1,3,22,25,28
Sitokin
Sitokin merupakan mediator peptida yang dilepaskan sel inflamasi, dapat menentukan bentuk dan lama respons infla-masi serta berperan utama dalam inflamasi kronik.1,2,4 Sitokin dihasilkan oleh limfosit T, makrofag, sel mast, basofil, sel epitel dan sel inflamasi.1,4,22,24,25 Sitokin IL-3 dapat memper-tahankan sel mast dan eosinofil pada saluran napas. Inter-leukin-5 dan GM-CSF berperan mengumpulkan sel eosinofil, Interleukin-4 dan IL-13 akan merangsang limfosit B mem-bentuk IgE.1,2,4,10,24,25
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 8

Endotelin Endotelin dilepaskan dari makrofag, sel endotel dan sel
epitel. Merupakan mediator peptida poten yang menyebabkan vasokonstriksi dan bronkokonstriksi. Endotelin-1 meningkat jumlahnya pada penderita asma. Endotelin juga menyebabkan proliferasi sel otot polos saluran napas, meningkatkan fenotip profibrotik dan berperan dalam inflamasi kronik asma.4,8,22,29,30
Nitric oxide (NO)
Berbentuk gas reaktif yang berasal dari L-arginin jaringan saraf dan nonsaraf, diproduksi oleh sel epitel dan makrofag me-lalui sintesis NO. Berperan sebagai vasodilator, neurotrans-miter dan mediator inflamasi saluran napas. Kadar NO pada udara yang dihembuskan penderita asma lebih tinggi diban-dingkan orang normal.4,5,8,22
Radikal bebas oksigen
Beberapa sel inflamasi menghasilkan radikal bebas seperti anion superoksida, hidrogen peroksidase (H2O2), radikal hidroksi (OH), anion hipohalida, oksigen tunggal dan lipid peroksida. Senyawa tersebut sering disebut senyawa oksigen reaktif.1,5,22 Pada binatang percobaan, hidrogen peroksida dapat menyebabkan kontraksi otot polos saluran napas. Superoksid berperan dalam proses inflamasi dan kerusakan epitel saluran napas penderita asma.1,5,22
Jumlah oksidan yang berlebihan pada saluran napas akan menyebabkan bronkokonstriksi, hipersekresi mukus dan ke-bocoran mikrovaskular serta peningkatan respons saluran napas. Radikal bebas oksigen dapat merusak DNA, menyebab-kan pembentukan peroksida lemak pada membran sel dan menyebabkan disfungsi reseptor β adrenergik saluran napas.1,22
Bradikinin
Berasal dari kininogen berat molekul tinggi pada plasma lewat pengaruh kalikrein dan kininogenase. Secara in vivo merupakan konstriktor kuat saluran napas dan secara in vitro merupakan konstriktor lemah.1,10,22 Pada penderita asma bradi-kinin merupakan aktivator saraf sensoris yang menyebabkan keluhan batuk dan sesak napas, menyebabkan eksudasi plasma, meningkatkan sekresi sel epitel dan kelenjar submukosa.1,22 Bradikinin dapat merangsang serat C sehingga terjadi hiper-sekresi mukus dan pelepasan takikinin.10,21
Neuropeptida
Neuropeptida seperti substan P (SP), neurokinin A dan calcitonin gene-related peptide (CGRP) terletak di saraf sen-sorik saluran napas. Neurokinin A menyebabkan bronkokons-triksi, substan P menyebabkan kebocoran mikrovaskular dan CGRP menyebabkan hiperemi kronik saluran napas.10
Adenosin
Merupakan faktor regulator lokal, menyebabkan bronko-konstriksi pada penderita asma. Secara in vitro merupakan bronkokonstriktor lemah dan berhubungan dengan pelepasan histamin dari sel mast.10
MEKANISME SARAF
Berbagai proses yang terjadi pada asma dapat disebabkan
melalui mekanisme saraf yaitu mekanisme kolinergik, adre-nergik dan nonadrenergik nonkolinergik. Kontrol saraf pada saluran napas sangat kompleks.1,5,22,23,31
Mekanisme kolinergik
Saraf kolinergik merupakan bronkokonstriktor saluran napas dominan pada binatang dan manusia. Peningkatan refleks bronkokonstriksi oleh kolinergik dapat melalui neurotransmiter atau stimulasi reseptor sensorik saluran napas oleh modulator inflamasi seperti prostaglandin, histamin dan bradikinin.1,22,23,31
Mekanisme adrenergik
Saraf adrenergik melakukan kontrol terhadap otot polos saluran napas secara tidak langsung yaitu melalui katekolamin/ epinefrin dalam tubuh. Mekanisme adrenergik meliputi saraf simpatis, katekolamin dalam darah, reseptor α adrenergik dan reseptor β adrenergik. Perangsangan pada reseptor α adrenergik menyebabkan bronkokonstriksi dan perangsangan reseptor β adrenergik akan menyebabkan bronkodilatasi.1,22,31
Mekanisme nonadrenergik nonkolinergik (NANC)
Terdiri atas inhibitory NANC (i-NANC) dan excitatory NANC (e-NANC) yang menyebabkan bronkodilatasi dan bron-kokonstriksi. Peran NANC pada asma belum jelas, diduga neuropeptida yang bersifat sebagai neurotransmiter seperti sub-stansi P dan neurokinin A menyebabkan peningkatan aktivitas saraf NANC sehingga terjadi bronkokonstriksi. Kemungkinan lain karena gangguan reseptor penghambat saraf NANC me-nyebabkan pemecahan bahan neurotransmiter yang disebut vasoactive intestinal peptide (VIP).1,6,22,23
PATOFISIOLOGI ASMA
Perubahan akibat inflamasi pada penderita asma merupa-kan dasar kelainan faal. Kelainan patologi yang terjadi adalah obstruksi saluran napas, hiperesponsivitas saluran napas, kon-traksi otot polos bronkus, hiperesekresi mukus, keterbatasan aliran udara yang ireversibel, eksaserbasi, asma malam dan analisis gas darah.5,7,9,23,32,33
Obstruksi saluran napas
Bersifat difus dan bervariasi derajatnya, dapat membaik spontan atau dengan pengobatan. Penyempitan saluran napas ini menyebabkan gejala batuk, rasa berat di dada, mengi dan hiperesponsivitas bronkus terhadap berbagai stimuli. Penyebab-nya multifaktor, yang utama adalah kontraksi otot polos bronkus yang diprovokasi oleh mediator yang dilepaskan sel inflamasi.5,23,32
Hiperesponsivitas saluran napas
Mekanisme pasti hiperesponsivitas saluran napas belum diketahui jelas, diduga karena perubahan sifat otot polos salur-an napas sekunder terhadap perubahan fenotip kontraktilitas. Inflamasi dinding saluran napas terutama di daerah peribron-kial dapat menambah penyempitan saluran napas selama kon-traksi otot polos. Hiperesponsivitas saluran napas dapat diukur dengan uji provokasi bronkus.5,23,32
Konstraksi otot polos bronkus
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 9

Pada penderita asma terjadi peningkatan pemendekan otot polos bronkus saat kontraksi isotonik. Perubahan fungsi kon-traksi mungkin disebabkan oleh perubahan aparatus kon-traksi.5,23
Hipersekresi mukus Terjadi hiperplasia kelenjar submukosa dan sel goblet pada
saluran napas penderita asma. Penyumbatan saluran napas oleh mukus hampir selalu didapatkan pada asma yang fatal.5,7,32 Hipersekresi mukus akan mengurangi gerakan silia, mempeng-aruhi lama inflamasi dan menyebabkan kerusakan struktur/ fungsi epitel.21
Keterbatasan aliran udara ireversibel
Penebalan dinding saluran napas adalah karakteristik re-modelling yang terdapat pada saluran napas besar maupun kecil. Gambaran ini terlihat secara patologi maupun radio-logi.2,5,8
Eksaserbasi
Episode eksaserbasi merupakan gambaran yang umum pada asma. Faktor penyebab eksaserbasi antara lain rangsangan penyebab bronkokonstriksi saja (inciter) seperti latihan, udara dingin, kabut / asap dan rangsangan penyebab inflamasi (in-ducer) seperti pajanan alergen, sensitisasi zat di tempat kerja, ozon dan infeksi saluran napas oleh virus.4,5,23
Asma malam
Biopsi transbronkus pada penderita asma malam menun-jukkan akumulasi eosinofil dan makrofag pada malam hari di alveolar dan jaringan peribronkus.2,5,23
Analisis gas darah
Asma menyebabkan gangguan pertukaran gas; derajat hi-poksemia berkorelasi dengan penyempitan saluran napas akibat ketidakseimbangan ventilasi perfusi.2,5,23
REMODELLING SALURAN NAPAS
Gambaran utama penderita asma adalah radang saluran napas; ditemukan pula kelainan saluran napas ireversibel seper-ti hipertrofi otot polos saluran napas, hiperplasia kelenjar mukosa, proliferasi pembuluh darah dan deposisi kelenjar pada membran subbasalis.2,5,8,11,13,17,20
Remodelling merupakan reaksi tubuh untuk memperbaiki jaringan yang rusak akibat inflamasi dan diduga menyebabkan perubahan ireversibel pada asma.5,11,13 Fibroblas berperan pen-ting dalam remodelling dan proses inflamasi. Fibroblas meng-hasilkan kolagen, serat elastik dan retikular, proteoglikans dan glikoproteindari matriks ekstraselular ( ECM ).2,5,34
KESIMPULAN 1. Asma merupakan penyakit inflamasi kronik saluran napas yang menyebabkan hambatan aliran udara dan peningkatan AHR. 2. Proses inflamasi pada asma khas ditandai dengan pening-katan eosinofil, sel mast, makrofag dan limfosit T di lumen dan mukosa saluran napas.
3. Kontrol saraf kolinergik, adrenergik dan nonadrenergik nonkolinergik ikut berperan dalam AHR. 4. Remodelling diduga merupakan penyebab obstruksi salur-an napas yang ireversibel pada penderita asma.
KEPUSTAKAAN 1. Supartini NI, Santoso DI, Kardjito T. Konsep baru patogenesis asma
bronkial. Paru 1995; 15: 156-61. 2. O’Byrne P. Pathogenesis. In: O’Byrompson NC. ed. Manual of asthma
management. 2nd ed. London: WB Saunders; 2001. p. 27-40. 3. Davies RJ, Wang J, Abdelaziz MM, Calderon MA, Khair O, Devalia JL,
et al. New insights into understanding of asthma. Chest 1997; 111: 2S-10S.
4. Barnes PJ, Drazen JM. Pathophysiology of asthma. In: Barnes PJ, Drazen JM, Rennard S, Thomson NC, eds. Asthma and COPD basic mechanisms and clinical management. 1st ed. London: Academic Press; 2002. p. 343-59.
5. National Institutes of Health. Definition. In: Global initiative for asthma. Bethesda: National Institutes of Health; 2002. p. 50-9.
6. Boushey HA, Corry DB, Fahy JV. Asthma. In: Murray JF, Nadel JA, Mason RJ, Boushey HA, eds. Textbook of respiratory medicine. 3rd ed. California: WB Saunders Co.; 2000. p. 1247-90.
7. Nadel JA, Busse WW. Asthma. Am J Respir Crit Care Med 1998; 157: S130-8.
8. Bousquet J, Jeffery PK, Busse WW, Johnson M, Vignola AM. Asthma from bronchoconstriction to airways inflammation and remodeling. Am J Respir Crit Care Med 2000; 161: 1720-45.
9. O’Donnell WJ, Drazen JM. Life-threatening asthma. In:Ayres SM, Grenvik A, Holbrook PR, Shoemaker WC, eds. Textbook of Critical Care. 3rd ed. London: WB Saunders Co; 1995. p. 750-5.
10. Hawrylowicz , Lee TH. Inflammatory mediators and cytokines in asthma. In: Clark TJH, Godfrey S, Lee TH, Thompson NC, eds. Asthma 4th ed. London: Arnold; 2000. p. 128-45.
11. Sundaru H. Respons imun pada asma bronkial. Dalam: Alwi F, Setiati S, Kasjmir YI, Bawazier LA, Syam AF, Mansjoer A, Suprahoita, eds. Naskah lengkap PIT IPD 2002. Jakarta: Pusat Informasi dan Penerbitan Bagian IPD FKUI; 2002. p. 1-6.
12. Vignola AM, Chanez P, Bonsignore G, Godard P, Bousquet J. Structural consequences of airway inflammation in asthma. J Allerg Clin Immunol 2000; 105: S514-7.
13. Baratawidjaja K. Patogenesis asma bronkial dan penatalaksanaannya. Dalam: Bahar A, Pitoyo CW, Mansjoer A, eds. Cardiovascular respira-tory immunology from pathogenesis to clinical application. Jakarta: Pusat Informasi dan Penerbitan Bagian IPD FKUI; 2003. p. 110-6.
14. Kaliner MA. Pathogenesis of asthma. In: Rich RR, Fleisher TA, Schwartz BD, Shearer WT, Strober W, eds. Clinical immunology principles and practice. Philadelphia: Mosby-Year Book Inc; 1996. p. 909-22.
15. Trowsdale J. Antigen presentation. In: Roitt I, Brostoff J, Male D, eds. Immunology. Edinburg: Mosby; 2001. p. 105-15.
16. Pearlman DS. Pathophysiology of the inflammatory response. J Allerg Clin Immunol 1999; 104: S132-7.
17. Busse WW , Lemanske RF. Asthma. N Engl J Med 2001; 344: 350-62. 18. Oettgen HC, Geha RS. IgE regulation and roles in asthma pathogenesis. J
Allerg Clin Immunol 2001; 107: 429-40. 19. Nayar R, Yeldandi AV. Pathology of acute asthma. In: Hall JB,
Corbridge TC, Rodrigo C, Rodrigo GJ, eds. Acute asthma assessment and management. 1st ed. Boston: McGraw-Hill; 2000. p. 49-55.
20. Jeffery PK. Pathology of asthma. In: Clark TJH, Godfrey S, Lee TH, Thompson NC, eds. Asthma. 4th ed. London: Arnold; 2000. p. 1265-76.
21. Donno MD, Bittesnich D, Chetta A, Olivieri D, Lopez-Vidriero MT. The effect of inflammation on mucociliary clearance in asthma. Chest 2000; 118: 1142-9.
22. Barnes PJ, Djukanovic, Holgate ST. Pathogenesis of asthma. In: Gibson GJ, Geddes DM, Costabel U, Sterk P, Corrin B, eds. Respiratory medi-cine, 3rd ed. London: Academic Press; 2003. p. 1212-52.
23. Sterk PJ, Roisin RR. Pathophysiology of asthma. In: Clark TJH, Godfrey S, Lee TH, Thompson NC, eds. Asthma. 4th ed. London: Arnold; 2000. p. 1278-92.
24. Busse WW, Parry DE. The biology of asthma. In: Fishman AP, Elias JA, Fishman JA, Grippi MA, Kaiser LR, Senior RM, eds. Fishman’s pulmo-
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 10

nary diseases and disorders. 3rd ed. New York: McGraw-Hill; 1998. p. 721-33.
25. Bingham CO, Austen FK. Mast-cell responses in the development of asthma. J Allerg Clin Immunol 2000; S527-34.
26. Hertert TV, Dworski RT, Mellen BG, Oates JA, Murray JJ, Sheller JR. Prostaglandin E2 decreases allergen-stimulated release of prostaglandin D2 in airways of subjects with asthma. Am J Respir Crit Care Med 2000; 162: 637-40
27. O’Byrne PM. Leukotrienes in the pathogenesis of asthma. Chest 1997; 111: 27S-34S.
28. O’Byrne PO. Asthma pathogenesis and allergen-induced late respons. J Allerg Clin Immunol 1998; 102: S85-9.
29. El-Gamal Y, Hossny E, Awwad K, Mabrouk R, Boseila N. Plasma endhotelin-1 immunoreactivity in asthmatic children. Ann Allerg Asthma Immunol 2002; 88: 370-3.
30. Borish L. Endhotelin-1: a useful marker for asthmatic inflammation ?.
Ann Allerg Asthma Immunol 2002; 88: 345-7. 31. Barnes PJ. Is asthma a nervous disease ?. Chest 1995; 107: 119S-23S. 32. Spahn J, Covar R, Stempel DA. Asthma: Addressing consistency in
results from basic science, clinical trials and observational experience. J Allerg Clin Immunol 2002; 109: S490-502.
33. Carroll NG, Mutavdzic S, James AL. Increased mast cells and neutrophils in submucosal mucous glands and mucus plugging in patients with asthma. Thorax 2002; 57: 677-82.
34. Djukanovic R. Asthma: a disease of inflammation and repair. J Allerg Clin Immunol 2000; 105: 522-6.
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 11

TINJAUAN KEPUSTAKAAN
Peranan Infeksi
Chlamydia pneumoniae dan Mycoplasma pneumoniae terhadap Eksaserbasi Asma
Ira Melintira, Faisal Yunus, Wiwien Heru Wiyono
Bagian Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/ Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta
PENDAHULUAN
Asma merupakan penyakit inflamasi kronik saluran napas dengan peningkatan insidens di seluruh dunia.1 Berbagai faktor berperan dalam terjadi asma termasuk infeksi saluran napas. Infeksi saluran napas mempunyai peran penting menimbulkan eksaserbasi asma pada anak dan dewasa.2,3 Eksaserbasi asma merupakan masalah yang sering dihadapi dalam penanganan asma. Penyebab tersering infeksi saluran napas adalah infeksi virus saluran napas biasanya rhinovirus, coronavirus atau influenza.4,5
Infeksi saluran napas karena bakteri atipik seperti Chlamy-dia pneumoniae (C. pneumoniae) dan Mycoplasma pneumo-niae (M. pneumoniae) merupakan penyebab eksaserbasi asma.3,4,6-8 Kedua mikroorganisme ini didapatkan dalam salur-an napas pasien asma yang stabil dan kronik.8 Allegra dkk.dikutip
dari 9 menemukan 11% kasus serokonversi infeksi kedua mikro-organisme ini dari 74 pasien asma dewasa yang mengalami eksaserbasi.
Penelitian lain pada anak dan dewasa muda menunjukkan bahwa infeksi dengan bakteri atipik ini berperan dalam eksaser-basi, menyebabkan infeksi yang persisten dan terlibat dalam patogenesis asma.1,2,3,8 Kedua mikroorganisme ini mempunyai struktur yang berbeda tetapi mempunyai kesamaan epide-miologis dan karakteristik klinis infeksi dan penyakit pada manusia.7
Diagnosis infeksi Chlamydia pneumoniae dan Myco-plasma pneumoniae sering berdasarkan temuan klinis saja se-dangkan diagnosis definitif infeksi dapat dikonfirmasikan me-lalui pemeriksaan serologis, biakan dan metode deteksi asam nukleat seperti polymerase chain reaction (PCR).10,11 Pemberi-an terapi antibiotik makrolid dari berbagai penelitian dapat memperbaiki eksaserbasi asma yang disebabkan infeksi kedua mikromikroorganisme ini. 8,10,12-14
ASMA DAN PATOGENESIS
Asma merupakan penyakit inflamasi kronik pada saluran
napas. Inflamasi kronik ini disebabkan oleh hiperesponsif saluran napas terhadap berbagai rangsangan dengan gejala ek-saserbasi yang berulang dan penyempitan saluran napas yang reversibel.4,15,16
Konsep terbaru patogenesis asma adalah proses inflamasi kronik pada dinding saluran napas yang menyebabkan penyem-pitan saluran napas dan hiperesponsif saluran napas. Gambar-an khas inflamasi ini adalah peningkatan sejumlah eosinofil teraktivasi, sel mast, makrofag dan limfosit T dalam lumen dan mukosa saluran napas. Sel limfosit berperan penting dalam respons inflamasi melalui pelepasan sitokin-sitokin multifung-sional.15,17 Limfosit T subset T helper-2 (Th-2) yang berperan dalam patogenesis asma akan mensekresi sitokin interleukin 3 (IL-3), IL-4, IL-5, IL-9, IL-13, IL-16 dan granulocyte-mono-cyte colony stimulating factor (GM-CSF). Hipertrofi dan hiper-plasi otot polos bronkus, sel goblet dan kelenjar bronkus serta hipersekresi kelenjar mukus menyebabkan penyempitan salur-an napas. Proses inflamasi saluran napas pada asma mendasari gangguan obstruksi saluran napas dengan gejala khas asma berupa batuk, rasa berat di dada, sesak dan mengi. Hiperes-ponsif saluran napas akan merangsang terjadi bronkokons-triksi.4,15,18
Faktor risiko terjadi asma yaitu faktor risiko pejamu (host) dan faktor risiko lingkungan. Salah satu faktor risiko lingkung-an yang berperan dalam eksaserbasi asma adalah infeksi salur-an napas (tabel 1).15
INFEKSI SALURAN NAPAS DAN EKSASERBASI ASMA
Eksaserbasi asma adalah episode peningkatan progresiviti secara cepat dengan pernapasan pendek, batuk, mengi, rasa berat di dada atau beberapa kombinasi dari gejala-gejala ini.15,18,19 Episode eksaserbasi merupakan masalah yang sering dalam penanganan eksaserbasi asma. Eksaserbasi yang dise-babkan oleh bakteri, walaupun cukup jelas tetapi insidens sulit ditentukan pasti karena biakan tidak selalu dilakukan dan virus
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 12

merupakan mikroorganisme lain penyebab penting eksaser-basi.8
Infeksi saluran napas mempunyai hubungan yang kom-pleks dengan asma. Infeksi pada awal kehidupan berhubungan dengan peningkatan risiko terbentuknya asma sedangkan infek-si yang terjadi pada tahap kehidupan selanjutnya dapat ber-hubungan dengan awitan (onset) eksaserbasi asma.20
Hubungan antara asma dan infeksi saluran napas merupa-kan hal penting ditinjau dari dua hal. Pertama yaitu infeksi saluran napas karena virus dan mikroorganisme seperti M. pneumoniae dan C. pneumoniae merupakan penyebab sering eksaserbasi asma. Kedua yaitu infeksi virus sinsitial saluran napas (respiratory syncytial virus= RSV), C. pneumoniae mungkin menyebabkan terjadi asma.6
Mekanisme patofisiologis yang berperan adalah kolonisasi bakteri, kerusakan bersihan mukosiliar, peningkatan sekresi mukus akibat hiperplasia sel goblet yang akhirnya menyebab-kan terjadi infeksi.2
Tabel 1. Faktor risiko potensial terbentuk asma FAKTOR PEJAMU (HOST) - Predisposisi genetik - Atopi - Hiperesponsif saluran napas - Jenis kelamin - Ras FAKTOR LINGKUNGAN Faktor yang mempengaruhi kerentanan terbentuk asma pada individu yang terpajan dengan faktor predisposisi • Alergen dalam rumah
- Tungau debu rumah - Alergen pada hewan - Alergen kecoa - Jamur
• Alergen luar - Tepung sari - Jamur
• Pajanan pekerjaan • Asap rokok
- Perokok pasif - Perokok aktif
• Polusi udara - Polutan luar rumah (outdoor pollutants) - Polutan dalam rumah (indoor pollutants)
• Infeksi saluran napas - Higiene
• Infeksi parasit • Status sosial ekonomi • Diet dan obat – obatan • Obesiti Faktor yang menyebabkan eksaserbasi asma dan atau menyebabkan gejala yang menetap. • Polutan dalam dan luar rumah • Polusi udara dalam dan luar rumah • Infeksi respirasi • Latihan dan hiperventilasi • Perubahan cuaca • Sulfur dioksida • Pengawet makanan • Asap rokok • Iritasi spray, parfum
Dikutip dari (15)
CHLAMYDIA PNEUMONIAE Karakteristik mikrobial
Genus Chlamydia terdiri atas tiga spesies yaitu Chlamydia pneumoniae (C. pneumoniae), Chlamydia psittaci dan Chlamydia trachomatis.13 Chlamydia pneumoniae merupakan bakteri gram negatif, obligat intraselular, bermultiplikasi dalam vakuol yang dibatasi membran dalam sel pejamu eukariotik tetapi tidak dapat membentuk energi sendiri yaitu adenosin trifosfat (ATP) sehingga tergantung dari deposit ATP sel pejamu.1,13,19,20-22
Chlamydia pneumoniae mempunyai siklus replikasi spesi-fik yang membedakan dengan mikroorganisme lainnya yaitu pembentukan badan inklusi intraselular.10,13,20 Selama siklus pembentukan terdapat dua bentuk C. pneumoniae yaitu badan elementer menyerupai spora infeksius (elementary body=EB) dengan diameter 0,3 µm dan badan retikulat replikatif nonin-feksius (reticulate body=RB).10,13,14
Epidemiologi
Dua isolasi klinis pertama C. pneumoniae diidentifikasi dari strain TW-183 yang diisolasi dari konjungtiva anak Taiwan tahun 1965 dan strain AR-39 yang diisolasi dari anak sekolah dengan faringitis tahun 1986.10 Gabungan dua strain isolasi ini secara resmi dikenal dengan nama C. pneumoniae strain taiwan acute respiratory tract (TWAR) tahun 1989 me-rupakan penyebab penting pneumonia.13,19
Chlamydia pneumoniae dapat menyebabkan infeksi salur-an napas atas seperti faringitis, otitis, sinusitis dan infeksi salur-an napas bawah seperti bronkitis akut, eksaserbasi bronkitis, asma dan pneumonia yang didapat dari masyarakat (commu-nity-acquired pneumoniae).23 Data klinis dan epidemiologis memperlihatkan peranan C. pneumoniae dalam peningkatan in-sidens asma. Gambaran khas Chlamydia adalah kecenderungan untuk menetap sehingga menyebabkan infeksi kronik berhu-bungan dengan berbagai penyakit kronik seperti penyakit paru obstruktif kronik dan asma.1
Penelitian seroepidemiologi menunjukkan bahwa infeksi C. pneumoniae telah tersebar luas dengan setengah dari po-pulasi dewasa muda menjadi seropositif.13 Survei epidemio-logis mengemukakan peningkatan prevalens antibodi terhadap infeksi C. pneumoniae dengan peningkatan umur yaitu dari 10% pada usia 5-10 tahun sampai mencapai 30-45% di usia dewasa muda dan sering meningkat sampai 80% pada usia tua.Dikutip dari 11
Penelitian lain mengemukakan bahwa 6-10% mikro-organisme ini dapat menyebabkan pneumonia yang didapat dari masyarakat dan dapat berhubungan dengan penyakit arteri koroner dan gejala mengi. Manusia merupakan reservoar C. pneumoniae dan penyebaran dari individu ke individu melalui droplet yang terinfeksi terutama dalam lingkungan tertutup seperti antar anggota keluarga, kelompok militer11,13,16 Gambaran klinis dan diagnosis
Penelitian terbaru memperlihatkan bahwa manifestasi klinis pneumonia yang disebabkan oleh patogen atipik tidak dapat dibedakan dengan mudah dari penyebab tipikal.11 Chlamydia pneumoniae sering menyebabkan infeksi tanpa
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 13

gejala (asimptomatik) atau infeksi ringan saluran napas atas.23 Pada keadaan infeksi berat dapat terjadi pneumonia, bronkitis, faringitis, sinusitis, eksaserbasi asma.13 Gejala infeksi saluran napas atas seperti sakit tenggorokan, serak dan rinitis dengan atau tanpa demam. Infeksi ringan dapat sembuh dengan spontan atau berlanjut ke infeksi saluran napas bawah seperti batuk kering yang persisten, rasa tidak nyaman di dada, nyeri dada.10 Infeksi primer dapat menyebabkan pneumonia ringan atau bronkitis yang lama pada dewasa muda, secara klinis sama dengan infeksi dengan M. pneumoniae.11,13
Pada pemeriksaan fisis paru didapatkan ronki dan mengi. Pemeriksaan laboratorium didapatkan peningkatan laju endap darah (LED), hitung leukosit, walaupun pada banyak kasus didapatkan normal. Gambaran klasik foto toraks pada infeksi bakteri atipik yaitu infiltrat unilateral, subsegmental dan inter-stisial tanpa konsolidasi merupakan gambaran foto toraks yang tidak banyak membantu secara diagnostik.13,14 Guckle dkk.dikutip
dari I menemukan infiltrat interstisial, konsolidasi yang unilateral atau bilateral.
Chlamydia pneumoniae biasanya didiagnosis secara sero-logis sedangkan isolasi sangat sulit.11 Pemeriksaan micro-immunofluorescence (MIF) terbukti merupakan pemeriksaan serologis terbaik untuk mendeteksi infeksi akut Chlamydia. Pemeriksaan ini dapat mendeteksi imunoglobulin M (IgM), IgG, IgA terhadap antigen Chlamydia.23 Kriteria diagnosis serologis infeksi Chlamydia yaitu pada infeksi akut didapatkan peningkatan empat kali titer IgG antara serum sampel yang diperoleh pada masa akut dan sembuh (convalescence) atau dari spesimen tunggal, titer IgM ≥ 1/16 atau titer IgG ≥ 1/512, dengan titer IgG sebelum dan setelah infeksi ≥ 1/16 dan <1/512.2,11,21,23 Infeksi kronik didefinisikan dengan titer IgM <1/16, IgG 1/16 sampai 1/256. Uji serologis antibodi IgA ter-hadap C. pneumoniae berguna juga untuk mendeteksi infeksi persisten pada asma karena waktu paruh (half life) IgA serum kurang dari satu minggu. Infeksi ulang (reinfeksi) C. pneumo-niae berkaitan dengan IgA spesifik C. pneumoniae.4,21,22 Cunningham dkk.dikutip dari 1 melaporkan IgA sekretori spesifik terhadap C. pneumoniae yang diperoleh dari aspirat nasal anak dengan minimal empat kali eksaserbasi asma lebih tinggi di-bandingkan dengan satu kali eksaserbasi. Titer IgA positif didefinisikan sebagai titer ≥ 1/16.4
Chlamydia dapat juga diisolasi dari apusan tenggorok, nasofaring, sputum dan cairan pleura pasien pneumonia, bron-kitis dan asma.16 Chlamydia dapat tumbuh lebih mudah dalam biakan pada sel yang berasal dari jaringan respirasi khususnya sel Hep-2 dan HL.10,18 Biakan dapat tumbuh dalam 4-7 hari. Chlamydia juga dapat diisolasi dalam biakan sel HeLa atau McCoy.14,22 Beberapa studi menggunakan pemeriksaan PCR untuk mendeteksi C. pneumoniae. Pemeriksaan ini lebih sen-sitif dibandingkan dengan biakan.10 MYCOPLASMA PNEUMONIAE Karakteristik mikrobial
Mycoplasma pneumoniae merupakan mikroorganisme pleomorfik, tidak mempunyai dinding sel yang kaku tetapi mempunyai tiga lapis membran.13,22 Bersifat gram negatif dan
dapat bereplikasi sendiri. Mycoplasma pneumoniae merupakan kuman patogen yang menginfeksi sel epitel silia saluran napas.24 Mikroorganisme ini sensitif terhadap tetrasiklin, eritro-misin dan tahan terhadap penisilin, sefalosporin serta van-komisin.22 Mycoplasma pneumoniae dapat tumbuh dalam pem-benihan tanpa sel dan pertumbuhan sangat lambat serta diham-bat oleh antibodi spesifik.10,13,22
Epidemiologi Mikroorganisme ini diidentifikasi pada sapi lebih dari 100
tahun yang lalu dan pertama kali diisolasi dari manusia tahun 1937.10 Infeksi ditransmisikan melalui droplet aerosol dari individu yang terinfeksi ke individu sehat.10,13,25 Infeksi M. pneumoniae cenderung menyebar cepat pada populasi tertutup seperti keluarga dan kelompok militer.13 Masa inkubasi 14-21 hari, dengan umur yang terkena infeksi ini berkisar 5-25 tahun. Infeksi terjadi secara epidemik setiap 3-4 tahun. Infeksi saluran napas bawah akibat mikroorganisme ini banyak terdapat pada anak usia 4-5 tahun dan meningkat pada usia dewasa muda.10
Patogenesis Mycoplasma pneumoniae merupakan mikroorganisme
ekstraselular tetapi dapat menyebabkan kerusakan silia dan sel mukosa. Inflamasi bronkial dapat terlihat pada kasus pneumo-nia yaitu infiltrasi selular interstisial dan alveol mononuklear. Mikroorganisme ini dapat bertahan dalam saluran napas selama beberapa minggu setelah infeksi walaupun setelah pemberian antibiotik. Antibodi spesifik dapat melawan infeksi tetapi in-feksi ulang dapat terjadi. Hal ini memperlihatkan sistem imun berperan dalam perjalanan penyakit.8,13
Gambaran klinis Gejala klinis yang terjadi adalah gejala umum infeksi
saluran napas. Gejala infeksi M. pneumoniae umumnya ter-dapat demam, malaise, pusing, sakit kepala, mialgia. Awitan gejala perlahan-lahan dengan manifestasi klinis lain mirip dengan infeksi oleh C. pneumoniae.3,13,22
Pada banyak kasus, diagnosis dugaan berdasarkan riwayat dan temuan klinis saja sedangkan pada kasus terseleksi diperlu-kan diagnosis definitif seperti infeksi berat dan pasien immuno-compromised.3 Isolasi M. pneumoniae dari berbagai spesimen klinis seperti apusan tenggorok, sputum, bronchoalveolar lavage, biopsi jaringan dalam media agar. Pemeriksaan aglu-tinin dingin (cold agglutinin) digunakan untuk mendiagnosis infeksi oleh mikroorganisme ini dengan titer antibodi serum aglutinin dingin 1/32 atau lebih tinggi. Pemeriksaan serologis dengan uji pengikatan komplemen (complement fixation) ada-lah uji akurat mendeteksi M. pneumoniae. Serum rangkap (paired sera) fase akut dan konvalesen dievaluasi selama 5-10 hari. Peningkatan titer antibodi empat kali atau lebih besar merupakan kriteria diagnostik.10
Pemeriksaan immunofluoresence dapat juga untuk mende-teksi antigen M. pneumoniae namun pemeriksaan ini tidak banyak membantu diagnostik. Polymerase chain reaction dapat mendeteksi sejumlah kecil deoxynucleact acid. Pemeriksaan ini lebih spesifik dan secara bermakna lebih sensitif dibandingkan biakan tetapi penggunaan untuk diagnostik memerlukan pe-nelitian lebih lanjut.10,26
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 14

HUBUNGAN CHLAMYDIA PNEUMONIAE DENGAN EKSASERBASI ASMA
Chlamydia pneumoniae dapat menjadi faktor pencetus asma bersama dengan RSV, parainfluenza dan M. pneumoniae karena kemampuan menyebabkan infeksi yang lama dan per-sisten selama beberapa bulan.4,20 Hubungan antara infeksi C. pneumoniae dan asma pertama kali dideskripsikan pada awal tahun 1990. Data klinis dan epidemiologi yang mendukung me-laporkan bahwa infeksi C. pneumoniae berperan dalam pening-katan insidens asma.1
Chlamydia pneumoniae dapat menyebabkan infeksi kronik, persisten dan asimptomatik. Infeksi persisten C. pneumoniae berperan dalam terbentuk penyakit kronik pada manusia termasuk aterosklerosis dan asma.27 Penelitian terbaru menunjukkan bukti serologis infeksi kronik C. pneumoniae lebih sering terjadi pada pasien asma.2,4 Penelitian pada popu-lasi memperlihatkan peningkatan seroprevalens C. pneumoniae yang dihubungkan dengan peningkatan prevalensi asma. Mekanisme yang memperlihatkan hubungan antara infeksi chlamydia dengan asma belum jelas, kemungkinan dihubung-kan dengan inflamasi kronik bronkus.19,28 Miyashita dkk. melaporkan bahwa C. pneumoniae berperan sebagai faktor pencetus eksaserbasi asma dewasa.4
Allegra dkk. melakukan penelitian hubungan infeksi akut C. pneumoniae terhadap eksaserbasi asma. Hasil penelitian memperlihatkan hubungan infeksi C. pneumoniae dengan eksa-serbasi asma.29,30 Hahn dkk.dikutip dari 20 pertama kali menunjuk-kan hubungan antara C. pneumoniae dan asma awitan dewasa dan mengi. Asma awitan dewasa ini dihubungkan dengan infeksi kronik C. pneumoniae. Mereka menemukan hubungan kuantitatif yang kuat antara titer antibodi infeksi C. pneumo-niae dengan mengi pada 365 pasien dengan penyakit saluran napas sebelumnya.dikutip dari 2
Hahn dkk.dikutip dari 2 mengevaluasi titer IgG dan IgM pada 163 pasien yang memperlihatkan episode akut mengi dan eksaserbasi asma kronik. Hasil penelitian 12 pasien didiagnosis mendapat infeksi C. pneumoniae berdasarkan pemeriksaan serologi.
Cunningham dkk.dikutip dari 30 menggunakan metode peme-riksaan PCR untuk melihat hubungan antara infeksi C. pneumoniae dengan eksaserbasi asma. Hasil penelitian didapat-kan C. pneumoniae dideteksi dari 24% anak yang mem-perlihatkan gejala eksaserbasi. HUBUNGAN CHLAMYDIA PNEUMONIAE, DERAJAT BERAT ASMA DAN PENGGUNAAN KORTIKOS-TEROID
Black dkk. menemukan peningkatan titer antibodi Chlamy-dia yang berkaitan dengan beratnya asma, termasuk fungsi paru dan nilai gejala. Studi kohort pada pasien asma didapatkan hubungan antara peningkatan titer antibodi C. pneumoniae dengan pasien asma derajat sedang-berat dan tidak didapatkan hubungan bermakna terhadap pasien asma derajat ringan.30
Penggunaan glukokortikoid dosis tinggi akan menyebab-kan peningkatan terhadap respons imun T helper-2 dan pene-kanan sistem imun T helper-1. Peningkatan titer antibodi C. pneumoniae dapat mempengaruhi derajat berat asma. Interaksi
C. pneumoniae, glukokortikoid dan sistem imun pejamu pada asma merupakan suatu siklus yang tidak berujung pangkal. Infeksi C. pneumoniae yang persisten dan berulang menyebab-kan inflamasi kronik, fibrosis dan pembentukan jaringan parut yang akan mempercepat progresiviti asma (gambar 1).20
Cook dkk.dikutip dari 1 menemukan peningkatan titer IgG dan IgA terhadap C. pneumoniae dan derajat berat asma. Penelitian ini juga mengungkapkan peningkatan titer IgG dan IgA ber-hubungan dengan penggunaan kortikosteroid dosis tinggi di-bandingkan dengan kortikosteroid dosis rendah. Peningkatan titer juga berkaitan dengan penurunan volume ekspirasi paksa detik pertama (forced expiratory volume).
Infeksi kronik C. pneumoniae yang mungkin berperan dalam beratnya asma. Hal ini disebabkan karena terdapat pe-ningkatan produksi sitokin-sitokin termasuk interleukin-1 (IL-1), tumour necrosis factor α (TNFα) dan interleukin-6 pada sel monosit yang terinfeksi dengan C. pneumoniae serta pening-katan regulasi dan aktivasi IL-1, sekresi regulated upon acti-vation in normal T cell expressed and secreted (RANTES), IL-16 dan GM-CSF yang akan mempengaruhi derajat berat asma.30
Penelitian kontrol terbaru pada 332 pasien asma terdapat bukti bahwa infeksi C. pneumoniae berperan dalam patogenesis asma.1 Infeksi C. pneumoniae mencetuskan respons imun lokal yang berkaitan dengan asma dengan produksi sitokin-sitokin proinflamasi yaitu TNF-α, IL-1β, IL-6, kemotaksis neutrofil dan menginhibisi apoptosis selular.20, 32 Infeksi mikroorganis-me ini tidak hanya menginfeksi epitel saluran napas dan sel mononuklear tetapi juga sel otot polos yang menghasilkan sejumlah besar sekresi IL-6 dan fibroblast growth factor. Data-data ini mendukung peranan C. pneumoniae terhadap pening-katan gejala dan derajat berat asma.20 Penelitian terbaru menun-jukkan bukti serologis infeksi kronik C. pneumoniae lebih sering terjadi pada pasien asma dan kemungkinan berperan dalam patogenesis asma.8
Gambar 1. Hubungan antara infeksi C. pneumoniae, kortikosteroid (glukokortikoid=GCs) dan sistem imun pejamu dengan asma.
Dikutip dari (20)
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 15

RESPONS IMUNOPATOLOGIS INFEKSI CHLAMYDIA PNEUMONIAE
Infeksi C. pneumoniae dapat mencetuskan respons imun humoral dan selular.20 C.pneumoniae merupakan parasit intra-selular, terutama menginfeksi sel epitel dan makrofag. Mikro-organisme ini bereplikasi dalam sel dengan menggunakan beberapa protein yang menyerupai protein pejamu sehingga mencegah pengenalan infeksi mikroorganisme ini dengan sistem imun pejamu.1,20,28 Secara umum pada kasus infeksi bakteri intraselular, sistem imun selular berperan secara ter-pisah dalam proses resolusi infeksi C. pneumoniae.20 Mikro-organisme ini diketahui menyebabkan infeksi persisten dan berulang disertai dengan kerusakan sistem imunopatologis pada target organ yang mengakibatkan respons imun terhadap pro-tein antigen Chlamydia.4,19,28 Infeksi persisten didefinisikan sebagai kontak lama Chlamydia dengan sel pejamu dan mikro-organisme ini tetap hidup tetapi biakan negatif.1
Infeksi kronik dan pajanan ulang C. pneumoniae dapat mencetuskan proses imunopatologis pada paru yang meliputi kerusakan epitel dan pelepasan mediator atau reaksi hiper-sensitivitas tipe lambat (delayed hypersensitivity) antigen protein C.pneumoniae yang menyebabkan inflamasi kronik saluran napas yang khas pada asma.4,17 Penelitian pada tikus secara genetik yang terinfeksi primer C. pneumoniae akan ter-jadi penurunan respons imun selular T helper 1 (Th-1) dan interferon-γ (IFN-γ) serta peningkatan respons imun T helper 2 (Th-2). Pada keadaan infeksi ulang (reinfeksi) terjadi pe-ngeluaran respons imun Th1 yang ditandai dengan peningkatan produksi IFN-γ.20
Pada infeksi Chlamydia akan dikeluarkan antigen protein a 57-60 kDa yang merupakan anggota heat shock protein 60 (hsp60) yang berasal dari kelompok stress protein. Protein diproduksi dalam jumlah sedikit, produksinya akan meningkat dalam jumlah besar saat terjadi infeksi seperti infeksi Chlamydia.20,28 Huittinen dkk.28 meneliti peranan hsp60 pada infeksi C. pneumoniae terhadap terjadi asma dan obstruksi pada bronkus. Hasil penelitian memperlihatkan terdapatnya antibodi IgA terhadap keberadaan hsp60 C. pneumoniae yang berkaitan dengan asma dan beratnya obstruksi bronkus. Mi-yashita dkk.28 menunjukkan tanda seroreaktiviti anti-hsp60 pada infeksi persisten C. pneumoniae yang akan menghasilkan gejala pulmoner. Pelepasan antigen hsp60 yang persisten dan berulang akan menyebabkan infeksi sel epitel mukosa atau makrofag alveolar akan menyebabkan stimulasi antigen yang lama sehingga terjadi inflamasi kronik dan pada akhirnya ber-peran terhadap kerusakan jaringan serta pembentukan jaringan parut pada paru penderita asma.1,19,20 PERANAN INFEKSI MYCOPLASMA PNEUMONIAE TERHADAP EKSASERBASI ASMA
Mycoplasma pneumoniae telah dilaporkan dapat menye-babkan eksaserbasi asma pada manusia tetapi peran mikro-organisme ini dalam patogenesis asma kronik tidak dapat di-terangkan dengan jelas.26 Kraft dkk. meneliti delapan pasien asma kronik yang stabil dengan 11 kelompok kontrol. Hasil penelitian didapatkan M. pneumoniae terdapat lebih besar pada saluran napas bawah pasien asma kronik yang stabil dibanding-
kan kelompok kontrol.2,8
Bowden dkk.2 melaporkan infeksi M. pneumoniae pada hewan dapat menyebabkan penyakit saluran napas dan gambar-an patologi yang mirip asma. Infeksi M. pneumoniae dapat menyebabkan mengi dan gejala-gejala respirasi saluran per-napasan bawah seperti meningkatnya batuk, mengi dan obs-truksi saluran napas bawah pada anak dengan asma.10,31 Pene-litian lain pada anak memperlihatkan bahwa infeksi M. pneumoniae dapat menginduksi gejala asma dan menyebabkan obstruksi bronkus. Penelitian ini menghasilkan kurang dari 5% eksaserbasi asma pada anak disebabkan oleh infeksi M. pneumoniae.31
Infeksi M. pneumoniae dapat menyebabkan peningkatan hiperesponsif saluran napas pada penelitian terhadap tikus jenis BALB/c (murine model).33 Bukti epidemiologis memperlihat-kan hubungan antara infeksi M. pneumoniae dengan hiperes-ponsif saluran napas pada individu bukan asma.26,33 Tidak ditemukan hubungan antara peningkatan titer IgG dan IgA dengan beratnya asma.1
PATOGENESIS INFEKSI MYCOPLASMA PNEUMO-NIAE TERHADAP EKSASERBASI ASMA
Hoek dkk. melaporkan bahwa M. pneumoniae dapat meng-infeksi sel epitel saluran napas dan mengaktivasi sel mast serta mencetuskan peningkatan produksi sitokin seperti IFN-γ, IL-1, IL-2, IL-4, IL-6 dan TNF-α yang berperan dalam eksaserbasi asma.32 Mycoplasma pneumoniae dapat menetap di dalam saluran napas selama beberapa bulan selama proses infeksi sehingga menyebabkan penurunan arus puncak ekspirasi dan peningkatan hiperesponsif saluran napas pada individu bukan asma.8,26
Pada murine model infeksi M. pneumoniae dapat terjadi hiperesponsif saluran napas yang terlihat pada hari ke- 3, 7 dan 14 setelah infeksi. Infiltrasi neutrofil terjadi pada hari ketiga, diikuti dengan pengurangan neutrofil dan peningkatan makro-fag pada hari ke-21. Interferon-γ dan T helper 1 disupresi pada hari ketiga dan ketujuh sehingga terlihat respons Th- 2 ter-hadap hiperesponsif saluran napas menyerupai asma.8,32
PENATALAKSANAAN
Penatalaksanaan eksaserbasi asma yang disebabkan oleh infeksi bakteri pada prinsipnya sama dengan penanganan eksa-serbasi dan pemberian antibiotik untuk mengatasi penyebab eksaserbasi.29 Prinsip penanganan eksaserbasi secara umum dapat dilihat pada algoritma berikut.15
Bukti penggunaan antibiotik dalam penanganan eksaser-basi asma masih sangat jarang.31 Antibiotik yang digunakan harus mempunyai aktiviti antibakteri yang mencapai fokus infeksi. Infeksi mungkin terbentuk dalam rongga interstisial jaringan atau dalam sel, sehingga kandungan fisikokimia obat diharapkan dapat terdistribusi dalam jaringan tubuh dan me-nembus ke dalam sel. Prinsip terapi antibiotik terbaik pada infeksi bakteri atipik seperti C. pneumoniae dan M. pneumo-niae adalah kombinasi obat dengan aktiviti tinggi dengan ke-mampuan mencapai konsentrasi intraselular yang tinggi.14
Obat-obat yang aktif secara potensial pada infeksi M. pneumoniae seperti tetrasiklin, makrolid, kloramfenikol dan
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 16

fluorokuinolon. Obat-obat seperti betalaktam, sulfonamid dan rifampisin tidak efektif untuk mengatasi infeksi oleh mikro-organisme ini.22
Gambar 2. Algoritma penatalaksanaan eksaserbasi asma
Dikutip dari (15)
Klindamisin, rifampisin, tetrasiklin, makrolid dan fluoro-kuinolon terakumulasi dalam sel fagosit. Makrolid menunjuk-kan kapasiti terbesar akumulasi intraseluler dalam sitosom dan lisosom.14 Pada sel neutrofil polimorfonuklear (PMN), makro-lid mempunyai perbandingan rasio konsentrasi selular dan
ekstraselular (C/E) bervariasi mulai dari 2-14 pada obat eritro-misin dan mencapai konsentrasi tertinggi untuk klaritromisin dan azitromisin. Azitromisin mempunyai waktu paruh sangat panjang sekitar 50 jam, konsentrasinya tinggi di jaringan dan intraselular khususnya PMN, makrofag alveolar dan fibroblas. Perbandingan C/E dalam makrofag sekitar 300 setelah 48 jam, tetapi nilainya mungkin meningkat lebih dari 1000 setelah 3-4 hari pemberian.14
Penggunaan makrolid telah dilaporkan dapat mengatasi asma kronik dan mengurangi responsif histamin terhadap bron-kus.31 Selain itu makrolid merupakan antimikrobial yang efek-tif untuk terapi infeksi C. pneumoniae dan M. pneumoniae.8 Konno dkk.dikutip dari 8 melaporkan bahwa makrolid dapat menu-runkan ekspresi TNFα, IL-3, IL-4, IL-5 pada murine model dan produksi mukus serta hiperesponsif bronkus. Pemberian azitro-misin dengan konsentrasi 1, 5 dan 10 µg/ml dapat menurunkan secara bermakna IL-1a dan TNFα pada 100% individu. 14
Makrolid efektif untuk terapi asma karena dapat memper-
lambat clearance metilprednisolon sehingga efek yang di-timbulkan menjadi lebih lama. Penggunaan makrolid seperti tro-leandomisin (TAO) dan klaritromisin dapat mengurangi penggunaan kortikosteroid pada pasien asma berat yang tergantung kortikosteroid.8,12 Troleandomisin dilaporkan dapat menghambat bersihan metilprednisolon.12 Garey dkk.dikutip dari 8 melaporkan tiga pasien asma berat tergantung kortikosteroid yang diterapi dengan klaritromisin 500 mg dua kali sehari, dua dari tiga pasien menghentikan pemberian prednison dan satu pasien dapat di tapering off dengan pemberian prednison 5 mg/hari.
Penilaian beratnya eksaserbasi • Arus puncak ekspirasi (APE) < 80%
dari nilai prediksi (selama 2 hari)/70% jika tidak respons terhadap bronkodilator
• Gambaran klinis : batuk , sesak napas, mengi, rasa berat di dada penggunaan
Hahn dkkdikutip dari 2 memberikan klaritromisin atau azitro-misin selama 6 hingga 16 minggu pada tiga pasien asma dewasa tidak terkontrol yang tergantung steroid dengan bukti serologis infeksi C. pneumoniae. Semuanya dapat menghenti-kan kortikosteroid oral dan tetap mendapatkan terapi asma. Hasil penelitian ini kurang bermakna karena sampel yang di-gunakan sangat kecil. Peneliti tersebut juga mengobati 46 pasien asma kronik yang stabil dengan doksisiklin, azitromisin atau eritromisin selama 3-9 bulan, setelah enam bulan terjadi resolusi sempurna pada empat pasien asma dengan infeksi C. pneumoniae.dikutip dari 30 Grayston dkk.21 menganjurkan pemberi-an tetrasiklin 2 gram per hari selama 7-10 hari atau 1 gram per hari selama 21 hari untuk infeksi C. pneumoniae. Yano dkkdikutip dari 8 mengobati pasien eksaserbasi asma disebabkan infeksi M. pneumoniae dengan eritromisin 1200 mg/hari sela-ma satu minggu didapatkan kesembuhan.
Terapi awal I h l i β i
Respons tidak sempurna
Episode sedang (APE 60-80% prediksi)
• Kortikosteroid oral
• Inhalasi antikolinergik β 2 i
Respons baik Episode ringan (APE 80%) respons terhadap β2 agonis diberi-kan selama 4 jam • β2 agonis tiap
3-4 jam (24-48
Respons buruk Episode berat (APE < 60% prediksi) • Kortikosteroid oral• Pengulangan β 2
agonis • Inhalasi
antikolinergik Makrolid dan tetrasiklin dilaporkan menunjukkan efek antiinflamasi yang tidak tergantung dari aktivitas antimikrobial tersebut.12 Klaritromisin dilaporkan merupakan makrolid yang mempunyai efek antiinflamasi sebaik efek antibiotik terhadap infeksi C. pneumoniae dan M. pneumoniae sehingga berperan dalam mengatasi asma kronik.8 Klaritromisin mempunyai efek antiasma sebaik efek antibiotik. Efek antiasma ini dihubungkan dengan penekanan infiltrasi eosinofil.21
Amasayu dkk.dikutip dari 8 memberikan klaritromisin 200 mg, dua kali sehari selama delapan minggu pada pasien asma derajat ringan sampai sedang, diperoleh perbaikan gejala klinis
dan penurunan eosinofil pada sputum. Pemberian jangka lama antibiotik ini dapat memperbaiki fungsi paru dan inflamasi saluran napas pada pasien asma walaupun aktiviti mekanisme farmakologis dan hubungan dengan patogenesis asma tidak diketahui. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa klaritro-misin ditoleransi baik dan efektif mengurangi hiperesponsif bronkus serta bronkokonstriksi yang diinduksi alergen.dikutip dari
21 Klaritromisin dan eritromisin dapat menghambat pelepasan endotelin-1 pada pasien asma kronik yang stabil. Endotelin-1 diketahui dapat menginduksi terjadinya bronkokonstriksi dan merangsang pengeluaran mukus serta menyebabkan edema mukosa.21 Hideaki dkk.dikutip dari 12 melakukan penelitian efek penekanan klaritromisin terhadap hiperesponsif saluran napas. Hasil penelitian memperlihatkan klaritromisin memperlihatkan efek antiinflamasi bronkus yang dihubungkan dengan penurun-an infiltrasi eosinofil. Klaritromisin berguna melawan infeksi C. pneumoniae dan M. pneumoniae dalam peranannya terhadap patogenesis asma.21 Pemberian terapi klaritromisin dapat me-nyebabkan penurunan bermakna IL-6 dan TNF-α pada 60-80%
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 17

individu. Pemberian azitromisin 1,5 gram selama lima hari hanya 70-83% mampu menyingkirkan C. pneumoniae dari pasien dengan biakan sekret nasofaring yang positif mikro-organisme tersebut.23 KESIMPULAN 1. Infeksi yang disebabkan oleh Chlamydia pneumoniae dan Mycoplasma pneumoniae dari berbagai penelitian dapat me-nyebabkan eksaserbasi asma. 2. Kedua mikroorganisme ini dapat menyebabkan infeksi yang kronik dan persisten 3. Diagnosis infeksi kedua mikroorganisme ini dengan pe-meriksaan serologi karena biakan kuman sulit dilakukan. 4. Makrolid merupakan antibiotik yang mempunyai sifat anti-mikrobial dan antiinflamasi mempunyai peranan penting dalam mengatasi eksaserbasi asma yang disebabkan oleh kedua mikroorganisme ini.
KEPUSTAKAAN 1. Gencay M, Rudiger JJ, Tamm M, Soler M, Perruchoud AP, Roth M.
Increased frequency of Chlamydia pneumoniae antibodies in patients with asthma. Am J Respir Crit Care Med 2001; 163: 1097-100.
2. Kraft M. Pathobiology of asthma: implications for treatment-the role of bacterial infections in asthma. Clin Chest Med 2000; 21: 1231-4.
3. Sharma S, Anthonisen N. Antibiotics. In: Barnes PJ, Drazen JM, Rennard S, Thomson NC, editors. Asthma and COPD basic mechanism and clinical management. London: Academic Press; 2002. p.573-83.
4. Miyashita N, Kubota Y, Nakajima M, Niki Y, Kawane H, MathsushimaT. Chlamydia pneumoniae and exacerbations of asthma in adults. Ann. Allergy Asthma Immunol 1998; 80: 405-9.
5. Liebermen D, Printz S, Ben-Yaakov M, Lazarovich Z, Ohana B, Friedman MG, et al. Atypical pathogen infection in adults with acute exacerbation of bronchial asthma. Am J Respir Crit Care Med 2003; 167: 446-50.
6. Issac D, Joshi P. Pathogenesis respiratory infections and asthma. Med J Austr 2002; 177(Supp 6): S50-1.
7. Cook PJ. Antimicrobial therapy for Chlamydia pneumoniae: its potential role in atherosclerosis and asthma. J Antimicrob Chemoter 1999; 44: 145-8.
8. Kraft M, Cassel GH, Pak J, MartinRJ. Mycoplasma pneumoniae and Chlamydia pneumoniae in asthma. Effect of clarithromycin. Chest 2002; 121: 1782-8.
9. Joanne JL. Asthma. In: Thurlbeck WM, Wright JL, editors. Thurlbeck’s chronic airflow obstruction. 2nd edition. London: B.C. Decker Inc; 1999. p.255-83.
10. Nelson CT. Mycoplasma pneumoniae and Chlamydia pneumoniae in pediatrics. Semin Respir Infect 2002; 17:10-4.
11. Hammerschlag MR. Chlamydia pneumoniae and the lung. Eur Respir J 2000; 16: 1001-7.
12. Spahn JD, Fost DA, Covar R, Martin RJ, Brown EE, Szefler SJ, et al. Clarithromycin potentiates glucocorticoid responsiveness in patients with asthma: result of a pilot study. Ann Allergy Asthma Immunol 2001; 87: 501-5.
13. Geddes GJ. Pneumonia and other acute respiratory infections. In: Gibson
GJ, Geddes DM, Costabel U, Sterk PJ, Corrin B, editors. Respiratory medicine. 3rd edition. London: WB Saunders: 2003. p.862-97.
14. Allegra L, Blasi F. Problems and perspectives in the treatment of respiratory infections caused by atypical pathogens. Pulmonar Pharmacol & Ther 2001; 14: 265-70.
15. National Institutes of Health. Risk Factors. In: Global Initiative for Asthma. Bethesda: National Institutes of Health; 2002. p.28-37.
16. Brinke AT, Van Dissel JT, Sterk PJ, Zwinderman AH, Rabe KF, Bel EH. Asthma, rhinitis, other respiratory diseases. J Allergy Clin Immunol 2001; 107: 449-54.
17. Hahn DL, Dodge RW, Golubjatnikov R. Associations of Chlamydia pneumoniae (strain TWAR) infection with wheezing, asthmatic bron-chitis, and adult onset asthma. JAMA 1991; 266: 225-30.
18. Lemanske RF, Busse WW. Asthma. J Allergy Clin Immunol 2003; 111: S502-19.
19. Hahn DL, Peeling RW, Dillon E, MCDonald R, Saikku P. Serologic markers for Chlamydia pneumoniae in asthma. Ann Allergy Asthma Immunol 2000; 84: 227-33.
20. Hertzen LC. Role of persistent infection in control and severity of asthma: focus on Chlamydia pneumoniae. Eur Respir J 2002; 19: 546-56.
21. Amayasu H, Yoshida S, Ebana S, Yamamoto Y, Nishikawa T, Shoji T, et al. Clarithromycin suppresses bronchial hyperresponsiveness associated with eosinophilic inflammation in patients with asthma. Ann Allergy Asthma Immunol 2000; 84: 594-8.
22. Josodiwondo S. Mycoplasma. Dalam: Chatim A, Sjahrurachman A, Soebandrio A, Karuniawati A, Santoso AU, Sudarmono P, editors. Buku ajar mikrobiologi kedokteran. Jakarta: Binarupa Aksara; 1993. p.242-4.
23. Hammerschlag MR. Minireview antimicrobial susceptibility and therapy of infections caused by Chlamydia pneumoniae. Antimicrob Agents Chemother 1994; 9: 1873-8.
24. Hoek KL, Cassel GH Duffy L, Atkinson TP. Mycoplasma pneumoniae-induced activation and cytokin production in rodent mast cells. J Allergy Clin Immunol 2002; 109: 470-6.
25. Phinogold SM, Goetz MB. Pyogenic bacterial pneumoniae, lung abscess, and empyema. In: Murray JF, Nadel JA, Mason RJ, Baushey HA, editors. Textbook of respiratory medicine. 3rd edition. Philladelpia: WB Saunders Company; 2002. p.986-1033.
26. Kraft M, Cassel GH, Henson JE, Watson H, Williamson J, Marmion BP, et al. Detection of Mycoplasma pneumoniae in the airways of adults with chronic asthma. Am J Respir Crit Care Med 1998; 158: 998-1000.
27. Kutlin A, Roblin PM, Hammerschlag MR. Effect of prolonged treatment with azithromycin, clarithromycin, or levofloxacin on Chlamydia pneumoniae in continuous-infection model. Antimicrob Agents Che-mother 2002; 46: 409-12.
28. Huittinen T, Hahn D, Antilla T, Walstrom E, Seiku P, Leinonen M. Host immune response to Chlamydia pneumoniae heat shock protein 60 is associated with asthma. Eur Respir J 2001; 17: 1078-82.
29. Allegra L, Blasi F, Centanni S, Cossentini R, Denti F, Raccanelli R, et al. Acute exacerbations of asthma in adults: role of Chlamydia pneumoniae infection. Eur Respir J 1994; 7: 2165-8.
30. Black PN, Scicchitotano R, Jenkins CR, Blasi F, Allegra L, Wlodarczyk J, et al. Serological evidence of infection with Chlamydia pneumoniae is related to severity of asthma. Eur Respir J 2000; 15: 254-9.
31. Lemanske RF, Lemen RJ, Gem JE. Infections in childhood. In : Barnes PJ, Left AR, Grunstein MM, Woolcock AJ, editors. Asthma. Philladelpia: Lippincott-Raven; 1997. p.1207-15.
32. Kroegel C. Chlamydia pneumoniae, clarithromycin, and severe asthma. Chest 2001; 120: 1035-6.
33. Martin RJ, Chu HW, Honour JM, Harbeck RJ. Airway inflammation and bronchial hiperresponsiveness. Am J Respir Cell Mol Biol 2001; 24: 577-82.
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 18

TINJAUAN KEPUSTAKAAN
Pengaruh Infeksi Virus
pada Perkembangan Asma
Adria Rusli, Faisal Yunus, Wiwien Heru Wiyono
Bagian Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/ Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta
PENDAHULUAN
Setelah ditemukannya teknik biologi molekular seperti pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR), hibridisasi in situ, reverse transcriptase (RT)-PCR dan PCR in situ, banyak penelitian yang melaporkan virus sebagai penyebab serangan asma. Infeksi virus dapat bersifat lokal pada saluran napas seperti Respiratory syncytial virus (RSV) atau bagian dari infeksi sistemik seperti campak atau cacar air. Infeksi virus dapat menyebabkan kelainan yang bervariasi seperti common cold, faringitis, trakeobronkitis, bronkitis atau pneumonia. Ke-lainan tersebut akhirnya dapat menyebabkan kelainan saluran napas yang bersifat kronik. Asma merupakan kelainan saluran napas kronik.1
Menurut National Heart, Lung, and Blood Institute tahun 1995, asma adalah gangguan inflamasi kronik saluran napas yang melibatkan berbagai sel inflamasi terutama sel mast, eosinofil, dan limfosit T. Pada individu yang rentan inflamasi ini menyebabkan episode berulang mengi, sesak napas, rasa berat di dada dan batuk pada malam atau pagi hari. Gejala tersebut biasanya dihubungkan dengan penyempitan saluran napas yang difus dengan derajat yang bervariasi dan dapat membaik seluruhnya atau sebagian secara spontan atau dengan pengobatan. Inflamasi menyebabkan peningkatan kepekaan (hipereaktiviti) saluran napas terhadap berbagai macam rang-sangan.2
Pada tinjauan pustaka ini akan dibahas mengenai epi-demiologi, patogenesis, respons imun selular infeksi virus dan hubungan mengi pada anak dengan asma. EPIDEMIOLOGI
Asma pada anak masih menjadi masalah kesehatan karena memerlukan biaya yang tinggi, ketidakhadiran di sekolah dan kunjungan ke rumah sakit yang masih tinggi.3,4 Kekerapan anak yang menderita asma di Inggris sekitar 20–33%.1 Infeksi virus pada saluran napas merupakan penyebab utama terjadinya mengi pada anak dan dewasa yang menderita asma yaitu 10-
85% pada anak dan 10-45% pada dewasa.3 Virus yang me-nyebabkan infeksi pada saluran napas adalah Respiratory syncytial virus (RSV), rhinovirus, parainfluensa, adenovirus, influensa, dan coronavirus1,5 seperti tampak pada tabel 1.
Tabel 1. Virus saluran napas dan penyakit yang diakibatkan Tipe Virus Serotipe cc Asma Pneumonia Bronkitis Bronkiolitis
rhinovirus 1-100 + +++ +++ + / - + + coronavirus 229E OC43 ++ ++ influensa A, B, C + + ++ + parainfluensa 1,2,3,4 + + +/- ++ + RSV A, B + + + + +++ adenovirus 1-43 + + ++ + + Keterangan : cc : common cold +/- : jarang + : diketahui ++ : sering +++ : penyebab utama
Dikutip dari (1)
Respiratory syncytial virus merupakan penyebab utama terjadinya mengi pada anak,6-12 sedangkan rhinovirus sebagai penyebab serangan asma akut.13-16 McIntosh melaporkan 32 anak usia 1-5 tahun yang menderita asma, dari 139 episode serangan asma ditemukan 58 episode (42%) disebabkan oleh RSV.3 Respiratory syncytial virus terdiri atas 2 subtipe yaitu tipe A dan B, namun tidak ada perbedaan antara keduanya dalam hal peningkatan insidens mengi atau bronkiolitis.1 Kira-kira 60-70% gejala mengi akan menghilang sejalan dengan bertambahnya usia dan hanya 30% yang akan berkembang menjadi asma, biasanya pada anak yang sebelumnya sudah mempunyai faktor atopi.3
Atopi dapat dijumpai pada anak yang terinfeksi campak atau tidak terinfeksi tuberkulosis (tb). Shaheen tahun 1994 melaporkan sepertiga dari jumlah anak yang menderita campak di Guinea-Bissau Afrika Barat mempunyai sensitisasi terhadap alergen lebih besar dibandingkan dengan anak yang mendapat vaksin campak. Hubungan tidak terinifeksi tb dengan atopi dilaporkan Shirakawa, 867 anak sekolah mendapat imunisasi
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 19

BCG pada saat lahir, 6 dan 12 tahun; pada anak dengan respons tuberkulin kuat mempunyai serum IgE dan sitokin Th2 rendah sedangkan sitokin Th1 meningkatdikutip dari 8(gambar 1). Healthy infant
20
RSV PIV Wheezing illness Resolution Child or adult with asthma Rhino Exaceration of Gambar 1. Hubungan infeksi Keterangan : RSV : respiratory synsytial viruPIV : parainfuenza virus TB : tuberkulosis
PATOGENESIS
Sebagian besar anak2 tahun dan dapat menye1. Terjadi respinflamasi pada individu t2. Anatomi sasehingga hasil reaksi infl3. Biasanya teakan me-ningkatkan sensrespons anti-virus sehing
Virus masuk ke sabereplikasi dalam 24 jamsaluran napas menyebabksel epitel dan fagosit srespons imun nonspesifikakan merangsang sistem nuclear factor kappa B mengeluarkan sitokin prophage colony stimulating6), IL-8, regulated on acsecreted (RANTES), dakeluarkan tumour necrosferon-α (IFN-α) yang mmasi.6-8 Pada respon imuvirus akan dihasilkan IFyang akan meregulasi selinflamasi,7,8 seperti tampa
Pada bayi baru lahirterutama ibunya, didapadibandingkan dengan buberhubungan dengan krokelainan kromosom 5q dMarsh (1994) yang men
IgE tinggi ditemukan kelainan kromosom 5q. Hal ini dibantah oleh Kamitani (1997) yang mengatakan tidak ada hubungan antara kromosom 5q dengan asma atau atopi. Folster (1998) melaporkan hubungan antara kelainan kromoson 11q pada orang dengan riwayat atopi dan serum IgE yang tinggi, hal yang sama dilaporkan juga oleh Shirakawa (1994).17
Atopy
Cermin Dunia Kedok
Early childhood
infections
virus
asthma
virus, mengi dan asma
s
Dikutip dari (8)
terinfeksi RSV pada usia kurang dari babkan mengi karena7 :ons imun yang menyebabkan ertentu. luran napas diameternya lebih kecil amasi akan menyumbat. rjadi penurunan sistem imun yang itisasi alergen dan tidak aktifnya ga infeksi semakin berat. luran napas melalui mukosilier dan pertama. Masuknya virus ke epitel
an respons imun nonspesifik dini dari erta respons imun dari sel T. Pada dini, setelah masuk ke sel epitel virus proteolisis kappa B dan mengaktifkan (NF kappa B) yang selanjutnya akan inflamasi seperti granulocyte- macro- factor (GM-CSF), interleukin-6 (IL-tivation normal T-cell expressed and
n IL-11.5,6,8 Dari makrofag akan di-is factor-α (TNF-α), IL-8, dan inter-empunyai efek antivirus dan proinfla-n seluler sel T yang teraktifasi oleh
N-γ, GM-CSF, IL-4, IL-5, dan IL-10 efektor dan eosinofil sehingga terjadi k pada gambar 2. dari orang tua dengan riwayat atopi tkan IL-4 dan IL-5 yang meningkat kan atopi. Pada manusia faktor atopi mosom 5q31- q33 dan 11q. Hubungan an atopi pertama kali dilaporkan oleh dapatkan pada orang dengan serum
Gambar 2. Respons inflamasi infeksi virus pada saluran napas Epi= epitel, IFN-γ= interferon, Mac= makrofag, IL-5= interleukin-5 TNF-α = tumour necrosis factor-α, GM-CSF= granulocyte macrophage colony stimulat-ing factor, RANTES= regulated on activation normal T-cell expressed and secreted .
Dikutip dari (8) RESPONS IMUN SELULAR Makrofag
Makrofag dapat ditemukan di mukosa, submukosa saluran napas dan alveoli. Makrofag di alveoli (makrofag alveolar) me-rupakan sel terbanyak yang ditemukan pada pemeriksaan kurasan bronkoalveolar yaitu kira-kira 90%.8 Fungsi makrofag memfagosit virus melalui TNF α dan INF α, selain itu fungsi-nya mempresentasikan antigen kepada sel T yang selanjutnya akan mengeluarkan sitokin dan mediator seperti INF γ, RANTES, GM-CSFdan IL-5.1,8 Limfosit
Pada infeksi virus jumlah limfosit bertambah di jaringan paru dan sebaliknya menurun di pembuluh darah perifer kerena terjadi migrasi. Peningkatan jumlah limfosit berbanding lurus dengan derajat reaktiviti infeksi virus.6 Respons antigen akan mengaktivasi Th2 atau Th1 dan Th2. Percobaan dengan binatang yang terinfeksi RSV didapatkan aktivasi Th1 atau Th2 ter-gantung pada jenis protein virus. Pada penderita asma yang terinfeksi rhinovirus 16 didapatkan sitokin Th1 dan Th2 yang
teran No. 141, 2003

seimbang banyaknya dalam sputum. Sitokin Th1 adalah INF γ dan sitokin Th2 adalah IL- 5 yang selanjutnya akan mempeng-aruhi produksi dan pematangan eosinofil.1
Sel mast Sel mast banyak ditemukan pada saluran napas terutama di
epitel bronkus, lumen saluran napas dan membran basalis. Jumlah sel mast akan meningkat setelah infeksi virus. Sel mast akan mengeluarkan mediator inflamasi leukotrien (LT)C4. Selama infeksi RSV terjadi peningkatan jumlah LT C4 yang berbanding lurus dengan beratnya gejala penyakit. Pada anak yang menderita bronkiolitis jumlah sel mast meningkat 5 kali lebih banyak dibandingkan dengan anak yang menderita gejala penyakit saluran napas atas. Leukotrien C4 merupakan salah satu mediator yang menyebabkan bronkokonstriksi pada asma.1 Eosinofil
Infiltrasi eosinofil di saluran napas merupakan gambaran yang khas pada penderita asma alergi.6,8 Pada biopsi epitel bronkus didapatkan jumlah eosinofil yang meningkat pada orang normal dan penderita asma yang terinfeksi rhinovirus. Eosinofil akan meningkat lebih dari 6 minggu pada penderita asma. Eosinofil berkumpul di saluran napas di bawah pengaruh IL-5, GM-CSF, IL-8 dan RANTES.1,18
Granulocyte-macrophage colony stimulating factor mem-pegaruhi pembentukan eosinofil di sumsum tulang dan mem-perpanjang umur eosinofil namun jumlahnya tidak meningkat pada penderita yang terinfeksi virus saluran napas atas. Re-gulated on activation normal T-cell expressed and secreted akan meningkat jumlahnya pada sekret hidung anak asma yang terinfeksi virus. Regulated on activation normal T-cell express-ed and secreted berfungsi mempengaruhi produksi eosinofil di sumsum tulang dan memperpanjang umur eosinofil. Pada bina-tang percobaan diketahui eosinofil mempunyai efek antivirus.1
Neutrofil
Jumlah neutrofil akan meningkat pada penderita asma dan bukan asma yang terinfeksi virus. Peningkatan terjadi pada hari ke 4 dan berbanding lurus dengan IL-8. Interleukin 8 me-rupakan kemokin yang mengaktivasi neutrofil, limfosit, basofil dan eosinofil. Pada penderita asma atopi yang terinfeksi Rhinovirus 16 didapatkan peningkatan IL-8 dan neutrofil pada kurasan cairan hidung selama masa akut infeksi, kadar neutrophil myeloperoxidase berbanding lurus dengan beratnya gejala asma.1
Wark melaporkan penderita asma yang terinfeksi virus akan terjadi peningkatan neutrofil yang berbanding lurus dengan berat serangan asma dan lama rawat di rumah sakit. Pada penelitian ini, Wark melakukan pengukuran eosinophil cation protein ( ECP) dan enzym lactate dehydrogenase (LDH).5
Natural killer cell (NK cell) Natural killer cell merupakan sel yang penting dalam
respons imun, fungsinya mengeliminasi sel target termasuk sel yang terifeksi virus. Natural killer cell dibentuk saat permulaan
infeksi virus namun perannya pada saluran napas penderita asma belum jelas.1 Hubungan infeksi virus dan inflamasi saluran napas
Hubungan infeksi virus dan infamasi saluran napas adalah pada penderita asma yang terinfeksi virus lebih berat gejala gangguan pernapasannya dibandingkan dengan penderita bukan asma yang terinfeksi virus. Mekanisme imonologi hu-bungan ini secara detail belum jelas namun diduga infeksi virus meningkatkan sensitivitas saluran napas penderita asma. Hipo-tesis lain tentang patogenesis serangan asma yang disebabkan infeksi virus dapat dilihat pada table 2.1 Tabel 2. Hipotesis patogenesis serangan asma karena infeksi virus Kerusakan epitel Gangguan bersihan siliar
Permiabilitas meningkat Kehilangan fungsi proteksi
Produksi mediator Komplemen Metabolisme asam arakidonat Produksi oksigen reaktif
Induksi inflamasi Sitokin Kemokin Aktivasi sel imun Induksi adesi molekul
Disregulasi Ig E Ig E total meningkat Produksi Ig E antivirus
Remodeling saluran napas Otot polos saluran napas Fibroblas Mielofibroblas Faktor pertumbuhan
Respons saraf Sensitivitas kolinergik meningkat Modulasi metabolisme neuropeptid Disfungsi reseptor β adrenergik
Dikutip dari (1)
Hubungan mengi bayi dan asma Mengi bayi dapat terjadi jika ada faktor predisposisi se-
perti prematur, fungsi paru yang rendah saat lahir ibu perokok, sering terinfeksi virus.dan faktor risiko utama infeksi virus terutama RSV dan terpajan asap rokok. Mengi bayi akan men-jadi asma bila mempunyai faktor risiko seperti lahir dari ibu yang menderita alergi atau asma, terpajan alergen, dan faktor risiko utama infeksi virus terutama rhinovirus dan terpajan asap rokok,20(tabel 3).
Interaksi faktor predisposisi dan faktor risiko sehingga me-nyebabkan gejala mengi dapat dilihat pada gambar 3.9 Tabel 3. Hubungan mengi bayi dan asma
Mengi Bayi Asma factor predisposisi
prematur fungsi paru rendah ibu perokok infeksi virus
foktor genetik ibu asma ibu atopi dermatitis atopi alergi makanan terpajan aeroallergen
faktor risiko utama
infeksi virus terutama RSV terpajan asap rokok
infeksi virus terutama RV terpajan aeroallergen terpajan asap rokok
Dikutip dari (20)
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 21

Gambar 3. Interaksi faktor predisposisi dan faktor risiko terjadinya
mengi
Dikutip dari (9) RANGKUMAN
Infeksi virus dapat menimbulkan gejala mengi pada bayi usia kurang dari 2 tahun. Virus yang tersering menyebabkan gejala mengi adalah RSV dan rhinovirus. Mengi akan ber-kembang menjadi asma bila bayi tersebut mempunyai faktor risiko seperti atopi, terpajan alergen, terpajan asap rokok, terinfeksi virus, ibu asma atau perokok. Faktor risiko atopi ber-hubungan dengan kelainan pada kromosom 5q31-q33 dan 11q.
Masuknya virus ke saluran napas akan mengakibatkan respons imun nonspesifik sel epitel dengan mengeluarkan sitokin proinflamasi seperti GM-CSF, IL-6, IL-8, RANTES, dan IL-11. Dari makrofag akan dikeluarkan TNF-α, INF-α, dan IL-8 yang mempunyai efek antivirus dan proinflamasi. Respons imun selular infeksi virus akan mengakibatkan sel T me-ngeluarkan IFN-γ, GM-CSF, IL-4. IL-5 dan IL-10. Pada infeksi virus terjadi peningkatan jumlah makrofag, limfosit, sel mast, eosinofil dan neutrofil.
KEPUSTAKAAN 1. Massage SD, Johnston SL. The immunology of virus infection in asthma.
Eur Respir J 2001; 18: 1013-25.
2. McConnell WD, Holgate ST. The definition of asthma: its relationship to other chronic obstructive lung diseases. In: Clark TJH, Godfrey S, Lee TH, Thomson NC eds. Asthma, 4th ed. New York. Oxford University Press Inc; 2000, p. 1-25.
Infeksi virus dan terpajan zat iritan
3. Sheth KK, Busse WW. Respiratory tract infection and asthma. In: Gershwin ME, Halpern GM eds. Bronchial asthma, 3th ed. New Jersey. Humana Press Inc; 1994, p. 481-512.
Atopi
4. Johnston SL, Pattemore PK, Sanderson G, Smith S, Campbell MJ, Josephs LK, at al. The relationship between upper respiratory infections and hospital admissions for asthma: A time- trend analysis. Am J Respir Crit Care Med 1996; 154: 654-60.
hiperreaktiviti saluran napasInflamasi 5. Wark PAB, Johnston SL, Moric I, Simpson JL, Hensley MJ, Gibson PG.
Neutrophil degranulation and cell lysis is associated with clinical severity in virus- induced asthma. Eur Respir J 2002; 19: 68-75.
6. Welliver RC. Immunologic mechanisms of virus- induced wheezing and asthma. J Pediatr 1999; 135: S14-9.
penurunan fungsi paru dan diameter saluran napas konginital
7. Gern JE, Busse WW. The role of virus infections in the natural history of asthma. J Allergy Clin Immunol 2000; 106: 201-12.
8. Gern JE. Viral and bacterial infections in the development and progression of asthma. J Allergy Clin Immunol 2000; 105: S497-502. mengi
9. Kattan M. Epidemiologic evidence of increased airway reactivity in children with a history of bronchiolitis. J Pediatr 1999; 135: S8-13.
10. Carlsen KH, Sterk PJ. Infection: friend or foe to the development of asthma? Eur Respir J 2001; 18: 744-7.
11. McBride JT. Pulmonary function changes in children after respiratory syncytial virus infection in infancy. J Pediatr 1999; 135: S28-32
12. Peebles RS, Hashimoto K, Collins RD, Jarzecka K, Furlong J, Mitchell DB, et al. Immune interaction between respiratory syncytial virus infec-tion and allergen sensitization critically depends on timing of challenges. The J Infect Dis 2001; 184: 1374-9.
13. Papi A, Papadopoulos NG, Degitz K, Holgate ST, Johnston SL. Corticosteroids inhibit rhinovirus- induced intercellular adhesion molecule- 1 up- regulation and promoter activation on respiratory epithelial cells. J Allergy Clin Immunol 2000; 105: 318-26.
14. Cheung D, Dick EC, Timmers MC, Klerk EPA, Spaan WJM, Sterk PJ. Rhinovirus inhalation causes long- lasting excerssive airway narrowing in response to methacholine in asthmatic subjects in vivo. Am J Respir Crit Care Med 1995; 152: 1490-6.
15. Fraenkel DJ, Bardin PG, Sanderson G, Lampe F, Johnston SL, Holgate S. Lower airways inflammation during rhinovirus colds in normal and in asthmatic subjects. Am J Respir Crit Care Med 1995; 151: 879-86.
16. Parry DE, Busse WW, Sukow KA, Dick CR, Swenson C, Gern JE. Rhinovirus- induced PBMC responses and outcome of experimental infection in allergic subjects. J Allergy Clin Immunol 2000; 105: 692-8.
17. Koppelman GH, Meijer GG, Blecker ER, Postma DS. Genetics of asthma. In: Clark TJH, Godfrey S, Lee TH, Thomson NC eds. Asthma, 4th ed. New- York. Oxford University Press Inc; 2000, p. 146-74.
18. Ehlenfield DR, Cameron K, Welliver RC. Eosinophilia at the time of respiratory syncytial virus bronchiolitis predicts childhood reactive airway disease. Pediatrics 2000; 105: 79-83.
19. Irvin CG. Interaction between the growing lung and asthma: Role of early intervention. J Allergy Clin Immunol 2000; 105: S540-6.
20. Heymann PW, Zambrano JC, Rakes GP. Virus-induced wheezing in children. Immunology and Allergy Clinics of North America 1998; 18: 25-45
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 22

TINJAUAN KEPUSTAKAAN
Asma Akibat Kerja
Teguh H. Karjadi
Subbagian Alergi-Imunologi, Bagian Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/ Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta
PENDAHULUAN
Asma akibat kerja merupakan penyakit paru akibat kerja yang sering dijumpai terutama di negara maju. Ini tergambar dari laporan di Kanada pada tahun 1977 dan 1986; pada tahun 1977 asma akibat kerja menempati urutan di bawah asbestosis dan silikosis, pada tahun 1986 menjadi urutan teratas melam-paui asbestosis dan silikosis. Prevalensi di masyarakat umum tak diketahui pasti, akan tetapi di Amerika Serikat ± 15% populasi penderita asma bronkial mempunyai hubungan dengan faktor lingkungan kerjanya.
Prevalensi asma akibat kerja di dalam beberapa populasi jenis industri tergambar sbb :1,2
1. Baker asma (akibat tepung terigu), dilaporkan dari be-berapa penelitian dapat mencapai 25-30 % dari pekerja yang terpapar. 2. Alergi latex pada tenaga medis didapat sebesar 17% 3. Asma pada pekerja pengecatan otomotif sebesar 17% di-banding 3,2 % pada kelompok kontrol.3 4. Sebesar 25% pekerja industri detergen yang terpapar enzim bahan detergen mengalami gangguan pernafasan. 5. Pada industri yang menggunakan bahan kimia isosianat (otomotif, pesawat terbang, kereta api) 10% pekerjanya men-derita asma akibat kerja.
Lebih dari 250 agent (polutan) organik dan anorganik di lingkungan tempat kerja diduga merupakan pencetus terjadinya asma akibat kerja, termasuk bahan-bahan di bawah ini ; − Debu organik dengan berat molekul besar seperti tanam-an, protein hewan, sayuran, latex alam, tepung, ikan, kepiting dll. − Bahan kimia dengan berat molekul kecil seperti diisosia-nat, garam platinum , nikel, colophony, obat, debu kayu dll. − Bahan iritan seperti gas klorin, sulfur dioksid, asap ke-
bakaran. DEFINISI DAN KLASIFIKASI2,4,5
Definisi asma akibat kerja adalah: adanya gangguan aliran udara pernafasan dan hiperreaktivitas bronkus akibat agent (polutan) spesifik di tempat kerja dan bukan di luar tempat kerja. Agent (polutan) tersebut dapat berupa gas, debu, kabut, maupun uap.
Bila berdasarkan definisi di atas maka pekerja penderita asma atau pernah menderita asma sebelumnya dan kemudian menjadi lebih buruk setelah terpapar polutan tempat kerja tak termasuk di dalamnya. Oleh karena itu asma akibat kerja dibagi dua kategori yaitu asma akibat kerja dan asma yang diper-buruk oleh lingkungan kerja.
Selain dua kategori di atas juga dikenal pembagian me-nurut masa laten ( waktu yang dibutuhkan dari mulai terpapar sampai timbulnya asma klinis). Terdapat masa laten
Asma akibat kerja dengan masa laten biasanya disebabkan oleh paparan agent dengan berat molekul besar. Mekanismenya melalui proses imunologi (IgE), walaupun sebagian kecil susah dibuktikan karena polutannya mempunyai berat molekul kecil (hapten). Tidak terdapat masa laten
Disebabkan oleh mekanisme iritasi bahan gas/ kimia dengan konsentrasi amat tinggi dalam waktu singkat yang menyebabkan gangguan pernafasan dan bronkus hiperrespon-sif. Contoh : RADS (Reactive Airway Dysfunction Syndrome).6
PATOFISIOLOGI1,7
1. Iritasi langsung
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 23

Iritasi menjadi provokasi langsung terjadinya asma bron-kial. Terutama disebabkan oleh asam khlorida, sulfur dioksid, amoniak yang banyak dipakai dalam industri perminyakan dan kimia. Pekerja yang sudah mempunyai kelainan pernafasan lain lebih mudah terserang asma akibat kerja jenis ini. 2. Alergi
Alergi berperan penting pada sebagian besar asma bronkial akibat kerja. Patofisiologinya sama dengan asma bronkial umumnya melalui hiperreaktifitas tipe I (IgE). Bahan polutan dengan berat molekul besar (> 5000 dalton) biasanya melalui mekanisme ini yaitu terbentuknya IgE spesifik terhadap bahan tersebut dan pada pemeriksaan tes kulit (prick test) hasilnya positif. IgE spesifik yang terbentuk bila berikatan dengan antigen (polutan) akan menyebabkan sel mast dan sel inflamasi lain mengeluarkan mediator seperti histamin, eosinophilic chemotactic factor (ECF-A), neutrophil chemotactic factor (NCF-A) dll sehingga terjadi proses inflamasi. Mediator ter-sebut ditemukan pada cairan BAL (broncho alveolar lavage) pasien asma yang diprovokasi oleh alergen tempat kerja.
Pada agent/polutan dengan berat molekul rendah (< 5000 dalton) tidak selalu ditemukan Ig E spesifik, karena diper-kirakan alergen tersebut hanya berupa hapten dan harus ber-konjugasi dengan protein lain untuk menjadi alergen; tetapi pada pemeriksaan BAL pasien-pasien tersebut menunjukkan mediator yang sama seperti asma yang disebabkan oleh berat molekul besar. Oleh sebab itu meskipun tak ditemukan IgE, tetap terbukti terjadi reaksi imunologis (inflamasi) pada pasien tersebut. 3. Farmakologik
Inhalasi udara tempat kerja dapat menyebabkan akumulasi bahan kimia yang ada dalam tubuh seperti histamin atau asetilkolin; akumulasinya dalam paru-paru menyebabkan asma bronkial. Contohnya insektisida dalam industri pertanian dapat menyebabkan terbentuknya asetilkolin dan menyebabkan kon-traksi otot pernafasan sehingga terjadi konstriksi saluran nafas. Klinis
Sama seperti asma bronkial pada umumnya yaitu adanya batuk-batuk, sesak nafas, mengi, yang kadang disertai rinitis dan mata gatal. Sedang derajat berat serangan dapat bervariasi. Diagnosis
Diagnosis asma akibat kerja pada prinsipnya adalah meng-hubungkan gejala klinis asma dengan lingkungan kerja; oleh karenanya dibutuhkan suatu anamnesis yang baik dan peme-riksaan penunjang yang tepat. − Anamnesis teliti mengenai apa yang terjadi di lingkungan kerjanya merupakan hal penting; seperti : kapan mulai bekerja di tempat saat ini, apa pekerjaan sebelum di tempat kerja saat ini, apa yang dikerjakan setiap hari, proses apa yang terjadi di tempat kerja, bahan-bahan yang dipakai dalam proses produksi serta data bahan tersebut. Dan yang tak kalah penting adalah peninjauan lapangan oleh pemeriksa (dokter) untuk lebih me-mahami situasi lapangan. Selain anamnesis mengenai tempat kerja, yang perlu juga diketahui adalah mengenai klinis yang terjadi. Kapan mulai timbulnya keluhan, sejak mulai masuk tempat tersebut atau yang dikenal sebagai masa laten.Masa
laten dapat beberapa minggu sampai beberapa tahun, umumnya 1-2 tahun.Klinis sesak, batuk, mengi dapat timbul sewaktu kerja, setelah kerja (sore maupun malam) atau keduanya. Bila frekuensi serangan lebih sering/memburuk sewaktu hari kerja dibandingkan hari libur atau akhir minggu maka dapat diduga asma yang timbul berhubungan dengan tempat kerja.1,2 − Pemeriksaan penunjang Spirometri (pemeriksaan FEV1) sebelum dan sesudah shift. Dikatakan positif bila terjadi penurunan FEV1 sebesar lebih dari 5% antara sebelum dan sesudah kerja; pada orang normal variabel tersebut kurang dari 3%. Pemeriksaan ini oleh banyak ahli diragukan sensitivitasnya karena pada suatu penelitian hanya 20% penderita asma disebabkan colophony yang turun FEV1nya selama workshift; sedangkan penurunan FEV1 juga dijumpai pada 10% kelompok orang yang tidak asma (kontrol). Cara lain adalah pengukuran FEV1 dan FVC pada pekerja (tersangka asma akibat kerja) yang dikeluarkan dari lingkung-an kerjanya dan kemudian diukur ulang sewaktu bekerja kembali. Apabila hasilnya memperlihatkan perbaikan selama meninggalkan tempat kerja dan didukung oleh perbaikan ke-luhan maka dapat disimpulkan adanya hubungan keluhan klinis dan tempat kerja.1,2,5
PEFR : Pemeriksaan serial PEFR (peak expiratory flow rate) selama hari-hari kerja dan beberapa hari libur di rumah, me-rupakan pemeriksaan asma akibat kerja yang terbaik. Di-katakan positif respons bila kurva pengukuran selama hari libur di rumah lebih baik dari sewaktu hari kerja.1,2,5
− Tes provokasi Ada dua macam pemeriksaan: • Non spesifik yaitu provokasi bronkus menggunakan histamin atau metakolin. Pemeriksaan ini hanya membuktikan adanya bronkus hiperreaktif . • Spesifik yaitu provokasi bronkus menggunakan alergen yang diduga penyebab. Pemeriksaan ini bila dapat dilaksanakan merupakan cara pembuktian terbaik bahwa alergen tempat kerja merupakan penyebab. Kesulitannya terletak pada penen-tuan alergen penyebab dan reproduksinya bila telah diketahui. − Tes kulit dan tes serologi
Pemeriksaan ini dapat dilakukan apabila agen penyebab-nya bahan dengan berat molekul besar karena akan merangsang terjadinya reaksi imunologi (IgE). Faktor Prediposisi
Seperti diketahui timbulnya asma adalah hasil interaksi antara faktor host (genetik) dan faktor lingkungan. Faktor predisposisi asma akibat kerja adalah atopi dan merokok. Atopi merupakan faktor predisposisi pada asma akibat bahan berberat molekul besar dan tidak pada yang disebabkan oleh bahan ber-berat molekul kecil. Sedangkan faktor merokok pada beberapa penelitian menunjukan bahwa orang atopi dan merokok lebih mudah tersensitisasi alergen dalam lingkungan kerja daripada orang atopi dan tak merokok. Penatalaksanaan − Untuk mencegah terjadinya asma akibat kerja maka pe-meriksaan kesehatan sebelum kerja, pemakaian alat pelindung, pemantauan polutan di udara lingkungan kerja sangat dianjur-
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 24

kan. − Bila telah terjadi asma akibat kerja, maka pemindahan ke luar lingkungan kerja merupakan hal penting. Apabila karena sesuatu hal tidak bisa dipindahkan maka harus dilakukan upaya pencegahan dan pemantauan penurunan fungsi paru. − Evaluasi fungsi paru secara berkala pada pekerja yang sudah menderita asma akibat kerja diperlukan untuk mencegah kecacatan. Klinis asma akan menetap sampai beberapa tahun meskipun pekerja tersebut sudah keluar dari lingkungan kerja-nya.
Gambar 1. Algoritma diagnosis asma akibat kerja1
− Pengobatan medikamentosa pada pasien asma akibat kerja sama seperti asma bronkial pada umumnya:5,8,9 • Teofilin, merupakan bronkodilator dan dapat menekan
neutrophil chemotactic factor . Efektifitas kedua fungsi di atas tergantung dari kadar serum teofilin. • Agonis beta, merupakan bronkodilator yang paling baik untuk pengobatan asma akibat kerja dibandingkan dengan anta-gonis kolinergik (ipratropium bromid). • Kombinasi agonis beta dengan ipratropium bromid mem-perbaiki fungsi paru lebih baik dibanding hanya beta agonist saja.8 • Kortikosteroid, dari berbagai penelitian diketahui dapat mencegah bronkokonstriksi yang disebabkan oleh provokasi bronkus menggunakan alergen. Selain itu juga akan memper-baiki fungsi paru, menurunkan eksaserbasi dan hiperespon-sivitas saluran nafas dan pada akhirnya akan memperbaiki kualitas hidup.
Subject still at work
Compatible clinical history and exposure to possible causal agents
Skin and radioallergosorbent
tests (if possible)
Assessment of bronchial responsiveness to pharmacologic agents
Consider return to work↓
Workplace or laboratory challenges with the suspected occupational agent, peak expiratoryflow monitoring, or both
Normal Increased
Subject no longer at work
Subject stillat work
Negative
Negative
No asthma Occupational Asthma Nonoccupational Asthma
Laboratory challenges with the suspected occupational agent
Positive
Positive
Agents Occupations Skin test Specific IgE
Berat Molekul Besar Animal products, insects, others laboratory animals (rats, mice, rabbits, guinea pigs)
Laboratory workers Veterinarians Animal handlers
+ +
Birds Pigeon, budgerigar Chicken
Pigeon breeders Poultry workers Bird fanciers
+ +
+
Insects Grain mite Cockroach Bee moth Moth and butterfly Plants Wheat/rye flour Coffee beans Castor bean Tea Tobacco leaf Biologic enzymes B. subtilis Vegetables Gums Gum Acacia Others Crab Prawn
Grain workers Laboratory workers Fish bait breeders Entomologist Bakers, millers Food processors Oil industry Teaworker Tobacco manufacturing Detergents industry Printers Crab processing Prawn processing
+ + + +
+ +
+ +
+
+
+ +
+ + +
+
+
+
Berat Molekul Kecil Toluene diisocyanate Polyurethane
industries, plastics, varnish
-
Diphenylmethane diisocyanate
Foundries - +
Hexamethylene diisocyanate
-
Wood dust Western red cedar
(Thuja plicata)
Carpenter, construction, cabinet maker, sawmill worker
+ +
California redwood (Sequoia sempervires)
-
Mahogany (Shorea sp) - Platinum Platinum refinery + Nickel Metal plating + Penicillins Pharmaceutical - Cephalosporin Pharmaceutical + Piperazine hydrochloride Chemist +
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 25

Disadur dari kepustakaan1
RINGKASAN − Asma akibat kerja merupakan penyakit paru akibat kerja yang sering dijumpai. − Mekanisme timbulnya melalui jalan iritasi, imunologi dan farmakologi. − Diagnosis adalah dengan menghubungkan klinis asma dengan lingkungan kerja; anamnesis dan pemeriksaan penun-jang yang tepat sangat membantu.
KEPUSTAKAAN 1. Yeung CM. Occupational Asthma. Chest 1990;98:1485-615. 2. Yeung CM, Malo JL. Occupational Asthma. N Engl J Med 1995; 333:
107-12.
3. Teguh Harjono. Penurunan Arus Puncak Ekspirasi pada Pekerja
Pengecatan Mobil di Jakarta (disertasi akhir PPDS). FKUI, 1994. 4. Sheppard D, Hughson W. Occupational Lung Diseases. in: La Dou J.
(ed.). Occupational Medicine. Connecticutt; Prentice Hall Int. Inc; 1990 : 221-36.
5. Shelden S. Determination of Airway Hyperreactivity to Allergens and Other Bronchoconstrictive Substance. in: Baddana JE. (ed.). Occupational Asthma. Philadelphia: Hanley & Belfus Inc. 1992:35-48.
6. Gautrin D, Boulet LP, Boutet M et al. Is Reactive Airways Dysfunction Syndrome a variant of Occupational Asthma. J Allerg Clin Immunol 1994;93:12-22.
7. Tips to Remember : Occupational asthma. AAAI. 2001 8. Gustavo JR,Carlos R. First line therapy for adult patients with acute
asthma receiving a multiple dose protocol of Ipratropium Bromide plus Albuterol in the emergency department. Am.J. Respir. Crit Care Med 2000 ; 161: 1862-8.
9. NHLBI / WHO. Global Initiative for Asthma. 1995.
KALENDER KEGIATAN ILMIAH PERIODE OKTOBER 2003 – JANUARI 2004
Waktu Kegiatan Ilmiah Tempat dan Sekretariat
10 – 12 Dutch Foundation for Postgraduate Medical Course on Cardiology
Hyatt Regency, Surabaya Telp. : 031- 5031752 Fax. : 031- 5997378 e-mail : [email protected]
12 – 16 Kongres Nasional PERHATI
Grand Bali Beach, Bali Telp. : 021-335088, 3914154 Fax. : 021-3914154, 392144 Email : [email protected], [email protected]
Oktober
16 – 18 Profesi Farmasis di Era Abad 21
Hotel Horison , Jakarta Telp. : 021-42873888 ext 563 Fax. : 021-4256326 Email : [email protected] Website : www.kalbe.co.id
5 – 6 The 2nd New Trend in Cardiovascular Management : The Integration of Cardiovascular Management
Tiara Convention Center, Medan Telp. / Fax. : +62-61-8366449 e-mail: [email protected]
Desember
6 – 7 Jakarta Diabetes Meeting 2003: Diabetes and Obesity
Hotel Borobudur Jakarta Telp. : 021-3928658 Fax. : 021-3928659 Email : [email protected]
10 – 16 5th Asian Conference of Neurological Surgeons
Imperial Aryaduta Hotel and Resort, Tangerang Telp. : 021-54210001 Fax. : 021-54210002 Website : www.acns.com Email : [email protected]
15 – 17 Kongres Nasional Persatuan Ahli Bedah Mulut Indonesia ke IX
Hotel Grand Aguilla Bandung Telp. : 022-2041196 Fax. : 022-2036169 Website : www.pabmi.org
Januari
30 – 1 Current Concept in Ophthalmology Hotel Borobudur, Jakarta Telp. : 021-335 600 Fax. : 021-390 4601
Informasi terkini, detail dan lengkap (jadwal acara/pembicara) bisa diakses di http://www.kalbe.co.id/calendar>> Complete
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 26

TINJAUAN KEPUSTAKAAN
Asma dan Polusi Udara
M. Yusuf Hanafiah Pohan, Faisal Yunus, Wiwien Heru Wiyono
Bagian Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/ Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta
PENDAHULUAN
Asma adalah penyakit yang telah mendapat banyak per-hatian dalam beberapa tahun ini. Salah satu aspek yang me-ngejutkan adalah prevalensi yang meningkat di banyak negara industri. Aspek lain dari industrialisasi yaitu polusi udara yang terus menerus di perkotaan akibat jumlah kendaraan yang makin banyak. Polusi udara secara meyakinkan berhubungan dengan bertambahnya gejala asma. Tingkat polusi udara berhubungan dengan efek yang merugikan kesehatan individu penyandang asma.1,2 Efek-efek tersebut antara lain penurunan fungsi paru, peningkatan hiperesponsivitas bronkus, angka kun-jungan ke gawat darurat dan rawat inap, peningkatan peng-gunaan obat, perubahan peradangan, interaksi antara polusi udara dan faktor alergen serta perubahan sistim imun.1
Tinjauan pustaka ini membahas hubungan antara polusi udara dengan tanda dan gejala asma, yang akan memaparkan hubungan polusi udara dengan masing-masing efek terhadap kesehatan penderita asma. Polusi udara
Polusi udara terdiri dari partikel dan berbagai gas yang dapat berasal dari berbagai sumber. Polusi udara sendiri dapat terjadi di dalam dan di luar ruangan (indoor dan outdoor).3 Sumber polusi udara dapat berasal dari alam dan aktivitas manusia. Sumber polutan alam meliputi aktivitas gunung ber-api, kebakaran hutan, badai debu dan radiasi zat radioaktif dari alam seperti radon. Sumber polutan yang berasal dari aktivitas manusia yaitu dari kendaraan bermotor, pembakaran bahan bakar fosil pada tempat tak bergerak (fuel combustion in stationary sources), pembuangan sampah padat, proses industri dan lain-lain. Ada pula yang berasal dari aktivitas manusia dalam ruangan seperti merokok, penggunaan kompor, mesin pengganda kertas, dan lain-lain.4
Jenis polutan utama pada polusi udara luar ruangan yaitu karbon oksida (CO dan CO2), sulfur oksida (SO2), nitrogen ok-sida (NOx), volatile organic compounds (VOC) seperti hidro-karbon, particulate matter (PM) dan ozon.3,4 Untuk melaporkan
konsentrasi udara sehari-hari banyak negara menggunakan pollutant standard index (PSI). Indonesia sendiri menggunakan istilah indeks standar pencemar udara (ISPU) dengan pembagi-an sebagai berikut:dikutip dari 3
− PSI < 50 sehat − PSI 50-100 sedang − PSI 101-199 tidak begitu baik − PSI 200-299 tidak sehat − PSI 300-399 berbahaya − PSI > 400 sangat berbahaya Hubungan antara faktor lingkungan dan genetik asma
Faktor lingkungan termasuk mutu udara dianggap berperan penting pada asma sejak permulaan kehidupan dan sebagai pencetus eksaserbasi asma. Faktor genetik termasuk atopi, hiperesponsivitas jalan napas intrinsik dan perbedaan struktur reseptor B2 pada jalan napas mungkin menunjang anak-anak menjadi penyandang asma. Peran gen-gen ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan antara lain dengan bioalergen seperti kecoa, tungau debu dan partikel udara luar ruangan.2
Pada gambar 1 dapat dilihat interaksi faktor lingkungan dan genetik dalam perjalanan asma. Fungsi paru normal saat kelahiran bayi yang nantinya dapat berkembang menjadi asma. Saat asma telah muncul maka pajanan lingkungan berperan sebagai pencetus disfungsi jalan napas dan eksaserbasi klinis. Penurunan Fungsi Paru
Spirometri dan metode pengukuran fungsi paru mekanik lainnya telah digunakan luas dalam studi efek polusi udara dan di bidang studi epidemiologis polusi udara. Banyak studi me-neliti subjek yang terpajan SO2, setelah diketahui bahwa pe-nyandang asma sensitif terhadap inhalasi SO2. Inhalasi SO2 1,0 ppm (part per million) selama 10 menit dalam aktivitas sedang dapat menurunkan VEP1 23% dan meningkatkan tahanan paru total rata-rata 67%.5 Koenig dan Pierson melaporkan bahwa pajanan selama 2,5 menit cukup untuk menimbulkan bronko-konstriksi pada penyandang asma.5
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 27

Kreit dkk6 mengevaluasi perubahan fungsi paru pada orang sehat dan asma setelah 2 jam terpajan 0,40 ppm ozon. Penyan- Environmental Exposures : Allergens, Infections, Tobacco Smoke “Trigers” Normal Lung Inception of Mild Severe Function Asthma Asthma Asthma Genetic Factors : Atopy Airways Hyperreactivity Gambar 1. Hubungan antara faktor lingkungan dan genetik pada asma
Dikutip dari (2)
dang asma mengalami penurunan fungsi paru lebih besar setelah pajanan. Basha dkk7 juga melakukan penelitian pada orang sehat dan asma. Subjek terpajan selama 6 jam dengan 0,20 ppm ozon dan udara tersaring. Bronchooalveolar lavage (BAL) dilakukan setelah 18 jam pajanan. Tidak ada kelompok yang menunjukkan perubahan fungsi paru berarti, namun pe-nyandang asma menunjukkan peningkatan hiperesponsivitas bronkus yang bermakna.
Penelitian pajanan PM dalam laboratorium sangat sulit, karena PM merupakan campuran debu, asap dan kabut di ling-kungan. Beberapa penelitian telah mengikutkan penyandang asma pada penelitian asam sulfur, salah satu bentuk PM. Seper-ti pada SO2, penyandang asma lebih sensitif terhadap asam sulfur daripada orang sehat. Penurunan VEP1 dan KVP dapat dilihat pada konsentrasi 35, 70 dan 100 ug/m3 selama 30-40 menit latihan.8 Penelitian dengan NO2 tidak menunjukkan pe-nurunan fungsi paru pada orang sehat dan penyandang asma.1
Beberapa penelitian menunjukkan perubahan arus puncak ekspirasi (APE) yang berhubungan dengan SO2, PM atau ozon. Satu penelitian di Jerman9 atas 155 anak dan 102 dewasa pe-nyandang asma melaporkan bahwa level SO2 berhubungan dengan penurunan APE. Penurunan APE rata-rata 0,9% (0,46%-1,35%) berhubungan dengan kenaikan SO2 rata-rata 128 mug/m3.
Peningkatan hiperesponsivitas bronkus Kriet dkk6 mengevaluasi efek pajanan ozon pada orang
sehat dan penyandang asma dan menemukan peningkatan res-pons terhadap uji provokasi metakolin hanya pada penyandang asma. Telah dilakukan penelitian meta analisis untuk menilai perubahan hiperesponsivitas bronkus setelah terpajan NO2. Meta analisis dari 20 studi yang menggunakan penyandang asma dan 5 studi dengan orang sehat menemukan peningkatan kecil hiperesponsivitas bronkus namun bermakna pada penyandang asma. Rata-rata kenaikan setelah pajanan NO2 adalah 60%.10 Kunjungan ke gawat darurat dan rawat inap
Tidak diragukan bahwa polusi udara di luar ruangan mem-perburuk asma. Beberapa polutan berhubungan dengan pening-katan kunjungan ke gawat darurat karena asma. Dalam tiga penelitian yang dilakukan di Anchorage11 dan Seattle12 ditemu-kan hubungan bermakna antara pengukuran bahan partikel (PM) dan peningkatan kunjungan karena asma. Di Anchorage
peningkatan PM10 10 ug/m3 berhubungan dengan 3%-6% pe-ningkatan kunjungan asma. Di Seattle perubahan PM 11 ug/m3 berhubungan dengan peningkatan 15% kunjungan asma. Karbon monoksida (CO) juga berperan pada kunjungan asma di Seattle. Tidak ada mekanisme biologis yang masuk akal bagi CO untuk menyebabkan eksaserbasi asma, namun CO diper-kirakan sebagai indikator umum polusi udara. Di Seattle ter-dapat korelasi tinggi antara kadar CO 24 jam dengan nilai PM10.12
Romieu dkk13 melaporkan ozon dan SO2 berhubungan bermakna dengan kunjungan gawat darurat karena asma di Meksiko. Penelitian terbaru kunjungan gawat darurat asma di 12 rumah sakit di London melaporkan peningkatan bermakna kunjungan yang berhubungan dengan SO2, NO2, dan PM10.14
Peningkatan gejala dan penggunaan obat Polusi udara berhubungan dengan peningkatan serangan
asma dan lama serangan serta gejala dan penggunaan obat. Pada penelitian di Kalifornia Selatan dengan 25 anak pe-nyandang asma menunjukkan bahwa perburukan asma ber-hubungan dengan PM. Penelitian ini juga menemukan bahwa konsentrasi rerata ozon 12 jam berhubungan dengan peng-gunaan bronkodilator pada penyandang asma anak.15 Perlu diketahui NO2 sebagal polutan umum luar ruangan juga me-rupakan polutan yang menetap dalam ruangan. Banyak laporan peningkatan gejala pernapasan pada anak yang terpajan NO2 dalam ruangan juga pada perempuan penyandang asma, se-bagai akibat emisi gas untuk memasak.16
Perubahan peradangan Seperti telah dijelaskan penyandang asma mengalami per-
ubahan fungsi paru terinduksi ozon lebih besar dibanding orang sehat. Menjadi pertanyaan apakah penyandang asma tersebut mengalami tingkat peradangan paru yang lebih tinggi. Peneliti-an terhadap 19 penyandang asma yang terpajan 0,2 ppm ozon selama 4 jam latihan, secara umum tidak menunjukkan per-ubahan uji fungsi paru yang lebih besar. Pada penelitian ter-sebut dilaporkan peningkatan IL-8 lebih tinggi, protein dan tanda peradangan lain dalam cairan BAL penyandang asma.17 Penelitian Basha dkk6 juga menemukan peningkatan IL-8 dan netrofil pada penyandang asma setelah paparan ozon.
Interaksi antara polusi udara dan faktor alergen Beberapa penelitian menunjukkan peranan pajanan polusi
udara dalam meningkatkan faktor alergen. Penelitian pertama melaporkan hubungan positif pada 7 penyandang asma dengan paparan ozon 0,12 ppm selama 1 jam mengurangi konsentrasi alergen rerumputan untuk menyebabkan penurunan 20% VEP1.18 Pajanan NO2 memperlihatkan peningkatan efek aler-gen pada penyandang asma. Penelitian ini menemukan setelah paparan NO2 terjadi peningkatan respons terhadap alergen serbuk sari pohon dan rumput.19 Penelitian lain dengan tungau debu20 juga memberi hasil serupa.
Perubahan sistem imun Ada satu laporan menyatakan bahwa pajanan ozon dapat
menyebabkan hiperesponsivitas bronkus, juga mempengaruhi sistem imun. Penelitian ini mengevaluasi kesehatan respirasi, faktor alergi dan respons imun pada 218 anak dalam komunitas
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 28

ozon tinggi (Grup A), dibandingkan dengan 281 anak dari komunitas tingkat ozon rendah (Grup B). Hiperesponsivitas bronkus lebih sering pada anak-anak grup A. Perbandingan serum IgE tidak menunjukkan perbedaan antara kedua kelom-pok. Pada grup A terdapat rasio sel T helper/supresor yang rendah secara bermakna.21 Interaksi antara polusi udara dan makanan
Konsentrasi vitamin antioksidan dalam makanan dan plasma berhubungan dengan status asma. Individu dengan asma mempunyai tingkat serum antioksidan lebih rendah, seperti vitamin C, E dan beta karoten dibandingkan populasi umum. Beberapa penelitian mencoba membedakan apakah suplemen vitamin akan berdampak pada respons terhadap ozon. Tujuh belas penyandang asma dewasa terpajan ozon 0,12 ppm atau udara selama 45 menit latihan sedang yang dilakukan secara intermiten. Hiperesponsivitas bronkus dinilai dengan 10 menit inhalasi SO2 (0,1 dan 0,25 ppm). Pemberian vitamin berhubungan dengan hiperesponsivitas bronkus yang lebih rendah terhadap SO2 dibandingkan dengan plasebo. Hasil ini menunjukkan suplemen vitamin C dan E berguna bagi penyan-dang asma dewasa yang terpajan polusi udara.22 Polusi udara dan penyebab asma
Telah dijelaskan hubungan antara polutan udara spesifik dengan perburukan asma. Kekuatan efek masing-masing polut-an terhadap perburukan asma dapat dilihat di Tabel 1.
Ada cukup bukti bahwa asap rokok adalah faktor risiko asma. Juga ada bukti dari penelitian kesehatan kerja bahwa polusi udara di tempat kerja seperti toluene diisocyanate dapat menyebabkan asma. Tidak terdapat bukti yang nyata bahwa polusi udara umum mempengaruhi perkembangan asma.23
Tabel 1. Hubungan efek asma dan paparan polutan
Efek Asma SO2 NO2 PM Ozon Penurunan fungsi paru ++ 0 + ++ Hiperresponsivitas bronkus +/- + * ++ Kunjungan GD/Rawat inap * + ++ ++ Gejala/penggunaan obat * + + + Peradangan +/- +/- * ++ Respons alergen * + * +/- Efek imun * + * +
Keterangan : * Tidak ada data Dikutip dari (1)
Pajanan SO2 dapat menyebabkan bronkokonstriksi. Pajan-an ozon berhubungan dengan banyak tanda perburukan asma seperti penurunan fungsi paru, peradangan jalan napas, angka kunjungan gawat darurat dan rawat inap serta peningkatan respons terhadap alergen udara secara umum. PM berhubungan dengan penurunan fungsi paru, peningkatan gejala gangguan respirasi, peningkatan penggunaan obat asma dan kunjungan tak terjadwal ke gawat darurat. KESIMPULAN
Tidak ada keraguan bahwa polusi udara berhubungan dengan perburukan asma. Kita masih menunggu penelitian
lanjutan untuk memastikan apakah polusi udara secara umum benar-benar menyebabkan asma. Para dokter harus menjelas-kan pada pasien bahwa polusi udara merupakan salah satu faktor yang dapat mencetuskan asma.
KEPUSTAKAAN
1. Koenig JQ. Air pollution and asthma. J Allerg Clin Immunol 1999; 104: 717-22.
2. Teague WG, Bayer CW. Outdoor air pollution: Asthma and other concerns. Pediatr Clin North Am 2001; 48: 1167-83.
3. Aditama TY. Penilaian polusi udara. J Respir Indon 1999; 1: 4-10. 4. Cohen MJ. Air Pollution. In: Miller GT, ed. Living the environment 7th
ed. California: Wadsworth Publ Co; 1992. p.5575-601. 5. Koenig JQ, Pierson WE. Air pollutans and the respiratory system:
toxicity and pharmacologic interventions. J Toxicol Clin Toxicol 1991; 29: 401-11.
6. Kreit JW, Gross KB, Moore TB, Lorenzen TJ, D’Arcy J, Eschenbacher WL. Ozone-induced changes in pulmonary function and bronchial responsiveness in asthmatic. J Appl Physiol 1989; 66: 217-22.
7. Basha MA, Gross KB, Gwizdala CJ, Haidar AH, Popovich J Jr. Bronchoalveolar lavage neutrophilia in asthmatic and healthy volunteers after controlled exposure to ozone and filtered purified air. Chest 1994; 106: 1757-65.
8. Hanley QS, Koenig JQ, Larson TV, Anderson TL, van Belle G, Rebol-ledo V, et al. Response of young asthmatic patients to inhaled sulfuric acid. Am Rev Respir Dis 1992; 145: 326-31.
9. Peters A, Goldstein IF, Beyer U, Franke K, Heindrick J, Dockery DW, et al. Acute health effects of exposure to high levels of air pollution in Eastern Europe. Am J Epidemiol 1996; 144: 570-81.
10. Folinsbee LJ. Does nitrogen dioxide exposure increase airways respon-siveness? Toxicol Indust Health 1992; 8: 273-83.
11. Gordian ME, Ozkaynak H, Hue J, Morris SS, Spengler JD. Particulate air pollution and respiratory disease in Anchorage, Alaska. Environ Health Perspect 1996; 104: 290-7.
12. Norris G, YoungPong SN, Koenig JQ, Larson TV, Sheppard L, Stout JW. An association between fine particles and asthma emergency visit for children in Seattle. Environ Health Perspect 1999; 107: 489-93.
13. Romieu I, Meneses F, Sienra-Monge JJL, Huerta J, VelasSR, White MC, et al. Effects of urban air pollutants on emergency visits for childhood asthma in Mexico City. Am J Epidemiol 1995; 141: 546-53.
14. Delfino RJ, Zeiger RS, Seltzer JM, Street DH. Symptoms in pediatric asthmatic and air pollution: differences in effects by symptom severity, anti-inflammatory medication use and particulate averaging time. Environ Health Perspect 1998; 106: 751-61.
15. Jarvis D, Chinn S, Luczynska C, Burney P. Association of respiratory symptoms and lung function in young adults with domestic gas appliances. Lancet 1996; 347: 426-31.
16. Atkinson RW, Anderson HR, Strachan DP, Bland JM, Bremmer SA, Ponce de Leon A. Short term association between outdoor air pollution and visit to accident and emergency departments in London for respiratory complaints. Eur Respir J 1999; 13: 257-65.
17. Scannell C, Chen L, Aris RM, Tager I, Christian D, Ferrando R, et al. Greater ozone induced inflammatory responses in subject with asthma. Am J Respir Crit Care Med 1997; 154: 24-9.
18. Molvino NA, Wright SC, Katz I, Tarlo S, Silverman F, McClean PA, et al. Effect of low concentrations of ozone on inhaled allergen responses in asthmatic subjects. Lancet 1991; 338: 199-203.
19. Strand V, Rak S, Barck C, Bylin G. Repeated exposure to an ambient level of NO2 enhances asthmatic response to a nonsymptomatic allergen dose. Eur Respir J 1998; 12: 6-12.
20. Rusznak C, Devalia JL, Davies RJ. Airway response of asthmatic subjects to inhaled allergen exposure to pollutants. Thorax 1996; 51: 1105-8.
21. Zwick H, Popp W, Wagner C, Reisser K, Schmoger J, Bock A, et al. Ef-fects of ozone on the respiratory health, allergic sensitization and cellular immune system in children. Am Rev Respir Dis 1991; 144: 1075-9.
22. Troisi RJ, Willet WC, Weiss, Trichopoulos D, Rosner B Speizer FE. A prospective study of diet and adult-onset asthma. Am J Respir Crit Care
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 29

Med 1995; 151: 1401-8. 23. Baur X. Occupational asthma due to isocyanates. Lung 1996; 174: 23-30.
TINJAUAN KEPUSTAKAAN
Refluks Gastroesofagus
pada Asma
Agus Dwi Susanto, Wiwien Heru Wiyono, Faisal Yunus
Bagian Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/ Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta
PENDAHULUAN
Refluks gastroesofagus didefinisikan sebagai gejala atau kerusakan mukosa esofagus akibat masuknya isi lambung ke dalam esofagus.1 Refluks gastroesofagus berhubungan erat dengan berbagai gejala dan kelainan saluran napas termasuk batuk kronik serta asma.2 Sekitar 10% pasien refluks gastro-esofagus ditemukan dengan gejala pernapasan yang diperkira-kan akibat sekunder refluks.3 Hubungan antara refluks gastro-esofagus dan komplikasi pada paru telah dilaporkan oleh Kennedy pada tahun 1962, ketika mengamati 25 penderita dengan bronkitis kronik, bronkiektasis atau pneumonia yang mengalami silent gastroesophageal reflux.dikutip dari 4,5
Jauh sebelum laporan Kennedy tahun 1962, hubungan fungsi gastroesofagus dan asma telah dipikirkan oleh William Osler. Pada tahun 1912 Sir William Osler pertama kali mem-buat laporan tentang pengamatannya bahwa gejala paroksismal berat mungkin diinduksi oleh kelebihan beban lambung. Oleh karena itu, pasien asma sebaiknya makan lebih banyak pada waktu pagi hari untuk menghindari serangan asma malam. Dia memperkirakan bahwa serangan asma mungkin disebabkan oleh iritasi langsung mukosa bronkus atau tidak langsung oleh pengaruh refleks dari lambung.6-9 Selanjutnya pada tahun 1934 Bray memperkirakan bahwa distensi lambung pada sore hari dapat meningkatkan refleks vagal dan menyebabkan bronko-konstriksi.9 Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan, hu-bungan antara refluks gastroesofagus dan asma sampai seka-rang masih belum jelas. Berbagai data mendukung hipotesis bahwa refluks gastroesofagus menyebabkan asma, di pihak lain asma menyebabkan refluks gastroesofagus. Selain itu pemakai-an bronkodilator pada pengobatan asma dilaporkan dapat menyebabkan refluks gastroesofagus.10
KEKERAPAN
Refluks gastroesofagus merupakan kondisi umum yang ada pada sekitar 20-25% populasi dewasa.9,11 Kekerapan gejala refluks gastroesofagus pada asma secara pasti tidak diketahui, diperkirakan antara 34-89%.7,12-14 Mays dkk.dikutip dari 7 melapor-kan bahwa sebanyak 46% dari 28 penderita asma yang diperik-
sa dengan menggunakan barium esophagogram terbukti mem-punyai refluks. Pada penelitian oleh Perrin-Foyalle dikutip dari 9,14 di Perancis tahun 1980, tercatat 65% dari 150 penderita asma mempunyai gejala refluks. Sontag dkk.dikutip dari 7,14 menemukan 82% dari 104 penderita asma mempunyai jumlah asam refluks abnormal dengan pemantauan pH esofagus 24 jam. Peneliti yang sama dengan endoskopi dan biopsi menemukan 43% dari 186 penderita asma mempunyai esofagitis atau Barrett’s esophagus.7 Penelitian terbaru Harding dkk.15 pada tahun 1999 menemukan 82% dari 199 penderita asma mempunyai gejala refluks.
Penderita asma mungkin mengalami reflux-associated respiratory symptoms (RARS) termasuk batuk, sesak napas dan mengi. Penderita asma tersebut mungkin membutuhkan inhaler agonis β-adrenergik selama periode gejala refluks gastro-esofagus terjadi.16 Fields dkk.dikutip dari 7,9,12,14,17 melaporkan 77% pasien asma mengeluh rasa panas di dada (heartburn), 55% mengeluh regurgitasi, 24% mengeluh kesulitan menelan, 41% tercatat RARS dan 28% menggunakan inhaler pada saat gejala refluks timbul. Erkstrom dkk.dikutip dari 4,12 melaporkan 50 dari 350 penderita asma sedang memberikan respons setelah di-terapi antirefluks. Diduga + 15% penderita asma mengalami gejala refluks dan sekitar setengah dari 50 penderita dengan gejala refluks menunjukkan RARS.
Beberapa penderita asma mungkin mempunyai refluks gastroesofagus tanpa gejala klasik. Irwin dkk.dikutip 7-9,14 me-laporkan silent reflux ditemukan pada 24% penderita asma. Harding dkk.17 melaporkan bahwa refluks gastroesofagus ter-jadi pada pasien asma yang stabil, meskipun tanpa gejala refluks gastroesofagus dengan angka kekerapan rerata 62%. Dismotiliti esofagus merupakan mekanisme fisiologik timbul-nya refluks gastroesofagus dan hal ini sering pada penderita asma. Kjellen dkk.dikutip dari 7,14 menemukan bahwa 38% dari 97 pasien asma mempunyai dismotiliti esofagus, 27% mempunyai hipotensi pada lower esophageal sphincter (LES) dan 24% mempunyai uji perfusi asam (uji Bernstein) positif. Sontag dkk.dikutip dari 7,14,18 melaporkan bahwa penderita asma mem-punyai tekanan LES yang rendah dan lebih sering mengalami
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 30

episode refluks serta waktu kontak asam esofagus lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol. Dari berbagai penelitian yang telah ada diperkirakan sekitar 80% pasien asma mempunyai refluks gastroesofagus.14
PATOFISIOLOGI Secara normal, antirefluks terdiri dari lower esophageal
sphincter (LES) dan konfigurasi anatomi gastroesophageal junction.4,19 Lower esophageal sphincter (LES) merupakan
Dikutip dari (1) Gambar 1. Patofisiologi terjadinya refluks gastroesofagus
faktor barier antirefluks terpenting.20 Terdapat dua kondisi yang harus ada untuk suatu episode refluks yaitu isi lambung siap untuk proses refluks dan mekanisme antirefluks pada LES mengalami gangguan.19 Kelemahan LES merupakan faktor ter-penting pada refluks gastroesofagus, meskipun begitu kebanya-kan refluks terjadi selama transient lower esophageal sphincter relaxations (TLESR), bukan akibat pengurangan tonus sfingter esofagus bawah.1,11 Refluks hanya terjadi jika tekanan LES menghilang, hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan tekanan dalam lambung atau penurunan sementara tonus sfingter. Pe-nurunan tonus sfingter kemungkinan disebabkan oleh kelemah-an otot atau gangguan relaksasi sfingter yang difasilitasi oleh saraf.19
Penyebab sekunder kelemahan LES antara lain penyakit mirip skleroderma, kehamilan, merokok, obat relaksan otot kecil seperti β-adrenergik, aminofilin, nitrat, kalsium antagonis dan kerusakan sfingter oleh operasi.4,19 Laporan terbaru meng-indikasikan bahwa serat otot diafragma crural yang menge-lilingi hiatus esofagus bekerja sebagai sfingter eksterna beker-jasama dengan sfingter interna esofagus bagian bawah. Ke-gagalan mekanisme diafragma crural ini mungkin diikuti oleh terjadinya hernia hiatus. Kantong hernia ini merupakan pre-disposisi timbulnya refluks gastroesofagus.1,9,19 Hernia hiatus mungkin menyebabkan refluks karena mengganggu mekanisme bersihan asam esofagus, sebagai penampung asam dan meng-
ganggu aksi diafragma crural sebagai sfingter.9 Gangguan mekanisme bersihan asam esofagus berupa gangguan peris-taltik esofagus bagian bawah, gangguan netralisasi asam lambung oleh saliva, keterlambatan pengosongan lambung atau refluks duodenum-gaster dapat mempengaruhi terjadinya refluks.1,19-20 Gambar 1 menjelaskan patofisiologi terjadinya refluks gastroesofagus.1
FAKTOR PREDISPOSISI REFLUKS GASTRO-ESOFAGUS PADA ASMA
Ada beberapa faktor yang mungkin berperan pada timbul-nya refluks gastroesofagus pada penderita asma. Faktor-faktor tersebut adalah : 1. Disregulasi otonom
Penderita asma terbukti mempunyai disregulasi oto-nom.9,14,21 Tonus LES dibentuk melalui nukleus dorsalis nervus vagus. Selanjutnya TLESR yang merupakan mekanisme utama terjadinya refluks juga diperantarai oleh nervus vagus.22 Pada uji fungsi otonom yang dilakukan pada 73 penderita asma dengan refluks gastroesofagus ditemukan respons normal se-banyak 27%, respons hipervagal 51%, hiperadrenergik 8% dan respons campuran sebanyak 14%. Data ini menunjukkan bahwa penderita asma dengan refluks gastroesofagus mempunyai dis-fungsi otonom yang terlihat dari peningkatan respons vagal.14,21
Disfungsi otonom menyebabkan penurunan LES dan mem-pengaruhi TLESR yang pada akhirnya dapat menimbulkan refluks.9,14,22
2. Perbedaan tekanan antara rongga toraks dan abdomen Peningkatan perbedaan tekanan antara esofagus intratoraks
dan lambung intraabdomen mungkin menyebabkan refluks gastroesofagus.7,9,13-14,22-23 Secara normal, tekanan abdomen lebih positif dibandingkan tekanan pleura dan esofagus.7 Pada saat akhir ekspirasi perbedaan tekanan antara lambung dan eso-fagus 4-6 mmHg, sehingga tekanan LES normal 10-35 mmHg saat akhir ekspirasi cukup untuk menahan perbedaan tekanan itu.14,22 Dengan terjadinya obstruksi saluran napas, tekanan rongga pleura menjadi lebih negatif dan tekanan intraabdomen menjadi lebih positif. Hal ini dapat meningkatkan perbedaan tekanan antara rongga toraks dan abdomen sehingga menye-babkan refluks.7,9,13-14,22-23
3. Fungsi diafragma crural Diafragma crural berperan penting pada pembentukan
tekanan LES.9,14,22 Perubahan fungsi diafragma dapat menye-babkan timbulnya refluks.7,9,13-14,22-23 Hiperinflasi dan air trapping akibat obstruksi saluran napas mungkin menyebabkan pendataran diafragma yang mengganggu fungsi LES sebagai barier antirefluks.7,13-14,22 4. Hernia hiatus
Pasien dengan asma mempunyai kekerapan tinggi ter-jadinya hernia hiatus.22 Kantong hernia ini merupakan predis-posisi timbulnya refluks gastroesofagus.1,9,19 Mays dkk.dikutip
dari 9,22 melaporkan 64% pasien asma berat mempunyai hernia hiatus. Sontag dkk.dikutip dari 16,22 melaporkan kekerapan hernia hiatus pada pasien asma sekitar 58%. Mittal dkk.dikutip dari 22 melaporkan TLESR sering diikuti oleh episode refluks jika terdapat hernia hiatus. 5. Penggunaan obat-obat asma
Penggunaan obat-obat bronkodilator mungkin dapat me-
Gangguan mekanisme pembersihan : Saliva Motiliti esofagus bagian distal Gangguan “sfingter eksterna” dari serat diafragma crural
Gangguan sfingter interna “LES”
Hernia hiatus
Pengosongan lambung terlambat
Asam dan pepsin (faktor utama, produksi tidak selalu meningkat
Refluks duodenum-gaster
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 31

nurunkan tekanan LES. Teofilin meningkatkan sekresi asam lambung, waktu total refluks dan menurunkan tekanan LES.7,9-
10,22-23 Penelitian Goyal dan Rattan3 pada tupai memperlihatkan bahwa isoproterenol dan teofilin menurunkan tekanan LES. Mereka menemukan bahwa penurunan tekanan LES ber-hubungan dengan kadar teofilin serum. Erkstrom dan Tibbling dikutip dari 14,22 meneliti 25 penderita asma persisten sedang dan berat yang mempunyai riwayat refluks gastroesofagus. Mereka melakukan pemantauan pH esofagus subjek selama 2 kali dengan dan tanpa minum teofilin. Ternyata didapatkan waktu harian refluks meningkat 24% dan gejala refluks gastroeso-fagus (heartburn, regurgitasi) meningkat 170% selama meng-gunakan teofilin. Obat agonis β2 oral dilaporkan dapat menu-runkan tekanan LES, sedangkan agonis β2 inhalasi tidak me-nyebabkan perubahan secara bermakna parameter refluks gas-troesofagus ataupun motiliti esofagus.3,7,10,13-14 Zfass dkk.dikutip
dari 3 pada tahun 1970 melaporkan bahwa tekanan LES menurun secara bermakna setelah pemberian agonis β-adrenergik. Namun hal ini masih menjadi bahan perdebatan.7,10 Hubert dkkdikutip dari 7,13-14 Sontag dkk.18 serta Harding dkk.15 melaporkan bahwa penggunaan obat bronkodilator tidak meningkatkan episode gejala refluks, waktu kontak refluks ataupun penurunan LES. Laporan terbaru Lazenby dkk.24 tahun 2002 memper-lihatkan bahwa kortikosteroid oral (prednison) meningkatkan refluks gastroesofagus pada pasien asma, tetapi mekanismenya masih belum diketahui. REFLUKS GASTROESOFAGUS SEBAGAI PENCETUS ASMA
Pada penderita asma, refluks gastroesofagus dapat menye-babkan bronkokonstriksi. Selain itu dapat terjadi peningkatan ventilasi semenit dan rerata pernapasan tanpa bronko-konstriksi.14 Efek perfusi asam esofagus terhadap fungsi paru dilaporkan minimal dan hanya pada sebagian kecil penderita asma yang terganggu.10,25 Mekanisme patofisiologi terjadinya bronkokonstriksi adalah refleks vagal esofago-bronkial, pe-ningkatan reaktiviti bronkus dan mikroaspirasi asam lambung ke saluran napas (gambar 2).14 Mekanisme lain yang mungkin berperan adalah inflamasi neurogenik dengan pelepasan tachy-kinin dan substansi P ke dalam saluran napas.9,22
1. Mekanisme refleks vagal Saluran napas bagian bawah, esofagus dan lambung ber-
asal dari segmen embrionik yang sama serta dipersarafi oleh nervus vagus.7,9,14 Penelitian oleh Wright dkk. dan Mansfield dkk. memperlihatkan refleks vagal berkaitan dengan refluks gastroesofagus.9 Penelitian Mansfield dan Steindikutip dari 7,9,13,22
pada anjing memperlihatkan bahwa asam esofagus menyebab-kan peningkatan tahanan saluran napas dan efek tersebut menghilang setelah dilakukan vagotomi bilateral. Mansfield dkk.dikutip dari 7,14,22 menemukan bahwa tahanan saluran napas total meningkat 10% pada penderita asma dengan uji perfusi asam (uji Bernstein) positif. Wright dkk.dikutip dari 9,14,22 melaku-kan penelitian pada 136 orang dengan pemberian asam eso-fagus. Terdapat penurunan yang bermakna aliran udara yang diukur dengan volume ekspirasi paksa detik pertama (VEP1) dan penurunan saturasi oksigen setelah pemberian asam eso-fagus. Penurunan VEP1 dan saturasi oksigen tidak ditemukan
pada subjek yang telah diberi atropin sebelumnya. Hal ini me-nunjukkan bahwa perfusi asam esofagus menginduksi refleks vagal.9,14,22 Mekanisme ini telah lama dikenal sebagai teori refleks.3-6,26
Dikutip dari (14)
ambar 2. Patofisiologi refluks gastroesofagus mencetus
. Peningk tiviti bronkus eliti pengaruh asam eso-
fagu
asi, isi lambung refluks ke proksimal esof
G kan bronko-
konstriksi
atan reak2Herve dkk.dikutip dari 7,9,13,22,25 mens pada udara ekspirasi menggunakan hiperventilasi isokap-
nik udara kering dan uji metakolin terhadap penderita asma. Pemberian asam esofagus menyebabkan bronkokonstriksi lebih kuat pada hiperventilasi isokapnik dan memerlukan dosis total metakolin yang lebih rendah secara bermakna untuk menurun-kan 20% VEP1 dibanding larutan garam fisiologis. Erkstrom dan Tibblingdikutip dari 13,25 melaporkan bahwa reaktiviti bronkus terhadap histamin meningkat secara bermakna diantara pende-rita asma dengan gejala RARS. Penelitian Wu dkk.27 tahun 2000 memperlihatkan bahwa peningkatan reaktiviti saluran napas penderita asma diinduksi oleh stimulasi HCl pada eso-fagus. Disimpulkan bahwa asam esofagus menyebabkan hiper-eaktiviti saluran napas.9,22,27
3. Mikroaspirasi Pada mikroaspiragus, hipofaring, laring dan trakea menyebabkan respons
pada saluran napas.22 Mekanisme ini telah lama dikenal sebagai teori refluks.3-6,26 Pengamatan Tuchman dkk.dikutip dari 13,22 pada kucing memperlihatkan bahwa 10 ml asam esofagus menye-babkan peningkatan 1,5 kali tahanan paru total dibandingkan peningkatan hampir 5 kali lipat setelah pemberian 0,05 ml asam trakea. Selain itu terlihat hanya 60% dari binatang percobaan secara bermakna mempunyai peningkatan tahanan saluran napas setelah pemberian asam esofagus tetapi hal ini terlihat pada 100% binatang percobaan yang diberikan infus asam trakea.14,22 Jack dkk.dikutip dari 9,14,22 melakukan uji pH
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 32

esofagus dan trakea secara simultan pada 4 orang penderita asma berat. Selama pemantauan ditemukan 37 episode refluks esofagus terjadi dalam 5 menit dan 5 episode refluks ber-hubungan dengan penurunan pH trakea. Peak expiratory flow rates (PEFR) menurun 84 L/menit bila terdapat asam esofagus dan trakea dibandingkan hanya menurun 8 L/menit bila hanya ada asam esofagus.14,22
4. Inflamasi neurogenik Sebagian besar persarafan saluran napas dan esofagus me-
rupa
EJALA KLINIS ada (heartburn) merupakan gejala klasik
reflu
IAGNOSIS refluks gastroesofagus ditentukan dari gejala
dan
abel 1. Gejala klinis refluks gastroesofagus pada asma
ejala khas refluks gastroesofagus
n Geja
kan
Perb pada saat
berbaring Peng
Asm sa dengan refluks (RARS)
Dikutip dari (13)
eskipun begitu tidak ada satupun dari beberapa
y) fluks
gast
igunakan dalam diagnostik refluks gast
kan saraf afferen atau sensorik.9,28 Refluks gastroesofagus dapat secara langsung mengaktivasi saraf nosiseptif pada mukosa esofagus, laring ataupun saluran napas bawah. Aktivasi saraf afferen tersebut dapat menginduksi batuk, bronko-konstriksi, edema mukosa dan penarikan sel inflamasi. Bruce dan Lewis dikutip dari 28 menunjukkan aktivasi saraf afferen dapat mencetuskan inflamasi neurogenik. Proses tersebut terkenal sebagai refleks akson yang diperantarai oleh saraf afferen nosiseptif melepaskan neurotransmitter tachykinin dan men-cetuskan respons inflamasi.9,28 Tachykinin seperti substansi P dan neurokinin-A ada pada serat-C dari epitel, otot-otot kecil dan pembuluh darah jaringan ikat saluran napas.26,28-29 Pelepas-an tachykinin menyebabkan batuk, bronkokonstriksi, sekresi mukus dan peningkatan permeabiliti pembuluh darah saluran napas.9,26,28-29 Hamamoto dkk.29 meneliti ekstravasasi plasma saluran napas yang diinduksi oleh HCl esofagus pada guinea pig. Mereka menyimpulkan bahwa pemberian HCl intraeso-fagus menghasilkan pelepasan substansi seperti tachykinin yang menyebabkan ekstravasasi plasma saluran napas. G
Rasa panas di dks gastroesofagus yang disebabkan oleh kontak isi refluks
dengan radang mukosa esofagus.1,4,13,19,30 Gejala khas lain yang dapat timbul adalah regurgitasi ataupun disfagia.13,30 Manifes-tasi klinis lain (ekstraesofagus) yang dapat timbul antara lain batuk kronik, bronkokonstriksi, laringitis kronik, disfonia, sakit tenggorokan, suara parau dan nyeri dada yang tidak khas.1,13,30 Asma malam atau timbulnya batuk malam hari, rasa tercekik, mengi pada saat bangun tidur perlu dipikirkan terdapat refluks gastroesofagus pada saat tidur.2,13 Penderita asma dengan refluks gastroesofagus sering mengeluh sesak napas, napas pendek, mengi dan batuk setelah episode refluks, setelah makan makanan tinggi lemak, kopi, coklat, alkohol serta pada posisi telentang.7,31 Gejala refluks gastroesofagus sebagai pen-cetus asma perlu dipikirkan jika gejala asma yang timbul mungkin sulit dikontrol dengan obat-obatan asma yang biasa dipakai.13,31 Karakteristik asma yang dicetuskan oleh refluks antara lain timbul pada usia dewasa, bukan perokok, bukan tipe alergenik, gejala batuk menetap, lebih dominan pada malam hari, memburuk setelah makan, tidak respons dengan peng-obatan asma dan respons dengan pengobatan antisekretori.32 Gejala klinis refluks gastroesofagus pada penderita asma dapat dilihat pada tabel 1.13
D
Diagnosis tanda klinis, pemeriksaan fisik serta pemeriksaan pe-
nunjang.1,9 Gejala dan tanda klinis khas adalah rasa panas di
dada (heartburn), regurgitasi dan disfagia. Selain itu dapat di-jumpai gejala lain (ekstraesofagus) seperti yang telah disebut-kan sebelumnya.1,13,30 Pemeriksaan fisik tidak banyak memban-tu karena tidak didapatkan tanda yang spesifik.9 Pemeriksaan penunjang akan lebih memperjelas dalam menegakkan diag-nosis refluks gastroesofagus yang berkaitan dengan asma.3,7,9
T
G
Rasa panas di dada (heartburn) Water brash Regurgitasi Nyeri menelala tidak khas Rasa tercekik Nyeri leher
Nyeri telingaSakit tenggoroSuara parau Nyeri dada
aurukan asmTidur
MakanMinum alkohol Posisi telentang/gunaan obat-obat bronkodilator Teofilin
adrenergik sistemik Agonis β-a yang timbul pada usia dewa
Gejala pernapasan yang berhubunganSilent reflux
M pemeriksaan penunjang tersebut dapat menentukan secara pasti kejadian refluks gastroesofagus. Masing-masing pemeriksaan mem-punyai kelebihan dan kekurangan.20 Barish dkk. menyarankan suatu pendekatan untuk menegakkan diagnosis penyakit atau kelainan paru yang dicurigai terdapat refluks gastroesofagus (gambar 3).3 Beberapa pemeriksaan penunjang yang diguna-kan untuk membantu menegakkan diagnosis adalah : 1. Radiologi dengan barium (Barium esophagograph
Pemeriksaan ini dapat digunakan untuk mengetahui reroesofagus dengan diperlihatkannya gambaran aliran balik
barium ke dalam esofagus.20 Selain itu barium esophagography dapat menunjukkan gangguan motiliti esofagus dan terdapatnya hernia hiatus.13,20 Meskipun begitu pemeriksaan ini mempunyai peranan minimal dalam evaluasi refluks gastroesofagus karena terbatas kemampunnya mengidentifikasi refluks atau kelainan mukosa.1,20,30 Penelitian Mays dkk.dikutip dari 13 pada penderita asma dengan barium esophagography memperlihatkan 46% terjadi refluks dan 64% terdapat hernia hiatus. Dari suatu penelitian barium esophagography pada pasien dengan gang-guan saluran napas berulang ditemukan refluks hanya terjadi pada 40% kasus.20 Bahkan penelitian lain menunjukkan 80% kasus refluks tidak terdeteksi dengan pemeriksaan ini.13
2. Manometer esofagus Pemeriksaan ini tidak droesofagus. Cara ini berguna untuk mengetahui tekanan
LES pada keadaan istirahat dan keadaan gangguan peristaltik; biasanya untuk menentukan lokasi elektroda pada pemantauan
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 33

pH esofagus dan penilaian fungsi peristaltik sebelum operasi antirefluks.20,30 Refluks gastroesofagus dapat diduga dengan adanya penurunan tekanan LES atau motilitas abnormal dari esofagus. Pada suatu penelitian ditemukan rerata 69% anak-anak dengan penyakit paru berulang menderita abnormalitas tekanan LES dan motiliti esofagus.33. Endoskopi
Endoskopi tidak dapat digunakan untuk mendiagnosis reflu
auan pH esofagus memegang peranan penting
dala
ni menggunakan radionukleotid (Tc99m)-sulp
ENATALAKSANAAN atalaksanaan refluks gastroesofagus
pada
vatif meliputi : • tu tidur
refluks seperti
• n
batan yang mempengaruhi lambung r
dipe
gunaan obat-obatan digunakan untuk pengobatan
reflu
a terapi obat-obat
ks gastroesofagus, tetapi dapat digunakan untuk melihat efek kronik akibat refluks seperti esofagitis.1,3,13,20,30 Endoskopi dengan biopsi merupakan standar prosedur untuk melihat tipe dan luasnya kerusakan jaringan pada refluks.20,30 Diantara penderita asma anak didapatkan kekerapan esofagitis dengan endoskopi antara 60-72%.3,13 Sontag dkk.dikutip dari 7,13 menemu-kan esofagitis atau Barrett’s esophagus pada 42,5% dari 186 penderita asma dewasa yang dilakukan endoskopi. Nakase dkk.33 menemukan pada pemeriksaan endoskopi 72 penderita asma dewasa terdapat 27,8% mempunyai kerusakan mukosa esofagus. 4. Pemant
Pemantauan pH esofagus m diagnosis refluks gastroesofagus, terutama pada pende-
rita asma tanpa gejala klasik refluks atau mereka yang sulit untuk diobati.4,7 Sampai saat ini pemantauan pH esofagus merupakan standar baku untuk mendiagnosis refluks gastroeso-fagus dan untuk menentukan hubungan episode refluks dengan gejala klinis.3,4,7,13,15,20 Dalam keadaan normal pH esofagus antara 6 sampai 7, dengan didapatkannya penurunan pH di bawah 4 merupakan petanda terjadinya episode refluks.20 Gejala-gejala saluran napas yang timbul selama episode refluks atau dalam 10 menit setelahnya dipikirkan berhubungan dengan refluks yang mencetuskan gejala tersebut.13 Pemantau-an pH esofagus yang paling baik dengan hasil yang dapat dipercaya adalah selama 24 jam.19-20 Pemeriksaan ini dianjur-kan pada semua penderita asma yang sulit dikontrol atau menggunakan terapi prednison jangka panjang.4,7 Harding dkk.15 tahun 1999 melaporkan bahwa 72% penderita asma dengan gejala refluks mempunyai pH 24 jam abnormal. Sedangkan penelitian Sontag dkk.dikutip dari 9 dengan teknik yang sama menemukan abnormaliti asam esofagus pada 69% pen-derita asma dengan gejala refluks. Pemantauan pH 24 jam juga membantu menentukan hubungan gejala asma dengan episode refluks.7,13 Sontag dkk.dikutip dari 7 menilai 142 episode mengi pada 48 pasien dan menemukan 20% terjadi sebelum refluks, 15% selama refluks serta 10% setelah refluks. Terakhir, pe-mantauan pH esofagus dapat digunakan untuk menilai adekuat tidaknya pengobatan dengan supresi asam.7
5. Skintigrafi Pemeriksaan ihur colloid yang dimasukkan ke lambung sebelum tidur
dan dilanjutkan scanning paru keesokan harinya.3,20 Pemeriksa-an ini merupakan satu-satunya cara menilai refluks secara kuantitatif.19-20 Skintigrafi dapat menilai ada tidaknya aspirasi isi lambung ke dalam paru.3,20 P
Beberapa langkah pen
penderita asma yang dianjurkan adalah :1. Konservatif
3-4,7,19,31Terapi konserMeninggikan kepala 15 cm pada wak
• Tidak makan 3 sampai 4 jam sebelum tidur • Hindari makanan yang memperburuk gejala
kopi, coklat, bawang, minuman berkarbonat, alkohol dan produk tinggi lemak. Mengontrol berat bada
• Berhenti merokok • Mengurangi obat-o• Menggunakan antasida sesudah makan dan sebelum tidu
Terapi konservatif refluks pada penderita asma telahrkenalkan oleh William Osler hampir 1 abad yang lalu.32
Kjellen dkk.dikutip dari 32 meneliti pengaruh terapi konservatif refluks pada penderita asma. Pada penelitian tersebut 31 pen-derita asma dengan refluks diberikan terapi konservatif di-bandingkan dengan kontrol. Setelah 2 bulan terlihat gejala sesak napas, mengi, batuk dan ekpektorasi menurun 46-54% pada kelompok yang diobati dibandingkan kelompok kontrol hanya 4-6%. Penurunan penggunaan obat-obat asma terjadi pada 75% kelompok yang diobati dan 42% pada kelompok kontrol. Pada pengukuran fungsi paru tidak ditemukan per-baikan. 2. Peng
Berbagai obat-obatan telahks gastroesofagus. Obat-obatan tersebut adalah antasid,
asam alginat, cisaprid, antagonis reseptor-H2, dan proton pump inhibitor (PPI).9 Dapat diperkuat dengan menambahkan obat-obatan yang meningkatkan tekanan LES seperti bethanechtol atau metoklopropamid.dikutip dari 4 Pada suatu penelitian, 54% pasien menunjukkan perbaikan gejala asma setelah diberi pengobatan kombinasi antasid-alginat.7,13-16 Tucci dkk.dikutip dari
13-16,32 menggunakan pengobatan kombinasi cisaprid dan kon-servatif pada 27 anak dengan asma yang sulit dikontrol. Di-dapatkan perbaikan pada 83% dari 95% anak-anak yang diobati dan terdapat pengurangan penggunaan obat-obat asma. Erkstrom dkk.dikutip dari 16,32 meneliti 48 pasien dengan ranitidin 150 mg 2 kali sehari selama 4 minggu. Didapatkan penurunan yang bermakna gejala asma malam dan penurunan penggunaan agonis β-2 serta tidak terdapat perubahan bermakna parameter fungsi paru. Proton pump inhibitor (PPI) merupakan obat ter-baik untuk mengobati refluks gastroesofagus.4,7,13 Obat tersebut mampu menurunkan refluks asam > 80% dan menyembuhkan esofagitis 80-85% pasien.4,7 Harding dkk.8 meneliti 22 pen-derita asma dengan refluks gastroesofagus diberikan peng-obatan omeprazole 20 mg/hari selama 3 bulan. Pada penelitian tersebut ditemukan penurunan gejala asma sebesar 30% sete-lah 1 bulan pengobatan, 43% setelah 2 bulan pengobatan serta 57% setelah 3 bulan pengobatan (gambar 4).
Berbagai penelitian menunjukkan bahwan antirefluks mengurangi gejala asma, mengurangi peng-
gunaan obat-obatan asma tetapi mempunyai efek minimal atau bahkan tidak ada pada fungsi paru.16 Hal ini terlihat dari laporan terbaru Field dan Sutherland16 yang merangkum be-berapa tulisan dari data MEDLINE tahun 1966 sampai 1996 tentang asma dan terapi reluks gastroesofagus (tabel 2).
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 34

Hasilnya adalah 69% subjek mengalami perbaikan gejala dan pemakaian obat-obat asma berkurang pada 62% subjek. Nilai PEFR pagi hari membaik pada 26% dan tidak ada peningkatan
nilai spirometri pada semua penelitian.
Dikutip dari (3) Gambar 3. Algoritma pendekatan diagnostik penderita yang dicurigai refluks gastroesofagus menyebabkan penyakit paru.
Dikutip dari (8)
Gambar 4. Skor gejala asma setelah diberikan pengobatan dengan omeprazole 20 mg/hari selama 3 bulan.
3. Pembedahan Sontag dkk.dikutip dari 4,7,32 melakukan pembedahan anti-
refluks pada 13 penderita asma dengan refluks gastroesofagus. Hasil yang didapat adalah 6 penderita sembuh, 4 orang dapat berhenti menggunakan bronkodilator jangka panjang, 6 orang mengurangi pemakaian obat dan 1 orang tidak ada perubahan. Secara keseluruhan hasil pembedahan menunjukkan 34% penderita bebas dari gejala asma, 42% mengalami perbaikan dan 24% tidak berubah. Spivak dkk.dikutip dari 32 melaporkan pengamatan jangka panjang setelah pembedahan fundoplikasi pada 39 pasien asma dengan refluks gastroesofagus. Terdapat penurunan bermakna frekuensi eksaserbasi akut, perbaikan ge-jala batuk dan mengi yang bermakna serta perbaikan toleransi aktiviti fisik. Penggunaan bronkodilator dan korstikosteroid sistemik menurun serta 7 dari 9 pasien yang tergantung steroid dapat menghentikan penggunaannya setelah pembedahan.32
1. Barium Esophagogram 2. Endoskopi saluran cerna atas3. Manometer esofagus
Minimal 2 hasil pemeriksaan menunjukkan refluks
Tidak ada / hanya 1 hasil pemeriksaan menunjukkan refluks
Pemantauan pH esofagus 6-24 jam REFLUKS
Terapi dengan obat antirefluks
Bukan aspirasi
Respons baikRespons tidak adekuat
Foto toraks normal Respons tidak adekuat Foto toraks normal
Terapi diteruskan
Nilai fungsi paru sebelum dan sesudah uji provokasi asam intraesofagus
Skintigrafi untuk menilai aspirasi
Prosedur bedah antirefluks
Tidak dapat dianggap sebagai kelainan paru akibat refluks
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 35

Pembedahan antirefluks mungkin menghasilkan perbaikan gejala refluks, perbaikan gejala asma, pengurangan penggunaan obat-obat asma tetapi sedikit berpengaruh pada fungsi paru (gambar 5). Hal tersebut dilaporkan oleh Field dkk.34 yang menganalisis berbagai literatur MEDLINE dari tahun 1966 sampai 1998 dan menemukan 417 pembedahan dilakukan pada pasien asma dengan refluks gastroesofagus. Disimpulkan bahwa pembedahan antirefluks menghasilkan perbaikan gejala refluks 90%, perbaikan gejala asma 79%, perbaikan peng-unaan obat-obat asma 88% dan perbaikan fungsi paru hanya 27%.34 Penelitian tentang terapi obat-obat antirefluks diban-dingkan pembedahan antirefluks telah dilaporkan oleh bebe-rapa peneliti (gambar 6).7,14,32,34 Pada prinsipnya terapi obat-obatan yang optimal mungkin menghasilkan efek yang sama
dengan pembedahan antirefluks.32,34 Penelitian Sontag dkk.dikutip
dari 7,14,32 membandingkan pembedahan (fundoplikasi Nissen) dengan penggunaan obat ranitidin 150 mg 3 kali sehari pada penderita asma dengan refluks gastroesofagus. Gejala sembuh atau perbaikan terlihat pada 75% pasien yang dilakukan pem-bedahan, 9% pasien dengan obat ranitidin dan 4% pada kelom-pok kontrol. Larrain dkk.dikutip dari 7,14,32 membandingkan tindak-an gastropeksi posterior dengan simetidin 300 mg 4 kali sehari. Terdapat penurunan gejala mengi pada 77% yang dilakukan pembedahan, 74% yang menggunakan simetidin dan 36% pada plasebo. Gejala saluran napas menghilang pada 35% yang dilakukan pembedahan, 48% yang menggunakan simetidin dan 4% pada plasebo.
Tabel 2. Berbagai penelitian tentang terapi refluks gastroesofagus pada penderita asma dengan obat-obat antirefluks.
Referensi Terapi Jumlah subjek
Gejala refluks
Gejala asma
Penggunaan obat-obat
asma PEFR Spirometri
Kjellen dkk Goodall dkk Lamrain dkk Nagel dkk Gustafsson dkk Ekstrom dkk Harper dkk Tucci dkk Ford dkk Meier dkk Harding dkk Teichtahl dkk
Konservatif ; antasid/alginat Simetidin, 1 gr/hr – 6 mgg Simetidin, 1,2 gr/hr – 6 bln Ranitidin, 450 mg/hr – 7 hari Ranitidin, 300 mg/hr – 4 mgg Ranitidin, 300 mg/hr – 4 mgg Ranitidin, 300 mg/hr – 8 mgg Cisaprid, 0,2 mg/kg 4x/hr – 3 bln Omeprazole, 20 mg/hr – 4 mgg Omeprazole, 40 mg/hr – 6 mgg Omeprazole, 20-60 mg/hr – 3 bln Omeprazole, 40 mg/hr – 4 mgg
62 18 55 15 18 48 15 19 11 15 30 20
↓ ↓
TN Tp Tp ↓ ↓ ↓ Tp ↓ ↓ ↓
↓ ↓ ↓
Tp Tp ↓ ↓ ↓
Tp TN ↓
Tp
↓
Tp ↓
Tp Tp ↓
TN ↓
Tp TN Tp Tp
TN
↑ malam hari TN Tp Tp Tp TN TN Tp Tp Tp
↑ malam hari
Tp Tp Tp TN Tp Tp
Perbaikan TN TN Tp Tp Tp
Keterangan : Tp = tidak ada perubahan; TN = tidak dinilai ; ↓ = berkurang ; ↑ = meningkat
Dikutip dari (16)
Dikutip dari (34)
Gambar 5. Efek pembedahan antirefluks. Kotak hitam menunjukkan
jumlah pasien yang mengalami perbaikan dan kotak putih
perbaikan.
menunjukkan jumlah pasien yang tidak mengalami
Dikutip dari (7)
mbar 6. Hasil penelitian pembedahan antirefluks
gejal
Ga dibandingkan dengan obat.
Berbagai penelitian menganjurkan apabila curiga terdapat a refluks gastroesofagus yang menyebabkan serangan
asma dapat diberikan terapi percobaan selama 3 bulan yang mencakup tindakan konservatif, penggunaan obat-obat anti-
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 36

refluks dan evaluasi terapi.7,9,13-14 Secara jelas penatalaksanaan refluks gastroesofagus pada asma dapat dilihat pada gambar
7.14
Gambar 7. Algoritma pendek
KESIMPULAN
Refluks gastroesofanya serangan asma. Keasma sekitar 34-89%. Tasma dipengaruhi oleh dintratoraks dan intraabdohiatus dan penggunaan gastroesofagus menyebakarena refleks vagal, peaspirasi dan inflamasi ne
Diagnosis refluks gdari gejala dan tanda klinan penunjang. Refluks gperlu dipikirkan jika terdmengi dan batuk akibat ean tinggi lemak, kopi, cbaring. Kondisi tersebut sulit dikontrol dengan Pemantauan pH esofagmendiagnosis refluks ghubungan episode refluklaksanaan penyakit ini pembedahan. Obat-obat
Pasien asma dewasa dengan gejala refluks gastroesofagus (GER)
Cermin Dunia Kedo
Pasien asma dewasa tanpa gejala refluks gastroesofagus (GER) yang memakai kortikosteroid oral ATAU pasien asma persisten sedang-berat meskipun telah diterapi optimal
atan tatalaksana refluks gastroesofagus pada asma
gus berhubungan erat dengan timbul-kerapan refluks gastroesofagus pada imbulnya refluks gastroesofagus pada isregulasi otonom, perbedaan tekanan men, fungsi diafragma crural, hernia obat-obat asma. Patofisiologi refluks bkan bronkokonstriksi diperkirakan
ningkatan reaktivitas bronkus, mikro-urogenik. astroesofagus pada asma ditentukan is, pemeriksaan fisik serta pemeriksa-astroesofagus sebagai pencetus asma apat gejala sesak napas, napas pendek, pisode refluks, setelah makan makan-oklat, alkohol serta pada posisi ber-perlu juga dipikirkan jika gejala asma obat-obat asma yang biasa dipakai. us merupakan standar baku untuk
astroesofagus dan untuk menentukan s dengan gejala klinis asma. Penata-adalah konservatif, obat-obatan dan
antirefluks ataupun pembedahan dapat
measm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pemantauan pH esofagus 24 jam
pH + : Silent reflux
Perbaikan -> Lanjutkan terapi pemeliharaan anti refluks dengan : * Proton Pump
(Inhibitor (PPI) * Antagonis H2 * Obat prokinetik * Evaluasi untuk
pembedahan pada pasien tertentu
kteran No. 141, 2003
Sebelum terapi : Nilai APE, variabiliti APE,gejala asma, penggunaan obatasma dan spirometri
Terapi percobaan selama 3 bulan dengan : omeprazole 20 mg BID / Lanzoprazole 30 mg BID. Lanjutkan penilaian di atas
Tidak ada perbaikan ->Pemantauan pH esofagus24 jam selama terapiantirefluks
pH - : Asma tidak berkaitan dng refluks (GER)
pH - : Asma tidak berkaitan dng refluks (GER)
pH + : Tingkatkan terapi antirefluks atau rujuk ke ahli gastroenterologi
Dikutip dari (14)
ngurangi gejala asma, mengurangi penggunaan obat-obat a tetapi mempunyai efek minimal terhadap fungsi paru.
KEPUSTAKAAN
Caestecker J. ABC of the upper gastrointestinal tract. Oesophagus: heartburn. BMJ 2001; 323: 736-9. Gislason T, Janson C, Vermeire P, Plaschke P, Bjornsson E, Gislason D, et. al. Respiratory symptoms and nocturnal gastroesophageal reflux. A population-based study of young adults in three European countries. Chest 2002; 121: 158-63. Barish CF, Wu WC, Castell DO. Respiratory complication of gastro-esophageal reflux. Arch Intern Med 1985; 145: 1882-8. Martini T, Yunus F. Refluks gastroesofagus (Gastroesophageal reflux) pada asma. J Respir Indo 1997; 17: 202-5. Gastal OL, Castell JA, Castell DO. Frequency and site of gastroeso-phageal reflux in patient with chest symptoms. Chest 1994; 106: 1793-6. Castell DO, Schnatz PF. Gastroesophageal reflux disease and asthma. Reflux or reflex?. Chest 1995; 108: 1186-7. Harding SM, Richter JE. The role of gatroesophageal reflux in chronic cough and asthma. Chest 1997; 111: 1389-402. Harding SM, Richter JE, Guzzo MR, Schan CA, Alexander RW, Bradley LA. Asthma and gastroesophageal reflux:acid suppressive therapy improves asthma outcome. Am J Med 1996; 100: 395-405. Stein MR. Gastroesophageal reflux disease and asthma in the adult. Immunol Allergy Clin North Am 2001; 21: 449-71.
Field SK. Asthma and gastroesophageal reflux. Another piece in the
2

puzzle?. Chest 2002; 121: 1024-6. 11. Ing AJ. Asthma and gastroesophageal reflux. Available from URL :
http://members.ozemail.com. Accessed August 22nd 2002. 12. Field SK, Underwood M, Brant R, Cowie RL. Prevalence of gastro-
esophageal reflux symptoms in asthma. Chest 1996; 109: 316-22. 13. Simpson WG. Gastroesophageal reflux disease and asthma. Diagnosis
and management. Arch Intern Med 1995; 155: 798-803. 14. Harding SM. Gastroesophageal reflux and asthma:insight into the
association. J Allergy Clin Immunol 1999; 104: 251-9. 15. Harding SM, Schan CA, Richter JE. 24-h esophageal PH testing in
asthmatics:respiratory symptom correlation with esophageal acid events. Chest 1999; 115: 654-9.
16. Field SK, Sutherland LR. Does medical antireflux therapy improve asthma in asthmatics with gastroesophageal reflux? A critical review of the literature. Chest 1998; 114: 275-83.
17. Harding SM, Guzzo MR, Richter JE. The prevalence of gastroesophageal reflux in asthma patients without reflux symptoms. Am J Respir Crit Care Med 2000; 162: 34-9.
18. Sontag SJ, O’Connell S, Khandelwal S, Miller T, Nemchausky B, Schnell TG, et al. Most asthmatics have gastroesophageal reflux with or without bronchodilator therapy. Gastroenterology 1990; 99: 613-20.
19. Goyal RK. Diseases of the esophagus. In:Isselbacher KJ, Braunwald E, Wilson JD, Martin JB, Fauci AS, Kasper DL, editors. Harrison’s Prin-ciples of Internal Medicine. 13rd ed. New York:McGraw-Hill Interna-tional Book Company; 1994. p.1355-63.
20. Hegar B, Firmansyah A. Diagnosis refluks gastroesofagus pada anak. MKI 1999; 49: 70-5.
21. Lodi U, Harding SM, Coghlan HC, Guzzo MR, Walker LH. Autonomic regulation in asthmatic with gastroesophageal reflux. Chest 1997; 111: 65-70.
22. Harding SM. Gastroesophageal reflux, asthma and mechanisms of inter-action. Am J Med 2001; 111(suppl): 8-12.
23. Ekstrom TK, Tibbling LI. Can mild bronchospasm reduce gastro-esophageal reflux? Am Rev Respir Dis 1989; 139:52-5.
24. Lazenby JP, Guzzo MR, Harding SM, Patterson PE, Johnson LF, Bradley LA. Oral corticosteroids increase esophageal acid contact times in patients with stable asthma. Chest 2002; 121: 625-34.
25. Field SK. A critical review of the studies of the effect of simulated or real gastroesophageal reflux on pulmonary function in asthmatic adults. Chest 1999; 115: 848-56.
26. Ricciardolo FLM. Mechanisms of citric acid-induced bronchocontriction. Am J Med 2001; 111(suppl): 18-24.
27. Wu DN, Tanifuji Y, Kobayashi H, Yamauchi K, Kato C, Suzuki K, et.al. Effect of esophageal acid perfusion on airway hyperresponsiveness in patients with bronchial asthma. Chest 2000; 118: 1553-6.
28. Canning BJ. Role of nerves in asthmatic inflammation and potential influence of gastroesophageal reflux disease. Am J Med 2001; 111 (suppl): 13-7.
29. Hamamoto J, Kohgori H, Kawano O, Iwagoe H, Fujii K, Hirata N, et.al. The role of substance P release in the lung with esophageal acid. Am J Med 2001; 111(suppl):25-30.
30. Tierney LM, McPhee SJ, Papadakis MA, editors. Disease of the esophagus In:Current Medical diagnosis & treatment. 40th ed. New York:Lange Medical Books/McGraw-Hill; 2001. p.584-604.
31. Stephenson A. Gastroesophageal reflux and asthma. Available from URL: http://www.calgaryallergy.ca/Articles/Gastroesophagealreflux.htm. Accessed July 25th 2002.
32. Bowrey DJ, Peters JH, DeMeester TR. Gastroesophageal reflux disease in asthma. Effect of medical and surgical antireflux therapy on asthma control. Ann Surg 2000; 231: 161-72.
33. Nakase H, Itani T, Mimura J, Kawasaki T, Komori H, Tomioka H, et. al. Relationship between asthma and gastro-oesophageal reflux:significance of endoscopic grade of reflux oesophagitis in adult asthmatics. Journal of Gastroenterology and Hepatology 1999; 14: 715-22.
34. Field SK, Gelfand GAJ, McFadden SD. The effect of antireflux surgery on asthmatic with gastroesophageal reflux. Chest 1999; 116: 766-74.
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 38

TINJAUAN KEPUSTAKAAN
Imunoterapi pada Asma Alergi
Frans Abednego Barus, Wiwien Heru Wiyono, Faisal Yunus
Bagian Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/ Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta
PENDAHULUAN
Asma merupakan penyakit yang prevalensinya meningkat dari waktu ke waktu dengan sebab yang belum diketahui.1 Diperkirakan asma disandang oleh 100-150 juta jiwa di seluruh dunia. Permasalahan ini tidak hanya timbul di negara maju namun juga di negara berkembang.2 Di Amerika setiap tahun sekitar 1,5-2 juta kunjungan ke unit gawat darurat dan kasus asma akut mencapai 2,5-10% angka kunjungan di pusat ke-sehatan perkotaan.2 Asma ditandai dengan penyempitan saluran pernapasan yang berhubungan dengan hipereaktiviti otot polos dan inflamasi yakni hipersekresi mukus, edema dinding saluran pernapasan, deskuamasi epitel dan infiltrasi sel inflamasi.1-3 Asma dapat timbul pada berbagai usia dengan derajat yang berbeda dan dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Pengobatan asma terus berkembang untuk mengatasi penyakit ini tetapi angka kematian akibat penyakit ini terus mengalami peningkatan.2
Patogenesis asma sangat kompleks dan hanya sebagian yang sudah dimengerti. Secara umum asma dibagi menjadi 2 golongan yaitu asma alergi/atopi dan nonalergi dengan gambar-an patologi yang ditemukan tidak berbeda walaupun berbeda penyebabnya.4 Suatu pendekatan lain dalam mengontrol asma alergi selain menghindari pajanan alergi adalah dengan imuno-terapi alergen. Definisi imunoterapi alergen adalah pemberian berulang alergen spesifik pada keadaan atau penyakit yang diperantarai imunoglobulin E, yang bertujuan sebagai pence-gahan dan perlindungan dari gejala alergi dan reaksi inflamasi yang berhubungan dengan pajanan alergen.5 Banyak penelitian yang telah dikembangkan mengenai hal ini termasuk hasil imunoterapi, pengetahuan yang baik tentang mekanisme kerja dan pembuatan alergen yang lebih murni dan baik yang mem-buat peranan imunoterapi menjadi pertimbangan dalam penata-laksanaan asma alergi pada masa yang akan datang.6 SEJARAH
Pertama kali imunoterapi alergen dilakukan dan dilaporkan oleh Noon dan Freemandikutip dari 7 pada tahun 1910 yang mengu-raikan pembuatan ekstrak grass pollen dan disuntikkan dengan dosis yang meningkat pada penderita rhinitis alergi. Sejak itu
digunakan selama kurang lebih 90 tahun untuk mengobati penyakit alergi yang disebabkan oleh alergen inhalasi dan ternyata efektif pada rhinitis dan juga asma alergi, tetapi tidak diindikasikan pada alergi makanan.dikutip dari 7 Tahun 1918 Cooke dikutip dari 8,9 dari Amerika Serikat melaporkan suatu kondisi aler-gi seperti hay fever dan asma yang berasal dari antibodi yang timbul setelah pajanan agen sensitizing. Pada tahun 1922 ia mengemukakan metode hiposensitisasi untuk mengobati pasien alergi dan hal ini yang berkembang menjadi imunoterapi sampai saat ini. Sebelum itu, Prausnitz dan Kustner tahun 1921 dikutip dari 9,10 melakukan percobaan dengan menyuntikkan serum yang tidak dipanaskan dari donor alergi kepada resipien non-alergi (uji P-K). Mereka berhasil membuktikan bahwa individu alergi memiliki serum terhadap antigen spesifik (reagin) yang dapat dipindahkan secara pasif kepada individu non alergi. Cookedikutip dari 10 tahun 1935 mengemukakan konsep antibodi penghalang (blocking antibody) yang meningkat pada pemberi-an imunoterapi. Tahun 1967 pertamakali dikemukan nama im-munoglobulin E (IgE) oleh Ischikawa dan tahun 1977 Yungiger dan Gleich mengemukakan bahwa terjadi kenaikan titer IgE pada saat musim semi dan terjadi penurunan apabila musim tersebut berganti.dikutip dari 9 MEKANISME KERJA
Atopi adalah peningkatan sensitivitas sebagai hasil pening-katan antibodi IgE spesifik terhadap alergen lingkungan yang umum seperti tungau, serbuk sari atau bulu hewan. Pajanan berulang terhadap alergen secara bermakna akan meningkatkan prevalensi asma.11 Sembilan puluh persen penyandang asma anak dan 80% dewasa adalah atopi.11,12 Asma alergi/atopi ditandai dengan infiltrasi eosinofil dan sel T helper 2 (Th-2) ke mukosa bronkus, peningkatan antibodi IgE spesifik dalam sirkulasi, uji kulit positif dengan menggunakan alergen yang umum dan hipereaktivitas bronkus. Melalui Interleukin-4 (IL-4) dan IL-13, sel B akan distimulasi untuk menghasilkan IgE dan melalui IL-5 akan terjadi pertumbuhan, diferensiasi dan mobilisasi eosinofil ke saluran pernapasan pada pajanan ulang terhadap alergen. Interleukin-13 berperan sebagai regulator respons inlamasi dengan menghambat aktivasi dan penglepasan
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 39

sitokin inflamasi.12-14 Gambar 1 menunjukkan inflamasi alergi sebagai dasar patogenesis asma atopi.
Gambar 1. Skema proses inflamasi alergi. LTs, leukotrien; Eos, eosino-
fil; Bas, basofil Dikutip dari (12)
Mekanisme kerja imunoterapi terhadap asma atopi masih
merupakan hipotesis.7 Efek imunologis yang terjadi setelah pemberian imunoterapi adalah sebagai berikut:7,12,15-18
1. Antibodi penghalang Imunoterapi akan menginduksi IgG spesifik alergen (IgG4) yang berperan sebagai antibodi penghalang yang bersaing dengan IgE untuk berikatan dengan alergen. Sejumlah studi mengemukakan bahwa terbukti ada hubungan antara pengurangan gejala alergi dengan jumlah IgG serum
2. Penurunan IgE Penurunan secara bertahap IgE spesifik alergen pada pemberian imunoterapi, walau pada awalnya terjadi peningkatan. Respons Th2 terhadap alergen akan dihambat dan menginduksi respons Th1 dengan peningkatan inter-feron γ (IFN-γ) dan IL-12. Perubahan fungsi ini akan mempengaruhi produksi IgE, pematangan populasi sel, penglepasan mediator oleh sel mast dan basofil sehingga akhirnya akan menurunkan respons alergi.
3. Modulasi sel mast dan basofil Imunoterapi memodulasi fungsi sel mast dan basofil se-hingga terjadi penurunan penglepasan mediator walaupun terdapat IgE spesifik pada permukaannya. Efek ini ditun-jukkan dengan penurunan penglepasan histamin pasca-imunoterapi setelah pajanan alergen spesifik yang di-dahului oleh penurunan IgE spesifik atau peningkatan IgG spesifik.
4. Peningkatan aktivitas limfosit T supresor Imunoterapi akan mengubah jaringan kerja pengaturan sel oleh karena peningkatan aktivitas limfosit T supresor. Produksi IgE, pematangan sel mast, aktifasi makrofag, penglepasan mediator oleh sel mast dan basofil akan ber-kurang dan mempengaruhi mekanisme alergi. Gambar 2 menerangkan secara skematis mekanisme kerja
imunoterapi dalam imunopatogensis asma.
Gambar 2. Mekanisme kerja imunoterapi
Dikutip dari (15) INDIKASI DAN KONTRAINDIKASI
Menurut panduan Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA)19 yang dirumuskan oleh 34 ahli yang bertemu pada bulan Desember 1999 di Jenewa, indikasi imunoterapi adalah untuk penyandang rhinitis atau asma alergi yang di-sebabkan oleh alergen spesifik. Alergen yang diberikan ter-sebut telah dijamin efektivitas dan keamanannya melalui penelitian klinis.19 Imunoterapi juga diindikasikan sebagai pro-filaksis untuk pasien yang sensitif terhadap alergen selama musim pollen atau perrenial.20 Penyandang asma yang di-maksud adalah penyandang asma derajat ringan-sedang dan gejalanya dapat berkurang dengan pengobatan atau sudah ter-kontrol dengan farmakoterapi.21,22
Sedangkan kontraindiikasi relatif imunoterapi pada asma adalah sebagai berikut: 18,23
1. penyakit imunopatologik seperti pneumonitis hipersensitif termasuk aspergilosis bronkopulmoner alergi 2. keadaan imunodefisiensi yang berat 3. keganasan 4. kelainan psikiatri yang berat 5. pengobatan dengan penyekat beta, karena reaksi anafilak-sis keadaan akan memberat dan sulit diatasi dengan cara konvensional 6. pasien tidak patuh 7. pasien mengalami efek samping yang berat yang berulang selama terapi 8. asma berat yang tidak terkontrol dengan farmakoterapi 9. obstruksi kronik saluran pernapasan dengan volume eks-pirasi paksa detik 1 (VEP1) < 70% prediksi walaupun telah mendapatkan farmakoterapi yang optimal 10. pasien dengan penyakit kardiovaskular berat yang disebab-kan oleh efek anafilaksis terhadap miokardium. Hipotensi dan vasokontriksi pulmoner akan menambah beban jantung juga perfusi miokardium sendiri akan berkurang
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 40

11. anak dibawah usia 5 tahun, untuk menghindari kesulitan penatalaksanaan pasien pada saat terjadi reaksi anafilaksis 12. usia tua, karena efek samping imunoterapi terhadap sistem kardiovaskular dapat ireversibel 13. keadaan hamil sebaiknya tidak dimulai imunoterapi, akan tetapi bila imunoterapi telah dilakukan sebelum kehamilan, maka dapat diteruskan.
Pertimbangan untuk memulai imunoterapi dapat dilihat dari tabel 1. Tabel 1. Pertimbangan untuk melakukan imunoterapi. Penyakit yang terbukti diperantarai IgE
Uji kulit positif dan/atau peningkatan IgE spesifik serum Terdapat riwayat sensitivitas spesifik sehingga menimbulkan gejala
Pajanan alergen (didapat dari uji alergi) yang berhubungan dengan gejala Bila perlu, dilakukan provokasi dengan menggunakan alergen yang berhubungan
Pajanan terhadap pencetus lain mungkin berhubungan dengan gejala Derajat berat dan lama gejala
Gejala subyektif Parameter obyektif seperti absen dari pekerjaan atau sekolah Faal paru: bukan derajat asma berat Pemantauan faal paru dengan menggunakan peak flow rate meter
Respons terhadap terapi nonimunologik
Respons terhadap penghindaran pajanan alergen Respons terhadap farmakoterapi
Ketersediaan vaksin dengan kualitas baik terstandar Kontraindikasi relatif
Pengobatan dengan penghalang β Penyakit imunologik lain Ketidakmampuan pasien untuk patuh
Faktor sosiologi
Biaya Pekerjaan Kualitas hidup tidak meningkat walau telah mendapat pengobatan adekuat
Bukti obyektif efikasi imunoterapi yang dilakukan kepada pasien tertentu (memiliki studi klinik terkontrol)
Dikutip dari (21) BENTUK DAN CARA PEMBERIAN
Keputusan untuk memberikan imunoterapi berdasarkan kriteria pemilihan pasien yang tepat, antigen yang tepat dan dilakukan hanya oleh tenaga medis yang telah mendapat pe-latihan dan pengalaman dalam bidang asma dan imunoterapi.11 Untuk persiapan pasien dapat mengikuti petunjuk di bawah ini:18
a. identifikasi pasien, kehadiran, memanggil nama lengkap dan mencocokkan tanggal lahir atau nomor pasien b. tanyakan pada pasien apakah gejala asma telah terkontrol c. tanyakan pada pasien apakah terjadi reaksi pada pemberian terakhir d. terapkan aturan “3 benar”, yaitu :
• kartu (chart) yang benar • antigen benar • pasien benar
e. triple check antigen, yakni : • label, nama pasien • isi • pengenceran • tanggal kadaluarsa • tanggal penyuntikan terakhir
Sebelum melakukan imunoterapi, harus memenuhi syarat se-bagai berikut:11,24,25
1. observasi pasien dalam 15 menit dan lakukan spirometri atau pengukuran arus puncak ekspirasi (APE). Bila hasil peng-ukuran 20% di bawah nilai tertinggi yang pernah dicapai maka penyuntikan imunoterapi tidak dilakukan. 2. petugas pelaksana memahami :
a. cara penyesuaian dosis untuk meminimalkan reaksi b. cara penatalaksanaan reaksi lokal dan sistemik c. telah mendapat pelatihan resusitasi jantung paru
3. memiliki alat resusitasi termasuk stetoskop, sfigmomano-meter, turniket, jarum suntik, epinefrin, antihistamin, steroid, oksigen, oral airway, cairan intravena, set infus, set trakeos-tomi, nebulizer dan obat bronkodilator inhalasi. Ekstrak alergen inhalasi
Diberikan dengan cara suntikan subkutan pada regio deltoid secara bergantian pada periode imunoterapi. Dengan menggunakan semprit 0,5-1,0 ml untuk pengukuran yang akurat jumlah antigen yang masuk dan jarum 27G untuk ke-nyamanan pasien. Jarum disuntikkan dan setelah masuk pada posisi subkutan jarum diaspirasi. Apabila darah teraspirasi maka semprit tersebut harus dibuang dan prosedur dimulai lagi dari awal. Semprit yang digunakan harus berbeda untuk setiap pasien untuk mencegah penularan penyakit infeksi. Setelah penyuntikan pasien diminta menunggu selama 20-30 menit untuk mengantisipasi reaksi sistemik yang mungkin muncul dalam periode tersebut. Pasien dengan derajat hipersensitivitas tinggi harus diobservasi selama 30 menit atau lebih.18 Lakukan penilaian ulang spirometri atau APE 30 menit setelah suntikan dan bila terjadi penurunan 10% akan menjadi dasar untuk mengurangi dosis pada suntikan berikutnya.11
Ekstrak alergen dapat diberikan secara tunggal atau di-campur (idealnya kurang dari 10 jenis alergen), akan tetapi campuran ini akan mengencerkan kadar setiap alergen dan dapat mengurangi respons terhadap imunoterapi.17,18 Jenis alergen yang diberikan tergantung penilaian klinisi didasarkan pada jenis alergen yang memberi hasil positif pada uji kulit dan yang menimbulkan gejala klinis bila terpajan. Jenis alergen yang dapat diberikan secara injeksi subkutan adalah bermacam jenis serbuk sari (pollen), tungau debu rumah dan bulu kucing.dikutip dari 7
Imunoterapi dapat diberikan satu sampai dua kali seming-gu dengan dosis awal dimulai dengan 0,05 ml alergen konsen-trasi 1:10.000 sampai 1:1.000.000 berat/volume (wt/vol) diting-katkan sampai tercapai dosis pemeliharaan yaitu 0,05 ml alergen konsentrasi 1:100. Lama penyuntikan 6-10 bulan untuk
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 41

mencapai dosis pemeliharaan.26 Dosis pemeliharaan diberikan dalam interval 2-4 minggu selama 3-5 tahun dan berdasarkan penelitian, cukup untuk memberikan perlindungan jangka pan-jang pada hampir semua pasien (cara lambat).11,18,26 Imuno-terapi dengan durasi yang lebih panjang ternyata tidak ber-guna.26
Pemberian imunoterapi dengan cara cepat menurut Dina Mahdi, dilakukan dengan menyuntikkan alergen 4 kali sehari dengan interval 1/2 jam dan diulang setelah 2 minggu. Respons antibodi yang diinginkan terjadi setelah 5 kali kunjungan.dikutip
dari 20 Cara Cluster merupakan modifikasi cara lambat dan cepat dengan memberikan 2-4 kali suntikan dalam sehari, diulang setelah 1-2 minggu sampai dosis maksimal dan dipertahankan dengan dosis pemeliharaan.dikutip dari 20 Seluruh tindakan dicatat dalam kartu jadwal imunoterapi seperti gambar 3.
Tanggal Konsentrasi
ekstrak Wt/vol
Konsentrasi ekstrak Protein Nitrogen Unit
(PNU)/ml Volume Catatan
1 : 10.000 100 0,05 0,10 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 1 : 1000 1000 0,05 0,10 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 1:100 10.000 0,05 0,10 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 Gambar 3. Contoh kartu jadwal imunoterapi ekstrak alergen inhalasi.
Dikutip dari (18)
Local nasal aeroallergen immunotherapy Merupakan bentuk imunoterapi alternatif yang mengguna-
kan larutan alergen yang disemprotkan ke mukosa hidung dengan interval waktu tertentu. Efek samping lokal yang timbul berupa pruritus, kongesti dan bersin. Belum ada penelitian yang merekomendasikan bentuk ini sebagai salah satu imunoterapi.18
Alum-precipitated allergen extracts
Adalah modifikasi ekstrak alergen cair dengan melakukan presipitasi protein dengan menggunakan aluminium hidroksida yang didahului dengan ekstraksi alergen dengan piridin untuk menghasilkan efek sistemik yang lebih sedikit. Dengan demi-kian dimungkinkan untuk memberikan imunoterapi dengan peningkatan dosis yang lebih cepat sehingga mengurangi jumlah suntikan. Contoh ekstrak piridin alum-precipitated pada rumput terbukti efektif tetapi pada ragweed akan mengalami denaturasi sehingga efektivitasnya berkurang.17-18
Ekstrak alergen dimodifiksi Agregasi protein dan ekstrak alergen cair akan mengurangi
sifat alergen sedangkan imunogenisitasnya dapat dipertahan-kan. Terdapat dua metode modifikasi yaitu formalin-treated allergen (allergoids) dan glutaraldehyde-treated allergen (polymerized allergen extracts). Regimen ini memungkinkan program imunoterapi diselesaikan 10-15 kali suntikan dengan efek samping reaksi sistemik kurang dari 1%.17,18
Imunoterapi sublingual/oral
Sebagai alternatif pemberian imunoterapi yang lebih aman dan nyaman bagi pasien adalah ekstrak tumbuhan yang di-campur dengan alergen dan diberikan secara oral atau sub-lingual. Beberapa studi menyebutkan keberhasilan imunoterapi pada rhinitis alergi. Cara kerja imunoterapi sublingual adalah dengan mengubah respons limfosit T terhadap alergen.27,28 Pemberian imunoterapi sublingual ternyata lebih hemat, lebih aman dan nyaman bagi pasien serta tidak memerlukan supervisi medis dalam pelaksanaan tetapi efektifitinya lebih rendah dari-pada imunoterapi suntikan.28 Andre dkk29 melakukan penelitian terhadap 690 subyek dengan rhinokonjungtivitis dengan atau tanpa asma selama 2 bulan - 4 tahun, menyimpulkan tidak ada efek samping serius pada pemberian imunoterapi sublingual kepada anak dan dewasa penyandang rhinitis alergi dan asma sedang. Penelitian LaRosa dkk30 pada 41 anak penyandang rhinokonjungtivitis alergi, menyimpulkan bahwa imunoterapi dengan alergen ekstrak Parietaria judaica sublingual dengan dosis 375 kali dosis suntikan secara bermakna menurunkan gejala rhinitis. Diperlukan penelitian yang lebih jauh untuk mengevaluasi keberhasilan imunoterapi sublingual.27-30
EFEK SAMPING DAN PENATALAKSANAANNYA
Alergen yang diberikan kepada penyandang asma alergi biasanya sudah dibuktikan terlebih dahulu dengan uji tusuk kulit (skin prick test), sehingga besar kemungkinan terjadi efek samping. Efek samping yang paling sering adalah manifestasi sistemik hipersensitivitas seperti serangan asma, urtikaria, spasme laring, hipotensi dan angioedema.18,31 Faktor risiko yang umum adalah penyandang asma, riwayat peningkatan dosis alergen, efek samping sebelumnya dan penyuntikan di-lakukan pada musim parenial. Beberapa studi menganjurkan premedikasi dengan antihistamin atau kortikosteroid, peng-ukuran APE sebelum penyuntikan dan penyuntikan anti-histamin atau epinefrin setelah imunoterapi untuk mencegah reaksi dan meningkatkan keamanan imunoterapi.31 Reaksi fatal yaitu kematian menurut The American Academy of Asthma, Allergy and Immunology18 tahun 1900-1991 sebanyak 10 kasus sedangkan di Inggris25 tahun 1986 sebanyak 26 kasus. Biasanya reaksi sistemik terjadi dalam 20-30 menit sedangkan reaksi lambat dapat terjadi 6 jam setelah penyuntikan imunoterapi.25,31 Imunoterapi dengan cara sublingual atau oral juga memiliki efek samping yang dapat dilihat pada tabel 2.
Selain efek sistemik yang telah diuraikan di atas dapat terjadi efek samping lokal dan reaksi vasovagal. Reaksi lokal yaitu kemerahan dan pembengkakan pada tempat suntikan yang menimbulkan sedikit keluhan. Pengobatannya dengan melakukan kompres dingin, pemberian antihistamin oral dan
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 42

Tabel 2. Efek samping imunoterapi sublingual pada anak.
Efek samping Imunoterapi Plasebo Anafilaksis Mulut gatal Pembengkakan bibir Keluhan gastrointestinal Konjungtivitis Rhinitis Serangan asma ringan Serangan asma berat Gatal yang menyeluruh
0 3 2 19 1 1 0 0 1
0 2 2 1 1 1 1 1 1
Total 27 10
Dikutip dari (30) pengurangan dosis. Reaksi vasovagal meliputi penurunan tekanan darah dengan perlambatan frekuensi nadi, kulit men-jadi dingin atau hangat disertai pengeluaran keringat tanpa timbul urtikaria atau angioedema. Reaksi vasovagal tidak me-merlukan pengobatan dan modifikasi dosis karena segera mem-beri respons dengan menelentangkan pasien.18 Penanganan
reaksi lokal dan sistemik dapat dilihat pada kedua bagan (Gambar 4 dan 5). PRO DAN KONTRA
Banyak studi yang melakukan penelitian efikasi imuno-terapi dalam tatalaksana asma alergi, walaupun demikian penggunaannya masih menjadi perdebatan.32 Hedlin dan kawan-kawan33 melakukan penelitian penggunaan imunoterapi pada asma alergi dikombinasikan dengan inhalasi budesonid, mendapatkan penurunan bermakna derajat berat asma, hiper-sensitivitas alergen dan hipereaktivitas bronkus terhadap histamin dalam 3 tahun pengobatan. Penelitian pada penyandang asma dewasa dilakukan oleh Creticos dan kawan-kawan membandingkan imunoterapi raweed dengan plasebo. Hasil penelitiannya, terdapat per-bedaan bermakna pada kelompok imunoterapi daripada pla-sebo, yaitu nilai rerata APE yang lebih tinggi, penggunaan obat lebih sedikit, peningkatan IgG spesifik terhadap ragweed dan penurunan sensitivias terhadap ragweed baik dengan uji kulit maupun uji provokasi bronkus dalam 2 tahun pengobatan.34 Penelitian tersebut dipertanyakan oleh Barnes
Gambar 4. Skema penanganan efek samping lokal imunoterapi alergen suntikan
Dikutip dari (20) dengan mengemukakan bahwa penelitian tersebut tidak mem-bandingkan imunoterapi dengan obat asma, risiko efek samping imunoterapi yang lebih besar, ketersediaan kortikosteroid sebagai obat pengontrol asma yang lebih efektif, aman, relatif
lebih murah dan mudah.35 Durham dan kawan-kawan dalam randomized double blind
placebo-controlled trial (RCT) dengan menggunakan imuno-terapi grass pollen, mendapatkan setelah 4 tahun akan terjadi
Efek samping lokal
Segera Lambat
Bengkak < 5 cm
Bengkak 5-≤ 10 cm
Teruskan dosis
Bengkak ≤ 10 cm
Ulangi dosis akhir
Teruskan dosis Bengkak
> 10 cm Kurangi dosis sampai dosis yang dapat ditoleransi Bengkak
> 10 cm
Berikan antihistamin Observasi sedikitnya 60 menit
Ulangi Dosis
yang sama
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 43

penurunan skor gejala klinik asma dan perubahan respons imunologi tetapi tidak terdapat perbedaan bermakna untuk jangka waktu yang lebih lama.36 Penelitian ini ditanggapi oleh Robinson dengan mengatakan bahwa hasil imunoterapi tersebut
hanya sedikit meningkatkan nilai APE dan tidak lebih baik daripada penggunaan kortikosteroid atau terapi konvensional asma.16
Gambar 5. Skema penanganan efek samping sistemik imunoterapi alergen suntikan
Dikutip dari (20)
Badan kesehatan dunia (WHO) merekomendasikan pem-berian imunoterapi dengan ketentuan sebagai berikut:37
44
1. imunoterapi sebagai terapi tambahan selain menghindari pajanan alergen dan sebagai pengobatan pasien rhinitis yang diinduksi alergen 2. imunoterapi harus dimulai sejak dini untuk mengurangi risiko efek samping dan untuk mencegah perkembangan pe-nyakit menjadi lebih berat. Argumen untuk melakukan imuno-terapi adalah sebagai berikut : • respons terhadap farmakoterapi tidak maksimal • terjadi efek samping obat • penolakan tatalaksana dengan menggunakan farmako-terapi
3. imunoterapi spesifik secara injeksi (subkutan) dapat di-gunakan pada rhinitis berat dan berkepanjangan (biasanya berhubungan dengan asma) 4. imunoterapi spesifik secara lokal (intranasal dan sub-lingual-oral) dapat digunakan pada pasien tertentu dengan riwayat terjadi efek samping dan menolak suntikan.
Dari beberapa studi metaanalisis yang pernah dilakukan mendapatkan hasil yang bervariasi. Portnoy melakukan dua metaanalisis untuk mengidentifikasi efikasi imunoterapi dan menyatakan dalam kesimpulannya, bahwa terdapat kegagalan untuk menunjukkan efek terapeutik imunoterapi karena hasil-nya bervariasi yang disebabkan heterogeniti setiap uji klinik. Perbedaan tersebut meliputi seleksi subyek, populasi, protokol
Reaksi Sistemik
Reaksi umum Syok anafilaksis
Asma, rhinitis, eksim, urtikaria, angioedema
Gejala dini syok : Tenggorokan gatal,
telapak tangan, kaki dan seluruh tubuh dingin
Segera/ lambat
Timbul beberapa
Tanpa asma : - adrenalin subkutan:
dewasa: 0,5 ml anak: 3 tahun 0,2 ml 10 tahun 0,4 ml
- hidrokortison dosis 100-1000 mg iv/im (dewasa=anak)
- antihistamin oral/iv - monitor tanda vital warna kulit, faal paru Dengan asma : - agonis β-2, aerosol/nebulisasi - teofilin 5 mg/kgBB (10-15 menit) - oksigen 2 l/menit
- Segera injeksi 0,3-0,5 ml adrenalin 1:1000 subkutan. Ulangi 15 menit Jika perlu ulangi 15-30 menit
- Posisi terlentang, trendelenberg, bebaskan saluran pernapasan
- Turniket proksimal tempat suntikan, tiap 10-15 menit longgarkan
- Infiltrasi intradermal dengan 0,2 ml adrenalin di sekitar lokasi
- Infus dextrose 0,5% - Pertimbangkan rawat inap
Kurangi dosis sampai
dosis terakhir yang
Stop imunoterapi
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003

pengobatan, efek pengobatan yang dilakukan secara con-comitant atau concurrent, durasi pengobatan dan follow up.32
Abramson dan kawan-kawan melakukan metaanalisis ter-hadap 20 RCT tentang penggunaan imunoterapi pada asma. Mereka mendukung imunoterapi sebagai terapi tambahan asma alergi, walaupun harus ada panduan yang harus diikuti. Faktor yang harus diperhatikan adalah penilaian risiko, kontraindikasi, penilaian awal, supervisi ketat seorang konsultan, follow up dilaksanakan dengan baik, ketersediaan ekstrak alergen yang spesifik dan efektif serta fasilitas dan sumber daya yang me-ngerti pengelolaan efek samping yang timbul.6 Pengkajian ter-hadap data studi metaanalisis Abramson tersebut dilakukan oleh Finegold dan menyimpulkan imunoterapi pada asma merupakan pengobatan yang efektif namun perlu pertimbangan sebagai yang utama dalam pengobatan asma alergi.38
KESIMPULAN 1. Mekanisme kerja imunoterapi adalah memberikan efek imunologi yaitu menginduksi antibodi penghalang yang ber-saing dengan IgE, menurunkan IgE, memodulasi sel mast dan basofil dan peningkatan aktivitas limfosit T supresor, sehingga terjadi penurunan respons alergi. 2. Indikasi imunoterapi adalah penyandang rhinitis dan asma alergi derajat ringan sedang yang sudah terkontrol. 3. Imunoterapi alergen diberikan dengan cara suntikan sub-kutan tetapi disamping itu ada cara lain yang relatif lebih aman dan mudah yaitu lokal nasal dan sublingual-oral. 4. Penggunaan imunoterapi sebagai pengontrol dalam tata-laksana asma masih menjadi kontroversi karena penggunaan steroid inhalasi masih lebih efektif dan memberikan hasil yang baik. Selain itu imunoterapi direkomendasikan sebagai tambah-an bukan sebagai yang utama dalam penatalaksanaan asma.
KEPUSTAKAAN 1. Lemanske RF Jr, Busse WW. Asthma. JAMA 1997;278:1855-73. 2. Brenner B. Asthma. Available at: http://www.emedicine.com/emerg/
topic43.htm. Accessed October 24, 2000. 3. McConnell W, Holgate S. The definition of asthma: its relationship to
other chronic obstructive lung disease. In: Clark TJH, Godfrey S, Lee TH, Thomson NC, eds. Asthma, 4th ed. London: Arnold; 2000.p. 1-31.
4. National Institute of Health National Heart, Lung and Blood Institute. Definition. In: Global initiative for asthma, 2002 (revised).p. 1-7.
5. Condemi JJ, Dykewicz MS, Fineman SM, Hannaway PJ, Lockey RF, Nicholas SS et al. Practice parameters for allergen immunotherapy. J Allergy Clin Immunol 1996; 98: 1001-11.
6. Abramson MJ, Puy RM, Weiner JM. Is allergen immunotherapy effective in asthma? A meta-analysis of randomized controlled trial. Am J Respir Crit Care Med 1995; 151: 969-74.
7. Palilingan JF. Dasar-dasar imunoterapi alergen. Dalam: Margono B, Widjaja A, Amin M, Sargowo Dj, Saleh WBMT, Kabat H dkk, editor. Proceeding Book Pertemuan Ilmiah Paru Milenium. Surabaya, 2002.
8. Finegold I. Immunotherapy historical prespective. Ann Allergy Asthma Immunol 2001; 87(Suppl): 3-4.
9. Norman PS. Immunotherapy: past and present. J Allergy Clin Immunol 1998; 102: 1-10.
10. Platts-Mills TAE, Mueller GA, Wheatley LM. Future direction for allergen immunotherapy. J Allergy Clin Immunol 1998;102:335-43.
11. Field PI, Gillis D. Specific allergen immunotherapy for asthma. MJA 1997; 167: 540-4
12. Creticos PS. The consideration of immunotherapy in the treatment of allergic asthma. Ann Allergy Asthma Immunol 2001; 87(Suppl): 13-27.
13. Humbert M, Menz G, Ying S, Corrigan CJ, Robinson DS, Durham SR et al. The immunopathology of extrinsic (atopic) and intrinsic (non-atopic) asthma: more similarities than differences. Review Immunology Today 1999; 11: 528-33.
14. Corry DB, Kheradmand F. Induction and regulation of the IgE response. Nature 1999; 402(Suppl): 18-22.
15. Durham SR, Till SJ. Immunologic changes associated with allergen immunotherapy. J Allergy Clin Immunol 1998; 2: 157-64.
16. Robinson DS. Allergen immunotherapy: does it work and, if so. How and for how long? Thorax 2000; 55(Suppl 1): S11-4.
17. Ledford DK. Immunotherapy: A practical review and guide. Efficacy of immunotherapy. Immunology and Allergy Clinics of North America 2000; 3: 35-57.
18. Tippet J. Allergen immunotherapy. Immunology and Allergy Clinics of North America 1999; 1: 129-48.
19. Lockey RF. “ARIA”: Global guidelines and new forms of allergen immunotherapy. J Allergy Clin Immunol 2001; 108: 497-9.
20. Moeliawan H. Imunoterapi praktis efek samping dan penanganannya. Dalam: Margono B, Widjaja A, Amin M, Sargowo Dj, Saleh WBMT, Kabat H dkk, editor. Proceeding Book Pertemuan Ilmiah Paru Milenium. Surabaya, 2002.
21. Bousquet J, Demoly P, Michel FB. Specific immunotherapy in rhinitis and asthma. Ann Allergy Asthma Immunol 2001; 87(Suppl): 38-42.
22. Manuhutu EJ. Imunoterapi pada asma alergi. Disampaikan pada Kongres Nasional Perhimpunan Dokter Paru Indonesia IX tanggal 8-11 Juli 2002 di Medan.
23. Moeliawan H. Imunoterapi pada asma bronkial di tahun 2002 dan di era mendatang. Dalam: Margono B, Widjaja A, Amin M, Sargowo Dj, Saleh WBMT, Kabat H dkk, editor. Proceeding Book Pertemuan Ilmiah Paru Milenium. Surabaya, 2002.
24. Georgitis JW. Immunotherapy and allergen avoidance for allergic airway disorders. Available at: http://www.chestnet.org/education/pccu/vol12/ lesson03.htm. Accessed July 28, 2000.
25. Lockey RF, Nicoara-Kasti GL, Theodoropoulos DS, Bukantz SC. Systemic reactions and fatalities associated with allergen immunotherapy. Ann Allergy Asthma Immunol 2001; 87(Suppl): 47-55.
26. Patterson R. The role of immunotherapy is respiratory allergic diseases. J Allergy Clin Immunol 1998; 101: S403-4.
27. Frew AJ, White PJ, Smith HE. Sublingual immunotherapy. J Allergy Clin Immunol 1999; 104: 267-70.
28. Frew AJ, Smith HE. Sublingual immunotherapy. J Allergy Clin Immunol 2001; 107: 441-4.
29. Andre C, Vatrinet C, Galvain S, Carat F, Sicard H. Safety of sublingual-swallow immunotherapy in children and adults. International Archives of Allergy and Immunology 2000; 121: 229-34.
30. LaRosa M, Ranno C, Andre C. Clinical and immunological effects of a rush sublingual immunotherapy to Parietaria species: a double-blind, placebo-controlled trial. J Allergy Clin Immunol 1999; 104: 425-32.
31. Greineder DK. Risk management in allergen immunotherapy. J Allergy Clin Immunol 1996; 98: S330-4.
32. Portnoy JM. Immunotherapy for asthma: unfavorable studies. Ann Allergy Asthma Immunol 2001; 87(Suppl): 28-32.
33. Hedlin G, Wille S, Browaldh L, Hildebrand H, Holmgren D, Lindfors A et al. Immunotherapy in children with allergic asthma: effect on bronchial hyperreactivity and pharmacotherapy. J Allergy Clin Immunol 1999; 103: 609-14.
34. Creticos PS, Reed CE, Norman PS, Khoury J, Adkinson NF, Buncher CR et al. Ragweed immunotherapy in adult asthma. N Engl J Med 1996; 334: 501-7.
35. Barnes PJ. Is immunotherapy for asthma worthwhile? N Engl J Med 1996; 334: 530-2.
36. Durham SR, Walker SM, Varga EM, Jacobson MR, O’Brien F, Noble W et al. Long-term clinical efficacy of grass-pollen immunotherapy. N Engl J Med 1999; 341: 468-75.
37. Bousquet J, Van Cauwenberge P, Khaltaev N. Alergic rhinitis and its impact on asthma. J Allergy Clin Immunol 2001; 108: S147-334.
38. Finegold I. Analyzing meta-analysis of specific immunotherapy in the treatment of asthma. Ann Allergy Asthma Immunol 2001; 87 (Suppl) : 33-7.
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 45

Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 46
TINJAUAN KEPUSTAKAAN
Peranan Magnesium pada Asma
Bambang Irawan Harsono, Faisal Yunus, Wiwien Heru Wiyono
Bagian Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/ Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta
PENDAHULUAN
Penyakit infeksi di Indonesia tetap menduduki peringkat teratas sebagai penyebab utama kesakitan dan kematian. Ber-bagai jenis antimikroba terbaru telah dikembangkan untuk mengatasinya. Sedangkan penanggulangan medik penyakit noninfeksi atau degeneratif seperti kanker paru, bronkitis kronik, emfisema dan asma saat ini semata-mata ditujukan pada peningkatan kualitas hidup dan bukan penyembuhan dalam arti sebenarnya.
Pasien asma sering dijumpai di beberapa rumah sakit baik di unit rawat jalan maupun gawat darurat.1 Survai kesehatan rumah tangga (SKRT) Departemen Kesehatan RI tahun 1986, 1992 dan 1995 memperlihatkan asma masih menduduki peringkat ke 3 dari 10 penyebab kematian utama di Indo-nesia.dikutip dari 1
Kejadian akumulasi asma berimbas pada beban pelayanan kesehatan masyarakat. Mark dan Burney tahun 1998 melapor-kan sejak tahun 1950 sampai dengan akhir abad duapuluhan, walaupun rerata angka kematian asma pada orang tua menurun, angka kematian karena asma pada orang muda tetap atau meningkat dengan beberapa epidemi. Harrison dan Smith (1971) melaporkan peningkatan prevalensi asma pada anak sekolah di Birmingham, Inggris tahun 1960-an. Studi lain memperlihatkan mengi merupakan suatu atopi jalan napas yang memberikan respons terhadap agen kolinergik, merokok dan elektrolit
Di Amerika Serikat asma anak sebanyak 4,8 juta merupa-kan penyakit kronik dengan peningkatan prevalensi sampai dengan 75 % dari tahun 1980 sampai dengan 1994. Peningkat-an kurang lebih 160 % pada anak 0 - 4 tahun, diiringi dengan peningkatan angka kesakitan dan kematian. Tahun 1980-1994 angka rerata perawatan rumah sakit penderita asma anak dari lahir hingga 4 tahun meningkat 47%, sementara angka kemati-an pada anak dan orang dewasa meningkat dua kali lipat dari 1975-1995.
Untuk pasien di instalasi gawat darurat (IGD) dengan serangan asma akut sedang sampai berat, National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) merekomendasikan penggunaan agonis β2 dan kortikosteroid sistemik. Beberapa percobaan
klinis memperlihatkan bahwa terapi agonis β2 dan kortiko-steroid sering tidak memuaskan sehingga memerlukan perawat-an rumah sakit. Sejumlah 31% anak-anak dengan serangan asma akut sedang sampai berat di IGD yang diterapi dengan prednison (19-50%), atau dengan nebulasi albuterol selama 4 jam tidak membaik sampai memerlukan perawatan rumah sakit; sehingga kelihatannya pasien tertentu dengan serangan asma akut sedang sampai berat mungkin memerlukan terapi tambahan.7
HOMEOSTASIS Mg
Magnesium merupakan salah satu kation esensial utama dalam kehidupan dan terlibat dalam reaksi enzimatik untuk sintesis protein; Mg juga berperan mempertahankan potensial listrik membran sel, dalam pembentukan ATP; proses sintesis dan replikasi asam ribonukleat - asam deoksiribonukleat secara absolut memerlukan Mg.2,15 Pengetahuan mekanisme homeos-tasis untuk mempertahankan konsentrasi Mg di serum sangat terbatas; faktor utama regulasi keseimbangan Mg adalah ab-sorpsi gastrointestinal dan ekskresi oleh ginjal. Pengetahuan tentang kontrol hormonal juga terbatas, beberapa penelitian menyatakan parathyrin berpengaruh terhadap homeostasis Mg; defisiensi Mg merupakan efek dari terganggunya sintesis atau pelepasan parathyrin. Pada hipomagnesemia terjadi peningkat-an konsentrasi parathyrin imunoreaktif serum setelah pemberi-an Mg.
Magnesium mungkin menurunkan neutrofil yang berhu-bungan dengan respons inflamasi pada asma dan juga men-stabilkan membran sel mast serta menghambat ion kalsium sebagai antagonis kompetitif.2 Mekanisme bronkodilatasi tidak diketahui, mungkin dengan menghambat kanal kalsium otot polos jalan napas serta menghalangi mediasi kalsium pada kontraksi otot. Magnesium juga menurunkan pelepasan asetil-kolin pada neuromuscular junction setelah stimulasi para-simpatis.8,17
Mg dalam tubuh manusia kurang lebih 0,33 mg/kg (1,32 mmol/kg), atau untuk dewasa rerata 24 gram. Orang dewasa sehat memerlukan 200-350 mg/hari. Sebagian besar (99%) di dalam ruang intraselular, kurang lebih dua pertiga terdapat di

tulang dan sisanya terdapat di otot dan jaringan lunak seperti di otot jantung, otot rangka dan hati.8 Magnesium serum seper-tiganya terikat dengan albumin, duapertiga dalam bentuk ultra-filtrable yang terdiri dari 80% dalam bentuk ion bebas, 20% berbentuk ikatan kompleks dengan fosfat, sitrat dan lain-lain.17 Berbeda dengan kalsium, homeostasis Mg tergantung asupan diet. Sistem regulasi Mg pada fungsi mobilisasi tulang dan sirkulasi tidak diketahui. Beberapa faktor yang menyebabkan berubahnya rasio Mg intraseluler dan ekstra-seluler antara lain asidosis dan iskemi, dan stimulasi reseptor alfa dan beta yang menyebabkan Mg keluar dari sel. Pada perawatan di ICU dapat terjadi pergeseran akut Mg di dalam sel, seperti pada sindrom refeeding, penggunaan insulin, infus glukosa dan asam amino.8 Sejumlah 65% pasien di unit perawatan intensif menderita hipomagnesemia.
Kadar Mg dalam tubuh diatur oleh ginjal dan saluran pen-cernaan serta menggambarkan keterlibatan metabolisme kalsi-um, kalium dan natrium. Kadar Mg intraseluler dapat rendah walaupun kadar Mg ekstraseluler normal.5 Hipomagnesemia ringan tidak menyebabkan kelainan patofisiologik yang ber-makna, jika berat akan tampak eksitabilitas neuromuskuler seperti tremor, twitching, seizures, tetani dan kelelahan otot termasuk otot pernapasan.19
ABSORPSI DAN ELIMINASI
Absorpsi Mg dilakukan di usus halus; yang diserap kurang lebih 24%-76%, dilakukan secara aktif mirip dengan sistem transpor Ca; pada pemberian Mg kadar rendah akan terjadi peningkatan absorpsi Ca. Ekskresi dilakukan di ginjal, kurang lebih 120-140 mg/24 jam pada orang dengan diet normal dan dalam keadaan tertentu ginjal dapat mensekresi sampai dengan 5000 mg/24 jam tergantung konsentrasi Mg plasma.17 Ginjal merupakan regulator utama konsentrasi serum dan kandungan total Mg tubuh. Magnesium difiltrasi oleh glomerulus dan dire-absorpsi di tubulus, 60-75% di tubulus asendens. Hipo-magnesemia dapat hanya sementara, mungkin disebabkan karena migrasi dari ekstraselular ke intraselular akibat turunnya konsentrasi ion Mg intraselular.27
Sumber Mg dari berbagai jenis makanan dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2. Sumber diet Mg
Sumber makanan Magnesium mg/100g Kacang-kacangan 200 Sereal belum diproses 66 Kacang polong 20 Sayuran 14 Produk susu 15 Air minum 30-90 (mg/liter) Daging 14-30
Dikutip dari (25)
HIPOMAGNESEMIA Beberapa pendapat tentang terjadinya hipomagnesemia
antara lain: − Belum dapat dijelaskan tetapi sebagian dikeluarkan oleh urin. − Penggunaan obat, misal agonis β, steroid, dan metilsantin. − Asupan yang rendah atau hilangnya Mg karena proses
memasak.20,21 Faktor-faktor yang berpengaruh pada reabsorpsi Mg dalam
tubuh dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1. Etiologi defisiensi magnesium
Renal Obat-obatan Diuretik, digoksin, amfoterisin-B,
aminoglikosid, cisplatin, siklosporin, albuterol dan agonis beta, diuretik loop dan tiazid, pentamidin, agen osmotik, alkohol, diabetes
Gastrointestinal Diare, emesis, penghisapan nasogastrik, short bowel syndrome, malabsorption syndrome, pankreatitis
Pergeseran intraseluler akut Refeeding syndrome, infus glukosa, infus asam amino, insulin, katekolamin, asidosis metabolik
Lain-lain Malnutrisi, nutrisi parenteral total, deplesi fosfor, alkohol, hungry bone syndrome, darah sitrat, hipotiroid, hiperkalsemia, cardiopulmonary bypass, ekspansi volume intravaskuler,hipoalbuminemia
Dikutip dari (20)
PEMAKAIAN MAGNESIUM PADA ASMA
Tradelenberg pertama kali memperkenalkan bahwa Mg mempunyai potensi sebagai bronkodilator dan tahun 1912 telah dicobakan pada sapi. Rosselo dkk. melaporkan pemberian Mg pada manusia penderita asma diharapkan dapat mengurangi gejala stridor dan dispnea. Penelitian selanjutnya menggunakan Mg pada pasien asma serangan ringan, sedang sampai berat dengan cara yang bervariasi dari intravena sampai dengan nebulasi. Fantidis dkk (1995) pertama kali melaporkan kadar Mg yang rendah di polimorfonuklear (PMN) pasien asma dibandingkan dengan kontrol.dikutip dari 3 Selain itu magnesium menyebabkan perubahan kapasitas volume paksa dan atau volume ekspirasi paksa detik pertama.4
Studi cross sectional memperlihatkan hubungan antara asupan rendah magnesium (Mg) dengan asma, dan pada pasien asma didapatkan kadar Mg intraselular rendah.dikutip dari 2
Magnesium merupakan obat standar untuk preeklamsi dan dianjurkan juga untuk berbagai masalah medis seperti aritmi jantung sampai migren. Pertama kali digunakan untuk peng-obatan asma tahun 1936 pada pasien rawat inap dengan asma berat yang tidak responsif dengan pengobatan standar masa itu seperti beladona (atropin) dan epinefrin.5 Hipomagnesemia pada penderita asma dan penderita asma kronik berhubungan dengan peningkatan perawatan di rumah sakit; asupan Mg yang rendah mungkin berperan dalam etiologi asma serta kejadian sekunder akibat penggunaan obat asma sendiri seperti agonis beta, steroid dan xantin.6 Beberapa pe-nelitian membuktikan bahwa pemberian MgSO4 iv. pada pasien asma yang tidak memberikan respons adekuat terhadap agonis beta, menghasil-kan perbaikan bermakna.7
Pasien dengan serangan asma akut sedang sampai berat yang tidak responsif dengan pengobatan standar, membutuhkan tambahan pengobatan, seperti Mg. Picado dkk dengan mem-berikan Mg peroral harian mendapatkan hasil tidak berbeda antara subyek sehat dengan pasien asmadikutip dari 9 sedangkan McKeever dkk (1991) menyatakan ada hubungan kuat antara
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 47

Mg dengan fungsi paru dan hiperresponsivitas saluran napas; pada tahun 2000 kembali ditemukan hubungan positif antara asupan magnesium dan fungsi paru.10 Ciaralo dkk mengguna-kan dosis 25 mg/kgbb. MgSO4 pada anak yang tidak responsif terhadap agonis β2 dan menghasilkan perbaikan ber-makna.dikutip dari 9 Studi nutrisi cross sectional memper-lihatkan hubungan antara asupan diet Mg dengan fungsi paru dan reakti-vitas bronkus.
Pemberian MgSO4 iv. pada pasien asma menyebabkan bronkodilatasi.11 Ada sembilan percobaan dari tahun 1989 sampai 1997. Empat percobaan menyatakan secara statistik tidak bermakna dan lima percobaan melaporkan perbaikan ber-makna; kesembilan percobaan ini melibatkan 859 pasien dengan hasil perkiraan target yang positif dan tidak ada efek samping yang berat 12
Magnesium bernomor atom 12 dan massa atom 24,32 Da merupakan kation ke 4 terbanyak dalam tubuh manusia dan ke 2 terbanyak di cairan ekstraseluler.16
Mg menyebabkan relaksasi sel otot polos, sedangkan hipo-magnesemia akan menyebabkan kontraksi otot polos. Pem-berian parenteral pada penderita asma serangan akut meng-hasilkan bronkodilatasi.2,3
Magnesium untuk terapi asma bukan suatu yang baru; efek relaksan Mg pada otot polos telah diperlihatkan pada trakea hewan percobaan yang diberi histamin (Hirota dkk). dikutip dari 8
Skobeloff dkk memperlihatkan perbaikan bermakna arus puncak ekspirasi dan menurunkan angka perawatan pada 38 pa-sien dengan eksaserbasi sedang sampai berat setelah pemberian 1,2 g MgSO4 pasca terapi agonis β2 dengan nebulizer. Bloch dkk. melaporkan peningkatan bermakna VEP1 pada menit ke 120 dan 240 dan perawatan di rumah sakit yang singkat (kurang lebih 33% dibanding 78%) pada penderita di unit gawat darurat dengan pemberian 2 g iv. sebagai terapi tambah-an; sedangkan Mills dkk melaporkan tambahan MgSO4 menghasilkan perbaikan bermakna pada pasien weaning dari ventilator mekanik setelah agonis β2, steroid dan teofilin hanya memberikan perbaikan minimal.dikutip dari 13
Efek langsung yang dikeluhkan pada pemberian Mg iv. adalah rasa panas dan tidak nyaman pada 3 dari 10 orang, tekanan darah turun dari 144/94 mmHg menjadi 102/85 mm-Hg, serta rasa lelah pada 1 dari 10 orang; setelah berbaring 5 menit hipotensi dan rasa lelah menghilang.14
Percobaan Noppen M dkk.20 memperlihatkan peran MgSO4 dalam pengobatan asma. Perubahan VEP1 selama infus MgSO4 dan inhalasi albuterol secara berurutan dapat dilihat perban-dingannya di Gambar 1. Infus MgSO4 sebelum inhalasi albu-terol meningkatkan bermakna nilai VEP1, menunjukkan Mg meningkatkan kerja agonis β2 pada penderita asma. Pada pasien terjadi perbaikan: sesak dan mengi berkurang. Tiga puluh menit setelah infus MgSO4 terjadi penurunan VEP1 pada seluruh pasien tetapi tidak mencapai nilai basal saat sebelum pemberian MgSO4. Inhalasi albuterol 30 menit setelah selesai infus MgSO4 menyebabkan peningkatan bermakna VEP1 pada seluruh pasien, peningkatan ini lebih tinggi lagi bila dilihat setelah pemberian MgSO4.20
Gambar 1. Perubahan VEP1 selama infus MgSO4 dan dilanjutkan pem-
berian inhalasi albuterol
Dikutip dari (20) MEKANISME INTERAKSI STRES, HORMON STRES DENGAN MAGNESIUM
Aktivasi sistem simpatis oleh stimulasi sensoris atau emosi seperti nyeri, lapar, rasa takut dan kemarahan meningkatkan ekskresi epinefrin dalam urin; dalam keadaan geram/marah, agresif akan dilepaskan terutama norepinefrin. Jantung juga mensintesis, menyimpan serta melepaskan norepinefrin. Isolasi atau keributan, latihan yang berlebihan, lingkungan yang dingin atau panas, bising, cahaya lampu, syok listrik, stimuli karena ansietas termasuk frustrasi, mendengar hal yang tidak menyenangkan akan menyebabkan peningkatan sekresi kateko-lamin oleh medula adrenal, saraf dan ganglia.22 Gambar 2 memperlihatkan mekanisme interaksi berbagai keadaan ter-hadap Mg karena stres psikologis, stres metabolis, trauma fisis dan stres lingkungan.
Hipomagnesemia terjadi pada pasien dengan kadar katekolamin darah yang tinggi; pemberian epinefrin pada suka-relawan dengan atau tanpa penghambat Ca sebelumnya akan menghasilkan Mg dan K serum yang rendah; pemberian epi-nefrin atau/dan terapi salbutamol menurunkan kadar Mg plas-ma pada subyek normal. Infus MgSO4 menghambat lepasnya katekolamin pada stres intubasi trakea dan pada atlet didapat-kan kadar Mg meningkat dalam sel darah merah. Pemberian suplemen Mg akan menurunkan ekskresi kortikosteroid. Ak-tivitas glukokortikoid dan mineralokortikoid menyebabkan ke-seimbangan Mg negatif dan mempengaruhi penyerapan Mg di usus halus.22
Penggunaan diuretik menyebabkan keluarnya Mg melalui urin dan menipisnya simpanan Mg total dan regional tubuh23,24 Inhalasi histamin menurunkan kadar Mg eritrosit (gambar 3), sedangkan Mg plasma tidak terpengaruh (kadar Mg plasma hanya 1%). Induksi histamin menurunkan kadar Mg dan tidak berhubungan dengan derajat hipereaktivitas bronkus. Peneliti lain berasumsi ketika terjadi bronkokonstriksi selama uji provokasi histamin, radikal bebas seperti hidrogen peroksida
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 48

Gambar 2. Berbagai keadaan yang menyebabkan defisiensi Mg dalam
tubuh. Dikutip dari (22)
(H2O2) dapat terlepas melalui direct action histamin terhadap reaksi enzimatik dan sel inflamasi atau indirect action me-lalui aktivasi C-fibres dan takikinin. H2O2 dapat melakukan aksi indirect trigger terhadap eritrosit (penghancuran Na+/Mg2+ ATPase antiport) menyebabkan keluarnya Mg.25,26
Gambar 3. Konsentrasi Mg dalam eritrosit, sebelum dan setelah provo-
kasi histamin. (1,84 fmol cell-1menjadi 1,78 fmol cell-1)
Dikutip dari(25)
Asma akut berhubungan dengan kadar Mg eritrosit yang rendah, sedangkan konsentrasi Mg plasma tidak berubah. Eleftherios dkk.26 mengatakan ketika terjadi bronkokonstriksi Mg keluar dari ruang intrasel dan secara alamiah mengatur calcium–channel blocker untuk selanjutnya menyebabkan re-laksasi otot polos saluran napas. Mekanisme pasti bronko-
dilatasi yang diinduksi Mg belum diketahui20. Agonis beta 2 (albuterol) dosis terapeutik dapat menurunkan konsentrasi Mg secara bermakna, mungkin disebabkan beta adrenergic-induced intracellular shift of Mg. Menormalkan konsentrasi Mg serum dan intraselular dapat dipertimbangkan sebelum pengobatan asma.
Dalam sistem neuromuskular, Mg secara langsung bersifat depresan otot rangka. Penambahan Mg akan menyebabkan penurunan lepasnya asetilkolin oleh impuls saraf, menurunkan sensitivitas motor end-plate terhadap asetilkolin serta menurun-kan amplitudo potensial motor end-plate. Magnesium pada fungsi neuromuskular bersifat antagonis terhadap Ca. Konsen-trasi Mg yang rendah pada cairan ekstraselular menyebabkan peningkatan asetilkolin dan meningkatkan perangsangan otot menyebabkan tetani.27
KESIMPULAN − Magnesium merupakan elektrolit esensial karena terlibat pada kurang lebih 300 reaksi enzimatik. − Magnesium terutama terdapat di intraselular (terutama tulang); hanya sedikit di ekstraseluler. − Berperan pada otot polos bronkus yang mempunyai sifat relaksan, berkompetisi dengan kalsium. − Penderita asma diduga memiliki kadar Mg intraselular rendah yang diperberat dengan penggunaan obat-obat asma. − Magnesium sulfat dapat dipakai sebagai terapi tambahan pada asma akut sedang sampai berat, yang tidak responsif dengan terapi standar.
KEPUSTAKAAN 1. Mangunnegoro H . Respirologi kini dan mendatang. Pros Temu Ilmiah
Respirologi 2001. Solo 24-25 Maret 2001. 1-17. 2. Burney PGJ. Epidemiology. In: Asthma. 4th ed. New York, Oxford:
University Press Inc., 2000. 197-217. 3. Fantidis P. Magnesium deficiency in bronchial asthma. Asthma and the
influence of magnesium. Available from http://www.Asthmaworld .org/mag.htm. Accesed 21/05/2002.
4. Bernstein WK, Khastgir T, Khastgir A et al. Lack of effectiveness of magnesium in chronic stable asthma. Arch Intern Med 1995; 155:271-6.
5. Silvermen R. The pathobiology of asthma: implications for treatment. Clin Chest Med, 2000; 21: 361-79.
6. Alamaodi OSB. Hypomagnesemia in chronic, stable asthmatics: pre-valence correlation with severity and hospitalization. Eur Respir J, 2000; 16: 427-31.
7. Scarfone RJ, Loiselle JM, Joffe MD, et al. A randomized trial of magne-sium in the emergency department treatment of children with asthma. Ann Emerg Med, 2000; 36: 572-8.
8. Murray PT, Corbrige T. Pharmacotherapy of acute asthma. In: Hall JB, Corbrige TC, Rodrigo C, Rodrigo GJ eds. Acute asthma assessment and management. Singapore : McGraw-Hill, 2000; 139-53.
9. Picado C, Deulfeu R, Agusti M, Mullol J, Quinto L, Torra M. Dietary micronutrient / antioxydants and their relationship with bronchial asthma severity . Allergy 2001; 56: 43-9.
10. McKeever TM, Scrivener S, Broadfild E, Jones Z, Britton J, Lewis SA. Prospective study of diet and decline in lung function in a general population. Am J Respir Crit Care Med, 2002; 165: 1299-303.
11. Fogarty A, Britton J. Nutritional issues and asthma. Curr Opin Pulm Med, 2000; 6: 86-9.
12. Rowe BH, Bretzlaff JA, Bourdon C, Bota GW, Camargo CA. Intravenous magnesium sulfate treatment for acute asthma in the emergency depart-ment: a systematic review of the literature. Ann Emerg Med, 2000; 36: 181-90.
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 49

13. Alter HJ, Koepsell TD, Hilty WM. Intravenous magnesium as an
adjuvant in acute bronchospasm: A meta analysis. Ann Emerg Med, 2000; 36: 191-7.
14. Emelyanov A, Fedosev G, Barnes PJ. Reduced intracellular magnesium concentrations in asthmatic patients. Eur Respir J. 1999; 13: 38-40.
15. Cydulka R, JarvisHJ. New medication for asthma. Emerg Med Clin North Am, 2000; 18: 789-801.
16. Britton J, Pavord I, Richards K, Wisniewwski A, Knox A, Lewis S et al. Dietary magnesium, lung function, wheezing, and airway hyperre-activity. Lancet 1994; 344: 357-62.
17. Elin Rj. Assessment of magnesium status. Clin Chem, 1987; 33: 1965-70. 18. Manaker S, Tietze KJ, Wittbrodt ET. Pulmonary pharmacotherapy. In
Fishman AP, Elias JA, Fishman JA, Grippi MA, Kaiser LR, Robert M, eds. Pulmonary diseases and disorders 3rd ed.New York: McGraw-Hill, 2001, 2648-9.
19. Rodenberger CH, Ziyadeh F. Electrolyte disorders. In. Lanken P, Hanson CW, Manaker S. eds. The intensive care unit manual. Philadelphia: WB Saunders Co, 2001; 415-33.
20. Noppen M, Vanmaele L, Impens N, Schandevyl W. Bronchodilating effect of intravenous magnesium sulfate in acute severe bronchial asthma. Chest, 1990; 97: 373-6.
21. Dacey MJ. Endocrine and metabolic dysfunction syndromes in the
critically ill: hypomaganesium disorders. Crit Care Clin, 2001; 17: 155-73.
22. Okayama H, Aikawa T, Okayama M, Sasaki H, Suetsugu M, Takashima T. Bronchodilating effect of intravenous magnesium sulfate in bronchial asthma. JAMA, 1987;1076-8.
23. Seelig M. Consequences of magnesium deficiency on the enhancement of stress reactions; preventive and therapeutic implications. Am J Nutrition, 1994; 13: 429-46.
24. Ralston MA, Murnane MR, Kelley RE, Altschuld RA, Unerferth DV, Leier CV. Magnesium content of serum, circulating mononuclear cells, skeletal muscle and myocardium in congestive heart failure. Circulation 1989; 80: 573-80
25. Zervast E, Lokides S, Papatheodorou G, Psathakis K, Tsindiris K, Panagou P et al. Magnesium level in plasma and erythrocytes before and after histamine challenge. Eur Respir J, 2000; 16: 621-5
26. Zervast E, Paptheodorou G, Psathakis K, Panagou P, Georgatou N, Loukides S. Reduced intracellular Mg concentration in patient with acute asthma. Chest, 2003; 123: 113-8.
27. Reinhart RA. Magnesium metabolism. Arch Intern Med, 1988; 2415-20.
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 50

Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 51
PRAKTIS
Carpal Tunnel Syndrome
Rudiansyah Harahap
Bagian Ortopedi, Rumah Sakit Umum Daerah Kusta, Tugurejo Semarang
PENDAHULUAN
Carpal Tunnel Syndrome (CTS) yang dikenal juga sebagai Tardy Median Nerve Palsy adalah kumpulan gejala dan tanda akibat penekanan n. medianus di rongga/ terowongan carpal. Sering terjadi pada usia antara 30 dan 60 tahun; wanita 5 kali lebih sering terkena dibandingkan laki-laki.(1,2)
ANATOMI CARPAL TUNNEL
Rongga carpal dibatasi oleh dinding kaku yang di-bentuk oleh tulang dan sendi carpal serta ligamentum carpal transversum (flexor retinaculum) yang tebal.(3) Tero-wongan carpal dibatasi oleh tulang distal radius, lunatum dan capitatum di sisi dorsal; tulang skaphoid, jaringan fibrous untuk terowongan flexor carpiradialis di sisi radial; tulang triquetrum dan ligamentum pisohamatum di sisi ulnar; ligamentum carpal transversum yang tebal mem-bentang dari tulang pisiform ke skaphoid-trapezoid di sisi volar. Carpal tunnel berisi ligamentum flexor digitorum superficialis (FDS) dan profundus (FDP), flexor pollicis longus (FPL), dan n. medianus yang lebih ke radial.(4)
ETIOLOGI Berbagai faktor yang dapat menyebabkan Carpal
Tunnel Syndrome antara lain (1,3,5)
1. Trauma langsung ke carpal tunnel yang menyebabkan penekanan, misalnya Colles fracture, dan edema akibat trauma tersebut.
2. Posisi pergelangan tangan, misalnya fleksi akut saat tidur, imobilisasi pada posisi fleksi dan deviasi ulnar yang cukup besar.
3. Trauma akibat gerakan fleksi-ekstensi berulang per-gelangan tangan dengan kekuatan yang cukup seperti pada pekerjaan tertentu yang banyak memerlukan gerakan pergelangan tangan.
4. Tumor atau benjolan yang menekan carpal tunnel se-perti ganglion, lipoma, xanthoma.
5. Edema akibat infeksi. 6. Edema inflamasi yang disertai artritis rematoid, tenosy-
novitis seperti penyakit de Quervain dan trigger finger. 7. Osteofit sendi carpal akibat proses degenerasi.
8. Kelainan sistemik seperti : obesitas, diabetes melitus, disfungsi tiroid, amiloidosis, penyakit Raynaud.
9. Edema pada kehamilan (hormonal). KLASIFIKASI
Berdasarkan percobaan dan observasi klinis, Galberman dkk. membagi CTS menjadi stadium akut, awal/dini, intermediate dan kronik.(1)
Jose J. Monsivais MD., dkk. mengklasifikasikan CTS menjadi 3 derajat :(6)
Derajat Tinel’s Sign
Phalen’s Test
Diskrimi-nasi 2 titik
Vibratory Capacity
Conduction Velocities EMG
Atrofi Otot
(Thenar)Ringan - - atau + dgn
provokasi 3- 6 mm Normal atau
terganggu Normal
atau minimal
terganggu
Normal atau
minimal terganggu
-
Sedang + + 6-10 mm Absen Memanjang Abnormal - Berat +/- + ≥ 10 mm Absen Abnormal Abnormal +/-
Gambar 1. Anatomi Carpal Tunnel

Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 52
Gambar 2. Anatomi Carpal Tunnel beserta isinya CTS
Gambar 3. Efek Penekanan Pada Saraf Perifer(7)
Gangguan gliding
Kompresi
Akut Pekerja tak dominan Pekerja dominan menggerakkan
pergelangan tangan
Deformasi serabut saraf
Iskemi lokal
Disfungsi Serabut Saraf
Peningkatan EFP
Kronik
Peningkatan
permeabilitas vaskuler
Akut/Awal Intermediate/
Edema
Perubahan
Invasi fibroblast
Iritasi kronik jaringan
Fibrosis Sedang/ berat
Ringan
Konservatif (Non Operatif)
Gagal Operasi Carpal Tunnel Release

Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 53
Biologi Efek Penekanan Saraf Perifer Efek penekanan saraf perifer termasuk pada CTS, ter-
gantung lama (akut, intermediate, kronik) dan besarnya (ringan, besar, sangat besar) tekanan.(7)
Rata-rata pada orang normal tekanan intra carpal tunnel 2,5 mmHg pada posisi netral, 31 mmHg pada fleksi pergelangan tangan dan 30 mmHg pada dorsofleksi/ekstensi pergelangan tangan. Pada penderita CTS, rata-rata tekanan intra carpal tunnel 32 mmHg pada posisi netral, 99 mmHg pada fleksi 90° dan 110 mmHg pada ekstensi 90° per-gelangan tangan.(1) Tekanan intra carpal tunnel 30 mmHg menimbulkan parestesi (baal) dan hambatan sensorik; pada tekanan 50-60 mmHg, fungsi motorik dan sensorik diblok secara komplet; sensorik hilang dalam waktu 25-50 menit, motorik hilang 10-30 menit setelah sensorik hilang. Jika tekanan segera dihilangkan, pada banyak kasus, fungsi motorik dan sensorik kembali secara komplet dalam waktu 3-6 bulan.(7)
DIAGNOSIS
CTS adalah kumpulan gejala atau tanda akibat pe-nekanan n. medianus di carpal tunnel. Gejala dan atau tanda tersebut serta faktor penyerta atau penyebab perlu dievaluasi lebih lanjut. Gejala yang sering adalah rasa baal/kesemutan (parestesi) dan nyeri di sisi volar mulai ibu jari hingga sebagian/sisi radial jari manis tangan, rasa terbakar/panas dan tebal di tangan saat terbangun setelah beberapa jam tidur dan hilang jika posisi pergelangan tangan diluruskan (splinting) atau dengan exercise.(1,2,5)
Tanda yang sering timbul berupa gangguan sensorik pada posisi volar ibu jari hingga sisi radial jari manis, tanda Tinel positif (nyeri pada perkusi n.medianus di area carpal tunnel), tes Phalen positif yaitu fleksi pergelangan tangan secara akut selama 60 detik menimbulkan atau menambah rasa kesemutan (parestesi). Jika proses sudah lama atau derajat yang berat dapat menimbulkan atrofi otot thenar.(1,5)
Pemeriksaan tambahan yang paling dapat dipercaya adalah tes Nerve Conduction Studies.(1) Pemeriksaan lain yaitu Electromyography, Vibratory Capacity, Semmes - Weinstein Monofilament Test.(6)
Pengobatan
Pada CTS stadium awal dan derajat ringan, pengobatan non operatif dapat dilakukan dengan cara menghilangkan penyebab, posisi pergelangan tangan dibuat netral/lurus (displint), penggunaan NSAID hingga suntikan kortiko-steroid di carpal tunnel. Jika tak ada respons atau gejala dan tanda tak berkurang atau bahkan timbul atrofi otot
thenar, prosedur operasi dilakukan.(1,5) Kaplan, Glickel dan Eaton mengidentifikasi lima faktor penting untuk menentu-kan keberhasilan pengobatan non operatif: usia lebih 50 tahun, durasi lebih 10 bulan, parestesi menetap, stenosing flexor tenosynovitis, tes Phalen positif dalam kurang dari 30 detik. Makin banyak atau lengkap faktor tersebut terdapat pada penderita, makin kecil keberhasilan pengobatan non operatif. Tidak ada pengobatan non operatif jika 4 atau 5 faktor tersebut ada.(1)
Gelberman dkk. melakukan operasi carpal tunnel release pada derajat intermediate dan kronis dengan respon baik.(1) Studi Jose J. Monsivais di ElPaso-Texas pada pe-kerja penderita CTS yang dominan menggunakan atau menggerakkan tangan/pergelangan tangan (fleksi-ekstensi), menunjukkan bahwa operasi lebih awal dan rehabilitasi memberikan hasil lebih baik untuk kembali bekerja diban-dingkan dengan pengobatan non operatif.(6)
KESIMPULAN
CTS merupakan kumpulan gejala dan tanda akibat pe-nekanan n.medianus di carpal tunnel yang dibatasi oleh dinding yang kaku; lebih sering terjadi pada wanita. Banyak faktor yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan dalam carpal tunnel. Berdasarkan tanda (pemeriksaan fisik) dan pemeriksaan tambahan, CTS diklasifikasikan menjadi dera-jat ringan, sedang dan berat.
Pengobatan CTS berdasarkan derajat, durasi dan sifat pekerjaan.
KEPUSTAKAAN
1. Wright II PE. Carpal Tunnel and Ulnar Tunnel Syndromes and Ste-
nosing Tenosynovitis. in : Crenshaw AH, ed. Campbell’s Operative Orthopaedics, Vol.5, 8th ed. St. Louis: Mosby Year Book Inc,; 1992: 335-45.
2. Apley AG, Solomon L. Apley’s System of Orthopaedics and Frac-tures. 7th ed, , Oxford: Butterworth-Heinemann Ltd; 1993 : 306- 7.
3. Salter RB. Textbook of Disorders and Injuries of the Musculos-keletal System. 3rd ed. Baltimore: William & Wilkins, 1999 : 326.
4. Hoppenfeld S, De Boer PMA. Surgical Exposure in Orthopaedics. Philadelphia: J.B. Lippincott Co, 1984 : 162-70.
5. Milford L. The Hand. 2nd ed. St. Louis:CV Mosby Co, 1982 : 282-5. 6. Monsivais JJ, Bucher PA, Monsivais DB. Nonsurgically Treated
Carpal Tunnel Syndrome in the Manual Worker. Plast. Reconstr. Surg. 1994;94 : 695,
7. Bodine SC, Lieber RL. Peripheral Nerve Physiology, Anatomy and Pathology. In : Simon SR. (ed). Orthopaedic Basic Science. Ameri-can Academy of Orthopaedic Surgeons, 1994 : 325-96.
It is better to suffer once than to be in perpetual apprehension

Kapsul
PELUPA ATAU PIKUN
Sampai saat ini masih sulit untuk menentukan/menilai daya ingat seseorang – apakah masih baik, atau mulai
menunjukkan gejala-gejala pikun/demensia. Berikut ini daftar pertanyaan yang dapat digunakan sebagai pedoman – apakah ‘sering lupa’ yang dikeluhkan
pasien anda sudah menjurus ke demensia : Beri nilai : 1 – jika hal tersebut hampir tidak pernah terjadi (1-2 kali setahun).
2 – jika kadang-kadang dirasakan (beberapa kali sebulan) 3 – jika agak sering dirasakan (beberapa kali seminggu) 4 – jika sering terjadi (praktis tiap hari) • Lupa letak benda/barang di rumah. • Tidak mengenali tempat-tempat yang biasa/sering dikunjungi. • Harus kembali untuk memeriksa ulang hal-hal yang (sudah) dikerjakan. • Melupakan/ketinggalan sesuatu saat ke luar rumah. • Lupa akan hal-hal yang telah diberitahu beberapa hari sebelumnya, atau harus selalu diingatkan. • Saat membaca koran atau buku, kehilangan konsentrasi – tidak dapat mengikuti jalan cerita. • Tidak dapat mengenali wajah sanak keluarga atau teman yang sering berjumpa. • Lupa menyampaikan suatu pesan penting, atau lupa mengingatkan seseorang mengenai hal-hal yang penting. • Lupa akan hal-hal penting mengenai diri sendiri; misalnya tanggal lahir atau alamat rumah. • Mengacaukan atau bingung mengenai hal-hal yang diberitahukan ke padanya. • Lupa di mana meletakkan sesuatu atau mencari di tempat yang salah. • Tersesat atau salah belok/salah jalan di tempat yang biasa dilewati. • Mengulang hal-hal yang rutin tanpa sadar, seperti berulang kali menyisir, dua kali menuang teh ke cangkir yang
sama. • Mengulang-ulang pertanyaan. Jika NILAI TOTAL anda : 14 – 19 : Daya ingat anda baik, tidak perlu cemas. 20 – 29 : Daya ingat anda rata-rata, mungkin memerlukan bantuan/cara mengingat, atau strategi mengingat tertentu. 30 – 39 : Daya ingat anda di bawah rata-rata, mungkin disebabkan oleh kesibukan yang membebani ingatan anda. 40 – 56 : Daya ingat anda sangat lemah, dapat mempengaruhi kehidupan anda.
Dari : Martyn C, Gate CR. Family Doctor Guide to Forgetfulness and Dementia. The British Medical Association, 1999. pp 16-9.
Brw
The mind is playful when unburdened
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 54

Produk Baru
Paxus®
Quantitative Composition (per ml) Each ml Paxus® injection contains 6 mg of paclitaxel, 527 mg of purified Cremophor® (polyoxyl 35 castor oil) and 49.7% (v/v) of dehydrated alcohol. Indications − Paxus® is indicated as first-line and subsequent therapy for the treatment of advanced carcinoma of the ovary. As first-line therapy Paxus® is indicated in combination with cisplatin. − Paxus® is indicated for the treatment of breast cancer after failure of combination chemotherapy for metastatic disease or relapse within 6 months of adjuvant chemotherapy. Prior therapy should have included an anthracycline unless clinically contraindicated. Contraindications
− Paclitaxel is contraindicated in patients who have a history of severe hypersensitivity reactions to paclitaxel or other drugs formulated in polyoxyl 35 castor oil. − Paclitaxel should not be used in patients with baseline neutrophil count of less than 1,500 cells/mm3 or in patients with AIDS related Kaposi’s sarcoma with baseline neutrophil counts of < 1000 cells/mm3.
Storage Store the vials in original cartons between 21-30°C. Retain in the original package to protect from light. Packag 1 Box @ 1 vial (5 ml) Registration Reg. No. DKL0303300143A1 Dosage and Administration 1) Premedication Following sequence of premedication shall be done to prepare patient for infusion with Paxus® injection. 12 hours before treatment………….. Dexamethasone 20 mg P.O. 6 hours before treatment…….………Dexamethasone 20 mg P.O. 30-60 minutes before treatment.…….Diphenhydramine 50 mg I.V. Cimetidine 300 mg or Ranitidine 50 mg I.V. PAXUS Inj
2) Preparation Prior to infusion to patients, Paxus® injection shall be diluted in any of following injection solutions to get a final concentration of 0.3-1.2 mg of paclitaxel/ml. − 0.9% Sodium Chloride Injection − 5% Dextrose Injection − 5% Dextrose/0.9% Sodium Chloride Injection − 5% Dextrose in Ringer Injection solution
3) Dose schedule Intravenous (i.v.) infusion at a dose of 175 mg/m2 over a 3 hour period. The treatment may be repeated every 3 weeks. 4) Repeat dosage Subsequent treatment shall not be given to patients until neutrophil count is at least 1,500 cells/mm3 and platelet count is at least 100,000 cells/mm3. For patients who experienced severe neutropenia (neutrophil < 500 cells/mm3) for a week or longer or moderate to severe peripheral neuropathy during Paxus® injection treatment, dosage shall be reduced by 20% for subsequent courses of Paxus® therapy. 5) Stability of diluted solutions Physically and chemically stable for up to 27 hours at ambient temperature (15-30°C). 6) Infusion set - Undiluted concentrate shall not come in contact with plasticized
PVC equipments during preparation. To minimize patients’ exposure to the plasticizer DHEP, which may be leached from PVC infusion bags or sets, diluted Paxus® solutions shall preferably be stored in bottles (glass, propylene) or plastic bags (polypropylene, polyolefin) and administered with polyethylene-lined administration sets.
- Paxus® shall be administered through an in-line filter with a microporous membrane not greater than 0.22 microns. Use of filter devices such as IVEX-2 filters which incorporate short inlet and outlet PVC-coated tubing has not resulted in significant leaching of DHEP.
Marketing Office:
PT. KALBE FARMA Tbk Gedung Enseval, Jl. Letjend. Suprapto, Jakarta 10510
PO Box 3105 JAK, Jakarta – Indonesia Tlp.: (021) 428 73888-89, Fax. : (021) 428 73680
Website : http://www.kalbe.co.id/paxus Hotline service (bebas pulsa): 0-800-123-0-123, Senin – Jumat (07.00-15.30)
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 55

Kegiatan Ilmiah
Laporan lengkap dari simposium di bawah ini, bisa diakses di http://www.kalbe.co.id/seminar. Pada topik yang diberi tanda Breaking News, berarti peserta simposium bisa memperoleh berita dalam bentuk cetak (print) bersamaan dengan acara di Stand Kalbe Farma, dan bisa langsung diakses pada homepage Kalbe Farma. Seminar Komorbiditas Depresi & Penatalaksanaannya dalam Praktek Sehari-hari, Jakarta, 28 Juni 2003
Mengobati pasien tidak semudah yang dibayangkan orang. Banyak penyakit yang saling tumpang tindih sehingga cukup sulit me-negakkan diagnosa. Penelitian menunjukkan bahwa 8-20% pasien di praktek umum dalam 1 tahun memiliki gangguan mood/perasaan yang bermakna. Demikian diungkap dr Hardi Pranata SpS dari RS Gatot Soebroto, pada acara seminar sehari Komorbiditas Depresi & Penata-laksanaannya dalam Praktek Sehari-hari. Seminar yang diselenggara-kan oleh IDI Jakarta bersama Kalbe Farma, juga menampilkan dokter Danardi S SpKJ dari FKUI, dan dr LS Chandra SpKJ dari Sanatorium Dharmawangsa. Pada kesempatan ini diperkenalkan produk Kalbe Farma yaitu Kalxetin® yang mengandung fluoxetine.
Sehat dan Cantik Pra dan Pasca Menopause ; Life Begin at 30's, Hotel Borobudur, 16 Agustus 2003
Kedelai mengandung estrogen dalam bentuk isoflavon, ganistein, dan daidzein yang mempunyai efek estrogen bagi manusia dan hewan. Peneliti kini sedang mempelajari efek fisiologis baru dari isoflavon dan menemukan isoflavon (Calvonin®) dapat bermanfaat seperti estrogen alami sehingga dapat menurunkan risiko penyakit pada masa menopause. Hal ini disampaikan dr. Jetty Sedyawan, SpJP (K) dalam seminar bertema ”Sehat dan Cantik Pra dan Pasca-menopause” di Hotel Borobudur beberapa waktu lalu. Simposium Nasional Telemedicine 2003, Hotel Sahid Jaya Jakarta, 9 Agustus 2003
Acara Simposium Nasional Telemedicine yang digelar Panitia Lulusan Dokter FKUI 2003-2004 berlangsung sehari di Hotel Sahid Jaya Jakarta, Sabtu 9 Agustus 2003. Simposium dibuka oleh Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Teknologi Informasi & Farmasi, Drs.Richard Panjaitan dan ditutup oleh Sekretaris Menteri Komunikasi
dan informasi, Dr. JB Kristiadi. Peserta terdiri dari masyarakat telemedi-cine Indonesia yang datang tidak hanya dari pulau Jawa, namun dari Sumatera, Kalimantan, Papua, dll. Pada akhir acara dibaca kesepakat-an bersama untuk membentuk Asosiasi Telemedicine Indonesia. Kalbe Farma (kalbe.co.id®) turut berpartisipasi dalam acara ini. Seminar Awam Kanker pada Alat Reproduksi Perempuan, Aula Depkes RI, 3 Juni 2003
Kanker Leher Rahim tidak menular dan juga bukan penyakit keturunan. Hal ini dikatakan dr Toto Imam Soeparmono dari Sub-bagian Onkologi Ginekologi, Departemen Obstetri dan Ginekologi RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta. Saat memberi presentasi awam mengenai Kanker Leher Rahim di hadapan kurang lebih 150 peserta, ahli kebidanan & kandungan tersebut menyatakan bahwa seperti kepiting (arti kata cancer), sel-sel kanker bisa hidup di segala lingkungan. Acara ini diselenggarakan oleh yayasan yang bergerak di bidang kanker dengan disponsori oleh Kalbe Farma. Seminar Keputihan pada Wanita, Jakarta 1 Agustus 2003
Wanita dianjurkan untuk tidak menggunakan celana dalam, jika mengalami keputihan yang sukar sembuhnya. Hal ini terungkap pada Seminar setengah hari mengenai Keputihan pada wanita yang diada-kan Kalbe Farma (Naxogin®), Sari Ayu, Medika, dan Omni Medical Center, Jumat 1 Agustus 2003. Menurut pembicaranya dr Noroyono Wibowo SpOG, dalam praktek sehari-hari, anjuran tidak mengguna-kan celana dalam ternyata cukup ampuh untuk membantu mem-berantas penyakit keputihan. Forum Diskusi SARS pada Pekerja, RS Persahabatan Jakarta, 13 Juni 2003
SARS pada Pekerja merupakan salah satu topik Forum Diskusi yang diselenggarakan oleh Ikatan Dokter Kesehatan Kerja DKI Jakarta pada tanggal 13 Juni 2003 yang lalu bertempat di Ruang Seruni RS Persahabatan Jakarta. Menurut dr. Muchtaruddin Mansyur, MS, selaku pengurus IDKI DKI Jakarta, setiap 3 bulan akan diadakan forum diskusi seperti ini membahas topik-topik yang ada kaitannya dengan Kesehatan Kerja khususnya di wilayah DKI Jakarta.
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 56

Kongres Pertama Asosiasi Psikogeriatri Indonesia, Hotel Borobudur Jakarta, 14 - 16 Juni 2003
Depkes menyambut gembira berdirinya Asosiasi Psikogeriatri Indonesia (API) sebagai salah satu perkumpulan yang turut peduli terhadap usia lanjut. Hal itu disampaikan Asrul Azwar MPH saat memberi sambutan pada acara pembukaan Kongres Pertama API yang berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta, Sabtu 14 Juni 2003. Dengan demikian, lanjut Asrul, harapan pemerintah, kompleksitas masalah-masalah masyarakat lanjut usia dapat ditangani sebaik-baiknya. Manajemen Pemberitaan Kasus Rumah Sakit di Media Massa, Hotel Menara Peninsula Jakarta, 18 Juni 2003
Rumah sakit menganggap wartawan sebagai musuh begitu pula sebaliknya wartawan sangat membenci rumah sakit (baca: sakit). Demikian pernyataan ekstrim dalam nada serius tapi becanda dike-mukakan oleh Andy F Noya, Pemimpin Redaksi Media Indonesia pada acara CEO Gathering yang diselenggarakan oleh PERMAPKIN (Perhimpunan Manajer Pelayanan Kesehatan Indonesia) dengan spon-sor utama PT ENSEVAL. Selain Andy, tampil dengan presentasi yang menarik, berturut-turut: Husen Karbala SH (Coorporate Secretary PT Pertamedika), Mus Aida (Direktur Medis & Bisnis RS Pondok Indah), dan Yudhistira ANM Massardi (Wadir & Redaktur Pelaksana Majalah Gatra). PIN PERALMUNI II, Hotel Sahid Jaya Jakarta, 21-22 Juni 2003
Pertemuan Ilmiah Nasional II yang diadakan oleh Perhimpunan Alergi-Imunologi Indonesia di Hotel Sahid Jaya tanggal 21-22 Juni 2003 ini mengambil tema utama ”Peranan Peralmuni pada Era Globalisasi dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup”. Dihadiri oleh cukup banyak dokter umum dan spesialis dari berbagai disiplin ilmu, banyak topik utama yang dibahas, di antaranya mengenai alergi tipe I dan obat-obat antihistamin golongan baru, kortikosteroid dan permasalahannya, serta asma. Konferensi Nasional Autisme I, Jakarta 2 - 4 Juli 2003
Autisme merupakan suatu hal yang relatif baru. Meskipun pengetahuan Autisme berkembang pesat, namun masih banyak yang belum diketahui mengenai penyakit tersebut. Pernyataan ini disampai-kan Achmad Sujudi, Menteri Kesehatan RI sewaktu membuka Konferensi Nasional Pertama Austisme yang diselenggarakan oleh tiga organisasi profesi tanggal 2 Juli kemarin. Konferensi yang ber-langsung hingga tanggal 4 Juli diselenggarakan bersama-sama antara Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (PERDOSSI). Tema yang diambil adalah “Towards a Better Life for Autistic Individuals”. Pertemuan Ilmiah Khusus X PDPI, Hotel Sahid Jaya Makassar, 2-5 Juli 2003
Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) mempunyai agenda kerja tahunan berupa PIK (Pertemuan Ilmiah Khusus), Konker (Kon-ferensi Kerja), serta Konas (Kongres Nasional) yang diadakan setiap tahun secara berurutan dan bergantian. PIK tahun 2003 kali meng-ambil tempat di Makassar dengan tema ‘Penanggulangan Infeksi Saluran Nafas Bawah Sebagai Salah Satu Strategi Baru Untuk Meningkatkan Efektifitas Kerja’. Acara yang berlangsung dari tanggal 2 hingga 5 Juli 2003 ini dihadiri oleh lebih 500 peserta dari kalangan anggota PDPI, dokter umum, maupun dokter spesialis lain. Konas XI PGI-PEGI dan PIN XII PPHI, Batu - Malang, 4-7 Juli 2003
Acara KONAS XI PGI (Perkumpulan Gastroenterologi Indo-nesia), PEGI (Perkumpulan Endoskopi Gastroenterologi Indonesia) dan PIN XII PPHI (Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia) ini diseleng-
garakan di Batu Malang tanggal 4–7 Juli 2003. Ketua panitia pe-nyelenggara acara ini, Prof. DR. Dr. Harijono Achmad, SpPD-KGEH, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memajukan penelitian ilmiah, epidemiologis dan klinis, diagnosis dan terapi gastrointestinal, termasuk juga penyakit hepatobilier dan pankreas.
Kongres Nasional Obstetri & Ginekologi Indonesia (KOGI XII), Hotel Sheraton Yogyakarta, 4-9 Juli 2003
Kongres Obstetri dan Ginekologi (KOGI XII) yang dilaksanakan di hotel Sheraton Mustika, Yogyakarta, 4-9 Juli 2003 dihadiri oleh kurang lebih 1800 peserta yang terdiri dari dokter ahli obstetri dan ginekologi, dokter umum, dan bidan serta dimeriahkan pula oleh 64 sponsor yang terdiri dari perusahaan farmasi, perusahaan alat kesehat-an dan susu / suplemen kesehatan.
Pertemuan Ilmiah Dua Tahunan PDSKJI 2003, Hotel Sahid Jaya Jakarta, 5-8 Juli 2003
Acara ini merupakan pertemuan yang menjadi agenda rutin Per-himpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) yang diadakan setiap dua tahun sekali. Seminar ilmiah kali ini mengambil tema ‘Paradigma Baru Psikiatri di Indonesia’, diadakan di Hotel Sahid Jaya Jakarta dari tanggal 5 Juli hingga 8 Juli 2003. Upacara pem-bukaannya sendiri dilakukan sehari sebelumnya di tempat yang sama, dengan menampilkan musik dan paduan suara yang menawan. Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) XIV Ikatan Ahli Bedah Indonesia (IKABI) ke XIV, Jakarta Convention Centre, 10-12 Juli 2003
Acara pembukaan yang dibuka oleh Menteri Kesehatan, dr. Ahmad Suyudi SpB, MHA, pada seminar kali ini cukup meriah dengan dihadiri sekitar 1400 dokter, yang terdiri dari para Guru Besar Ilmu Bedah, Ketua Cabang IKABI di seluruh Indonesia, Ketua Kolegium Ilmu Bedah dan para Ketua Program Studi Ilmu Bedah, Para Ahli Bedah dari seluruh Indonesia, para dokter yang sedang mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah serta para dokter umum. Harapan dari pelaksanaan PIT IKABI kali ini adalah agar para dokter bedah yang hadir lebih berbekal ilmu dan teknologi bedah yang baru serta bermanfaat. Indonesian Digestive Week (IDDW) in Conjunction with the American Gastroenterological Association (AGA) , Hotel Kartika Plaza Kuta, 9-12 Juli 2003
Saat ini infeksi Helicobacter pylori (Hp) masih merupakan salah satu masalah penyakit saluran cerna di Indonesia. Prevalensi infeksi Hp tinggi terutama pada pasien dispepsia (data dari bagian gastro-enterologi Surabaya : 60-70%), sehingga pemeriksaan untuk bakteri ini dianjurkan, apalagi pada penderita dengan keluhan dispepsia se-lama 4 minggu dengan atau tanpa alarm symptoms (perdarahan salur-an cerna, anemia, dan lain-lain). Hal ini disampaikan pada seminar Indonesian Digestive Disease Week (IDDW) in conjunction with the American Gastroenterological Association (AGA) yang dilaksanakan di Hotel Kartika Plaza, 9-12 Juli 2003.
The Recent Advances in Critical Care Management of Trauma Cases, Jakarta, 19 - 20 Juli 2003
Indonesia merupakan negara yang sangat berisiko akan terjadinya musibah massal atau bencana, baik yang disebabkan oleh manusianya maupun yang disebabkan oleh alamnya sendiri seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, pertentangan antar etnis, teroris dan lainnya. Hal ini diungkapkan oleh dr Tengah Kuning Atmadja sewaktu membawakan presentasi berjudul Pre Hospital Disaster Relieve System was down in Bali Blast. PIT IPD 2003 FKUI, Hotel Sahid Jaya, 25 - 27 Juli 2003(Breaking News)
Dalam melakukan praktek klinik, pasien harus dipandang secara
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 57

utuh sebagai mahluk biopsikososial. Demikian dikatakan Prof.Wiguno Prodjosudjadi dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan Ilmu Penyakit Dalam FKUI yang berlangsung selama 3 hari (25-27 Juli 2003) di Hotel Sahid Jaya Jakarta. Acara pertemuan dengan suasana yang berbeda dengan pertemuan-pertemuan terdahulu diisi oleh pelbagai stand-stand yang menampilkan Teknologi Informasi yang menarik. Kalbe Farma tidak mau ketinggalan dengan menampilkan website yang bisa online, promosi pelbagai produk baru secara menarik, dll. Jangan kaget jika pengunjung stand Kalbe disapa oleh satu pasangan yang berpakaian hitam-hitam. Siapakah dia?
Kuliah Guru Besar FKUI : Erupsi Alergi Obat, Aula FKUI Salemba Jakarta, 29 Juli 2003
Hati-hati mengonsumsi jamu atau obat tradisional, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, karena sebagian dibubuhi obat bahan kimia yang dapat memberikan efek samping termasuk Erupsi Obat Alergik (EOA). Anjuran ini ditekankan oleh Prof. Dr. dr. Adhi Djuanda, Sp.KK(K) dalam kuliahnya di aula FKUI Salemba tanggal 29 Juli 2003. Beliau menambahkan bahwa selama ini pengobatan tradisional tersebut dianggap tidak berbahaya, padahal dalam kenya-taannya tidak semuanya aman.
Perubahan Fundamental Masalah Demam Berdarah di Dunia dan Khususnya di Indonesia, Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 30 Juli 2003
Simposium yang dihadiri oleh sekitar 2.500 dokter umum dari pelbagai daerah seluruh Indonesia, dibuka oleh Ketua Bagian Ilmu Penyakit Dalam FKUI yang diwakili oleh dokter Nelwan. Menurut Ketua Subbagian Penyakit Tropik dan Infeksi FKUI/RSCM tersebut, pertemuan ini dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan penyakit infeksi, pengobatan dan pencegahannya. Meskipun teknologi obat-obat sudah sedemikian maju, namun ternyata perkembangan penyakit tak kalah ketinggalannya. Jika tahun lalu, sewaktu JADE digelar, sedang heboh-hebohnya virus chikungunya, sekarang virus SARS pun menjadi perhatian dunia termasuk perhatian para medis kedokteran. Temu Ilmiah Perhimpunan Hematologi dan Transfusi Darah Indonesia (PHTDI) ke-V , Hotel Grand Aquila Bandung, 1-2 Agustus 2003
Prognosis kanker payudara tergantung banyak faktor, mulai dari faktor genetik, klinis, gambaran histologis tumor, dan pemeriksaan biologi molekuler. Hal ini sangat membantu untuk dapat menentukan pengelolaan selanjutnya. Pada saat ini pemeriksaan Her2/neu menjadi penentu yang penting bagi prognosis kanker payudara karena dike-tahui onkogen ini memberi petunjuk akan agresifitas dari tumor, Dr. Bethy S. Hernowo, SpPA, PhD mengemukakan hal tersebut dalam kuliahnya di acara Temu Ilmiah Perhimpunan Hematologi dan Trans-fusi Darah Indonesia PHTDI) ke-V Onkologi Medik 2003 di Hotel Grand Aquila Bandung, tanggal 1-2 Agustus 2003 lalu. KOPAPDI XII: Memantapkan Peran Profesionalisme Medis dalam Menyongsong Indonesia Sehat 2010, Hotel Ritzy Manado, 6-9 Agustus 2003
Seminar KOPAPDI yang dilangsungkan di hotel Ritzy Manado beberapa waktu lalu telah mencatat beberapa terobosan baru, antara lain dengan diluncurkan konsensus nasional malaria dan konsensus nasional tentang imunisasi pada orang dewasa. Seminar KOPAPDI yang dilangsungkan selama tiga hari tersebut memang cukup banyak menyedot seribu lebih peserta. Acara itu sendiri dibuka oleh Kepala Litbang Kesehatan Depkes RI, Dr. Sumaryati Aryoso SKM, yang mewakili Menkes. Pembukaan ditandai dengan pengguntingan pita oleh dr. Aryoso, dengan disaksikan oleh ketua PB PAPDI DR. Dr. Samsuridjal Djauzi, dan ketua panitia Prof. Dr. Dr. AR Sumual SpPD-KE serta para undangan lain.
Plenary Annual Meeting on Emergency Surgical and Medical Update, Hotel Borobudur Jakarta, 9-10 Agustus 2003
Pemberian misoprostol oral sebanyak 3 tablet dapat membantu mengurangi kejadian perdarahan post partum (Post Partum Hemorr-hage / PPH) dan kasus atonia uteri. Tablet ini dapat langsung bekerja dalam waktu lima menit. Hal ini diketahui melalui sebuah penelitian yang dilakukan di Jawa Barat pada 1322 wanita melahirkan. Hasilnya cukup menjanjikan, dimana tidak ada satu kasus pun yang diteliti meninggal akibat PPH. PPH merupakan salah satu penyebab kematian ibu, dimana dari AKI (angka kematian ibu) yang 334 di Indonesia, 43% adalah akibat PPH. Hospital Management Refreshing Course & Exhibition II, Jakarta, 19-21 Agustus 2003
Saat ini manusia tidak hanya dilihat sebagai sumber daya, namun sudah dianggap sebagai kapital/modal. Hal itu dijelaskan oleh Menkes RI, dr Ahmad Sujudi SpB saat berbicara sekaligus membuka acara Hospital Management Refreshing Course di Auditorium Binakarna, Komplek Bidakara Jakarta. Acara yang diselenggarakan oleh Perhim-punan Manajer Pelayanan Kesehatan Indonesia (PERMAPKIN) ber-langsung selama 3 hari dengan tema: Hospital Human Capital Deve-lopment in Indonesia. Selain seminar-seminar ilmiah management perumahsakitan turut juga diadakan pameran alat kesehatan, rumah-rumah sakit dalam dan luar negeri, software house, hardware, dll. The 3rd Annual Scientific Meeting On Pharmacology and Therapy : Considerations in Drug Use, Hotel Millennium Sirih Jakarta, 22-23 Agustus 2003
Sebenarnya penelitian-penelitian klinik efek antioksidan terhadap proses aterosklerosis sudah dimulai sejak tahun 1986. Namun hingga kini penggunaan antioksidan pada pencegahan primer dan sekunder penyakit-penyakit kardiovaskular masih merupakan ”issue yang kon-troversial”. Masalah ini diungkit oleh dr. Miftah Suryadipraja, SpPD-KKV, SpJP dalam acara Pekan Ilmiah Tahunan Farmakologi di Hotel Millennium Sirih Jakarta beberapa waktu lalu. DIGM 2nd Annual Meeting: Updates in Obstetric - Gynaecology & Urology, Jakarta, 23-24 Agustus 2003
Orang Indonesia yang belajar di Jerman (khususnya tenaga ke-sehatan), jangan hanya mempelajari teknik kedokteran semata, namun harus juga mempelajari semangat orang Jerman yang mau kerja keras dan disiplin waktu atau dalam bahasa asingnya diistilahkan everything should be in order, tutur Menkes RI, dr Ahmad Sujudi SpB sewaktu membuka acara Pertemuan Tahunan kedua Dokter-dokter Indonesia yang pernah mengenyam pendidikan di Jerman (Deutsch-Indonesische Gesellschaft fur Medizine).
Acara simposium yang berlangsung selama dua hari dan diikuti oleh sekitar 600-an dokter umum, PPDS dan spesialis menyajikan topik-topik mutakhir terbaru tidak hanya di Indonesia namun dalam skala dunia dalam bidang Obstetri, Ginekologi dan Urologi. Seminar Demam Tifoid dan Para Tifoid : Epidemiologi dan Faktor Risiko, Hotel Acacia Jakarta, 30 Agustus 2003
Demam enterik terus menjadi masalah kesehatan masyarakat di Jakarta, dan menurut penelitian dari kelompok studi tifoid proporsinya ternyata cukup tinggi, yaitu 23%. Oleh karena itu kecurigaan harus terus ditingkatkan pada pasien dewasa muda dengan demam yang berkepanjangan, disertai menggigil, delirium dan/atau nyeri perut, walaupun gambaran klinis tidak dapat memastikan. Laporan penelitian itu dipaparkan pada Seminar Demam Tifoid dan Para Tifoid : Epide-miologi dan Faktor Risiko di Hotel Acacia Jakarta beberapa waktu lalu.
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 58

Indeks Karangan Cermin Dunia Kedokteran Tahun 2003
CDK 138. KESEHATAN LINGKUNGAN
English Summary 4 Risa Febriana, Faisal Yunus, Wiwien Heru Wiyono : Kelainan Paru pada Ketinggian
5 - 10
Agus Dwi Susanto, Faisal Yunus, Wiwien Heru Wiyono, Mukh-tar Ikhsan : Pengaruh Inhalasi Ozon terhadap Kesehatan Paru
11 - 16
Diah Handayani, Faisal Yunus, Wiwien Heru Wiyono : Peng-aruh Inhalasi NO2 terhadap Kesehatan Paru
17 - 22
Wahyuningsih, Faisal Yunus, Mukhtar Ikhsan, Wiwien Heru Wiyono : Dampak Inhalasi Cat Semprot terhadap Kesehatan Paru
23 - 28
Eva Munthe, Faisal Yunus, Wiwien Heru Wiyono, Mukhtar Ikhsan : Pengaruh Inhalasi Sulfur Dioksida terhadap Kesehatan Paru
29 - 33 Zubaidah Alatas, Yanti Lusiyanti : Efek Kesehatan Radiasi Non Pengion pada Manusia
34 - 40
Zubaidah Alatas : Indikator Biologik Kerusakan Tubuh akibat Pajanan Radiasi
41 - 45
Susetyo Trijoko : Kendali Mutu Dosimetri Akselerator Linier Medik
46 - 48
Produk Baru : Zypraz® 49 Kapsul : Perhatian untuk Risiko Aritmi Ventrikel 50 Internet Untuk Dokter : Pemanfaatan E-mail: Mailing List 51 Kegiatan Ilmiah 52 Abstrak
Pengobatan Community- Acquired Pneumonia Drugs 1998; 55(1): 39
54
Nitrit untuk Penyakit Raynaud Lancet 1999; 354: 1670-75 54 Kanabis untuk Nyeri BMJ 2001; 323: 13-6 54 Risiko Transmisi HIV Lancet 2001; 357: 1149-53 54 Endarterektomi untuk Mencegah Stroke Lancet 2001; 357: 1154-60
54
Prediksi AIDS Acrh. Neurol. 2002; 59: 923-8 55 Efek Antiinflamasi terhadap Risiko PJK Lancet 2002; 359: 118-23
55
Galantamin untuk Demensia Lancet 2002; 359: 1283-90 55 Angioplasti vs. Fibrinolisis Lancet 2002; 360: 825-9 55 Konsultasi Psikologik Lancet 2002; 360: 766-71 55
CDK 139. KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN
English Summary 4 John Rambulangi : Beberapa Cara Prediksi Hipertensi dalam Kehamilan
5 - 8
William Sanjaya, Jetty RH Sedyawan, T. Dewi Anggraini : Balon Mitral Valvotomi pada Kehamilan
9 - 12
I Putu Sudinaya : Insiden Preeklampsia – Eklampsia di Rumah Sakit Umum Tarakan Kalimantan Timur – tahun 2000
13 - 15
John Rambulangi : Penanganan Pendahuluan Prarujukan Penderita Preeklampsia Berat dan Eklampsia
16 - 19
Eddy Suparman, Aloysius Suryawan : Management of Placental Abruption and Incomplete Uterine Rupture caused by Accidental Trauma of Abdomen
20 - 21 Eddy Suparman : Diabetes Mellitus dalam Kehamilan 22 - 26 Azamris : Ekspresi CD 44 pada Jaringan Tumor Karsinoma Payudara
27 - 32
Azamris : Giant Mammary Dysplasia (Penyakit fibrokistik) 33 - 35 AM Adam, Hardy Suwita : Trikomoniasis dan Penatalaksanaan-nya
36 - 40
Salma Ma’roef, Soeharsono Soemantri : Toksoplasmosis Ibu Hamil Di Indonesia (Studi Tindak Lanjut Survei Kesehatan Rumah Tangga 1995)
41 - 45 Vivianty Hartiono, R. Satriono : Akondroplasia 46 - 48 Produk Baru: Peran Isoflavon untuk Kesehatan Reproduksi Wanita
49
Kapsul : Efek Samping Obat ‘Herbal’ 50 Internet untuk Dokter : Website atau Homepage 51 Kegiatan Ilmiah 52 Abstrak
Intervensi Dini untuk Infark Miokard Lancet 2002; 360: 743-51
54
Kanker dan Diet Lancet 2003; 360: 861-8 54 Tamoxifen Mencegah Kanker Payudara Lancet 2003; 360: 817-24, 813-4
54
Pengaruh Kematian Anak pada Orangtuanya Lancet 2002; 361: 363-67
54
Kelainan Otak pada Skizofrenia Lancet 2003; 361: 281-88 55 Single Parent dan Risiko Gangguan Psikiatrik Lancet 2003; 361: 289-95
55
Tamoxifen vs. Raloxifen Lancet 2003; 361: 296-300 55 Risiko Kanker setelah IVF Lancet 2002; 361: 309-10 55 Asam Folat dan Kelainan Janin Lancet 2003; 361: 380-84 55 Petanda untuk Eklampsia Lancet 2002; 306: 1215-19 55
CDK 140. BUNGA RAMPAI PENYAKIT DALAM
English Summary 4 Bambang Singgih, Edward Jim, Karel Pandelaki Pola Kompli-kasi Kronik Diabetes Mellitus tipe II pada Lansia di RSUP Manado 5 - 7 Suharmiati : Pengujian Bioaktivitas Anti Diabetes Mellitus Tumbuhan Obat 8 - 13 M. Wien Winarno, Diah Sundari : Gambaran Histologi Kelenjar Pankreas Tikus Putih akibat Infus Daging Buah Pare (Momordica charantia L.) 14 - 17 Candra Wibowo : Hepatitis Virus G 18 - 19 Sudung O. Pardede : Sindrom Hepatorenal 20 - 28 Candra Wibowo : Farmakoterapi Terkini Hepatitis Virus Kronik 29 - 33 Harsinen Sanusi : Osteoporosis akibat Glukokortikoid 34 - 40 Kusnindar Atmosukarto, Mitri Rahmawati : Mencegah Penyakit Degeneratif dengan Suplemen Makanan 41 - 49 Kapsul : Pengaruh Diet terhadap Risiko Kanker 50 Produk Baru : Metrix, Forres, dan Pardoz 51 Kegiatan Ilmiah 52 Informasi Produk : Hepasil Menurunkan Enzim Hati dan Me-ningkatkan Respon Imun pada Penderita Hepatitis Virus Kronik 54 141. ASMA
English Summary 4 Indah Rahmawati, Faisal Yunus, Wiwien Heru Wiyono : Pato-genesis dan Patofisiologi Asma
5 - 11
Ira Melintira, Faisal Yunus, Wiwien Heru Wiyono : Peranan In-feksi Chlamydia pneumoniae dan Mycoplasma pneumo-niae ter-hadap Eksaserbasi Asma
12 - 18 Adria Rusli, Faisal Yunus, Wiwien Heru Wiyono : Pengaruh In-feksi Virus pada Perkembangan Asma
19 - 22
Teguh H. Karjadi : Asma Akibat Kerja 23 - 26 M. Yusuf Hanafiah Pohan, Faisal Yunus, Wiwien Heru Wiyono: Asma dan Polusi Udara
27 - 29
Agus Dwi Susanto, Wiwien Heru Wiyono, Faisal Yunus : Re-fluks Gastroesofagus pada Asma
30 - 38
Frans Abednego Barus, Wiwien Heru Wiyono, Faisal Yunus : Imunoterapi pada Asma Alergi
39 - 45
Bambang Irawan Harsono, Faisal Yunus, Wiwien Heru Wiyono: Peran Magnesium pada Asma
46 - 50
Rudiansyah Harahap : Carpal Tunnel Syndrome 51 - 53 Kapsul : Pelupa atau Pikun 54 Produk Baru : Paxus® 55 Kegiatan Ilmiah 56 Indeks Karangan Tahun 2003 59
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 59

Ruang Penyegar dan Penambah Ilmu Kedokteran
Dapatkah saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini?
1. Sel mast berasal dari :
a) Epitel jalan napas b) Sumsum tulang c) Jaringan limfe d) Hepar e) Granulosit
2. Makrofag berasal dari : a) Netrofil b) Limfosit c) Monosit d) Granulosit e) Sel mast
3. Yang bukan mediator inflamasi : a) Epinefrin b) Sitokin c) Leukotrien d) Histamin e) Prostaglandin
4. Yang bukan faktor risiko asma : a) Obesitas b) Cuaca c) Jenis kelamin d) Logam berat e) Jamur
5. Chlamydia digolongkan sebagai : a) Jamur b) Protozoa c) Virus d) Parasit e) Bakteri
6. PSI (pollutant standard index) yang berbahaya adalah jika lebih dari : a) 100 b) 200 c) 300 d) 400 e) 500
7. Yang bukan anti oksidan : a) Beta karoten b) Tokoferol c) Ozon d) Asam askorbat e) Semua anti oksidan
8. Fungsi paru diperiksa dengan : a) Foto rontgen thorax b) Spirometri c) pO2 darah d) Bronkoskopi e) Bronkografi
JAWABAN RPPIK :
1. B 2. C 3. A 4. D 5. E 6. C 7. C 8. B
The things which are perfect by nature are better than those which are perfect by art
(Cicero)
Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 60