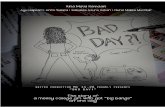BUDAYA ISLAM DALAM KAPITALISME BARU (Logika Jangka Pendek dan Komodifikasi Hijab)
description
Transcript of BUDAYA ISLAM DALAM KAPITALISME BARU (Logika Jangka Pendek dan Komodifikasi Hijab)
BUDAYA ISLAM DALAM KAPITALISME BARU(Logika Jangka Pendek dan Komodifikasi Hijab)
Makalah untuk Ujian Akhir Semester Seminar Industri dan Teknologi Komunikasi pada Program Pascasarjana Departemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,Universitas Indonesia - 2014
Logika jangka pendek (short-term thinking) merupakan konsep milik Richard Sennett dalam bukunya The Culture of the New Capitalism (2006). Sennett (2006:176-177) menyatakan bahwa logika jangka pendek menekankan pada proses cepat dengan mencurigai kelambanan dan bentuk-bentuk perkembangan atau pertumbuhan berkelanjutan atau ajeg.Logika jangka pendek menuntut proses berlangsung cepat, instan, dan tidak terlambat. Proses yang berjalan lambat dan ajeg dapat mengindikasikan kegagalan dan bisa menghambat tujuan perusahaan. Logika jangka pendek merupakan buah dari kapitalisme baru. Kapitalisme baru atau kapitalisme tidak sabar bukan berarti menunjukkan tujuan yang berbeda dari pemilik modal. Tujuan kapitalisme baru tidak berbeda dengan kapitalisme era Marx, yaitu mencari keuntungan bagi pemilik modal. (Sennett, 2006:40). Sennett menyodorkan argumen bahwa budaya kapitalisme baru bergerak tidak berbeda dengan era Karl Marx, ketika lapisan sosial hanya tersusun antara kelas pekerja dan pemilik modal. Pada kapitalisme baru, ekonomi masih menjadi struktur utama yang menentukan dasar kehidupan individu dan masyarakat. Perbedaanya pada cara mendapatkan keuntungan. Kapitalisme baru ditandai dengan pemilik modal yang menginginkan hasil jangka pendek dibandingkan jangka panjang. Pemilik modal atau investor lebih berkepentingan pada keuntungan jangka pendek lewat harga saham dari pada keuntungan jangka panjang dalam dividen. Pemilik modal yang berorientasi pada hasil jangka panjang ini menunjukkan ketidaksabaran. Sennett pun menggunakan istilah milik Bennet Harrison, yaitu kapitalisme tidak sabar (impatient capital). (Sennett, 2006:5-7 & 39-40)Perusahaan yang tidak sabar akan mendorong pekerja beradaptasi dengan perubahan demi keuntungan jangka pendek. Perusahaan harus melakukan proses yang berlangsung dan tidak terlambat untuk memperoleh keuntungan bagi para pemilik modal. Kapitalisme baru pun mendorong para pekerja juga mengadopsi logika yang sama dengan para pemilik modal, yaitu mencari keuntungan demi kelanggengan kapitalisme. Semua pekerja yang berpikir dengan logika jangka pendek bahwa dia akan kaya dengan mengembangkan potensinya dan tidak menyesali apapun. Ketika seorang pekerja berorientasi jangka pendek maka dia bersedia melepaskan pengalaman masa lalu. Ini yang kemudian memunculkan prinsip ketidakgunaan dalam budaya kapitalisme baru. (Sennett, 2006:5-7) Pekerja merasa tidak berguna ketika dia tidak bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan. Pekerja pun terdorong untuk selalu beradaptasi dan mengikuti tren terbaru agar perusahaan tetap menganggapnya berguna. Ketidakgunaan ini membuat pekerja khawatir akan kehilangan pekerjaan. Sennett (2006:177) berpendapat bahwa perubahan yang tiba-tiba dalam sebuah perusahaan akan memproduksi kecemasan dan kegelisahan. Budaya kapitalisme baru pun tidak mendatangkan pencerahan, melainkan mendorong terjadinya kerusakan struktural di masyarakat. Kapitalisme tidak sabar gagal menciptakan komunitas yang menekankan pada hubungan tatap muka berdasarkan kepercayaan dan solidaritas. Kapitalisme baru membuat hubungan harus terus dinegosiasikan dan diperbaharui, alam komunal di mana setiap peka terhadap kebutuhan orang lain (Sennett, 2006:2). Kapitalisme baru atau kapitalisme tidak sabar didasarkan pada logika jangka pendek yang mendorong setiap individu, baik itu pemilik modal, kelas menengah atau buruh intelektual, dan pekerja, untuk mencari keuntungan dan kekayaan pribadi. Pada era kapitalisme baru, perusahaan mendorong pekerja beradaptasi dengan perubahan dan menerapkan pola kerja dinamis. Perubahaan terus-menerus ini menyebabkan pekerja merasa tida aman sehingga kapitalisme baru pun mengacaukan nilai-nilai di masyarakat. Sennett (2006:12) menjelaskan bagaimana kerusakan struktural yang didasari logika jangka pendek terjadi dalam tiga hal, yaitu perubahan-perubahan dalam institusi atau organisasi, pekerja yang semakin teralienasi, dan perilaku konsumsi masyarakat. Kapitalisme baru dibangun dalam logika jangka pendek meneguhkan pada fleksibilitas dan migrasi pekerja. Perusahaan yang terfragmentasi membuat kehidupan individu atau pekerja juga terfragmentasi dan tidak stabil. Pekerja tidak lagi menyelesaikan pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki, melainkan tugas yang harus diselesaikan atau task oriented. Proses kerja yang mengadopsi logika jangka pendek pun mendorong pekerja mengadopsi kepribadian konsumen, yaitu membuang barang tua meski masih berguna. Logika jangka pendek mendorong pekerja memiliki gairah untuk mengkonsumsi barang dan layanan baru. Sennett (2006) menyatakan bahwa gairah konsumsi yang menggerakkan pola konsumsi individu dipicu dua hal. Pertama, iklan dan media massa sebagai penggerak mode yang membentuk keinginan individu sehingga individu merasa tidak puas dengan apa yang dia miliki. Kedua, kapitalisme memproduksi benda yang bakal usang di masa mendatang sehingga publik akan terus membeli benda baru (Sennett, 2006:137 & 139-140).Dua hal tersebut menempatkan konsumen dalam peran pasif, yaitu korban iklan atau korban mode. Kapitalisme baru yang menghadirkan perubahan pekerjaan dan keahlian memunculkan gairah mengkonsumsi sehingga pekerja lebih aktif membeli barang (Sennett, 2006:139-140). Konsumsi ini bertahan karena memainkan peran penting dalam melengkapi dan legitimasi pengalaman. Hasrat mengkonsumsi pribadi membuat orang membeli barang untuk memasarkan diri sendiri. Inilah yang memunculkan branding dan potensi. Branding dapat dilakukan dengan cara menghubungkan barang yang dibeli dengan keterampilan pekerja yang dibutuhkan. Cara lainnya, marketing akan mencegah konsumen berpikir mengenai kegunaan produk. Potensi berkaitan dengan sesuatu yang bisa dibeli, misalnya dalam industri elektronik yang membuat konsumen biasa membeli perangkat yang sebenarnya tidak akan pernah mereka gunakan. Hal-hal ini akhirnya membuat masyarakat menjadi konsumen.
Logika Jangka Pendek dan Komodifikasi HijabLogika jangka pendek pun menular pada pola konsumsi simbol agama. Logika jangka pendek ini bisa terlihat pada komodifikasi hijab sekarang ini. Hijab pernah dianggap sebagai gaya berbusana yang ketinggalan zaman. Perempuan berhijab dianggap tidak merepresentasikan kekinian, karena terkungkung pada era nabi. Sekarang ini, simbol-simbol Islam dapat dengan mudah dilihat di lingkungan sekitar. Perempuan-perempuan mengenakan hijab warna-warni di pusat perbelanjaan. Hijab juga mendapatkan tempat di pertunjukkan-pertunjukkan fashion. Ada transformasi Islam di masyarakat Indonesia. Dari agama yang dianggap kolot dan pemberontak ketika Orde Baru menjadi tren arus utama di kalangan masyarakat Indonesia. Kondisi ini seolah menunjukkan ilusi bahwa Islam telah memengaruhi gaya hidup. Padahal, Islam telah masuk dalam budaya populer. Budaya popular tidak dapat dipisahkan dari perkembangan industrialisasi, kapitalisme, dan konsumerisme. Budaya popular terkait dengan apa yang disebut dengan budaya massa atau budaya yang diproduksi mengikuti pola produksi massa. Artinya, umat Muslim telah didorong oleh sistem yang membuat masyarakat berinteraksi karena konsumsi ekonomi. Proses ini berlangsung karena adanya manipulasi. Penganut Islam seolah-seolah menganggap bahwa apa yang mereka lakukan berdasarkan keinginan sendiri untuk mematuhi perintah agama, padahal mereka mengikuti logika kapitalisme untuk mendapatkan keuntungan. Azyumardi Azra menyatakan, Islam dengan penganut lebih dari satu miliar jiwa menjadi gejala pasar. Sebagai gejala pasar, Islam juga mengalami proses komodifikasi.[footnoteRef:1] [1: Azyumardi Azra. Komodifikasi Islam. Republika edisi 11 September 2008.]
Itu menunjukkan bahwa kapitalisme telah mengubah nilai-nilai hijab menjadi sesuatu yang bisa ditukar dengan uang atau komodifikasi. Roy Shuker (2002, halaman 55) mendefinisikan komodifikasi sebagai konsep sosiologi yang mengacu pada proses di mana sebuah produk, termasuk pekerja, digunakan sebagai komoditas di pasar. Komodifikasi membuat segala sesuatu, termasuk manusia dan benda, yang awalnya tidak mengikuti aturan pasar berubah menjadi obyek yang mengikuti aturan pasar. Artinya, umat Muslim telah didorong oleh sistem yang membuat masyarakat berinteraksi karena konsumsi ekonomi.
Komodifikasi IslamDalam ajaran Islam, agama bukanlah benda yang bisa diperjualbelikan demi mendapatkan keuntungan. Islam juga melarang perdagangan simbol-simbol agama. Bahkan, para ulama juga dilarang memenuhi kebutuhan hidupnya melalui dakwah. Sebab, berdakwah merupakan kewajiban Muslim. Namun, logika kapitalisme membuat komodifikasi Islam seolah tidak bisa dihindarkan. Industri mengambil kebudayaan dalam Islam, seperti hijab, untuk diubah menjadi benda yang mendatangkan keuntungan bagi kelompok kapitalisme. Greg Fealy menyakan keimanan dan simbol-simbol Islam sudah diubah menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk mendapat keuntungan.[footnoteRef:2] [2: Greg Fealy. Consuming Islam: Commodified Religion and Aspirational Pietism in Contemporary Indonesia dalam Greg Fealy & Sally White (eds), Expressing Islam: Religious Life and Politics in IndonesiaSingapore: ISEAS, 2008, halaman 17.]
Nabil Echchaibi dalam artikel berjudul Mecca Cola and Burqinis: Muslim Consumption and Religious Identities menunjukkan bagaimana kapitalisme telah melakukan komodifikasi Islam melalui label Halal. Para pemilik modal menyadari bahwa label Halal bisa mendatangkan potensi pasar yang sangat besar. Artinya, keuntungan yang diraup bakal meningkat dengan memromosikan halal. Echchaibi menunjukkan bahwa pasar halal di dunia sekarang ini tidak hanya melakukan penyesuaian dalam makanan, seperti Mecca Cola dan MacBurger. Namun, berbagai produk lainnya, seperti Fulla yang merupakan versi Barbie untuk anak-anak Muslim dan burqini yang merupakan versi bikini syariah. Dia menyebutkan bahwa industri halal secara global diestimasikan mencapai 2,3 miliar Dolar Amerika Serikat (sekitar Rp 28 triliun).[footnoteRef:3] [3: Nabil Echchaibi. Mecca Cola and Burqinis: Muslim Consumption and Religious Identities dalam Gordon Lynch and Jolyon Mitchell, (eds.) Religion, Media and Culture: A Reader. London & New York: Routledge. 2011.]
Dengan demikian, Islam sebagai komoditas sudah mengikuti logika pasar. Demi mendapatkan keuntungan, kapitalisme mentransformasi nilai guna simbol-simbol keimanan menjadi nilai tukar atau bisa dibayarkan dengan uang. Para pemilik modal menangkap adanya kebutuhan-kebutuhan para penganut Islam atas berbagai kewajiban memenuhi aturan agama. Selanjutnya, industri memproduksi benda-benda yang bisa membuat Muslim menganggap mereka sudah memenuhi kewajiban kepada Tuhan. Kebutuhan yang meningkat akan mendorong industri untuk membuat produk yang lebih banyak atau secara massal. Agar produk-produk tersebut bisa menjangkau lebih banyak penganut Islam di seluruh dunia, maka para pemilik modal membuat standardisasi dan penyeragaman. Ini sesuai dengan pernyataan Theodor Adorno dan Max Horkheimher melalui esai berjudul The Culture Industry pada 1944. Adorno menyatakan bahwa proses produksi budaya telah menjadi industri yang tidak berbeda dengan industri lainnya. Industri budaya memproduksi komoditas untuk keuntungan, sehingga ada keseragaman budaya.[footnoteRef:4] [4: Robert E Babe. Cultural Studies and Politcal Economy: Toward A New Integration. Plymouth: Lexington Books. 2009, halaman 23.]
Keseragaman merupakan dampak dari komodifikasi budaya. Keseragaman menunjukkan adaya tren yang sama. Dalam konteks agama, ada semangat dari para penganut Islam untuk mempraktikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Umat Muslim membutuhkan berbagai produk untuk bisa tetap hidup sesuai aturan, lalu apa yang salah dengan itu? Apa yang salah dari keseragaman yang menunjukkan semangat beragama? Komodifikasi memang tidak selamanya buruk. Namun, dampak negatif yang paling mencolok dari komodifikasi adalah alasan menjalankan agama dikalahkan dengan pertimbangan mendapatkan keuntungan. Pada akhirnya, komodifikasi akan menghancurkan tatanan dalam masyarakat. Ketika kapitalisme masih berpihak kepada agama, masyarakat dimanipulasi dengan seolah menginginkan benda tertentu. Padahal, masyarakat tidak diberikan pilihan karena adanya keseragaman. Ini akan menyebabkan masyarakat berpaling dari perilaku aktif dan kritis dalam masyarakat. Selain itu, kapitalisme hanya berpihak pada benda yang bisa mendatangkan keuntungan. Ketika agama sudah tidak mendatangkan keuntungan maka dia akan ditinggalkan. Ada masalah yang melekat ketika menetapkan nilai ekonomi untuk hal-hal yang secara tradisional tidak dilihat dari segi tersebut. Komodofikasi ini bisa menyebabkan terjadinya banalitas Islam. Berbagai hal yang dianggap tidak sesuai Islam justru menjadi bagian yang turut mempromosikan islam. Akibatnya, ritual keagamaan menjadi kesenangan tanpa adanya penghayatan. Azyumardi Azra menyatakan komodifikasi membuat kehidupan keislaman menjadi penuh syiar dan kemeriahan. Kendati demikian, kemeriahan ini bisa membuat Islam menjadi dangkal karena bergerak sesuai dengan kemauan pasar. Bahkan, kemeriahan dapat membuat agama atau keagamaan kehilangan maknanya.[footnoteRef:5] [5: Azyumardi Azra, loc cit.]
Komodifikasi HijabHijab di media massa. Komodifikasi hijab mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir karena difasilitasi kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan teknologi informasi mendorong kepentingan bisnis dalam skala yang lebih besar. Teknologi komunikasi dan informasi berperan mempromosikan berbagai simbol Islam untuk bisa dikonsumsi di seluruh dunia. Sebagai contoh, fenomena hijab sebagai fashion di Indonesia dimulai oleh Hana Tajima asal Inggris. Tajima yang merupakan mahasiswi sekolah desain kerap memposting caranya mengenakan hijab melalui laman di internet. Kemudian, gaya Tajima meluas di negara-negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, fenomena hijab sebagai fashion itu menjalar mulai dari internet Gejala Hana Tajima dan hijabers menunjukkan bahwa simbol Islam dapat menjadi barang yang diperdagangkan di seluruh dunia, tidak hanya di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Dari fenomena hijab ini juga terlihat bagimana peran media massa dalam produksi dan reproduksi budaya. Pada giliran, komodifikasi hijab ini mengarah pada komodifikasi konten media massa. Komodifikasi hijabdalam konten-konten media massa terlihat ketika Ramadhan. Selama lebih dari satu dekade, media massa sudah menjadikan Ramadhan, bulan suci umat Islam, sebagai waktu yang tepat untuk memperdagangkan simbol-simbol agama melalui program di media massa, khususnya televisi. Selebriti yang tampil mengenakan pakaian sopan dengan jilbab atau kerudung ketika tampil di televisi. Seiring berjalan waktu, komodifikasi hijab tidak hanya terjadi ketika Ramadhan. Perempuan-perempuan berjilbab tidak lagi hanya tampil ketika Ramadhan, namun setiap hari. Hijab dan konsep perempuan. Hijab merupakan pakaian perempuan muslim, sehingga komodifikasi hijab sebagai pakaian yang sehari-hari yang dilakukan secara masif berdampak pada perempuan di Indonesia. Komodifikasi yang dilakukan oleh media massa terkait hijab memunculkan konsep baru soal perempuan. Konsep baru tersebut, yaitu perempuan ideal adalah berjilbab. Hijab atau jilbab menjadi identifikasi bahwa perempuan tersebut baik dan patuh pada suami sesuai perintah agama. Alhasil, hijab bisa menjadi personal branding dan positioning sebagai perempuan baik-baik. Kemunculan merek-merek hijab atau pakaian Muslimah juga menyebabkan adanya personal branding dan positioning. Melalui merek hijab atau pakaian Muslimah yang dikenakan, setiap perempuan Muslim bisa mencitrakan dirinya. Sebab, merek bisa menjadi kelas sosial. Komodifikasi hijab juga memunculkan peluang usaha lain berkembang, seperti salon dan kosmetik. Salon dan yang dikunjungi dan kosmetik yang digunakan bisa menjadi cara individu memberi tanda kelas sosial di mana dia berada. Praktik seperti ini menunjukkan kedangkalan pemikiran sehingga melenakan perempuan Muslim. Kualitas perempuan dinilai dari sekedar berjilbab atau tidak berjilbab. Komodifiaksi hijab seolah-olah mempromosikan perempuan dengan pakaian tertutup, seolah-olah menghormati tubuh perempuan. Padahal, tubuh perempuan lagi-lagi menjadi komodifikasi bagi industri. Melalui tubuh yang tertutup, perempuan didikte barang (merek) apa yang harus dia konsumsi. Industri mengambil kebudayaan dalam Islam, seperti hijab, untuk diubah menjadi benda yang mendatangkan keuntungan bagi kelompok kapitalisme. Greg Fealy (2002, halaman 17) menyatakan keimanan dan simbol-simbol Islam sudah diubah menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk mendapat keuntungan.Nabil Echchaibi (2011) dalam artikel berjudul Mecca Cola and Burqinis: Muslim Consumption and Religious Identities menunjukkan bagaimana kapitalisme telah melakukan komodifikasi Islam melalui label Halal. Para pemilik modal menyadari bahwa label Halal bisa mendatangkan potensi pasar yang sangat besar. Artinya, keuntungan yang diraup bakal meningkat dengan memromosikan halal. Dengan demikian, Islam sebagai komoditas sudah mengikuti logika pasar. Demi mendapatkan keuntungan, kapitalisme mentransformasi nilai guna simbol-simbol keimanan menjadi nilai tukar atau bisa dibayarkan dengan uang. Para pemilik modal menangkap adanya kebutuhan-kebutuhan para penganut Islam atas berbagai kewajiban memenuhi aturan agama. Selanjutnya, industri memproduksi benda-benda yang bisa membuat Muslim menganggap mereka sudah memenuhi kewajiban kepada Tuhan.
Bacaan tambahanRoy Shuker. Popular Music: The Key Concept. London dan New York: Routledge. 2002. Azyumardi Azra. Komodifikasi Islam. Republika edisi 11 September 2008.Greg Fealy. Consuming Islam: Commodified Religion and Aspirational Pietism in Contemporary Indonesia dalam Greg Fealy & Sally White (eds), Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia. Singapore: ISEAS, 2008.Nabil Echchaibi. Mecca Cola and Burqinis: Muslim Consumption and Religious Identities dalam Gordon Lynch and Jolyon Mitchell, (eds.) Religion, Media and Culture: A Reader. London & New York: Routledge. 2011.Robert E Babe. Cultural Studies and Politcal Economy: Toward A New Integration. Plymouth: Lexington Books. 2009.